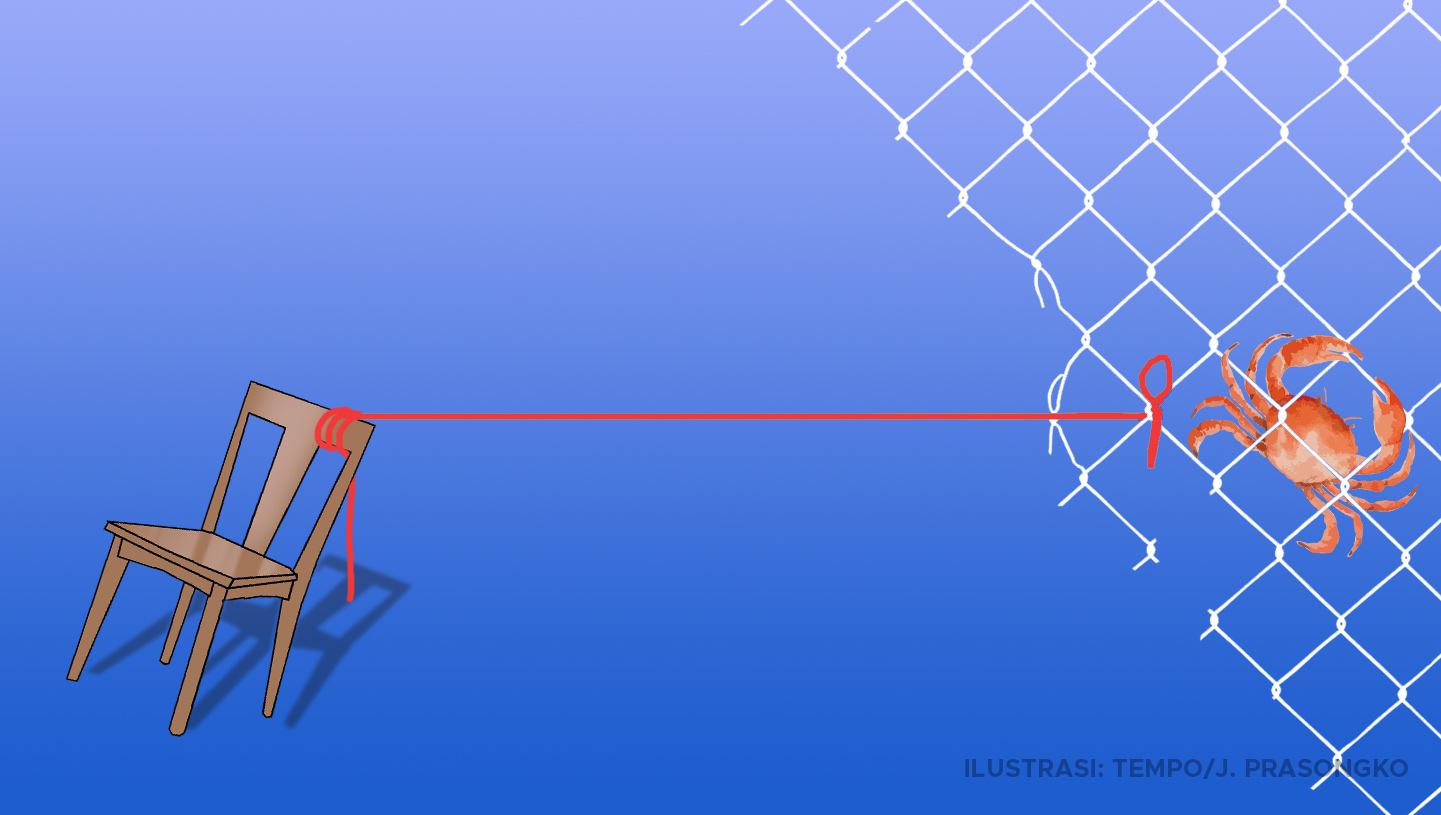Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
GAJAH mati meninggalkan gading, Toni Morrison meninggalkan hantu—bukan hantu dirinya, melainkan hantu yang datang saat orang melupakan masa lalu Amerika yang keji.
Toni Morrison menulis novel, 11 buah, tapi saya terpaku pada Beloved. Saya ingat saya tak bisa tidur setelah membacanya. Sastrawan perempuan hitam ini bercerita dari apa yang dekat dengan kulit dan bawah sadarnya, trauma nenek moyangnya, bilur panjang perbudakan: jutaan Negro yang di abad ke-16 ditangkapi dan diangkut paksa dari dusun-dusun Afrika, dan setelah mengarungi laut—yang selama berpuluh-puluh hari tak pernah mereka lihat dari dalam kurungan kapal—dijual untuk disekap di perkebunan-perkebunan Amerika yang asing dan keras.
Yang menghunjam dari Beloved bukan hanya apa yang diceritakannya, tapi—seperti laiknya novel yang autentik—bagaimana semua itu diceritakan. Kata-kata Morrison seakan-akan datang dari endapan tubuh yang disakiti bertahun-tahun: kalimat-kalimat pendek, persis, seakan-akan untuk memperkuat diri, cetusan yang di sana-sini mengalir menenggelamkan koma, imaji yang puitis yang terkadang seperti menggugat. Tentu, yang puitis dalam Beloved tak seintens dalam novel Morrison yang lain, Song of Solomon—tapi ada yang membuatnya membekas lama.
Dalam Beloved, adegan yang ajaib dan yang banal berkelindan, takhayul muncul sebagai bagian hidup sehari-hari, kekerasan bisa mengejutkan, tapi sekaligus begitu biasa, dan yang erotis bisa merangsang tapi juga sayup-sayup.
Kisah ini dimulai di Cincinnati, Ohio, di tahun 1873. Persisnya di rumah bernomor “124” di Bluestone Road. Di sana, selama 18 tahun terakhir, Sethe, seorang perempuan bekas budak, tinggal bersama Denver, anaknya perempuan, si bungsu. Juga bersama hantu dan rasa bersalah dan bekas penyiksaan dan hidup yang makin tipis.
Di rumah itu juga pernah tinggal Baby Suggs, mertua Sethe, perempuan tua yang sesekali bertindak sebagai pengkhotbah tanpa gereja (“unchurched”) di sebuah petak hutan yang tak ditumbuhi pohon, tempat para bekas budak sesekali berkumpul. Ia memberi mereka keyakinan untuk setia kepada diri, ketika, nun di sana, tubuh hitam mereka ditampik. Cintailah daging tubuhmu di sini, katanya, cintailah dengan tari dan tawa. “In this here place, we flesh; flesh that weeps, laughs; flesh that dances on bare feet in grass. Love it.”
Bagi Sethe, Baby Suggs juga ibu yang memijit dan melemaskan lehernya yang tegang, ibu yang nasihatnya melemaskan amarahnya kepada dunia. Sethe patuh. Ia letakkan “pisau-pisau pertahanannya yang berat”, senjatanya untuk melawan “nestapa, sesal, kepahitan, dan luka”. Dengan kata lain: untuk melawan masa lalu.
Meskipun ia tak berhasil.
Masa lalu menelan Sethe sepenuhnya. Perempuan ini pernah mencoba melarikan diri dari Sweet Home, tempat ia diperbudak. Majikannya menghukumnya dengan menguliti punggung perempuan yang dulu cantik ini dalam keadaan hamil. Ketika Sethe berhasil lepas bersama keempat anaknya, majikannya dan para pemburu budak datang ke tempatnya bersembunyi. Sethe pun melakukan sesuatu yang dianggapnya pilihan terakhir: membunuh semua anaknya, mengirim mereka ke akhirat yang tak disentuh perbudakan. Sethe gagal. Hanya si upik yang tewas disembelihnya.
Anak kecil itu belum diberi nama. Nama “Beloved” yang tertulis di nisannya—“yang tercinta”—diambil dari khotbah pak pendeta waktu pemakaman.
Tapi tak semua hal bisa dikuburkan. Hantu mendatangi rumah No. 124 di Cincinnati. Kedua anak lelaki Sethe kabur. Sebaliknya bagi Denver, si bungsu yang kesepian, hantu itu temannya. Ia marah ketika pacar ibunya, Paul D, membuat roh yang tak tampak itu terusir.
Beberapa tahun kemudian, seorang gadis berumur sekitar 19 tahun muncul dari air rawa, tapi dengan pakaian lengkap. Ia lelah dan haus, tapi sepatu dan bajunya baru. Kulitnya mulus, kecuali tiga bekas gores di dahinya. Dengan susah payah orang-orang mengangkut tubuhnya ke rumah nomor 124. Di depan Sethe dan Denver, dengan suara serak, gadis aneh itu menyebut namanya. “Dalam gelap di sana, namaku Beloved.”
Sethe percaya, gadis itu roh si upik yang dulu ia sembelih. Rasa berdosa membuat dirinya mati-matian melayaninya….
Tapi benarkah? Novel ini tak menjawab. Si Beloved mungkin reinkarnasi anak yang terpaksa dibunuh ibunya, tapi mungkin juga titisan masa lalu yang lebih luas dan gelap. Gadis berusia 20 tahun ini terkadang seperti tak sadar mengucapkan rasa pedih orang-orang Afrika yang diangkut di kapal sekian abad yang lalu: ribuan kulit hitam yang dijualbelikan seperti ternak dan di saat kehausan hanya diberi air kencing si kulit putih.
Dengan ambiguitas itu Beloved menawarkan makna lain sejarah Amerika—sebuah sejarah peradaban yang juga sejarah kebiadaban.
Dan itulah hantu dalam wasiat Toni Morrison. Hantu yang mengingatkan kita ketika Trump dan kaum rasis berkuasa di Amerika: lihat, kekejian tak mati-mati. “...nothing ever dies,” seperti kata si Denver.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo