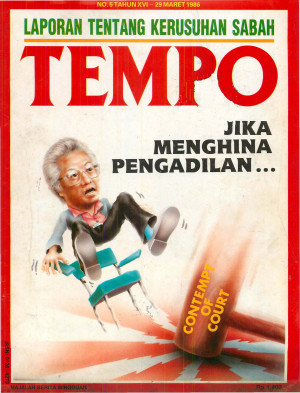KAMI berjalan sore-sore menyusuri desa Prancis tua itu, yang membanggakan diri dengan taman rajanya yang luas, dari zaman Louis XIV. Musim gugur seperti membentangkan permadani Turki pada daun-daun hutan agak di kejauhan. Di belakang kami suara angin. Tak ada deru mobil. Hanya sesekali bel sepeda. "Aku menyukai tempat ini," kata teman saya, seorang penulis tak terkenal kelahiran Belgia. Ia memang tinggal di desa itu, sejak beberapa belas tahun. "Aku menyukai tempat ini lebih dari banyak tempat di Eropa," katanya setengah mengulang. Ketika kami selesai satu jam berjalan -- menyeberangi taman dan hutan perburuan, melihat kolam dan pohon-pohon yang membisu -- teman-itu menunjuk ke satu tempat agak di tepi jalan. Sebuah kafe kecil. Kami pun ke sana, duduk, memesan shery. Tempat itu lengang tampaknya, tapi agak di bagian dalam tampak lima pasang anak muda merayakan sebuah perkawinan. Mereka menari dengan lagu pada akordeon. Pengantin dusun yang riang. "Apakah jadinya hidup ini jika kegembiraan kecil seperti itu hilang, jika kafe kecil ini berubah jadi restoran besar, jika desa ini berubah jadi Paris atau New York?" teman saya terus berkata-kata. Saya memandangi pasangan-pasangan itu, yang menari, dengan gelas anggur di tangan, dan dengan ketawa dan nyanyi yang mulai terhuyung-huyung. "Karena itu, kau beruntung, di Indonesia," kata teman saya pula. "Orang masih bisa menghibur diri, menyanyi dan menari, dan tak cuma menunggu acara musik televisi. Kau tentu menyukai dusun-dusun di khatulistiwa itu, bukan? Mungkin lebih nyaman dari ini?" Saya mengangguk, "ya, ya", dan mencoba mengingat dusun-dusun yang pernah saya kenal. Di sana memang ada kegembiraan, juga pengantin, meskipun tanpa tarian dan anggur. Di sana ada kedai, juga orang menembang atau bermain gamelan. Tapi di sana ada kemiskinan. Dan kepadatan. "Di Dunia Ketiga orang berseru untuk industrialisasi, modernisasi. Mobil, tv, pabrik, dan entah apa lagi didatangkan. Apa yang sebenarnya hendak didapat? Kebahagiaan? Lalu teman itu memungut selembar daun yang jatuh, dan menciumnya. "Harum daun ini adalah sebagian tari surga yang hampir hilang," katanya lagi. "Maka, Dunia Ketiga tak perlu kehilangan harum daun jati," tiba-tiba ia seperti menasihati. "Tutup pintu kalian dari angin buruk, tumbuhlah seperti padi tumbuh, dengan sifat-sifatnya sendiri." Sore mulai gelap. Rombongan pengantin itu masih menyanyi, sampai pada sebuah lagu yang tiba-tiba membuat mata saya nyalang: melodi itu pernah diajarkan kakak saya, dulu, jauh, di sebuah dusun di Indonesia. Bagaimana melodi itu bisa datang menyeberangi lautan dan benua, tak tahulah saya. Saya teringat radio besar ayah di pojok rumah. Dan saya teringat tiang-tiang listrik, tempat burung-burung hinggap sebelum magrib. Seakan unggas itu mendapatkan tempat beristirahat. Dunia Ketiga pun membangun tiang-tiang listrik juga - lebih banyak. Bung Karno menyuruh orang membongkar alam, bikin telaga buatan dan Jatiluhur, juga pabrik baja dan stasiun tv. Orang komunis bicara akan membawa abad ke-20 ke antara pematang sawah. Orde Baru memasang satelit, memperkenalkan padi unggul, dan bahkan para pesindennya menembangkan semboyan "modernisasi desa". Tampaknya, pilihan memang tak banyak. Mungkin itu-itu juga, dengan pelbagai variasinya. Untuk melawan kemiskinan, untuk mengurangi tekanan kepadatan. Saya tak tahu apa yan harus saya katakan kepada teman saya. Bahwa ia bicara klise, mengulang suara romantik, mencari Dunia Ketiga yang sebenarnya hanya imajiner karena ia kehilangan sesuatu di Dunia Pertama? Tapi ia bisa mengatakan seperti Dr. Sutomo mengatakan setengah abad yang silam: berhati-hatilah. Kesalahan yang pernah dialami Dunia Pertama, toh bisa dihindari. "Janganlah terjadi yang kita juga akan menderita beberapa 'kesedihan dan kesakitan' masyarakat, seperti di Benua Eropa . . .," tulis Sutomo, tahun 1936. Masalahnya, kemudian: apa pula yang dianggap "kesedihan dan kesakitan?" Dan oleh siapa? Oleh mereka yang tak ingin kehilangan surga semula yang lebih tenteram? Atau oleh mereka yang menginginhn surga baru? Dua sisi itu adalah kenyataan-kenyataan kita, dan dua sisi itu bergolak di tengah kita. Dan pergulatan antara keduanya bukanlah sekadar pergulatan antara keindahan daun dan kemegahan pabrik. Yang terjadi akhirnya adalah pergulatan yang lebih kasar: pergulatan kepentingan -- mungkin kepentingan seorang atau lebih, nun di atas sana yang tak semua kita tahu. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini