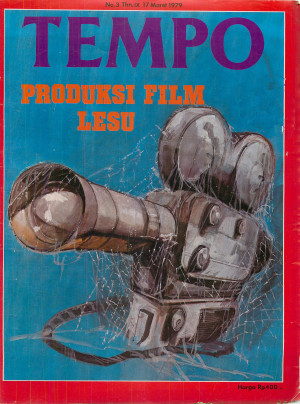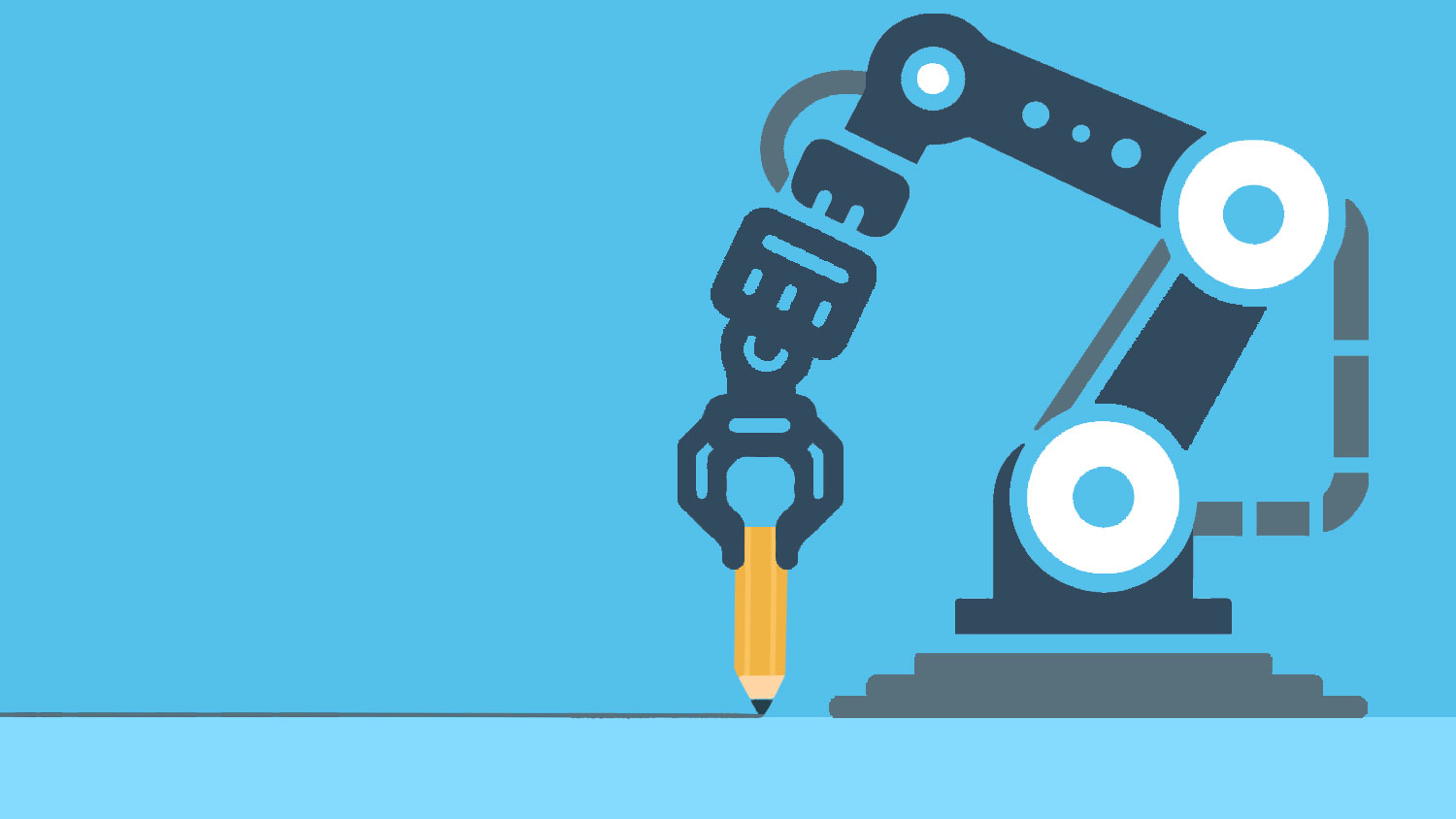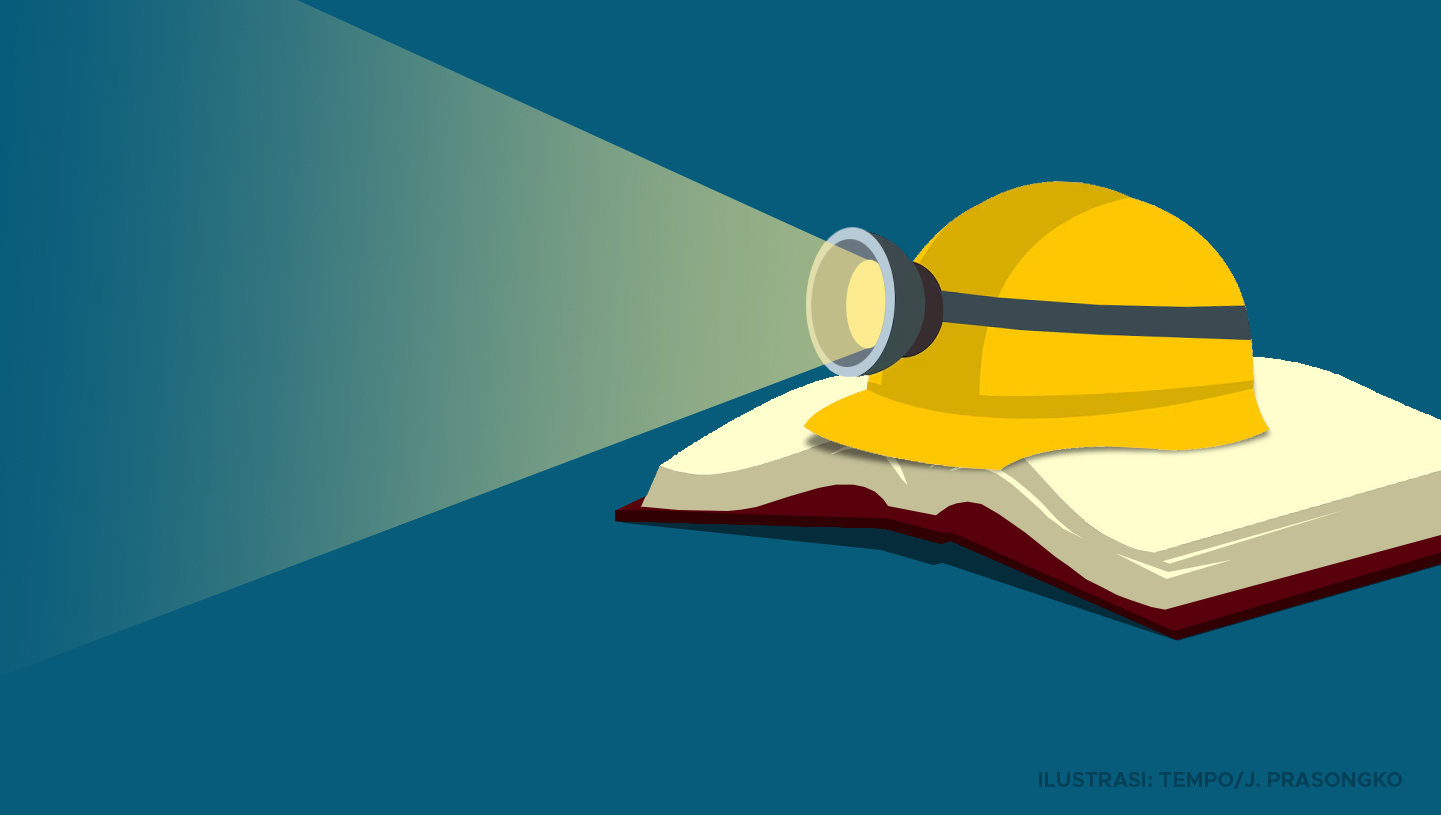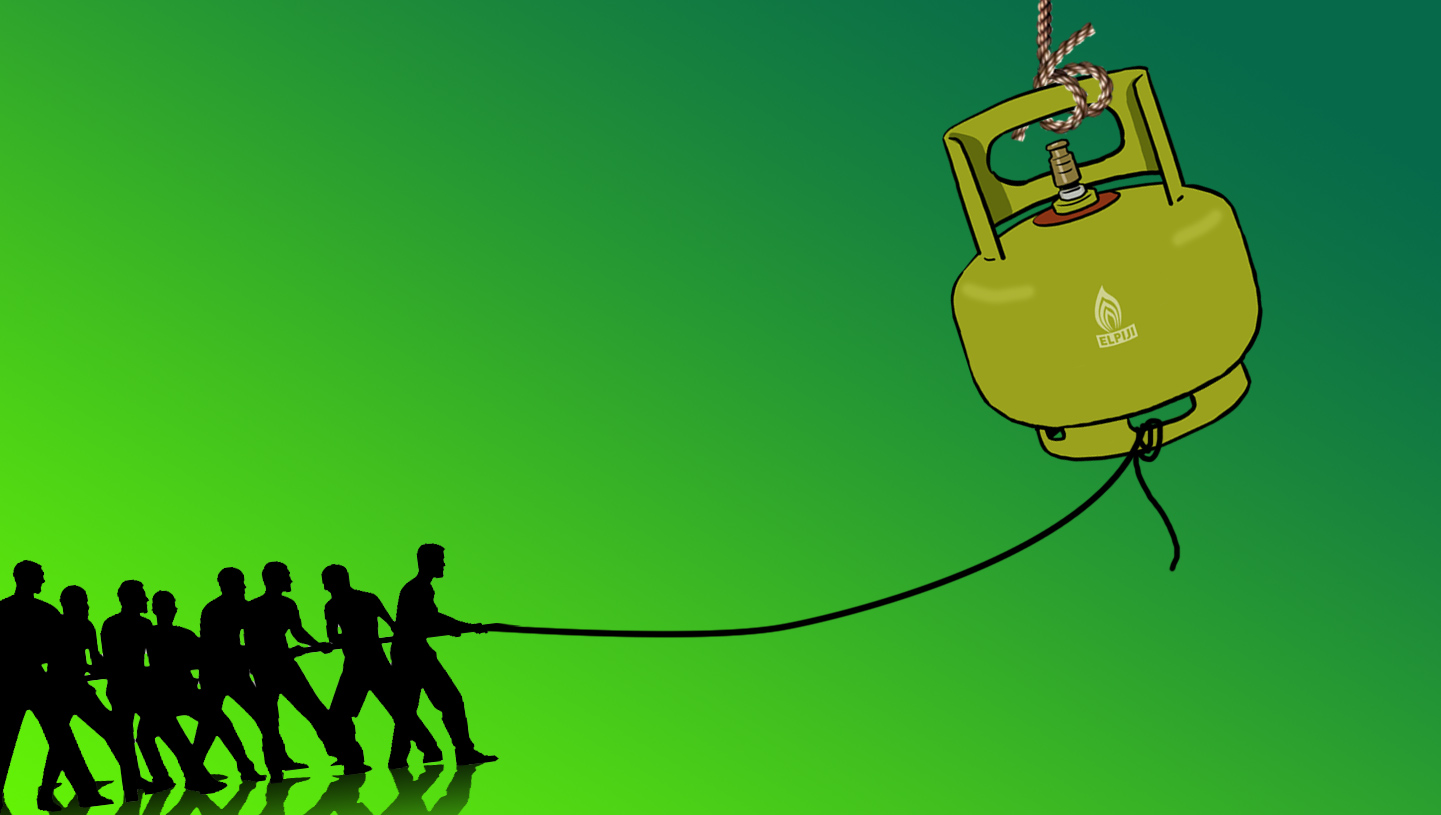SUNGGUH mengherankan kegetolan sementara kalangan umat Islam di
sini untuk berbicara lagi tentang fundamentalisme pada zaman
ini, meskipun ada fenomen Ayatullah Khomeini.
Gerakan Khomeini cenderung dilihat begitu sempit sebagai gerakan
untuk menampilkan kembali Islam zaman Nabi. Aspek populis dari
gerakan itu, yang dilambangkan oleh kesederhanaan dan gaya
kerakyatan Khomeini, jarang diperhatikan. Padahal justru aspek
itulah yang paling menonjol, karena ia menampilkan kontras yang
jelas dengan gaya Shah yang tak akrab dengan rakyat.
Usaha keras Shah untuk mencari legitimasi pada kekaisaran Persia
kuno misalnya, yang sudah tak ada sisanya yang hidup setelah
datangnya Islam, juga menunjukkan sikap "anti populis" Shah yang
kuat. Ia meremehkan "agama rakyat"-seperti juga tampak pada
konflik yang laten antara penguasa Vietnam Selatan (sebelum
jatuh) dengan kaum Budhis.
Yang jadi persoalan bukannya doktrin, tetapi kecenderungan untuk
memperagakan elitisme dengan memusuhi "agama kampung" atau
mencari legitimasi lain yang menyaingi agama rakyat itu.
Islam yang ditunjukkan oleh Khomeini adalah Islam yang populis.
Ia membangkitkan nasionalisme ekonomi, yang melawan
kecenderungan elitis dari kelompok modernizers yang kosmopolitan
itu. Citra Islam yang dibangkitkan Khomeini lain dengan citra
Islam yang dibangkitkan kaum Wahabi, atau Al Afgani, Abduh dan
Iqbal, yang bercorak fundamentalistis dan modernis itu.
Cara kita melihat dan menafsirkan fenomen lran untuk sebagian
juga menggambarkan sikap kita dalam menafsirkan tantangan dan
jawaban Islam terhadap sejarah. Dan kecenderungan untuk balik
lagi kepada fundamentalisme merupakan manifestasi dari keinginan
untuk balik kepada jawaban lama, walaupun yang dihadapi adalah
tantangan yang baru -- suatu ciri dari generasi epigon. Agaknya
kita belum menyaksikan lahirnya generasi baru dalam Islam yang
bangkit untuk menjawab tantangan baru ini.
Fundamentalisme memang lahir dari keinginan untuk kembali kepada
dasar Islam yang murni, yang sudah dibersihkan dari khurafat dan
bid'ah. Tetapi janganlah dilupakan bahwa fundamentalisme
sebagaimana kita kenal sekarang adalah fenomena Islam modern. Ia
lahir ketika suatu generasi Islam harus memberi jawab tentang di
mana tempat Islam dalam hidup modern.
Dihadapkan kepada semacam cemooh bahwa lslam itu kolot,
tradisionil menolak kemajuan, generasi itu menangkis dengan
menunjukkan Islam yang rasional, yang menghargai ilmu dan
terbuka terhadap kemajuan. Itu dianggap Islam yang "sejati",
yang diwartakan oleh Nabi, yang dibuka dengan perintah
membaca.Adaplm yang kolot, yang tradisional, yang menolak
kemajuan, itu dianggap yang khurafat, yang bid'ah, yang dibikin
oleh beberapa generasi sesudah Nabi. Maka Islam harus
dikembalikan kepada yang dasar, dengan membersihkan "nodanoda"
ini.
Masyhurlah semboyan di seantero dunia Islam kala itu bahwa Islam
yang sejati telah dikabuti oleh umatnya sendiri (Al Islamu
mahjubun bil Muslimin). Dengan demikian, fundamentalisme
sebenarnya paralel dengan modernisme dan apologia, suatu jawaban
yang dipersiapkan oleh suatu generasi yang sedang melangkah ke
arah modernisasi.
Efek Samping
Tetapi fundamentalisme juga memiliki kekurangannya sendiri. Ia
telah mengangkat Islam dalam bangsal kaca sementara menempatkan
umatnya dalam lumpur. Islam itu hebat, katanya, tapi umatnya
payah. lslam itu tinggi dan tak ada lagi yang melebihi, dan
umatnya merupakan persoalan lain lagi. Doktrin dilepaskan dari
pendukungnya, yang ideal dilepaskan dari realitas.
Akibatnya, fundamentalisme kehilangan kontak dengan kenyataan.
Dan ketika misi sqarahnya -- memberi pembenaran tentang
kehadiran Islam di zaman modern -- menjelang usai,
fundamentalisme tampak sebagai eksklusivisme yang emosional,
pencemburu dan garang. Dalam masyarakat yang makin pluralistik
dan berdiferensiasi, ia menginginkan dilaksanakannya fiqh dengan
sanksi politik.
Di tengah umat yang sarat dengan keInelaratan, khatib berkhotbah
tentang sorga dengan menerima honor ribuan rupiah. Sementara
madrasah menurut penelitian mutakhir makin menjadi "waduk
penampung" anak-anak melarat yang tak kuat sekolah, para ustaz
masih asyik mengajari mereka nahu sharaf dan batalnya wudlu,
tanpa melengkapi mereka dengan ketrampilan sebagai bekal hidup.
Dan yang lebih tragis lagi adalah rnoduksi elite umat yang masih
menaruh shalawat Nariyah di meja kerja menteri yang didudukinya
bertahun-tahun, tetapi tidak tahu tentang nasib umatnya. Sebab
yang diperlukan oleh fundamentalisme yang dekaden adalah makna
simbolis: cukuplah asal panjipanji agama dijunjung
tinggi-tinggi. Akan umatnya, itu persoalan lain lagi.
Dekadensi fundamentalisme itu menunjukkan bahwa ia tak lagi
relevan untuk menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam masa
kini. Tantangan Islam sekarang bukan lagi doktrinnya, tetapi
peri keadaan umatnya. Akan datangkah suatu generasi untuk
menjawabnya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini