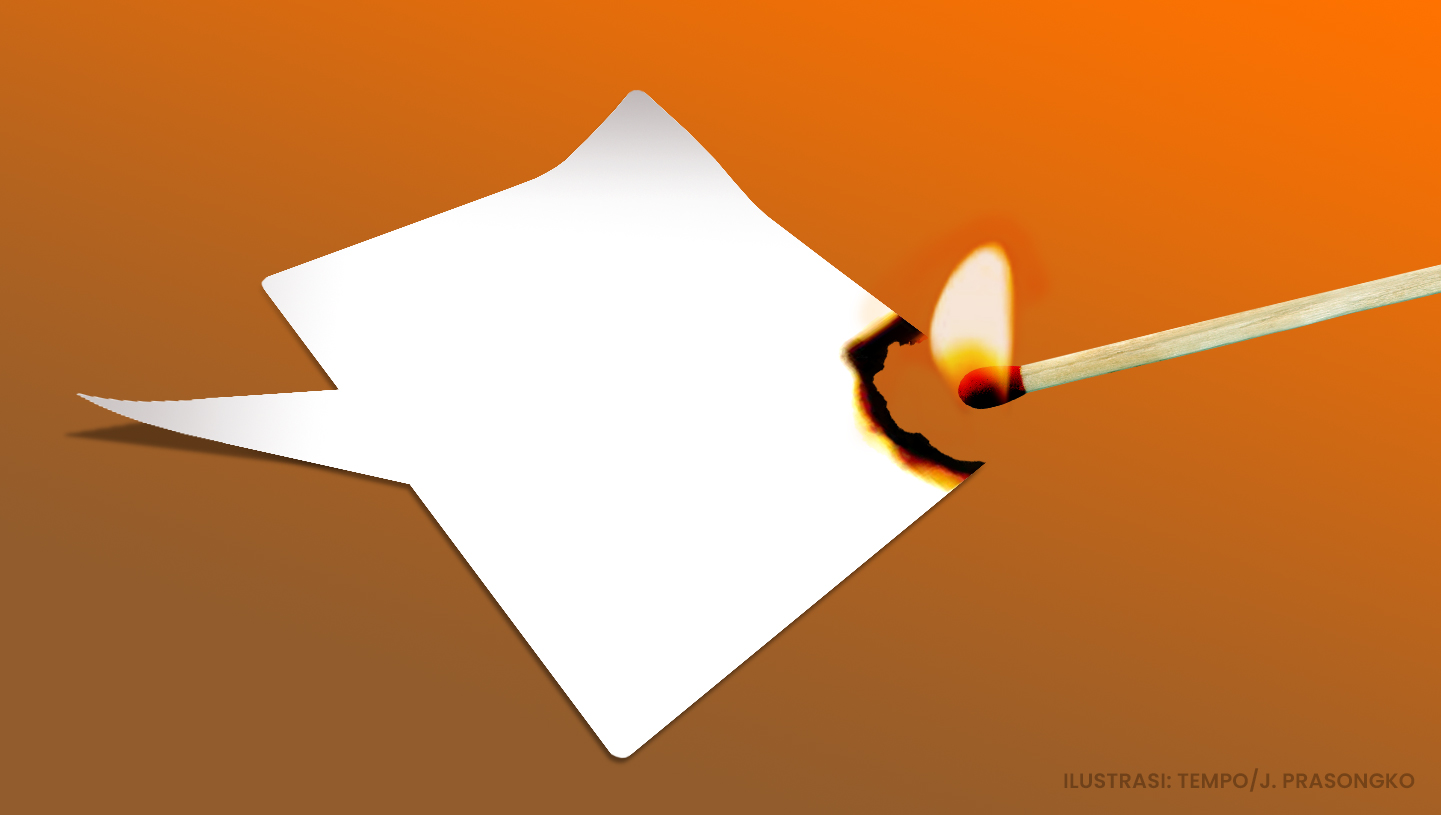Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Ariel Heryanto *)
Ariel Heryanto *)
*) Pengamat sosial politik
| Dua tahun setelah runtuhnya diktator Ferdinand Marcos pada 1986, saya berjumpa seorang aktivis Filipina yang terlibat aktif dalam gerakan people's power di sana. Ia menceritakan betapa sulit mempertahankan optimisme masyarakat sesudah sang diktator dienyahkan. Singkat cerita, sebelum dan sesudah diperintah Marcos, Filipina masih tidak banyak berbeda dalam sejumlah masalah yang pokok.
Ini beberapa contohnya yang penting. Marcos mewariskan utang luar negeri segunung. Harta negara yang dijarah keluarga Marcos dan kroninya tidak dapat diraih kembali untuk kepentingan bangsa dan negara. Aneka kasus kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Marcos tidak dapat disidangkan. Ini antara lain karena para pelaku dan dalangnya ikut duduk dalam pemerintahan Aquino—bahkan mereka dianggap pahlawan people's power. Adapun administrasi negara kacau karena diserahkan ke para mantan aktivis yang berjasa dalam demonstrasi prodemokrasi tetapi kikuk dalam seluk-beluk birokrasi istana, parlemen, atau kementerian. Suatu hari pada 1988, dua tahun setelah Marcos jatuh, teman Filipina ini bertanya dengan nada menggugat: ''Kalian di Indonesia giat menuntut berakhirnya rezim otoriter Orde Baru. Apakah kalian siap menggarap Indonesia pasca-Orde Baru? Bagaimana kalau tiba-tiba Soehato mati minggu depan? Apakah kalian sudah tahu apa yang akan kalian kerjakan? Dua tahun lalu kami tidak menduga Marcos jatuh dalam proses yang begitu cepat. Kami tergagap-gagap menerima kenyataan itu. Ternyata, lebih mudah turun ke jalan dan rutin berdemonstrasi semasa ia berkuasa ketimbang mengurus negara yang morat-marit ditinggalkan sang diktator." Dua tahun setelah Soeharto jatuh, Filipina masih tidak jauh lebih baik daripada tahun 1988. Kekayaan negara yang dijarah Marcos serta kroninya masih belum terjangkau penegak hukum. Kejahatan politik rezim itu tetap tertutup, para korban dan keluarganya tidak tersentuh keadilan. Sementara itu, percekcokan antarelite politik menguras tenaga yang sebenarnya diperlukan untuk membangun stabilitas politik dan ekonomi negeri itu. Dua tahun setelah Soeharto jatuh, sulit untuk tidak membandingkan Indonesia dengan Filipina. Kemiskinan ada di mana-mana, dan berlarut-larut. Tetapi situasi ini tidak menjadi krisis ekonomi yang mematikan. Lama-kelamaan rakyat terbiasa dengan situasi itu dan menerimanya sebagai keadaan yang normal. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada seorang diktator tetapi terpecah-pecah di antara kelompok elite. Pers menikmati kebebasan luar biasa tetapi tanpa peningkatan kualitas jurnalisme, khususnya dalam hal etika. Tidak lagi ada pembantaian yang disponsori negara terhadap satu golongan tertentu, tetapi kriminalitas swasta merajalela dalam kehidupan jelata sehari-hari. Apakah sepuluh tahun dari sekarang Indonesia masih seperti hari ini, seperti Filipina? Sejak pertengahan 1980-an atau awal 1990-an Orde Baru tampil dan secara serentak dirumuskan berbagai pihak dalam negeri sebagai ''musuh bersama" yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial Indonesia yang majemuk, tak terorganisasi, bahkan tercerai-berai. Akibatnya, merebaklah sebuah angan-angan ''kalau saja Orde Baru sudah tiada, segalanya menjadi beres". Orang berharap berbagai larangan dan sensor dihapuskan. Para tahanan politik dilepaskan. Golkar dan TNI tidak lagi merajalela dalam kehidupan sipil. Kewajiban mengikuti indoktrinasi Pancasila atau Dharma Wanita dihentikan. Hukum dan pengadilan menjadi lebih sehat dan berfungsi sebagai pengayom kaum lemah yang benar. Pertukaran pemikiran lebih kritis, terbuka, dan dewasa. Begitu juga persaingan politik dalam pemilu dan persaingan ekonomi di pasar berdasarkan kualitas produk dan harga. Angan-angan itu wajar, dan sebagian telah menjadi kenyataan. Partisipasi politik dalam partai ataupun ekstraparlemen menjadi lumrah. Kebebasan pers meluber, malahan ada yang menilai kebablasan. Sejumlah tahanan politik dibebaskan. Sebagian lain dari angan-angan itu masih di awang. Misalnya penghapusan militerisme secara total atau pengadilan atas sejumlah kejahatan politik serta ekonomi oleh pejabat Orde Baru dan kroni-kroninya. Malah ada yang lebih mencemaskan di Tanah Air ketimbang di Filipina pasca-Marcos. Misalnya, perang saudara berdasarkan perbedaan agama atau etnisitas yang berkepanjangan, atau ancaman perpecahan Negara Kesatuan RI. Yang biasanya kurang dicermati di Indonesia, proses perubahan sejarah tidak sama dengan menebang pohon, membuang sampah, atau mencabut gigi busuk. Pada kiasan-kiasan itu apa yang dibuang dan disimpan terpisah jelas. Dalam perubahan sejarah sosial keduanya tidak jelas. Ketika Orde Baru runtuh, Indonesia tidak menjadi sebuah halaman yang bersih dan siap ditulisi sejarah baru. Indonesia penuh noda. Jatuhnya Orde Baru lebih tepat diibaratkan runtuhnya bangunan kota yang didirikan dengan anggaran yang sudah dikorupsi habis-habisan, di atas tanah rampasan milik petani, lalu diguncang gempa dahsyat. Indonesia seperti banyak negara yang baru merdeka dari otoriterisme berkepanjangan mirip sebuah wilayah yang penuh taburan puing. Sampah berserakan. Darah tercecer di mana-mana. Aneka kuman dan binatang liar berkeliaran mencari mangsa. Di sela-sela reruntuhan itu Indonesia menggeliat dan berusaha bangkit membangun peradaban baru. Yang disebut gerakan Reformasi berusaha tegak di antara timbunan sampah Orde Baru: utang luar negeri, premanisme, rusaknya lingkungan hidup, selain yang biasa disebut KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Di antara timbunan sampah otoriterisme Indonesia, tidak selalu mudah menemukan mawar dan anggrek. Tetapi bukan tak ada. Pertimbangkan beberapa gejala ini. Kini untuk pertama kalinya kita bisa punya presiden yang dipilih dalam sebuah persaingan seru dan terbuka, dan relatif demokratis dalam batas-batas yang tersedia. Untuk pertama kalinya sebuah pemerintahan baru dibentuk tidak dengan pembunuhan massal. Bertolak belakang dengan rezim pendahulunya, presiden dan wakil presiden tidak melancarkan politik balas dendam terhadap para mantan penguasa yang dulu berkali-kali menyerangnya secara brutal. Di Australia, rakyat berjiwa besar menuntut pemerintahnya meminta maaf kepada kaum Aborigin, korban politik negara. Tetapi tuntutan rakyat itu diabaikan. Di Indonesia, tanpa dituntut beramai-ramai, Presiden Abdurrahman datang ke Timor Timur dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat yang menderita. Pada zaman Orde Baru, seperti di banyak negara lain, rakyat berjuang mati-matian menuntut kebebasan berpendapat yang ditindas pemerintah. Di Indonesia, Presiden Abdurrahman malahan menawarkan kebebasan lebih banyak ketimbang yang siap dicerna rakyatnya. Ketika ia mengusulkan kemerdekaan berpikir dan berpendapat dengan mencabut Tap MPR No. 25/1966, sebagian anggota parlemen yang dipilih rakyat malahan keberatan. Segera setelah Soeharto naik takhta, para lawan politiknya ditembak mati di jalanan atau dipenjara puluhan tahun. PKI bukan hanya dilarang, tetapi dimusnahkan secara fisik di luar hukum. Para bekas anggotanya dihukum seumur Orde Baru karena menjadi anggota partai yang pada masa itu disahkan hukum. Ketika Gus Dus dan Megawati menjadi kepala negara dan wakilnya, Soeharto dijaga tentara yang dibayar negara supaya tidak diganggu demonstrasi mahasiswa. Ia tidak perlu melarikan diri terbirit-birit dalam keadaan sakit dan sengsara seperti Marcos. Golkar tidak dinyatakan sebagai partai terlarang. Banyak tokoh Orde Baru ditampung dalam pemerintahannya yang baru. Yang lebih hebat, seorang tokoh Orde Baru seperti Akbar Tandjung dengan enak bisa menghardik kebijakan dan kewibawaan Presiden di depan umum. Anda bisa membayangkan Akbar Tandjung melakukan itu terhadap Presiden Soeharto yang diabdinya bertahun-tahun? Atau membayangkan seorang Presiden Soeharto pada tahun 1968 dikritik seorang tokoh PKI seperti Aidit yang juga Ketua MPR RI? Indonesia tidak sama dan bukan hanya Presiden Abdurrahman atau Wakil Presiden Megawati. Keduanya bukan semata-mata mawar di antara sampah. Tanpa kedewasaan sosial dan politik lembaga swasta dan anggota masyarakat, seorang kepala negara yang hebat sekalipun tidak akan banyak artinya. Tanpa kematangan sikap rakyat Indonesia, pemilihan umum tahun lalu tidak akan berjalan semulus itu. Masa depan Indonesia penuh tanda tanya. Tapi kalau kita tengok ke belakang dua, dua belas, atau dua puluh tahun yang lalu, siapa yang ingin kembali ke sana yang penuh dengan tanda seru? Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |