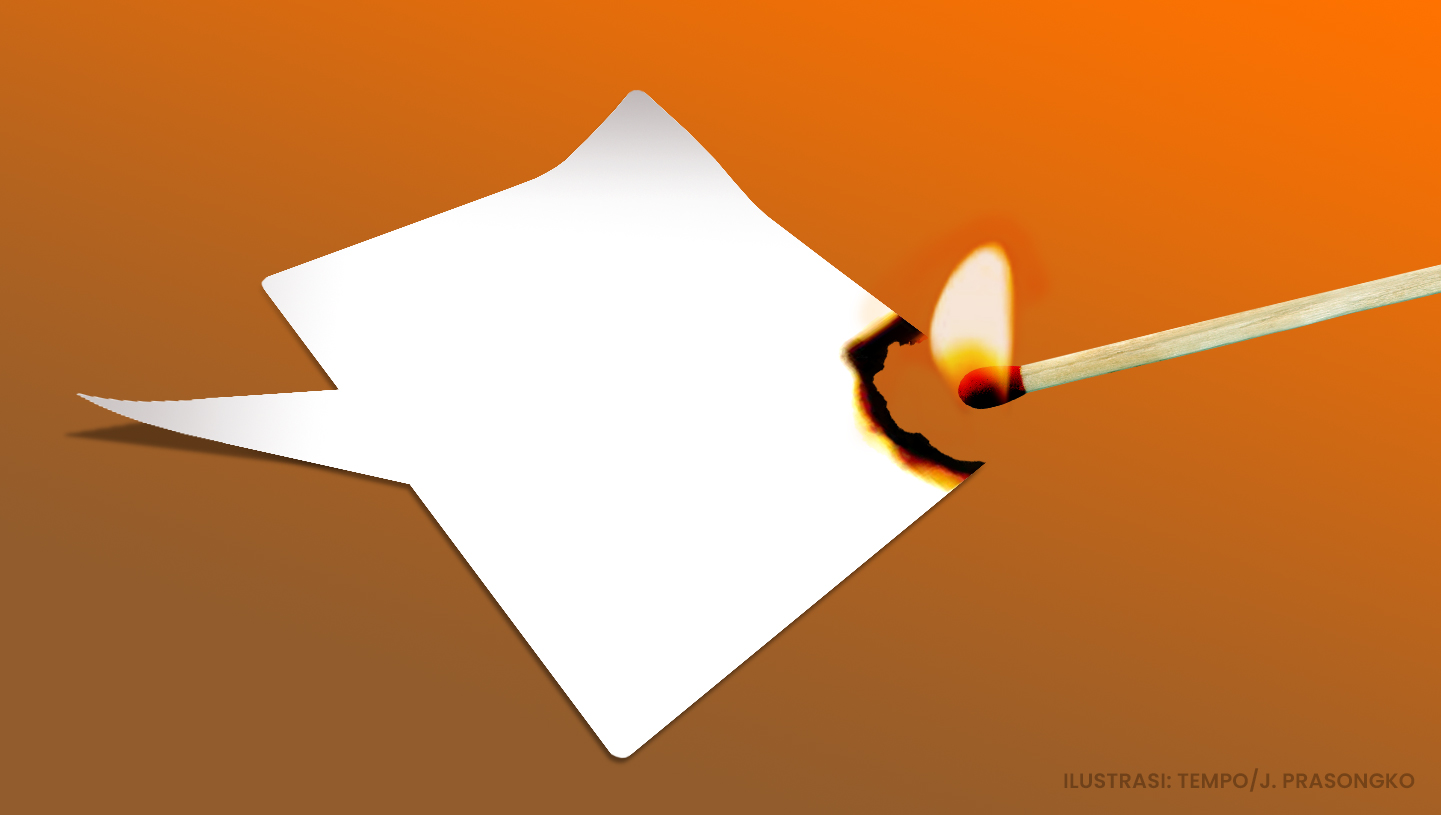Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Daniel S. Lev *)
Daniel S. Lev *)
*) Pakar politik, tinggal di Seattle
SEJARAH kadang-kadang kejam. Dalam waktu dua tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia seolah-olah dipermainkan emosinya: membuka harapan yang luar biasa untuk perubahan yang mendalam, lantas dengan terlalu cepat menyapukan harapan itu, diganti dengan kekecewaan dan kejengkelan. Persoalan pokok adalah negara hukum yang sudah lama hilang, sampai pengadilan, kejaksaan, polisi, birokrasi umum, dan pamong praja, yang semestinya jadi sumber keadilan, malah menjadi landasan korupsi, pemerasan, dan yang lebih buruk lagi. Orang mengharapkan—dan berhak mengharapkan—reformasi proses hukum yang cepat. Tetapi justru soal lembaga-lembaga peradilan terbukti terlalu sulit, dan hampir setahun sesudah dilantiknya seorang presiden dan perwakilan baru yang menjanjikan reformasi, warga negara yang dulu mulai sedikit optimistis malah jadi pesimistis. Bicara tentang optimisme atau pesimisme, tentu itu sebaiknya tidak dipukul rata. Baik optimisme maupun pesimisme banyak bergantung pada kedudukan orang dan penilaiannya tentang nasib Tanah Air atau nasib diri sendiri. Orang yang sejak dulu membenci Orde Baru karena pelanggarannya terhadap hak asasi manusia, korupsinya, dan ketidakadilannya, sekarang merasa agak optimistis. Soalnya, orang-orang yang dulu kuat dan sok kuasa kini tidak berperan lagi. Dan suatu perubahan fundamental, walau tertunda di sana-sini, jelas tidak mungkin dielakkan lagi. Dapat dikatakan juga, dalam keadaan sekarang yang penuh ketegangan, pembunuhan, kesengsaraan, kesulitan ekonomi, dan kejanggalan elite politik, orang yang tidak merasa pesimistis semestinya berkonsultasi dengan psikiater. Namun, kalau memikirkan jangka panjang, pesimisme bisa menjadi optimisme. Apalagi kalau pemikiran terfokus pada masyarakat Indonesia yang cukup sehat, dan mampu melihat adanya kelemahan struktural dan organisasi dalam pimpinan politik. Namun, apakah itu optimisme atau pesimisme atau cuma apatisme, hal-hal tersebut tidak terlalu berarti karena selalu dipengaruhi oleh kedudukan orang dan kejadian sehari-hari. Lain soalnya kalau memikirkan optimisme dan pesimisme bukan sebagai reaksi terhadap keadaan, melainkan sebagai unsur dalam filsafat praktis politik. Dalam perspektif ini, kedua pandangan itu sebaiknya jangan dipisahkan. Optimisme selalu perlu karena tanpa harapan, orang sulit bergerak. Tapi pesimisme juga penting supaya orang jangan terlalu naif atau menghindari realitas. Mahasiswa yang turun ke jalan dengan penuh optimisme, kemarahan, kejengkelan, dan sikap yang nekat sangat berpotensi untuk menggerakkan orang sehingga mampu menghancurkan sesuatu yang perlu dihancurkan. Tapi, mahasiswa yang terjun ke politik praktis seperti itu jarang bisa menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan yang baru itu—apakah bentuk negara, birokrasi atau lembaga peradilan, atau kepartaian yang sehat—menuntut pesimisme yang arif, sebagai landasan realistis buat perencanaan strategis. Satu contoh saja, sekarang sedang diperdebatkan persoalan reformasi pengadilan dan lembaga-lembaga negara. Ada yang mengira bahwa soal korupsi, ketidakmampuan, ketidakmandirian, dan sebagainya di peradilan, birokrasi, dan lembaga lain bisa selesai kalau untuk itu diangkat orang-orang yang terdidik baik, jujur, tegas, dan berani. Pandangan ini optimistis sekali, dan juga simplistis serta naif. Sebaliknya, pandangan pesimistis—yang cukup berakar pada sejarah, dan bukan hanya di Indonesia—menganggap bahwa yang bisa menjamin pelayanan untuk rakyat bukanlah orang baik, melainkan lembaga yang baik dan kuat yang bekerja berdasarkan aturan yang jelas, dan yang juga diawasi oleh pers, LSM, dan lembaga lain yang bertugas sebagai pengawas. Konsep negara hukum justru berdasarkan pandangan yang berbau pesimisme itu. Bahwa hampir semua pejabat dan pegawai bisa termakan godaan atau merasa terikat pada kepentingan atasannya, ini tentu sangat lazim. Karena itu, melalui proses hukumlah institusi yang terikat hukum semestinya menentukan. Hanya, menciptakan lembaga-lembaga kuat itu tidak gampang, antara lain karena berimplikasi bahwa pimpinan politik dan pegawai-pegawai pemerintah yang ada, semua tanpa kecuali, harus menyerahkan sebagian besar kekuasaannya kepada lembaga-lembaga itu. Mana ada yang mau, kecuali mereka sadar sedalam-dalamnya seraya siap menyikapi campuran pesimisme dan optimisme, bahwa hanya jalan itulah yang bisa menjamin persetujuan dan dukungan masyarakat yang kini semakin kecewa, marah, dan pesimistis. Dan semakin tua usia mereka, tentu semakin sukar dipermainkan. Ironis sedikit, tetapi justru pesimisme macam itu—pesimisme, bukan sinisme—baik di dalam masyarakat pada umumnya maupun pada generasi pimpinan baru yang sedang mencari jalannya sendiri, mungkin saja bisa memompakan optimisme lebih banyak. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |