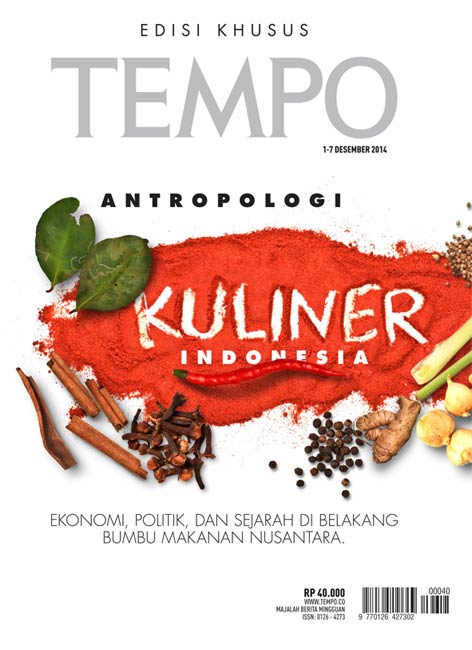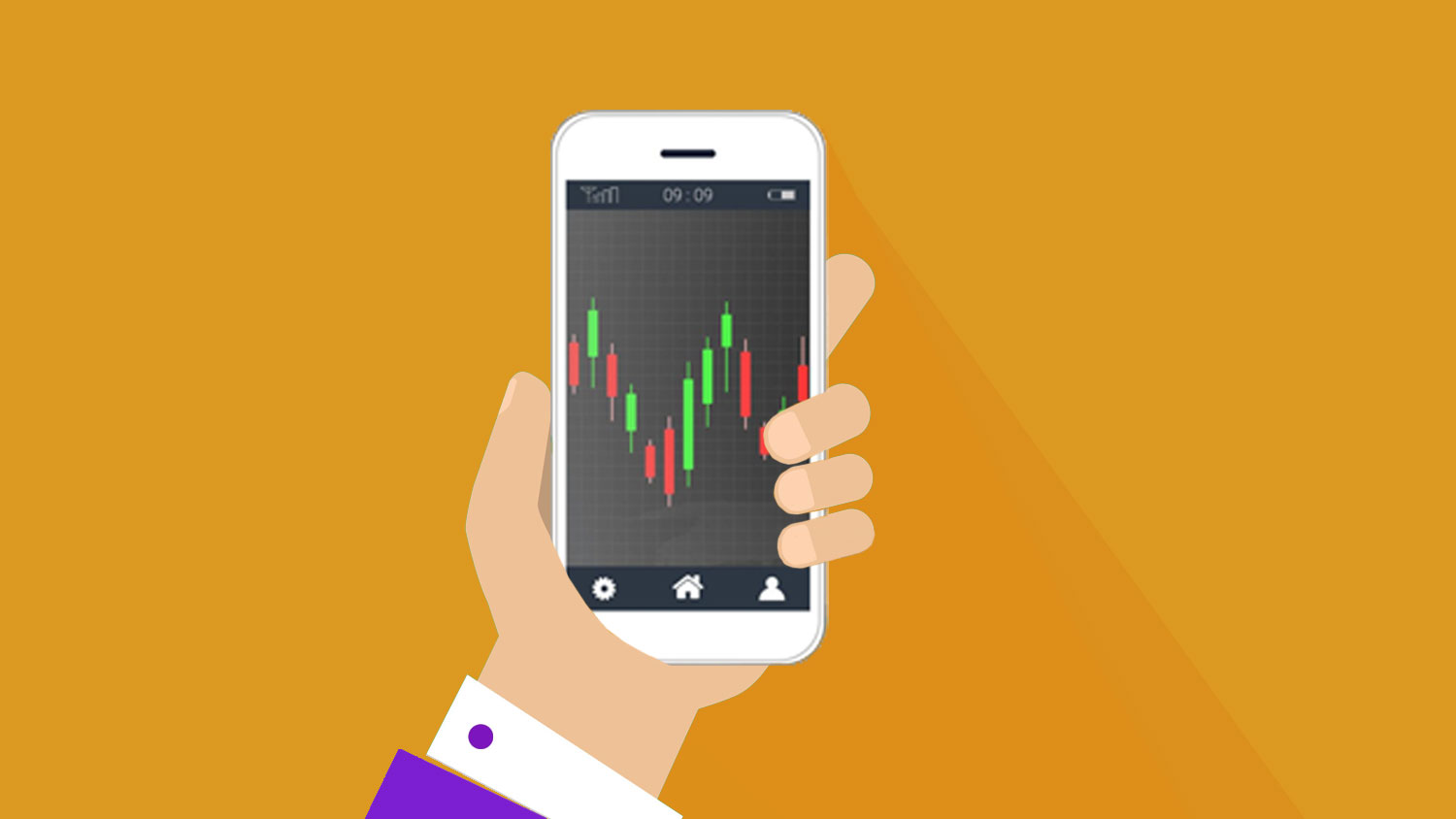Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anthony Salim lebih sering mengenakan baju batik ketimbang baju jenis lain. "Saya pakai batik karena saya suka batik. Ada orang-orang yang menyukai pakai Gucci karena mereka ingin dilihat berbaju merek itu. Biar saja…. Bagi saya, saya pakai batik karena nyaman."
Sosok Anthony, putra Liem Sioe Liong yang melanjutkan jaringan bisnis raksasa ayahnya, juga setelah rezim Soeharto yang mendukungnya jatuh, dilukiskan secara hidup dalam buku Liem Sioe Liong's Salim Group yang ditulis Richard Borsuk dan Nancy Chng, yang terbit pada 2014 ini—agaknya buku terbagus selama 10 tahun terakhir tentang sejarah bisnis di Indonesia.
Anthony, menurut buku ini, "tajam" dalam memandang kesempatan bisnis. Anthony berani ambil risiko. Anthony yang sejak kecil menunjukkan gairah bisnis. Anthony yang dipilih ayahnya, meskipun bungsu, buat jadi pengganti. Anthony yang berbeda dari kakak sulungnya, Albert.
Albert, menurut ayahnya, anak yang "sedikit malas", "gemar main gitar dan mobil balap". Sebaliknya Anthony: tak suka dandan, pakai kacamata model kokok-beluk gaya lama, dan tetap mengenakan kaus merek 777 produksi pabrik tekstil ayahnya di masa lalu.
Sambil setengah bercanda, Anthony menjelaskan apa yang tersirat dari batik. Desain batik yang rumit, katanya, itu mirip cara berbisnis di Indonesia. "Batik berbeda dari desain Burberry yang bergaris-garis sangat jelas, clear-cut, yang kotak dan batasnya segera tampak," katanya. Sementara itu, "Motif batik selalu agak gelap." Batas-batasnya "kabur". Tapi di tengah itu, "Bagaimana juga situasinya, kita akan dapat survive!"
Nama kecilnya Liem Fung Seng. Arti harfiahnya "menemu kehidupan", selamat dan hidup terus dari bencana. Hanya beberapa pekan sebelum ia lahir, pada 1949, ayahnya, pedagang yang waktu itu masih belum makmur, hampir tewas karena kecelakaan mobil. Si bungsu seakan-akan isyarat bahwa hidup bisa menjumpainya lagi. Berpuluh tahun kemudian, setelah krisis ekonomi 1997 mengguncang konglomerasi ayahnya—disebut "Grup Salim"—Fung Seng juga yang menemukan hidup kembali bagi usaha keluarga itu.
Riwayat usaha keluarga itu, seperti lazimnya kisah pebisnis di Indonesia—apalagi bila ia keturunan Tionghoa—memang bukan berlangsung di atas garis-dan-petak ala Burberry. Tapi Liem Sioe Liong memang berhak mengatakan ia mujur. Ia sangat percaya kepada feng shui. Ia tak mau merombak rumahnya yang tak mentereng di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Dengan alasan yang sama, di masa jayanya ia membiarkan makam ayah dan kakeknya yang sangat bersahaja di bukit di Niuazhai, sebuah dusun di Kota Fuqing, di Provinsi Fujian, di pantai Tiongkok sebelah tenggara.
"Saya beruntung," katanya sebagaimana dikutip Borsuk dan Chng. "Saya kerja dan saya berkembang. Kalau misalnya saya hidup di Afrika, Timur Tengah, pegimana saya bisa kerja? Waktu, tempat, dan keberuntungan… ini yang ndak bisa diubah."
Tapi ia bisa membuat tempatnya berubah: meninggalkan dusun tempat ia dilahirkan.
Di desa itu berlaku ucapan "jiu nian han, yi nian zai" (sembilan tahun kekeringan, satu tahun bencana). Antara gersang dan banjir, antara gunung dan pesisir, tanah pertanian itu nyaris tak bisa ditanami. Orang tua Liem, yang punya 11 anak, bukan peladang yang paling melarat. Tapi hidup tak gampang.
"Kami kebanyakan makan apa yang kami tanam," Liem mengisahkan masa kecilnya. "Jarang ada daging tersedia di meja." Hasil ladang juga tak menentu. Uang cepak. Orang terkadang harus pinjam ke lintah darat.
Liem muda berusaha bertahan. Ia berdagang mi mentah. Tapi pada 1937, ketika musim kering melanda, ayahnya meninggal, setelah pulang memikul ubi. Hidup berubah. Di saat itu juga Jepang mulai menyerbu Tiongkok.
Di umur 21 tahun, Liem meninggalkan dusunnya, mencoba naik kapal menuju Jawa. Ia nyaris gagal, tapi akhirnya ia berhasil mendarat di Surabaya pada 1938—dengan kantong uang yang dicopet. Dari Surabaya, ia ke Kudus di Jawa Tengah.
Di kota itu, Liem berdagang pakaian yang dipikulnya berkeliling jalan kaki. Dari sini ia mulai naik. Kudus menyenangkan hatinya. Liem merasa buah kerjanya segera tampak. Penduduk setempat ramah. Makanan juga enak—terutama soto Kudus.
Tapi baru di Semarang ia meloncat. Kota ini, pada akhir abad ke-19, adalah pusat kerajaan bisnis Oei Tiong Ham, "Raja Gula", saudagar besar pertama kelahiran Jawa yang berhasil membangun emporium internasional.
Liem kemudian menyusul, bahkan melampaui kejayaan itu. Tapi, sementara Oei Tiong Ham tak membangun koneksi bisnis dengan pemerintah Belanda, Liem berbeda: ia praktis ditegakkan kekuasaan Soeharto, jenderal yang dikenalnya sejak 1949 meskipun baru jadi rapat dengannya setelah 1966. Liem, yang selama perang kemerdekaan dari Semarang ikut menyalurkan barang kebutuhan ke wilayah Republik yang diblokade Belanda, dengan gampang menemukan teman di kalangan orang militer ini.
Soeharto menjadikan pebisnis yang jinak dan ulet ini pendukung kekuatannya—juga jadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ekonomi yang terbentuk ibarat bangunan besar yang tak stabil, sebab cuma disangga dua tiang: kekuasaan yang otoriter dan bisnis dengan monopoli yang dipaksakan.
Tapi Liem memang beruntung dan penggantinya, Anthony, memang Fung Seng. Soeharto jatuh dan digantikan sebuah sistem di mana monopoli tak berlaku. Tapi Anthony—bahkan setelah Bank BCA lepas dari tangannya—bisa memanfaatkan keadaan baru. Dan ia mengakui, "Cara kita berbisnis [kini] lebih terstruktur."
Yang kini dilupakan: pernah ada seorang mujur, yang dengan dukungan kekuasaan yang sewenang-wenang, bisa membuat orang lain tak beruntung.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo