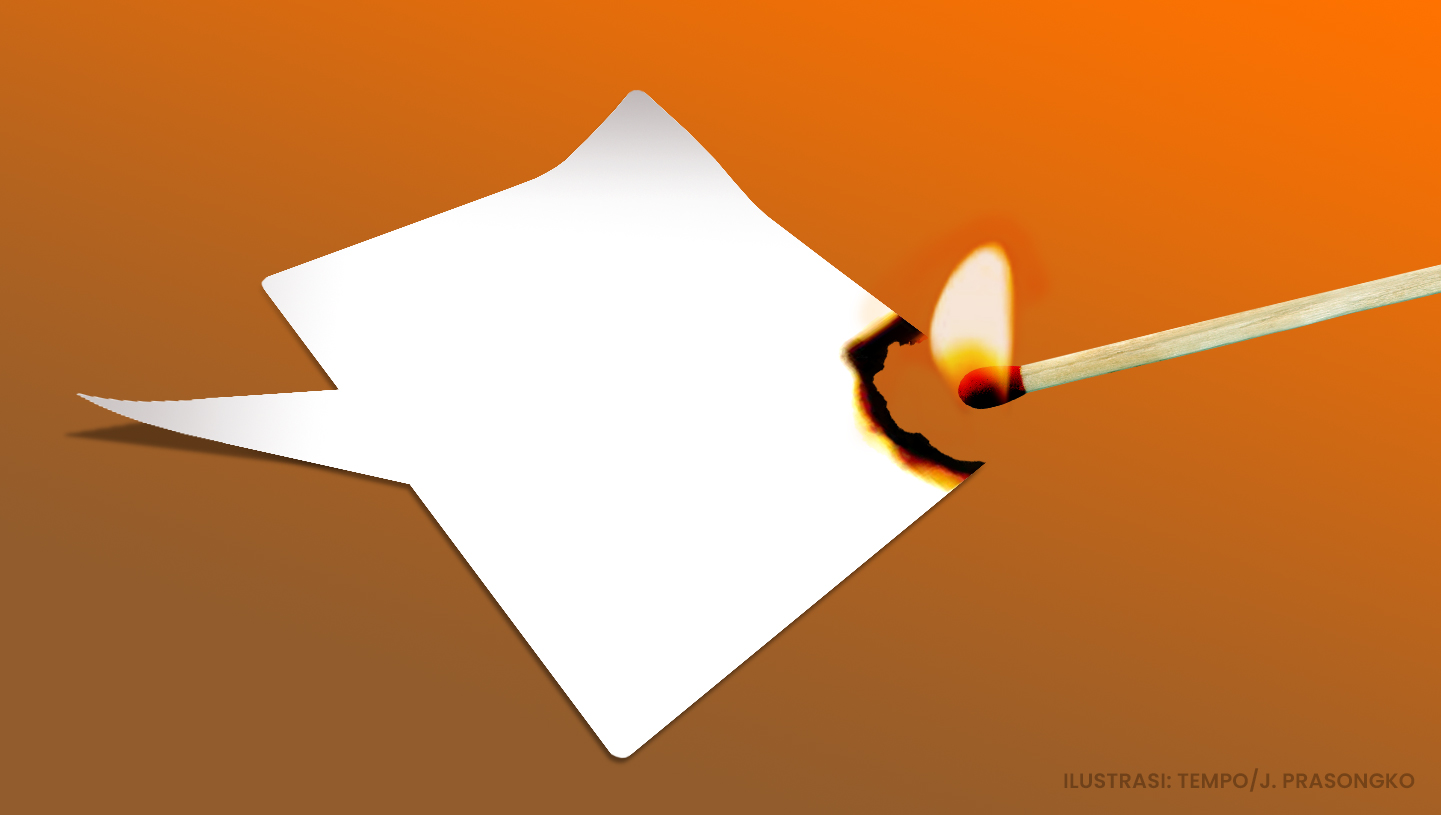KIAI Haji Irfan sangat terpandang di desanya, di Jawa Tengah, yang sebagian besar penduduknya amat miskin. Ia kaya sekali dan tanah miliknya berhektar-hektar luasnya. Cerita mengenai Pak Haji ini dianggap menarik untuk diungkapkan dalam suatu diskusi panel baru-baru ini oleh SiswonoJudo Husodo, tokoh pengusaha muda yang pernah tinggal di desa itu. Ikhwalnya, kekayaan Pak Haji yang demikian besar itu tidaklah membuatnya dibenci masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, keberadaan sang haji itu tampaknya di-"restui" oleh sekalian penduduk desanya. Bahkan di waktu lalu, ketika PKI gencar melansir landreform, Haji Irfan itu dilindungi oleh penduduk sekelilingnya. Kasus Haji Irfan ini bisa saja dipakai untuk menunjukkan bahwa kesenjangan sosial ekonomi tidak selalu harus menimbulkan konflik. Apabila memang demikian halnya, maka masalahnya terletak pada pengertian mengenai kesenjangan itu. Karena kesenjangan itu menyangkut cita rasa, ia sebenarnya merupakan masalah persepsi. Kuantifikasi belaka tampaknya tidak memadai. Di India, misalnya pembagian pendapatan antarkelompok masyarakat jauh lebih timpang daripada di Indonesia. Tapi masalah kesenjangan ekonomi itu lebih banyak dipermasalahkan di Indonesia mungkin karena lebih tampak. Restu yang diterima Haji Irfan dari masyarakat sekelilingnya mungkin merupakan konsekuensi peranannya sebagai bapak panutan, seorang bapak pelindung yang tidak hanya memberikan naungan spiritual tetapi juga keuntungan materiil. Apabila demikian, dapatkah model ini diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat kita dewasa ini, khususnya untuk menyerasikan hubungan antara pengusaha-pemilik modal dan lingkungannya? Contohnya ada, kata Kwik Kian Gie, pengusaha-cum-analis itu: perusahaan rokok Gudang Garam merupakan usaha besar pribadi swasta - notabene dari keturunan Cina - yang kehadirannya juga direstui masyarakat sekelilingnya. Hal ini rupanya karena manajemen Gudang Garam memberikan berbagai pelayanan yang jauh melampaui apa yang lazimnya dilakukan suatu perusahaan. Falsafah yang mendasarinya, katanya, adalah membagi keuntungan, yang sebenarnya cuma manifestasi "keberuntungan". Apa pun dasarnya, kasus-kasus di atas dilihat sebagai pencerminan dari apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial pengusaha. Setidaknya, dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Yayasan Prasetiya Mulya dan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia Kamis pekan lalu di Gedung YPM di Cilandak,Jakarta Selatan, tampaknya disepakati arti penting solidaritas sosial tersebut. Malahan telah dikembangkan pemikiran-pemikiran yang menunjukkan mengapa pada tahapan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dewasa ini diperlukan suatu solidaritas baru. Dalam rangka ini pengusaha dan wiraswasta patut diberi kedudukan yang layak, sebab mereka diperlukan sebagai ujung tombak menghadapi tantangan-tantangan berat di masa mendatang. Solidaritas baru ini kiranya memang diperlukan untuk mengakhiri keadaan, yang di dalamnya pengusaha swasta cenderung dilihat dengan sebelah mata, sebagai kelompok yang dalam hidupnya hanya mengenal berbisnis serta mencari uang, dan tidak peka terhadap keadaan masyarakat sekelilingnya. Citra negatif mengenai pengusaha swasta ini cukup menahun, karena bersumber pada faktor-faktor ideologis, kultural, dan emosional, antara lain karena dunia usaha tampaknya tetap didominasi kelompok keturunan Cina. Kalaupun juga disepakati bahwa hambatan-hambatan di atas dapat diatasi melalui keterlibatan sosial yang lebih besar dari para pengusaha dalam kehidupan masyarakat, cara keterlibatan itu sendiri masih perlu disepakati secara bersama. Sebab, esensi persoalannya adalah masalah membagi (redistribusi): mekanismenya, serta pola-pola yang digunakan untuk menghasilkan apa-apa yang kemudian dibagi itu. Mengenai mekanisme bisa dibedakan antara yang langsung (oleh perusahaan) dan yang tidak langsung (melalui pemerintah). Apabila sistem perpajakan berjalan dengan baik, maka masalah redistribusi secara adil diselenggarakan melalui anggaran pemerintah. Tanggung Jawab sosial pengusaha dilaksanakan melalui pembayaran paJak yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Cara yang lebih langsung, misalnya, adalah melalui sistem kekeluargaan dalam perusahaan, seperti yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Pilihan mengenai mekanisme ini pada akhirnya merupakan pilihan politis. Walaupun demikian, ia perlu memperhitungkan aspek efisiensinya. Apa pun pilihan yang diambil, masih ada masalah lain yang perlu diputuskan: Apa yang harus dibagi? Secara sederhana, pilihannya dapat diibaratkan membagi kue atau membagi buah-buah hasil pohon. Dalam diskusi panel itu ada dinyatakan bahwa kita di Indonesia sudah telanjur gandrung berbicara dalam bahasa membagi kue. Lalu masalahnya adalah kita lupa bahwa setelah dibagi kue itu pun habis. Lain halnya dengan membagi buah-buah hasil pohon secara implisit ada persetujuan bahwa apabila pohon-pohon dibolehkan untuk menjadi semakin besar, dapat diharapkan semakin banyak buah yang dihasilkan, dan dengan demikian semakin banyak yang dapat dibagikan. Diskusi panel sehari itu tidak memperoleh jawaban konklusif apakah falsafah pohon dan buahnya itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada kesan bahwa besar itu dianggap buruk, dan karenanya ada begitu banyak hambatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang. Tapi bagaimana mungkin Gudang Garam dapat berkembang menjadi demiklan besar, dan karenanya dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya, baik melalui pembayaran pajak maupun secara langsung melalui berbagai pelayanan sosial kepada masyarakat sekelilingnya? Mungkin memang karena keberuntungannya. Tidakkah sebenarnya keberhasilan Kiai Haji Irfan sebagai bapak pelindung itu dimungkinkan oleh kekayaannya yang besar? Solidaritas baru, seperti yang dibahas dalam diskusi panel sehari itu, perlu melibatkan seluruh masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia merupakan serangkaian partnership antara berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah. Ia menuntut kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, dan bukannya persaingan yang saling mematikan. Dilihat dan diatur secara demikian, kerja sama antara pengusaha dan pengusaha tidak perlu mempunyai arti dan akibat negatif bagi perkembangan bangsa dan negara. Malahan arti positif partnership ini merupakan inti tesis mengenai teori developmental state yang kini banyak diterapkan untuk menerangkan sebab-sebah keberhasilan beberapa negara melakukan transformasinya menuju industrialisasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini