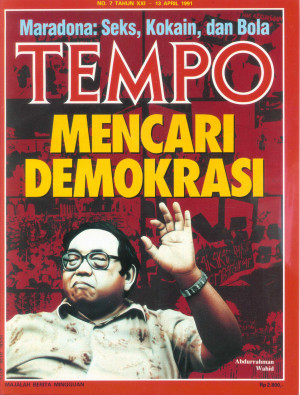HAK asasi adalah isu moral, atau sebuah moral principle yang seyogianya menjadi panduan berperilaku setiap orang bermoral. Itu menurut Bernard Cullen, dosen ilmu filsafat pada Queen's University di Belfast, Irlandia. Pandangan ini tampaknya sejalan dengan Lawrence Kohlberg, seperti yang dikutip oleh Alison Clarke-Stewart dari Universitas Chicago, yang menyatakan bahwa perkembangan moralitas seseorang ditandai dengan kedewasaan pandangannya tentang keadilan, tepo sliro, dan kehidupan sosial yang harmonis. Bahkan, menurut Kohlberg, rasa keadilan, tepo sliro, keadilan sosial, dan menghargai hak asasi manusia merupakan prinsip sikap etis yang tertinggi. Namun, kenyataannya, banyak pula orang yang menggunakan masalah hak asasi sebagai isu politik. Bahkan, barangkali di muka bumi ini lebih banyak yang menjadikan hak asasi sebagai isu politik ketimbang isu moral. Hak asasi hanya menjadi sebuah isu politik jika dilontarkan tatkala si pembicara berada di luar lingkup kekuasaan politik. Namun, begitu berada di dalamnya, ia akan melupakan apa yang dulu diperjuangkan. Pengalaman sejarah berulang-ulang membuktikan hal itu. Revolusi Prancis tahun 1789 mengumandangkan "Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara" dan menjanjikan pemerintahan yang demokratis. Tetapi, yang terjadi, pemerintah yang baru ternyata bersikap totaliter dengan alasan yang klise. Negara belum stabil. Ada ancaman dari dalam dan luar. Ada pula krisis ekonomi. Pembantaian tokoh-tokoh yang dianggap antirevolusi dilakukan tanpa proses pengadilan yang memadai. Pada zaman modern ini kita juga sering melihat hal serupa. Terutama di negara-negara komunis dan beberapa negara berkembang. Maka, seolah-olah sudah menjadi "aturan main" di negara-negara tersebut, pemerintah yang berkuasa selalu akan bercuriga begitu ada orang yang mempersoalkan masalah hak asasi. Mereka akan melihat siapa yang berbicara. Juga diteliti apa latar belakang politiknya. Atau, kira-kira siapa saja yang berada di balik gerakan itu. Demikian seterusnya. Setelah yang melempar isu hak asasi itu "naik kursi", ia pun akan bersikap seperti pihak yang dia kritik sebelumnya. Pola permainan "kacang yang lupa akan kulitnya" ini akan berulang lagi dengan pemain lain yang dapat giliran masuk gelanggang. Setiap pemain yang berkuasa cenderung merasa mengemban tugas suci yakni menyelamatkan negara dan rakyat. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai satu-satunya yang berhak berbicara soal rakyat. Kestabilan kekuasaan, dan bukannya kehidupan sosial yang harmonis, harus diutamakan. Jika perlu, dengan melupakan hak asasi. Dengan berkaca pada pengalamannya, pemain yang sedang berkuasa memandang dengan sinis bahwa pemain hak asasi baru itu pada dasarnya punya kepentingan politik belaka. Lain halnya pejuang hak asasi semacam Ibu Theresa, yang hidup bersama kaum papa di India, dan Mahatma Gandhi. Tak seorang pun melihatnya sebagai gerakan politik. Pejuang hak asasi semacam itu mampu membuktikan bahwa perjuangannya tak sedikit pun berkaitan dengan permainan politik, tendang-menendang pemimpin kekuasaan politik. Kedua tokoh itu memperjuangkan hak asasi sebagai masalah moral dan dengan tulus. Namun, seberapa jauh masalah hak asasi dapat dibuktikan sebagai isu moral yang universal? Sebab, nilai-nilai moral dalam masyarakat tak bisa terlepas dari perkembangan yang ter- jadi dalam masyarakat itu sendiri. Lawrence Kohlberg dan juga Rest dan Robbins berpendapat bahwa pandangan moralitas suatu masyarakat terhadap masalah hak asasi dan rasa keadilan sangat dipengaruhi oleh budaya dan peristiwa-peristiwa historis yang pernah mereka alami. Terutama peristiwa historis yang punya dampak dramatis. Sebagai contoh, menurut kesimpulan penelitian Rest dan Robins, pandangan masyarakat Amerika Serikat tentang keadilan banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ini agaknya dipengaruhi oleh peristiwa sejarah yang mereka alami. Dari sebelum perjuangan hak-hak sipil pimpinan Martin Luther King, sampai sesudahnya dan kemudian juga seusai Perang Vietnam. Sementara itu, Kohlberg berdasarkan penelitiannya di berbagai negara, dari Meksiko sampai Taiwan, berkesimpulan bahwa tingkatan pandangan moralitas suatu masyarakat tentang keadilan sangat dipengaruhi oleh kedewasaan mereka berpartisipasi lewat lembaga masyarakat yang formal. Semakin berpengalaman masyarakat itu dalam menggunakan lembaga-lembaga formal, semakin tinggi tingkat pandangan moralitasnya tentang keadilan sosial. Meskipun demikian, menurut Kohlberg, hanya sekitar 20% manusia dewasa di dunia ini yang dapat mencapai tingkatan tertinggi seperti halnya Ibu Theresa atau Mahatma Gandhi. Ini membuktikan bahwa masalah hak asasi adalah masalah moral, tanpa perlu mempertanyakan apakah hal itu dapat berlangsung di bawah pemerintahan tertentu, dan tanpa konotasi politis. Jika teori para peneliti di atas benar, perjuangan untuk hak asasi di negara berkembang memang tak harus segera mencapai penampilan seperti halnya di negara-negara maju. Diperlukan pematangan kedewasaan berpikir secara moral melalui pendidikan dan pengalaman. Barangkali jika para pejuang hak asasi di negara berkembang benar-benar tulus, proses inilah yang harus mereka upayakan lewat perbuatan nyata yang berkelanjutan dan tanpa bosan. Seperti yang dilakukan Ibu Theresa dan Mahatma Gandhi. Pada zaman penjajahan Belanda kita juga pernah melakukannya, dan ternyata membawa hasil yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Dengan harapan, tentunya, ketika tiba giliran mereka untuk memasuki gelanggang, tidak ada lagi permainan "kacang lupa akan kulitnya", berikutnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini