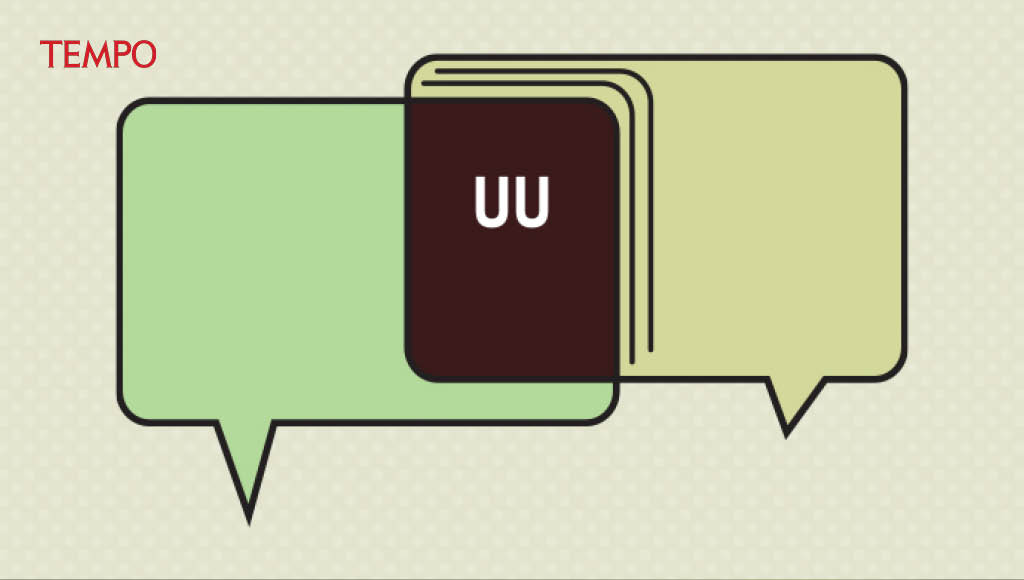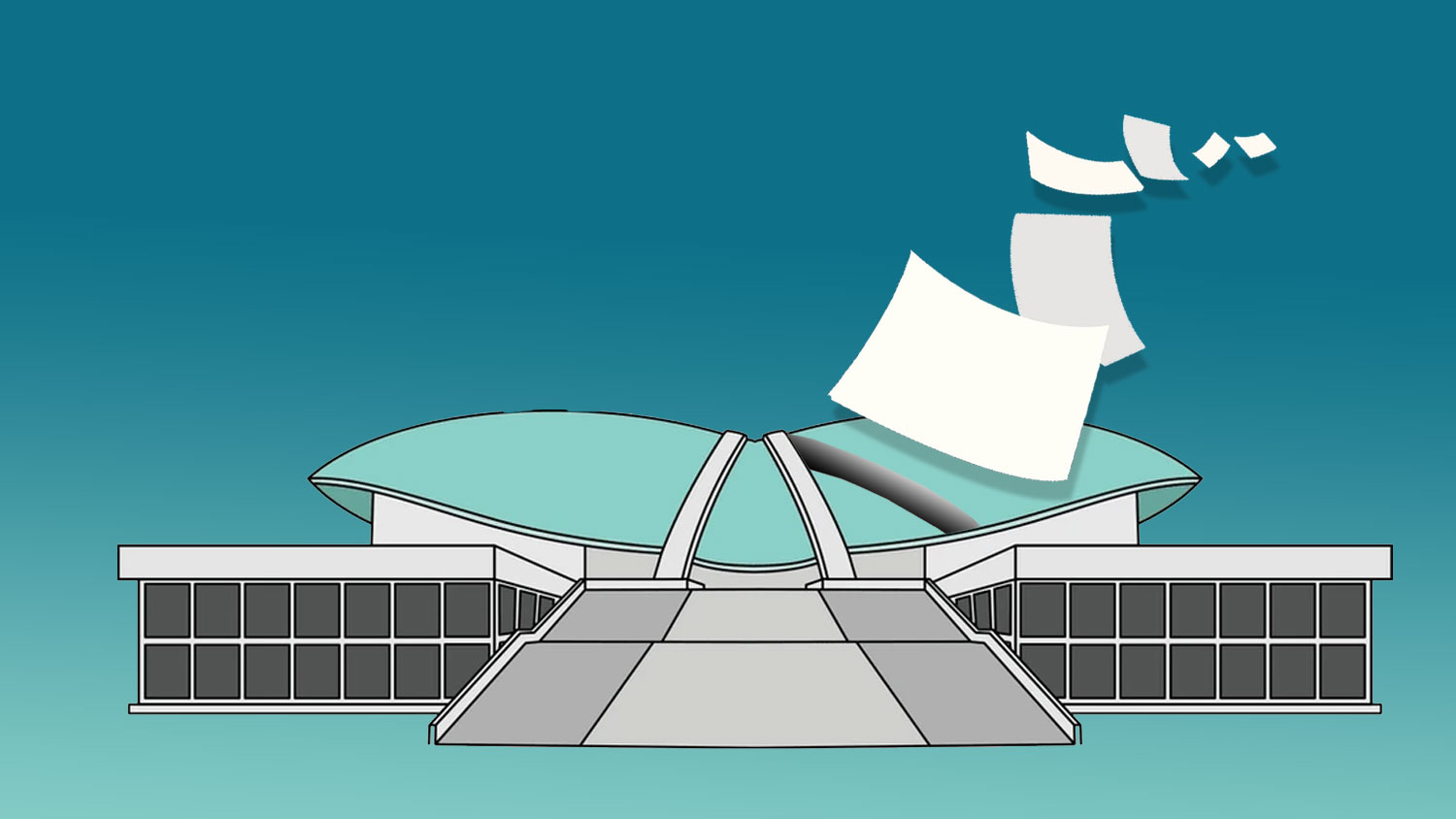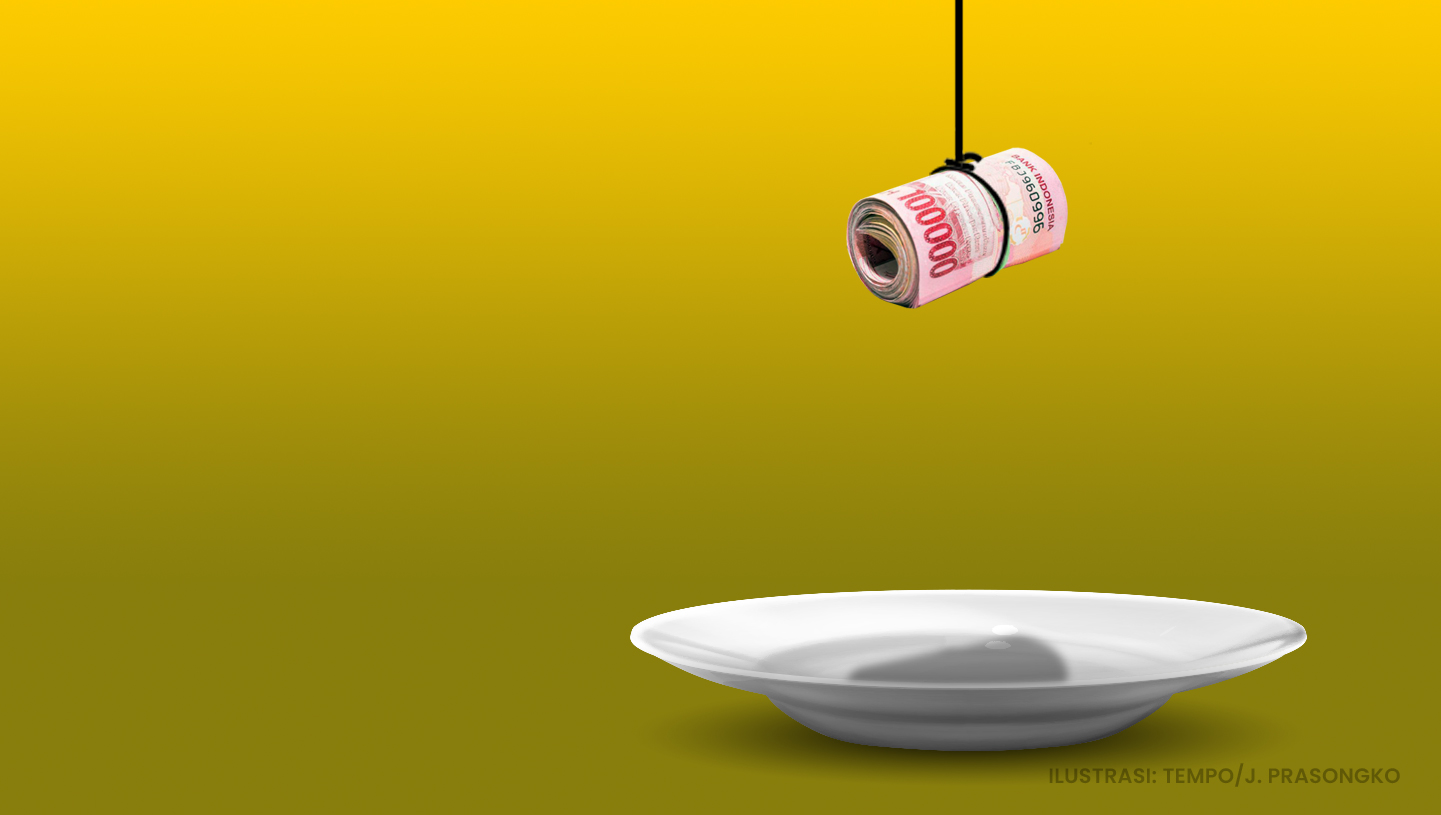Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pandangan pengamat isu pertahanan Andi Widjajanto yang menyatakan bahwa strategi Cina saat ini hampir mirip dengan gaya Jepang jelang Perang Dunia II sangat layak didalami. Karena itu, semacam “warning” dari Andi bahwa Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk dari puncak konflik antara Cina dan Amerika Serikat di Pasifik juga sangat patut dipertimbangkan oleh Indonesia, terutama oleh Kementerian Pertahanan RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pandangan tersebut disampaikan Andi dalam acara uji materi UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) terkait komponen cadangan (Komcad). Analisisnya didasarkan atas sikap Cina yang melakukan rencana strategis selama 70 tahun ke depan. Merujuk rencana strategis Cina itu ditetapkan tahap pertama dari tahun 1980 sampai 2000. Tahap kedua, rentang waktu antara tahun 2000 sampai 2020. Dan tahap ketiga, rentang waktu tahun 2020 sampai 2050.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saya tentu sepakat dalam beberapa hal dengan Andi Widjajanto. Terutama tentang strategi kebangkitan Cina yang bagaimanapun berpeluang mengundang konflik tingkat tinggi di berbagai arena internasional, terutama dengan Amerika Serikat di Kawasan Pasifik. Apalagi, sejak krisis finansial 2008, Cina nampaknya sangat yakin bahwa Amerika Serikat sudah berada pada fase-fase “decisive decline”. Keyakinan Cina tersebut tentu sangat masuk akal mengingat sejak peran Amerika Serikat di bidang ekonomi global memang secara perlahan terkikis yang imbasnya sangat terasa setelah krisis finansial 2008.
Dengan keyakinan itu, Cina pelan-pelan berusaha untuk mengambil alih peran ekonomi Amerika Serikat di tingkat global dengan menjadi penyelamat ekonomi dunia di saat krisis berlangsung. Ekonomi Cina yang sedang naik daun ketika itu menjadi penyerap utama komoditas ekspor dari seluruh dunia, terutama sumber daya alam seperti minyak, biji besi, nikel, dan batubara. Negara-negara yang bergantung kepada ekspor komoditas mentah, termasuk Indonesia dan Australia, sangat merasakan betapa besar peran Cina dalam membendung krisis ekonomi global yang bersumber dari Wall Street dan Euro Zone.
Peran tersebut mempertinggi kepercayaan diri Cina bahwa dalam satu atau dua dekade ke depan Cina akan menjadi kekuatan nomor satu dunia, terutama di bidang ekonomi. Meskipun tak semudah itu mengingat pendapatan per kapita Cina masih terpaut jauh dibanding negara-negara maju, walau peran heroik yang dimainkan China di saat krisis finansial global memang melejitkan citra ekonomi negeri Tirai Bambu tersebut. Di Afrika misalnya, Cina kini dianggap sebagai penyelamat dan menjadi mitra ekonomi utama di mana Cina berdiplomasi untuk menyelamatkan suplai bahan mentah dari Afrika dengan tawaran miliaran dolar investasi. Bahkan boleh jadi, gegara ekspansi ekonomi Cina di Afrika, peran Amerika Serikat nyaris hampir terkikis di sana.
Di Asia, Cina secara de facto mampu menetralisir pengaruh Amerika Serikat di beberapa negara. Cina mampu menghasilkan perjanjian unilateral maupun bilateral dengan negara-negara di Asia, termasuk ASEAN, dan menyabet banyak dukungan saat Cina mengajukan ide tentang Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB) sebagai alternatif dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang menjadi simbol supremasi moneter blok barat via Tokyo. Kemudian berlanjut dengan proyek-proyek Belt and Road Initiative dan Maritime Silk Road yang menghubungkan berbagai negara di Asia, mulai dari Asia Timur, Selatan, Sentral Asia, dan Asia Tenggara.
Dengan posisi dominan tersebut, negara-negara di Asia dipaksa bermain dua kaki, yang secara substantif bermakna “netral” jika konflik Cina-Amerika Serikat meningkat. Negara-negara di Asia menginjakkan kaki ekonominya di Cina, tapi menyandarkan kaki pertahanannya di Amerika Serikat. Kedua bidang ini saling terkait dan saling bergantung. Negara-negara Asia membutuhkan mitra ekonomi (mitra dagang dan investasi) seperti Cina untuk menjaga gerak positif perekonomian domestik, tapi juga membutuhkan jaminan keamanan dan pertahanan dari Amerika Serikat agar Cina tidak asertif dan agresif terhadap kepentingan teritorial mereka.
Jadi, secara prinsipil saya bersepakat dengan Andi Widjajanto tentang kebangkitan Cina dan ambisi Cina untuk melemahkan Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Untuk itu, saya juga bersepakat bahwa Indonesia, sebagai negara terbesar di dalam perhimpunan ASEAN, harus mulai “catch up” secara ekonomi dan pertahanan dengan Cina, terutama di kawasan kritis yang terkait langsung dengan area konflik. Tapi, saya masih belum menemukan indikasi pasti atas kemungkinan perang dalam waktu dekat dan masih meyakini bahwa Amerika Serikat dan Cina, bersama dengan negara-negara besar lainnya, termasuk Indonesia, akan memberikan peran maksimal agar tidak terjadi perang.
Amerika Serikat, sedari awal memang tidak menjadikan perang sebagai senjata diplomasi utama, sejak Monroe Doctrine sampai Kebijakan “Open Door” John Hay (termasuk mempersuasi negara imperialis lain seperti Inggris, Perancis, Rusia, Jerman, dan Jepang untuk mempertahankan integritas teritorial Cina/ Dinasti Qing) yang sukses diaplikasikan oleh Teddy Roosevelt, sampai ke FDR di Perang Dunia Kedua dan Richard Nixon yang justru menggandeng Cina secara terbuka serta mengakui Soviet sebagai negara super power, lalu berlanjut pada “engagement policy” pasca perang dingin dan gaya “strategic competition” Donald Trump. Selama tidak diserang terlebih dahulu, Amerika Serikat akan tetap memilih pendekatan diplomasi.
Amerika Serikat, sebagaimana saya meyakini, dengan segala cara akan melakukan pendekatan “balance of power” di Asia Pasifik, agar tidak ada satu kekuatan utama yang sangat dominan. Pada Russo-Japan War, Teddy Roosevelt (TR) buru-buru mengintermediasi kedua negara agar tidak ada yang mendeklarasikan diri sebagai pemenang dan menganggap dirinya penguasa Asia (Jepang). TR mendapat anugerah Nobel Perdamaian atas inisiatif tersebut, meskipun di belakang layar TR memberikan sinyal hijau kepada Jepang untuk menduduki Korea. Untuk sementara waktu, ”balance of power” kembali terjaga di Asia ketika itu.
Di era kebangkitan Jepang situasinya berbeda. Ada Jerman dan Italia sebagai “penguat keyakinan” Jepang untuk menjadi agresif. Pun Jepang telah memulai langkah-langkah super-agresif jauh hari sebelum Amerika Serikat memutuskan memerangi Jepang pasca Pearl Harbor. Setelah Manchuria, Jepang merebut Formosa di tahun 1895 dari Cina, lalu Korea sepuluh tahun kemudian, dan merangkak ke teritorial Cina setelah itu yang memicu Amerika Serikat memberlakukan embargo minyak kepada Jepang. Embargo tersebut berimbas pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak oleh Jepang terhadap Amerika Serikat dan memaksa Jepang untuk menduduki sumber-sumber minyak baru di Asia Tenggara, terutama Plaju (Sumsel) dan Tarakan (Kalimantan), dalam aksi besar penaklukan Asia, yang semuanya bukanlah daerah kekuasaan Jepang sebelumnya.
Berbeda dengan Cina, baik di Hong Kong, Taiwan, Sengkaku, ataupun Laut Cina Selatan, yang memang dulunya berada di bawah Dinasti Qing, Cina berusaha merebutnya kembali dengan cara damai. Meski demikian, saya cukup yakin, Cina tidak akan gegabah seperti Jepang dalam menyatukan kembali teritorial yang hilang tersebut. Yang paling mungkin terjadi adalah situasi mirip “perang dingin”, yang berbeda dengan era perang dingin antara Soviet dan Amerika Serikat, mengingat interdependensi dan interelasi antara Cina dan Amerika Serikat secara ekonomi sangatlah intens.
Tapi, dengan asumsi perang dingin gaya baru tersebut, saya mendukung rekomendasi Andi Widjajanto, bahwa Indonesia harus bersiap-siap. Indonesia mau tak mau harus mendorong ASEAN menjadi kekuatan regional seperti era Soekarno dan Soeharto (Non Blok), dengan membangun basis kekuatan pertahanan regional dan nasional dan menjadi penghubung signifikan antara Cina dan Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, selama perang dingin dengan Soviet, perang secara langsung antara Amerika Serikat dan Soviet tidak terjadi, tapi mendidihkan gejolak perang di negara-negara pinggiran. Untuk itu, gerakan Non Blok harus dikuatkan kembali agar tidak terseret ke dalam pusaran perang dingin gaya baru. Pun geostrategi dan grand strategi Indonesia di bidang pertahanan dan ekonomi haruslah dipertegas dan diperjelas dengan dukungan anggaran yang masuk akal pula. Semoga!