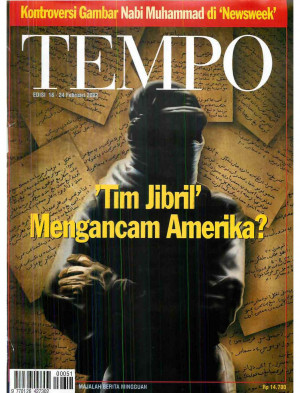Sjahrir
Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Baru
LUAR biasa body language Menteri Negara Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi Ali Marwan Hanan?Sekjen Partai Persatuan Pembangunan?di televisi pekan lalu. Kita harus paham kenapa menurut dia perangkapan jabatan di partai politik dengan jabatan pemerintahan bukanlah suatu isu (non-issue). Bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan setelah menemui Presiden Megawati Sukarnoputri (Ketua Umum PDI Perjuangan), makin menguatkan kesan bahwa para pejabat negara yang memimpin partai politik sama sekali tidak melihat adanya masalah, sekecil apa pun, yang menyangkut jabatan rangkap itu.
Lebih politis dari sekjennya, Wakil Presiden Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) berbicara tentang perlunya undang-undang yang mengatur perangkapan jabatan di partai dengan posisi di pemerintahan ataupun dalam lembaga legislatif. Lebih "pintar sedikit" dari kedua tokoh tersebut, Ketua MPR Amien Rais (Ketua Umum Partai Amanat Nasional) memberikan kesan responsif terhadap isu yang menunjukkan adanya keberatan dari sebagian masyarakat tentang perangkapan jabatan tersebut. Dia menuturkan bahwa partainya akan mendiskusikan hal tersebut, dan dia mengharap pula adanya polling untuk mengetahui apakah isyarat sebagian masyarakat itu betul-betul dirasakan benar oleh publik yang lebih luas.
Dari sisi partai Golkar, kita tahu apa yang akan dikatakan Ketua DPR Akbar Tandjung (Ketua Umum DPP Golkar). Boro-boro masalah jabatan rangkap yang dihebohkan itu, dalam hal seruan moral tentang perlunya Taufiq Kiemas mundur dari DPR (lembaga legislatif) karena dia adalah suami Megawati (presiden, pemimpin lembaga eksekutif), jelas-jelas Akbar membenarkan posisi Taufiq, dengan suatu penjelasan yang terasa begitu jernih. Menurut dia, tidak ada undang-undang atau peraturan yang melarang orang menjadi anggota parlemen semata-mata karena istrinya adalah presiden.
Ali Marwan Hanan bahkan menganggap perangkapan jabatan itu menjadi isu semata-mata karena diangkat oleh pers, padahal sebenarnya tak ada sedikit pun masalah yang perlu dipersoalkan.
Jadi, potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang menjadi dasar dari semua upaya untuk memikirkan kemungkinan dipisahkannya jabatan kepartaian dengan jabatan pemerintahan dan legislatif praktis dianggap mengada-ada.
Menurut para pemangku jabatan rangkap itu, mereka pasti bisa membeda-bedakan posisi mereka di lembaga eksekutif dan legislatif, dengan posisi di partai mereka masing-masing. Tetapi, bila dikatakan bahwa isu rangkap jabatan itu semata-mata diangkat oleh pers, dan tidak berdasarkan "kenyataan sosiologis" dalam masyarakat, itu tidaklah seratus persen benar. Lemhannas pun urun rembuk dan memberikan kontribusi gagasan dengan menyatakan tetap perlu dipertimbangkannya jabatan rangkap sebagai masalah yang cukup serius. Hanya, dari sisi lain, yang menyangkut TNI, Lemhannas tidak merasa perlu memberikan pendapat tentang diangkatnya Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoedin sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI, hal yang secara konkret justru sudah menimbulkan reaksi menolak dari sebagian masyarakat, mengingat posisi Sjafrie sebagai Pangdam Jaya pada masa kerusuhan Mei 1998, panglima yang punya kekuasaan operasional untuk bertindak.
Apa persamaan "reaksi" para pejabat pemerintahan dan legislatif dengan "non-reaksi" dari TNI tentang keberatan sebagian masyarakat terhadap pengangkatan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin? Persamaan yang menonjol adalah tidak adanya sama sekali kepekaan terhadap penilaian yang berkembang secara dinamis setelah berhentinya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998.
Mari kita bandingkan perilaku para pemimpin partai tersebut dengan masa Soeharto. Karena kekuasaan Presiden Soeharto yang begitu besar, orang sebetulnya tidak mengacuhkan siapa yang menjadi Ketua Umum Golkar, apakah itu Sudharmono ataukah Harmoko. Yang penting adalah posisi Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar merupakan posisi yang praktis memberi dia hak veto untuk menentukan siapa yang memimpin Golkar dan siapa yang akan diajukan oleh Golkar sebagai presiden, yang tentu saja adalah dirinya sendiri.
Apa bedanya hal yang berlangsung selama 30 tahun lebih itu dengan yang berkembang dalam alam demokrasi sekarang yang katanya adalah "era reformasi"? Sedikit pun tak ada bedanya! Kalau kita melihat ketetapan yang dibuat PPP dan Golkar yang menyatakan bahwa kongres partai berlangsung setelah Pemilu 2004, dapat dipastikan bahwa calon pemimpin pemerintahan dari presiden hingga jabatan eksekutif dan legislatif lainnya praktis berada di tangan ketua umum partai. Dari sisi itu bisa dijelaskan kenapa ada simpati pada kehadiran K.H. Zainuddin M.Z. yang mendirikan PPP Reformasi dan berargumen bahwa amat tidak demokratis bila menjelang Pemilu 2004 tidak ada kongres partai yang menyiapkan partai-partai itu dalam menyusun calon pemimpin mereka yang akan bertarung dalam Pemilu 2004.
Dari PDIP, misalnya, kita tidak melihat kehendak untuk membuka diri bagi keragaman. Sekalipun Kongres PDIP diadakan sebelum Pemilu 2004, bisa dipastikan Megawati akan dipilih secara aklamasi oleh kongres partai sebagai calon presiden 2004. Seandainya dalam PDIP ada suasana yang lebih toleran, tentu saja Sophan Sophiaan tidak perlu mundur dari posisinya di DPR. Begitu juga Dimyati Hartono. Dia tak perlu berhenti sama sekali dari DPR dan PDIP, dan kabarnya akan membentuk partai baru. Begitu juga tidak perlu ada usul dari Dewan Pertimbangan PDIP agar Megawati memberikan kepemimpinan partai kepada orangnya yang ditunjuk, atau kepada ketua pelaksana sehari-hari partai. Usul ini membuat Megawati bergeming. Selama Megawati menjadi presiden, kita sering menyaksikan kedatangannya di Kantor PDIP di Pecenongan, Jakarta Pusat, dan memimpin rapat PDIP sebagai hal yang dianggapnya sepenuhnya normal! Kita tidak melihat sedikit pun kepekaan Megawati untuk membedakan posisi pemerintahannya dengan kedudukannya sebagai Ketua Umum PDIP. Bahkan ulang tahunnya yang bersifat pribadi dia buat berupa acara dengan tokoh-tokoh PDIP yang mengelilinginya, bukan dikelilingi keluarga ataupun orang-orang dari lingkungan pemerintahan tempat dia bekerja.
Reaksi tokoh-tokoh partai politik terhadap keberatan masyarakat untuk jabatan rangkap ini sama dengan reaksi yang sering diperlihatkan Abdurrahman Wahid ketika dia masih berkuasa dulu, yang populer dengan ucapan "gitu aja kok repot". Tanggapan itu menunjukkan begitu tidak sensitifnya mereka terhadap suara-suara yang berkembang dalam masyarakat, yang punya kecurigaan amat besar akan adanya konflik kepentingan antara kedudukan sebagai pemimpin partai dan posisi di pemerintahan serta badan legislatif. Konflik kepentingan ini begitu mencolok dirasakan sekarang, karena rakyat berada dalam krisis berkepanjangan, yang telah berlangsung selama 55 bulan.
Krisis ekonomi yang menghasilkan inflasi double digit, institusi bank yang tidak berfungsi sebagai lembaga intermediasi, pertumbuhan yang rendah yang tidak mampu menyerap tenaga kerja, serta merosotnya solidaritas sosial yang kita rasakan ketika banjir hampir menenggelamkan Ibu Kota tapi tidak disikapi dengan sensitif oleh pemerintah, dari presiden hingga gubernur.
Dalam setiap polling yang dilakukan berbagai media, secara amat gamblang tampak fakta bahwa partai-partai telah kehilangan begitu banyak kredibilitas. Partai sudah disinonimkan dengan interest golongan, interest pribadi, dan sama sekali bukan organisasi politik yang bergerak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan bangsanya. Kita mengalami dilema yang dalam, karena di satu pihak kredibilitas partai politik terus merosot menuju titik nadir, sementara peran partai poiltik dalam alam demokrasi sekarang justru merupakan satu-satunya peran yang tersedia bagi setiap orang yang ingin berpolitik dan mencoba memperbaiki kondisi politik, baik secara nasional maupun regional.
Bagaimana nasib perpolitikan nasional di masa datang dan bagaimana pula memvisualkan pemilihan umum 2004 nanti?
Pertama, kita melihat betapa lack of sensitiveness para pemimpin partai politik yang kebetulan memegang jabatan pemerintahan akan memperbesar jarak antara elite politik dan sebagian besar bangsanya. Ini mengandung implikasi terbuka lebarnya pilihan-pilihan politik yang amat berbeda dengan apa yang tersedia pada Pemilu 1999.
Kedua, kita melihat bahwa polling yang dilakukan berbagai kalangan tetap merujuk pada pentingnya melakukan pemulihan ekonomi. Selama para pemimpin pemerintahan dan pemimpin badan legislatif tidak bisa memfokuskan perhatian mereka pada masalah pemulihan ekonomi, selama itu pula mereka akan terjerat oleh berbagai isu yang sama sekali tidak akan dianggap penting oleh rakyat. Isu perangkapan jabatan adalah isu penting, karena rakyat curiga terhadap adanya konflik kepentingan antara jabatan di pemerintahan serta legislatif dan kepentingan partai. Sebagai pejabat pemerintahan serta legislatif, mereka yang menduduki jabatan rangkap itu harus memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi. Tetapi, sebagai pejabat partai, mereka harus mencari duit sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu 2004.
Sesungguhnya amatlah simpatik bilamana para pejabat partai tersebut bersedia melepaskan jabatan kepartaiannya, dan seratus persen memfokuskan diri pada upaya pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Bisakah kita mengharapkan itu terjadi? Jawabnya mungkin harus ditanya kepada rumput yang bergoyang. Singkatnya, sepanjang sikap mental dan sikap dasar tokoh-tokoh partai politik tetap seperti sekarang, bahaya kegagalan demokrasi dan kehancuran ekonomi tetap menganga di hadapan kita. Pada masa seperti itu, satu-satunya partai yang tidak pernah pecah adalah "partai TNI/Polri".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini