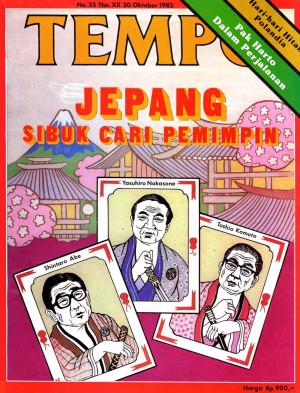DI antara negara industri maju, Jepang merupakan yang paling
tertutup terhadap aliran moneterisme, baik di lingkungan
pengelola ekonomi maupun dalam dunia akademis, apalagi di
kalangan politisinya. Sejauh ini ekonomi Jepang sebenarnya
dikelola dalam kerangka Keynesian, yang sepenuhnya mengandalkan
pada kebijaksanaan fiskal sebagai perangsang kegiatan
ekonominya.
Kebijaksanaan moneter yang diterapkan di Jepang memang tidak
netral terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri, tapi
tindakan-tindakan moneter semata-mata ditujukan untuk mengoreksi
sektor eksternalnya, sesuai dengan gerakan neraca pembayarannya.
Sudah sejak beberapa tahun ini dirasakan bahwa struktur fiskal
Jepang sukar mendukung pola pengelolaan yang sudah menjadi
tradisi itu. Peningkatan pengeluaran pemerintah melalui
anggaran, sebagai alat perangsang ekonomi, hanya bisa
dilanjutkan dengan meningkatkan penerbitan obligasi atau
surat-surat utang kepada masyarakat. Selain karena beban
pembayaran kembali semakin berat bagi pemerintah, sektor
perbankan Jepang juga sudah lama mengeluh karena kesulitan
menyerap peredaran obligasi tersebut.
Tahun 1979 pembiayaan defisit di Jepang melonjak mencapai
sekitar 40o dari seluruh pengeluarannya. Di Amerika Serikat dan
Prancis ratio itu berkisar pada 7-8%, di Inggris dan
Jerman-Barat antara 14-16%.
Salah satu janji utama Zenko Suzuki ketika ditetapkan menjadi
Perdana Menteri adalah untuk merombak struktur fiskal Jepang
sehingga dalam tahun anggaran 1984 tidak lagi terjadi defisit
yang perlu dibiayai dengan penerbitan obligasi. Namun dalam
tahun anggaran 1981 defisit meningkat menjadi 2,5 trilyun yen.
Akhir Agustus lalu Menteri Keuangan, Watanabe, mengumumkan suatu
"keadaan darurat fiskal" atas dasar perkiraan bahwa defisit
untuk tahun anggaran 1982 ini akan meningkat mencapai 5-6
trilyun yen. Hal ini memaksa pemerintah menerbitkan obligasi di
atas pembatasan sebesar 3 trilyun yen.
Baru 2 minggu setelah pengumuman Watanabe, Perdana Menteri
Suzuki berbicara di depan umum untuk menerangkm keadaan darurat
fiskal tersebut. Tapi keterangannya dinilai sangat mengecewakan.
Suzuki mengkambing-hitamkan resesi ekonomi dunia dan tidak
melontarkan gagasan drastis untuk menyelesaikan masalah fiskal
Jepang. Suzuki yang menghadapi pemilihan kembali sama sekali
tidak menyinggung tindakan kenaikan pajak. Ini justru dinantikan
masyarakat. Bila di waktu lalu Ohira dijatuhkan karena berani
mengusulkannya tampaknya Suzuki akhirnya 'dijatuhkan' karena
tidak berani mengusulkan tindakan tersebut.
Siapa saja yang menjabat Perdana Menteri Jepang akan sulit
mengatasi krisis fiskal itu. Usul menaikkan pajak, seperti
dilakukan Ohira sekitar 2 tahun lampau, memang sangat tidak
populer secara politis dan amat riskan bagi seorang politisi
Jepang. Namun dalam struktur politik Jepang dituntut keberanian
untuk mengambil risiko tersebut. Citra dan krelibilitas Suzuki
hancur karena ia mungkin terlalu memperhitungkan kedudukannya.
Masalah fiskal uni cuma satu dari sekian faktor lain yang telah
menjatuhkan Suzuki. Suasana intern LDP (partai demokrasi
liberal) menjadi sernakin sulit untuk dikelola oleh Suzuki. Ia
mengetahui benar pengangkatannya sebagai Perdana Menteri
merupakan hasil kompromi antar-fraksi-fraksi dalam LDP sendiri.
Karena itu pula Suzuki dini hari sudah memproklamasikan falsafah
Wa no Seiji (politik harmoni) sebagai landasan pengelolaan
negara dan pemerintahan.
Namun Suzuki sendiri akhirnya mengkhianati falsafah itu dengan
semakin berkiblat pada fraksi Tanaka. Antara lain dengan
perombakan kabinet, Suzuki telah memungkinkan Susumu Nikaido,
pimpinan fraksi Tanaka, menjadi Sekretaris Jenderal LDP, suatu
hal yang sangat menggusarkan fraksifraksi lain.
TIDAK mengherankan seketika Watanabe mengumumkan keadaan
darurat fiskal, segera pula Fukuda, Komoto dan Shintaro Abe
menuntut sidang khusus parlemen (Diet) untuk mencari jalan
keluar. Isu fiskal ini kiranya dipakai oleh tokoh-tokoh fraksi
non-mainstream tersebut untuk mengkonfrontasi Suzuki. Intinya
sederhana: Suzuki diminta mengambil sikap politik--bukan
mengenai ekonomi--apakah akan terus tunduk pada Tanaka atau
bersedia mengambil kebijaksanaan yang lebih independen (artinya,
lebih berimbang).
Suzuki yang mengundurkan diri atas alasan menjaga persatuan
dalam tubuh LDP sebenarnya 'dijatuhkan' untuk menjatuhkan Tanaka
dari mimbar politik Jepang selama-lamanya. Tanaka yang belum
bebas dari skandal penyuapan Lockheed dilihat sebagai simbol
praktek politik yang korup.
Dengan landasan finansial yang kuat, Tanaka tetap berhasil
menggalang dukungan terbesar dalam LDP, dan di belakang layar
tetap memainkan peran politik yang penting, termasuk sebagai
king-maker. Padahal dalam pemilihan umum ia mencalonkan dirinya
di antara kelompok independen, dan baru setelah terpilih
berpindah lagi ke LDP, prosedur yang memang dimungkinkan di
Jepang.
Jatuhnya Suzuki sebenarnya tidaklah perlu mengejutkan. Suzuki
telah 2 tahun menjadi Perdana Menteri. Sebelumnya, Tanaka hanya
memimpin selama 2,5 tahun, Miki dan Fukua masing-masing untuk 2
tahun, dan Ohira sekedar 1,5 tahun. Yang menarik dari kasus
Suzuki adalah pelajaran bahwa nasib seorang Perdana Menteri
Jepang ditentukan oleh Jepang antara mereka sendiri. Betapa pun
besar kesalahan Suzuki dalam menangani masalah-masalah luar
negeri, bidang ini tidak akan menjatuhkannya dari tahta.
Mungkin kenyataan ini merupakan indikator bahwa Jepang belum
menjadi suatu negara 'besar' seperti Amerika Serikat atau Uni
Soviet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini