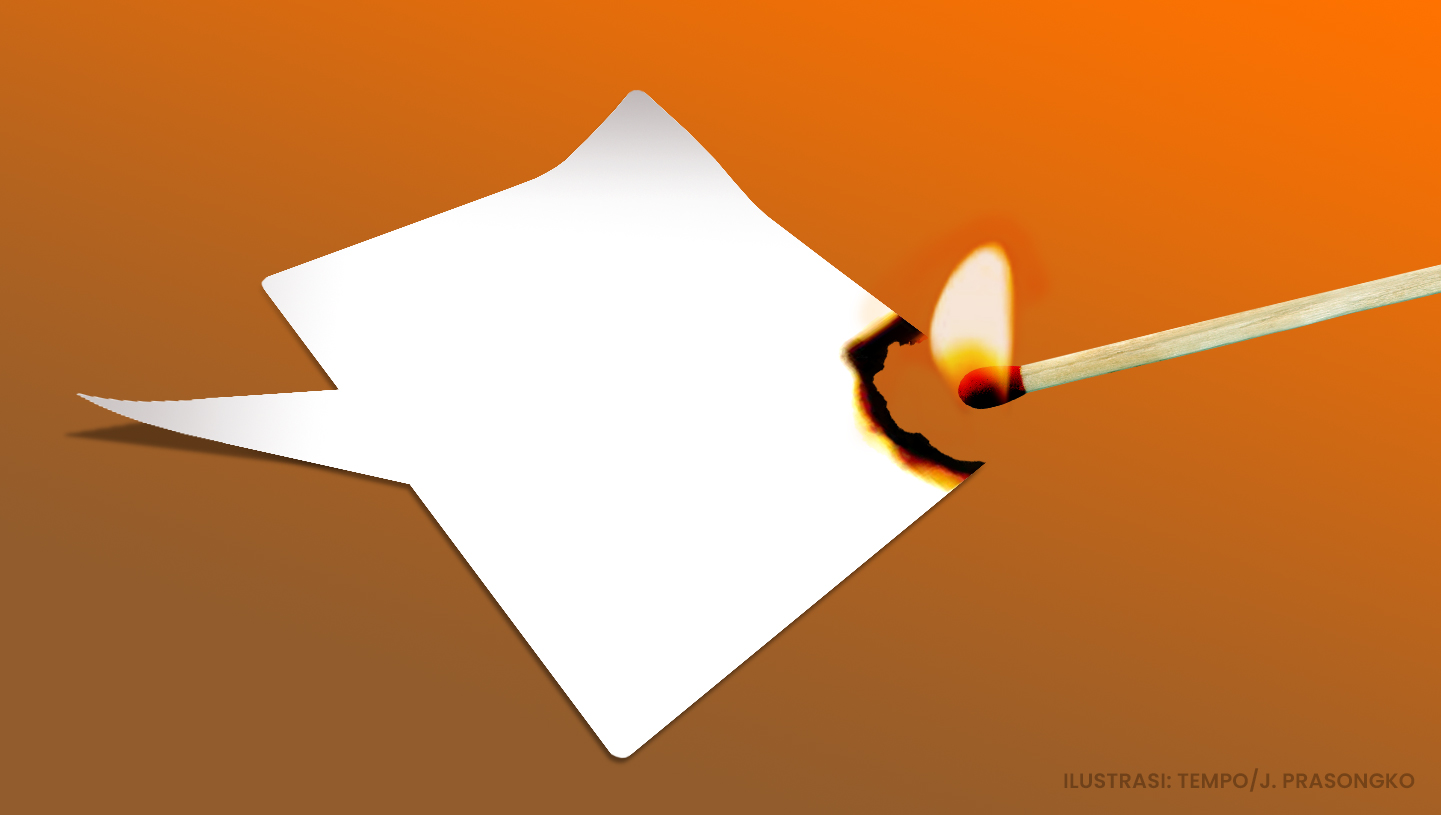Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Nono Anwar Makarim *)
Nono Anwar Makarim *)
*) Ketua Dewan Pelaksana Yayasan Aksara
| Biasabiasa sajalah dan, jika mungkin, cukup merangkak; niscaya semuanya akan tercapai. Beaumarchais SUATU senja dahulu kala, Adi Sasono bertandang ke rumah orang tua saya di seberang rel kereta api, dekat Pasar Cikini. Di depan televisi hitamputih, kami menonton pidato seorang mayor jenderal yang baru diangkat menjadi pejabat presiden sementara. Soeharto berbicara tentang prioritas pembangunan ekonomi. Bahasanya "Indojawa", suaranya datar, pengetahuan ekonominya dangkal. Adi bercerita tentang seorang pamannya yang menyaksikan pidato Soeharto, lalu mencibir: "Wong, presiden kok gitu, huuu! Hlaa, lain toh sama Bung Karno?" KARISMA Menjelang akhir dasawarsa 1960an Soeharto tidak memiliki karisma. Yang diwarisinya adalah perbandingan yang tidak adil antara bobot pamornya dan karisma Sukarno. Dalam "budel" warisannya dari Sukarno, terdapat suatu krisis ekonomi yang besar. Soeharto kemudian mengumpulkan segerombolan sarjana ekonomi lulusan FE-UI dan USC Berkeley. Dalam sekejap, "Mafia Berkeley" ini mendemonstrasikan rem inflasinya yang pakem. Lalu, perekonomian Indonesia tumbuh 8 persen setahun selama seperempat abad. Indonesia dianggap sebagai satu-satunya sukses negara "minyak" di dunia ke-3. Negara penghasil minyak lainnya di belahan dunia yang miskin tidak berhasil membangun ekonominya seperti Indonesia. Kemudian, Indonesia kebanjiran karisma "the smiling general". Moral dongeng masa lalu ini adalah bahwa karisma bukan suatu pembawaan, melainkan sekadar hasil akhir dari serangkaian prestasi, dan bahwa seorang manajer krisis tidak perlu punya karisma. Suatu pagi hari, juga dahulu kala, saya berhasil lolos masuk istana presiden, hanya dengan kartu pers mahasiswa. Kabarnya Sukarno marah besar kepada mahasiswa yang terusmenerus berdemonstrasi sambil bergembargembor slogan "Ampera", akronim dari "amanat penderitaan rakyat" ciptaan Sukarno. Pagi itu ia akan berpidato. Saya berdiri di baris terdepan ruang pidato yang sudah dipajang bunga dan mikrofon tegak berdiri. Sukarno masuk ruangan didampingi para ajudan, menuju mikrofon. Pundak dan dadanya penuh dengan bintang dan lencana. Tangan saya mulai semutan. Saya juga mulai menyesal mengambil posisi di baris terdepan. Ruangan sunyi-senyap diganggu terus oleh kicauan burung gereja, yang tidak begitu peduli pada suasana khidmat menanti pidato Bung Karno. Sukarno mengetukngetuk mikrofon, sambil terus mengamati wajahwajah para hadirin. Posisi saya serba salah, mau mundur ke belakang kalah gengsi, tetap di depan cemas jadi sasaran sorot pandangan Pemimpin Besar Revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, dan Presiden Seumur Hidup. Benar saja! Suaranya meninggi dan menurun dalam retorika yang memang memikat: "Mereka bicara tentang Ampera, Ampera, Ampera. Hai rakyatku, hai anakanakku, tahukah engkau bahwa saya sudah bergelimang dalam Ampera, meringkuk dalam penjara dari Sukamiskin sampai Bengkulu, dari Cipinang sampai Endeh untuk Ampera, demi Ampera, sebelum kalian lahir, sebelum kau lahir, sebelum kau lahir!" Pada saat itu jari telunjuknya menuding ke arah hadirin dan berhenti sejenak di udara persis terarah kepada saya: "SEBELUM KAMU LAHIR!", terdengar hardikannya. Katakata itu serasa sambaran setrum listrik tegangan tinggi menggetar diri saya. Presiden yang itu, dari ujung rambut di kepalanya sampai kuku jari di kakinya tereja "KARISMA". Akan tetapi, saksikanlah arti karisma itu bagi bangsanya bila dibandingkan dengan malapetaka dan kebangkrutan yang ditinggalkannya. Karisma tanpa disiplin membangun kesejahteraan rakyat menghasilkan arogansi. Jarak antara arogansi dan kejatuhan hanya dua jengkal. Kita sudah menyaksikannya paling sedikit dua kali: sekali pada tanggal 11 Maret 1966, dan sekali lagi pada tanggal 21 Mei 1998. KRISIS Masyarakat pluralis yang melangkah ke jurusan demokrasi akan mengalami banyak krisis. Itu gejala biasa dalam perubahan yang bersinambung. Suatu masyarakat dalam krisis juga selalu kehilangan paradigma lama yang menjadi pegangannya. Percaya dirinya menguap, kepercayaan pada pemerintahnya menghilang. Elemen psikologis ini muncul dalam setiap krisis. Unsur psikologis inilah yang pertama harus dimenangi sebelum substansi krisis dapat dipecahkan. Sebelum elemen psikologis ditangani, apa pun yang dilakukan pemerintah akan disambut dengan sinisme, sarkasme, nonkooperasi, bahkan harapan gagal. Elemen psikologis dalam suatu krisis membuat orang kritikal di luar batas kelaziman, membuat orang pesimistis akan kemampuannya sendiri untuk membantu meredakan krisis. Ia juga rnendorong tuntutantuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Roger Fisher, bapak program negotiation & dispute resolution di Harvard, pengarang Getting to Yes, karya klasik penuntun seni berunding, November tahun lalu berpesan kepada saya: "Jangan lupa, pihak yang sedang berkonflik selalu menuntut lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik!" Suasana yang diciptakan oleh sindrom tidak percaya ini sedemikian rupa melumpuhkan usaha pemecahan krisis, sampai orang berkesimpulan bahwa suatu krisis adalah 60 persen psikologis dan 40 persen substansi permasalahan. Dengan demikian, prioritas utama harus diberikan kepada upaya menghilangkan dampak psikologis dari krisis yang sedang dihadapi. Upaya ini hanya bisa berhasil bila masyarakat luas menyaksikan suksesnya upaya sejak awal. "Nothing succeeds like success," kata Dumas. SUKSES Seorang yang ingin upayanya berhasil harus benarbenar mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sukses. Jurang kepercayaan akan melebar kalau pemerintah menjanjikan bahwa masalah akan beres dalam tiga bulan, sedangkan kemudian terbukti bahwa masalah tidak beres dalam waktu yang dijanjikan. Sering kali bahkan menjadi lebih parah. Implikasi dari kemungkinan meleset janji ini mengharuskan kita menekan tingkat risiko gagal serendah mungkin, dan menjamin sukses sepasti mungkin. Bagaimana tugas penting itu bisa terlaksana dengan krisis Indonesia yang umurnya sudah lanjut dan tampak memanjang pula? Ahli manajemen menasihati agar kita memecah permasalahan yang terdapat dalam suatu krisis dalam serangkaian tugas yang mudah dikelola. Masalah konflik fisik di bilangan Matraman, misalnya, dapat dipecah dalam bagianbagian yang "manageable" seperti (1) bagian penelitian sosial-ekonomi dan ruang, (2) bagian studi perbandingan proyekproyek teladan peremajaan kota di luar negeri, (3) bagian kelayakan proyek peremajaan kota, (4) bagian potensi sumber dana, besarnya subsidi yang dapat diharapkan dari pemerintah daerah, dan kemungkinan sumber pendanaan lain seperti pajak khusus untuk tujuan "urban renewal", atau peningkatan pajak yang sudah ada, (5) bagian tugas melobi anggota DPRD untuk memperoleh persetujuan dewan bagi pendanaan khusus, (6) potensi pandidikan, pemberdayaan, dan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja di Matraman, (7) pembentukan struktur dan rumusan tugas serta kewenangan badan otoritas proyek "urban renewal", (8) wadah dan mekanisme partisipasi penduduk Matraman dalam merumuskan kehendaknya tentang proyek, (9) sistem pengawasan, audit, dan transparansi pelaksanaan proyek semaksimal mungkin, dan masih banyak lagi bagian-bagian lain yang tak mungkin semua diuraikan. Keseluruhan ataupun setiap bagian proyek harus tampak dengan jelas. Denah proyek dapat diperiksa setiap saat oleh siapa pun yang ingin tahu. Data kuncinya di sini adalah TRANSPARANSI. Kemudian harus dipilih bagianbagian yang mudah dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, dengan jaminan sukses terbesar dan risiko gagal terkecil. Setelah satu, dua, tiga bagian proyek terlaksana dengan baik, mulailah terasa makna adagium "tiada keberhasilan yang lebih berhasil dari keberhasilan". Sukses yang satu cenderung melahirkan sukses yang lain. Perlahanlahan sinisme, sarkasme, pesimisme, dan kritik berkurang. Jurang kepercayaan mulai menyempit. Perkembangan ini memberi umpan balik kepada pemerintah. Rasa percaya diri pemerintah mulai pulih. Ini berdampak positif berlipat ganda. Bekerja dalam suasana sejuk embusan angin "sukses" menghasilkan insentif untuk menjadikan sukses suatu gejala yang kerap berulang. "HANDSON" Metode memecah tugas yang besar menjadi bagianbagian kecil yang mudah dilaksanakan ini bisa diterapkan pada semua permasalahan dan krisis. Ia tidak membutuhkan wibawa atau karisma. Seorang pimpinan proyek pemulihan kewarasan masyarakat tidak perlu cemerlang. Ia cukup berbekal akal sehat, pragmatis, dan berkemauan keras "menongkrongi" dan mewaspadai proyek dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan. Ia juga harus sepenuhnya bersedia diperiksa, diawasi, dan dikoreksi tanpa marah atau tersinggung. Itu barangkali yang dimaksudkan dengan istilah "handson" dalam bahasa manajemen. Katakata bersayap pada awal kolom ini bersumber pada Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, seorang tokoh drama dan penulis pamflet Prancis pada abad ke18. Indonesia sebenarnya punya pepatah yang sama maknanya: "Sedikitsedikit menjadi bukit!" Dalam amnesia kolektif yang sedang kita alami, kearifan kultural pun terlupa. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |