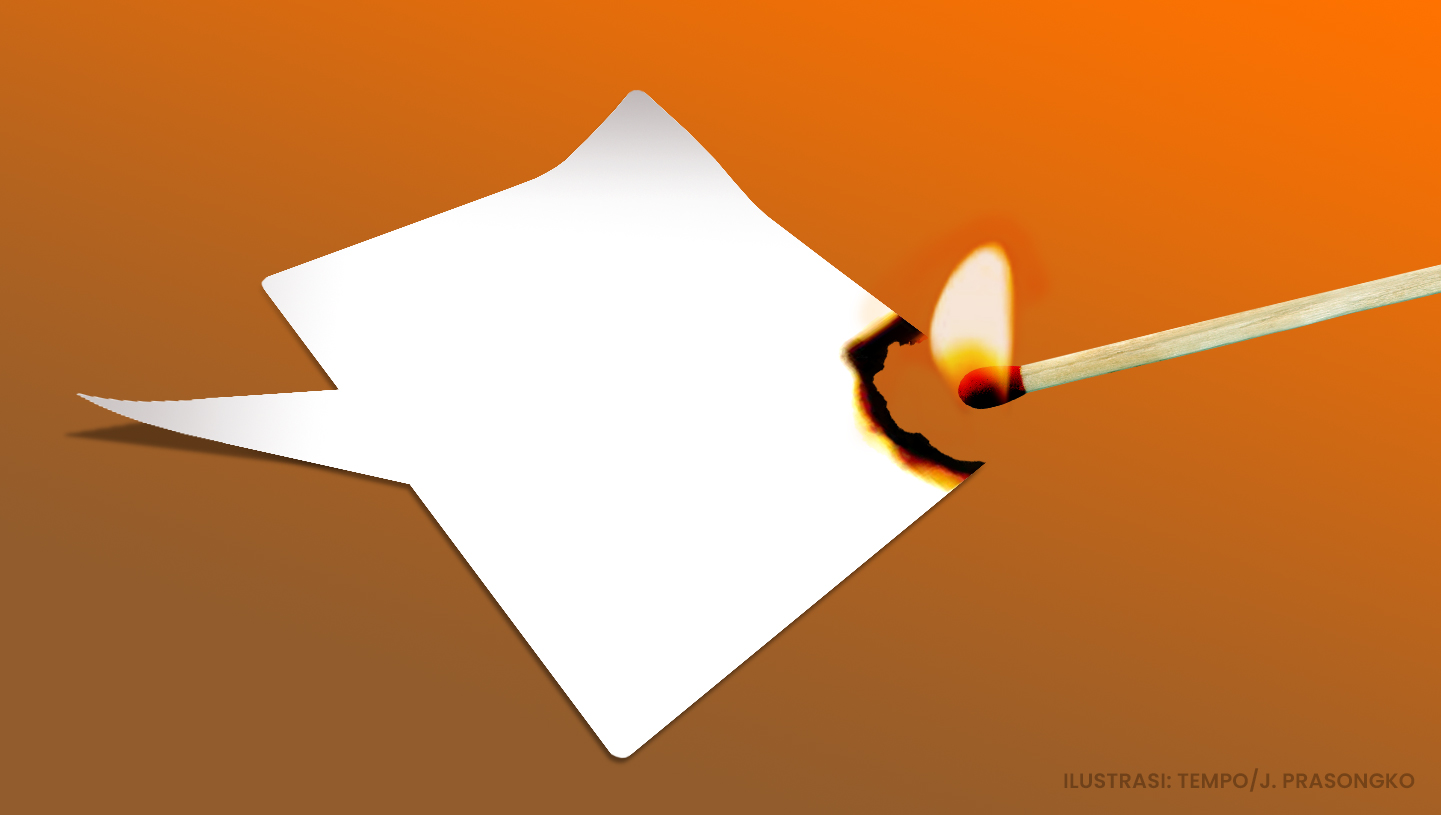Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Agus Wirahadikusumah *)
Agus Wirahadikusumah *)
*) Letnan Jenderal TNI, bekas Panglima Kostrad
| LAYAKKAH bersikap optimistis terhadap masa depan Indonesia? Jawabannya sangat bergantung pada sejauh mana para pemimpin bangsa di pemerintahan, parlemen, serta masyarakat umum berkiprah secara profesional di bidangnya, yakni dalam menertibkan bidang fungsi masing-masing untuk keluar dari krisis, untuk memperkuat kembali institusi ataupun kesatuan-kesatuan yang dipimpinnya.
Memang bukan soal mudah. Persoalannya, dalam tiga tahun ini, Indonesia sedang mengalami perubahan zaman, yang benar-benar berbeda dengan masa lalu. Banyak paradigma yang bergeser ke kutub seberangnya, seperti dari sentralistis menjadi desentralistis, dari pola instruksi ke partisipasi, dan dari bertumpu pada hasil akhir menjadi penekanan pada proses. Semua ini berbeda sekali, bahkan cenderung antagonistis, dengan masa lalu. Apalagi, dalam perubahan zaman ini, berlangsung pergantian rezim pemerintahan Soeharto ke pemerintahan Habibie pada masa transisi, kemudian masuk lagi ke pemerintahan Gus Dur. Semua ini berlangsung dalam kondisi yang genting, dalam krisis multidimensional pada setiap aspek, baik politik, sosial, ekonomi, termasuk finance, keamanan, maupun budaya. Walhasil, perubahan ini mengandung risiko yang sangat tinggi. Jika para pemimpin Indonesia tidak bisa membawa bangsa mengarungi bahtera tantangan perubahan ini dengan baik, negara akan bubar. Itu sebabnya pilihan strategi yang diambil untuk mengatasi berbagai krisis yang berlangsung sekarang ini menjadi sangat bermakna. Secara umum terdapat dua pilihan untuk bisa keluar dari krisis: dengan pendekatan hitam-putih atau melalui metode rekonsiliasi. Dengan cara yang pertama, prosesnya mudah saja. Mereka yang merupakan bagian dari masalah disuruh minggir lebih dulu karena sudah tidak punya kredibilitas, sudah tidak dipercayai, bahkan masih menyimpan masalah yang harus dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Kesempatan harus diberikan kepada orang atau organisasi yang benar-benar bersih dan bisa berlari cepat, yang masih bisa bertindak dengan tegas karena memang bukan bagian dari persoalan. Inilah yang disebut pilihan hitam-putih itu. Pilihan kedua adalah dengan cara merger atau rekonsiliasi—sebuah pendekatan yang menafikan perbedaan kekuatan lama dan baru demi menumbuhkan kesepakatan bersama untuk menyelamatkan bangsa dari krisis. Pilihan ini memang sangat menggoda karena kata rekonsiliasi sendiri mempunyai citra yang sangat positif. Tapi, sebelum pilihan dijatuhkan, harus jelas dulu bagaimana mekanisme pencapaian rekonsiliasi ini. Di masa lalu, rekonsiliasi sering dilekatkan dengan jargon persatuan dan kesatuan. Acap kali dilupakan bahwa persatuan dan kesatuan atau kebersamaan yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai tanpa menghilangkan dulu berbagai ketimpangan yang menimbulkan jurang perbedaan di antara berbagai pihak. Sebab, substansi permasalahan bangsa ini terletak pada ketimpangan-ketimpangan itu, baik dari segi pikiran maupun aspek-aspek sosial budaya dan sosial ekonomi. Itu sebabnya persoalan kunci yang menentukan sukses atau tidaknya pendekatan rekonsiliasi ini adalah penyelesaian persoalan ketimpangan ini sebagai langkah awalnya. Harus disadari bahwa mereka yang berasal dari kekuatan lama, yang sudah mapan dalam posisinya, jelas memiliki banyak sumber daya, termasuk uang. Sementara itu, mereka yang berasal dari kekuatan baru harus memulai dari keterbatasan berbagai sumber daya ini kendati mungkin mempunyai kualitas kemampuan yang sama bahkan lebih baik. Ibarat bertanding dalam perlombaan lari, kekuatan lama sudah lama meninggalkan garis start, sementara pihak reformis baru saja beranjak. Maka, tidak ada jalan lain, untuk menumbuhkan kebersamaan dalam menghadapi masa depan, semua pihak harus memulai dari garis yang sama. Dalam istilah teknis militer untuk mengoperasikan mortir, idiomnya adalah semua pihak harus "dikembalikan ke titik nol". Gagasan kembali ke posisi awal ini tak hanya berada di tataran teori. Implementasi cara ini sudah dilakukan di berbagai negara, termasuk di Korea. Bahkan, di Thailand, seorang konglomerat menjalankannya secara cukup radikal. Ia menyerahkan seluruh kekayaannya kepada negara dan kemudian bekerja sebagai pelayan hotel. Efek psikologis dari tindakannya ini cukup berdampak di masyarakat luas. Bila pemimpinnya saja mau menyerahkan semua harta dan rela bertobat demi membawa bangsa keluar dari krisis, mengapa tidak semua pihak secara bersama-sama melakukannya? Sayangnya, di Indonesia, banyak orang yang melakukan korupsi tapi tidak merasa sebagai koruptor. Mereka bahkan berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan karena akan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Dalam suasana seperti ini, kesenjangan meningkat sangat tajam. Karena itu, proses rekonsiliasi sulit dilaksanakan. Sebenarnya ada cara untuk memutus lingkaran setan yang mempertajam kesenjangan itu. Semua pejabat negara—baik sipil maupun militer—seharusnya diwajibkan untuk diaudit, kemudian ditentukan oleh DPR berapa pantasnya kekayaan mereka. Bagi kalangan tentara, juga seharusnya bisa ditentukan bahwa bintang satu berapa pantasnya dan seterusnya. Pihak militer tak dapat lagi bersembunyi dari desakan zaman terhadap perlunya transparansi di segala bidang dengan menggunakan tameng rahasia militer. Sebab, yang patut dirahasiakan adalah soal-soal teknis militer seperti rencana operasi atau sistem persenjataannya. Korupsi di jajaran tentara jelas tidak masuk dalam kategori yang harus ditutup-tutupi, apalagi dimasukkan sebagai bagian dari rahasia negara. Sebagai institusi yang menggunakan anggaran negara dan mendapatkan otoritas dari pemerintah, TNI tentu tak luput dari kewajiban untuk mempunyai public accountability yang memadai. Khusus untuk kalangan tentara, jurus mengembalikan semua pihak ke titik nol seperti ini lebih mudah dilakukan. Jika pucuk pimpinan militer secara tegas memerintahkan agar hal ini dilakukan, pasti akan berjalan. Soalnya, di jajaran tentara, berlaku kewajiban untuk taat kepada perintah atasan. Tentu ini dengan persyaratan panglimanya harus bersih dan bebas dari beban-beban masa silam. Buktinya, hal ini bisa dilakukan Soeharto pada 1960-an. Mereka yang terkooptasi kekuatan di masa lalu tentu harus disadarkan, sedangkan yang bermasalah seperti terlibat kegiatan penculikan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa silam harus dinonaktifkan. Kerelaan mereka untuk menerima keputusan ini merupakan pengorbanan demi pulihnya roh TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang. Optimisme terhadap masa depan Indonesia akan semakin berkibar bila hal ini dilakukan. Jika para jenderal yang korup saja ternyata ditangkap dan dimajukan ke pengadilan, tentu itu akan memberikan efek deteren yang besar terhadap para calon koruptor di masa depan. Disiplin di jajaran prajurit juga lebih mudah ditegakkan karena diktum supremasi hukum dirasakan berlaku bagi semua pihak dan bukan hanya pada tingkat bawahan seperti terkesan sekarang ini. Reformasi di jajaran TNI dan Polri seperti ini harus segera dilakukan karena upaya pemerintah untuk meraih masa depan yang lebih baik hanya dimungkinkan bila didukung oleh aparat negara yang kuat juga. TNI dan Polri yang kuat ini hanya dapat tercipta bila kedua institusi ini mampu mendapatkan dukungan rakyat. Cara yang paling mudah dan cepat untuk memperoleh kembali hati rakyat adalah dengan membersihkan diri dari kanker korupsi dan bersama-sama dengan pemerintah membebaskan negara dari berbagai jaring KKN dengan tetap menjunjung tinggi tatanan hukum yang berlaku. Tantangan dan cara mengatasinya sudah jelas. Sekarang persoalannya tinggal pada para pemimpin kita: mau melakukannya atau tidak. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |