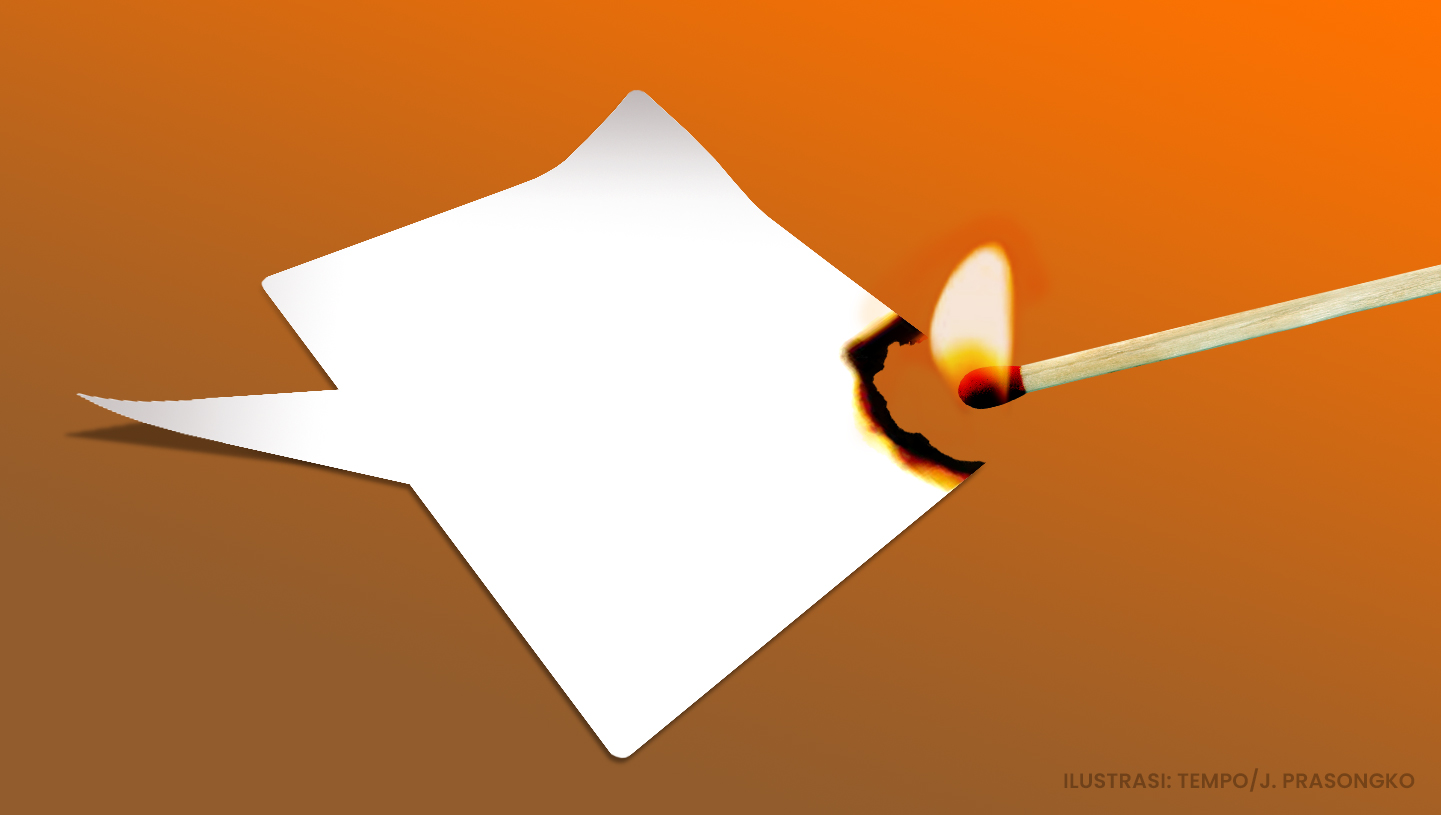Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Muhammad Chatib Basri *)
Muhammad Chatib Basri *)
*) Kandidat doktor Australian National University, Canberra
| TIAP negeri punya lamunan. Begitu juga negeri ini. Dan di pagi tujuh belas Agustus, Indonesia seperti bernyanyi untuk lamunan itu: "Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku…."
Tapi kita dipaksa menjadi lebih bijaksana ketika realitas datang dengan pesan: kita mesti banyak belajar, termasuk untuk bebas. Mungkin itu yang membuat "Indonesia Baru" lebih cocok disebut "Indonesia yang Mendewasa"—Indonesia yang mengkhayalkan masa depan, lalu tiba-tiba harus berhadapan dengan realitas. Pada tahap ini, beberapa indikator makro memang terlihat membaik, tapi masih terlalu pagi untuk berpuas diri. Ada soal struktural yang belum selesai. Karena itu, tak ada salahnya jika di tengah brisik politik dan pemulihan ekonomi yang seperti tersendat itu kita mengidentifikasi kembali beberapa hal yang berkaitan dengan krisis ini. Pertama, sulit disangkal, krisis ekonomi yang terjadi bersifat regional. Karena itu, penjelasan yang bersifat spesifik dan terbatas pada satu negara saja tidak akan membawa kita kepada akar dari krisis ini. Pernyataan bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah pemicu krisis, misalnya, tidak cukup untuk menjelaskan pola umum yang terjadi. Jika KKN adalah pemicu krisis, mengapa Cina atau Vietnam selamat? Demikian juga teori konspirasi yang mengasyikkan itu, mungkin, lebih cocok untuk sebuah cerita detektif ketimbang uraian lengkap tentang anatomi krisis. Sampai di sini, ada pertanyaan yang menarik: apakah krisis ini terjadi secara acak atau ada unsur-unsur yang sama (common factors) pada tiap negara yang dilanda krisis? Aaron Tornell dari Universitas Harvard dan Sebastian Edwards dari Universitas California Los Angeles menunjukkan adanya faktor yang sama yang terjadi di negara-negara yang dilanda krisis. Umumnya, krisis didahului oleh menguatnya (apresiasi) nilai tukar riil. Perhitungan nilai tukar riil yang dilakukan oleh J.P. Morgan dan Goldman Sachs menunjukkan, sebelum terjadi krisis, nilai tukar riil dari negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan relatif terlalu mahal (overvalued). Implikasinya, ada kemungkinan, mata uang negara tersebut akan melemah kelak di kemudian hari. Faktor kedua adalah perbankan yang lemah. Ini ditandai dengan tingginya rasio kredit macet di negara seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Tekanan terhadap mata uang, secara teoretis, dapat diantisipasi melalui tiga hal: melepas cadangan devisa, menaikkan tingkat bunga, atau mendepresiasi mata uangnya. Melepas cadangan devisa adalah pilihan yang relatif paling kecil risikonya, terutama jika negara yang bersangkutan memiliki cadangan devisa yang cukup besar. Tapi, jika cadangan devisa tidak memadai, pilihan ini menjadi tidak feasible. Di negara yang memiliki masalah kredit macet, pilihan menaikkan tingkat bunga akan melumpuhkan sistem perbankan. Akibatnya, pilihan ini tak bisa bertahan lama. Karena itu, pilihan yang tersisa hanyalah mendepresiasi nilai tukar. Kemungkinan depresiasi inilah yang kemudian mendorong krisis nilai tukar. Faktor kesamaan yang lain adalah meningkatnya porsi investasi portofolio. Ini memungkinkan terjadinya arus modal masuk dan keluar dengan cepat. Di Indonesia, meningkatnya investasi portofolio terjadi secara signifikan sejak 1993. Tiga faktor itu menunjukkan bahwa krisis ekonomi ternyata memiliki pola tertentu dan tak terjadi secara acak. Pengujian statistik memang mendukung argumentasi ini. Implikasinya, kebijakan ekonomi jangka pendek dan menengah harus mampu mengantisipasi faktor-faktor itu. Dengan kata lain, perlu antisipasi untuk mempertahankan daya saing rupiah melalui pengendalian uang beredar dan inflasi, restrukturisasi perbankan, dan solusi global dalam soal pergerakan modal. Tanpa itu, tak ada jaminan bahwa krisis tak akan terjadi lagi. Selain itu, jika benar krisis bersifat regional, mengapa Indonesia yang terparah dibandingkan dengan yang lain? Untuk menjawabnya, kita perlu masuk ke analisis yang lebih spesifik untuk Indonesia. Mungkin benar bahwa KKN bukan pemicu krisis, tapi sulit dibantah bahwa krisis yang ada menjadi lebih buruk karena adanya KKN dan guncangan politik. Di sini ada beda antara faktor "pemicu krisis" dan faktor "yang memperburuk krisis". Itu sebabnya pembahasan mengenai Indonesia harus masuk ke dataran ekonomi politik—untuk melihat bagaimana institusi yang lemah memperburuk krisis yang terjadi. Saya sendiri teringat pada Exit, Voice and Loyalty yang ditulis dengan memikat oleh Albert Hirschman, 30 tahun lalu. Ia menjelaskan reaksi pelaku ekonomi terhadap suatu produk atau kebijakan. Penjelasannya sederhana: jika konsumen dihadapkan pada suatu produk atau kebijakan yang buruk, ia bisa memilih untuk berhenti membeli produk tersebut (exit) atau mengekspresikan ketidakpuasannya dengan protes (voice). Keputusan untuk kedua hal itu harus dikaitkan dengan fenomena yang oleh Hirschman disebut loyalty (kesetiaan). Apakah loyalty akan mengurangi kemungkinan exit dan membuat voice menjadi lebih besar? Di sini, ada dua faktor yang menentukan. Pertama, tergantung apakah pelaku ekonomi bersedia membatalkan exit-nya dengan harapan perbaikan di masa depan. Kedua, tergantung seberapa jauh pelaku ekonomi percaya bahwa suara mereka didengar dan ada dampaknya bagi perbaikan kebijakan. Di sini, saya kira, analisis Hirschman—walau memiliki limitasinya sendiri—bisa membantu memahami fenomena Indonesia. Perbankan negeri ini yang ternyata rapuh, nilai tukar yang overvalued, dan mobilitas modal yang tinggi mengakibatkan pekanya pergerakan modal terhadap gejolak ekonomi dan politik. Pelaku ekonomi lalu dihadapkan pada dua pilihan: memindahkan modal keluar (exit) atau menyuarakan protes kepada kebijakan pemerintah (voice). Voice akan dipilih jika masyarakat masih melihat adanya harapan atau adanya akomodasi yang efektif untuk protes mereka. Bila tidak, exit akan menjadi pilihan yang rasional—setidaknya dalam jangka pendek. Sejarah politik Indonesia menunjukkan, tingkat represi dalam era Soeharto sulit untuk membuka peluang terhadap umpan balik bagi kebijakan pemerintah. Dan pelbagai KKN pun telah membuat exit menjadi pilihan yang paling optimal. Akibatnya, sistem otoritarian, institusi yang lemah, dan KKN mendorong bergeraknya modal ke luar Indonesia. Ini terbukti dengan arus modal neto keluar yang jumlahnya sekitar US$ 10 miliar pada 1997/98. Implikasinya, krisis menjadi lebih buruk. Ada satu pelajaran dari episode ini: pentingnya ruang bagi voice dalam sistem demokratis dan institusi yang baik. Itu sebabnya—walau terkesan brisik—transisi menuju demokrasi telah membuka peluang untuk sebuah Indonesia yang lebih baik. Amartya Sen, pemenang Hadiah Nobel Bidang Ekonomi 1998, menulis dengan antusias: walau tak ada korelasi yang konklusif antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, sejarah menunjukkan, kelaparan yang dahsyat tak pernah terjadi di negara yang merdeka, demokratis, dan memiliki pers yang bebas. Sen ingin menunjukkan betapa pentingnya kebebasan dan hak politik masyarakat. Kedua faktor itu dapat mencegah terjadinya petaka politik dan ekonomi yang lebih buruk. Memang, ketika semuanya berjalan lancar, kebebasan dan hak politik mungkin tidak memikat. Tapi, dalam kesulitan sosial dan ekonomi, institusi ekonomi dan politik yang efektif berperan cukup penting. Dan perkembangan Indonesia dewasa ini spontan seperti mengiyakan Sen. Guncangan akibat common factors menjadi lebih parah karena lemahnya institusi yang ada. Saya kira, pembenahan institusi politik dan ekonomi adalah agenda penting jangka panjang bagi kita. Tentu proses ini memakan waktu dan biaya yang tidak kecil. Hasilnya pun mungkin baru terlihat dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek, biayanya bisa melebihi manfaatnya. Lalu, orang semakin tidak sabar dan agenda ini terkesan tidak feasible. Argumen tersebut bisa saja benar. Tapi, jangan lupa, sebuah strategi kebijakan ekonomi tak hanya berorientasi jangka pendek. Krisis telah mengajarkan, ada harga sangat mahal yang harus dibayar ketika kebijakan ekonomi melupakan pembangunan institusi politik dan ekonomi. Demokrasi juga bukan tanpa cacat. Ia memiliki biayanya sendiri. Kita merasakan bagaimana proses keputusan ekonomi dan politik harus berjalan melalui proses tawar-menawar yang terkadang menjemukan. Acap kali proses tolak angsur dan berbagai variasinya itu membuat kita kurang sabar. Sebagai warga dari suatu bangsa yang selama 32 tahun dibiasakan berpikir seragam, kita mungkin sesekali merasa bahwa perbedaan pendapat terasa sebagai proses sia-sia dan buang-buang waktu saja. Apalagi jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru, ketika semuanya lancar teratur dan final dalam satu tangan. Tapi kita juga tidak menutup mata terhadap praktek korupsi masa itu yang dikultivasi melalui kekuasaan yang didagangkan. Selain itu, monopoli dan proteksi diberikan atas nama kepentingan nasional kepada kerabat dan konco. Teman dan saudara dibunuh atas nama stabilitas. Kita hidup dalam kungkungan negara yang hadir di tiap jengkal hidup kita—bahkan dalam pertunjukan puisi atau drama. Kita pernah mengeluhkan hal itu. Ini tak boleh terulang lagi. Itu sebabnya, walau brisik, ucapan Sen terasa kebenarannya. Tentu naif jika kita menganggap pembenahan institusi politik dan ekonomilah kunci dari semua soal. Masih banyak soal ekonomi teknis yang tak bisa diselesaikan dengan sekadar "kok repot" atau retorika politisi yang kerap membosankan. Di sinilah kita perlu mengantisipasi krisis ekonomi dengan lebih cermat. Indonesia memang punya lamunan. Dan di pagi tujuh belas Agustus ini, kita seperti mendengar ia menyanyikan lamunannya: "…bangunlah jiwanya, bangunlah badannya…." Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |