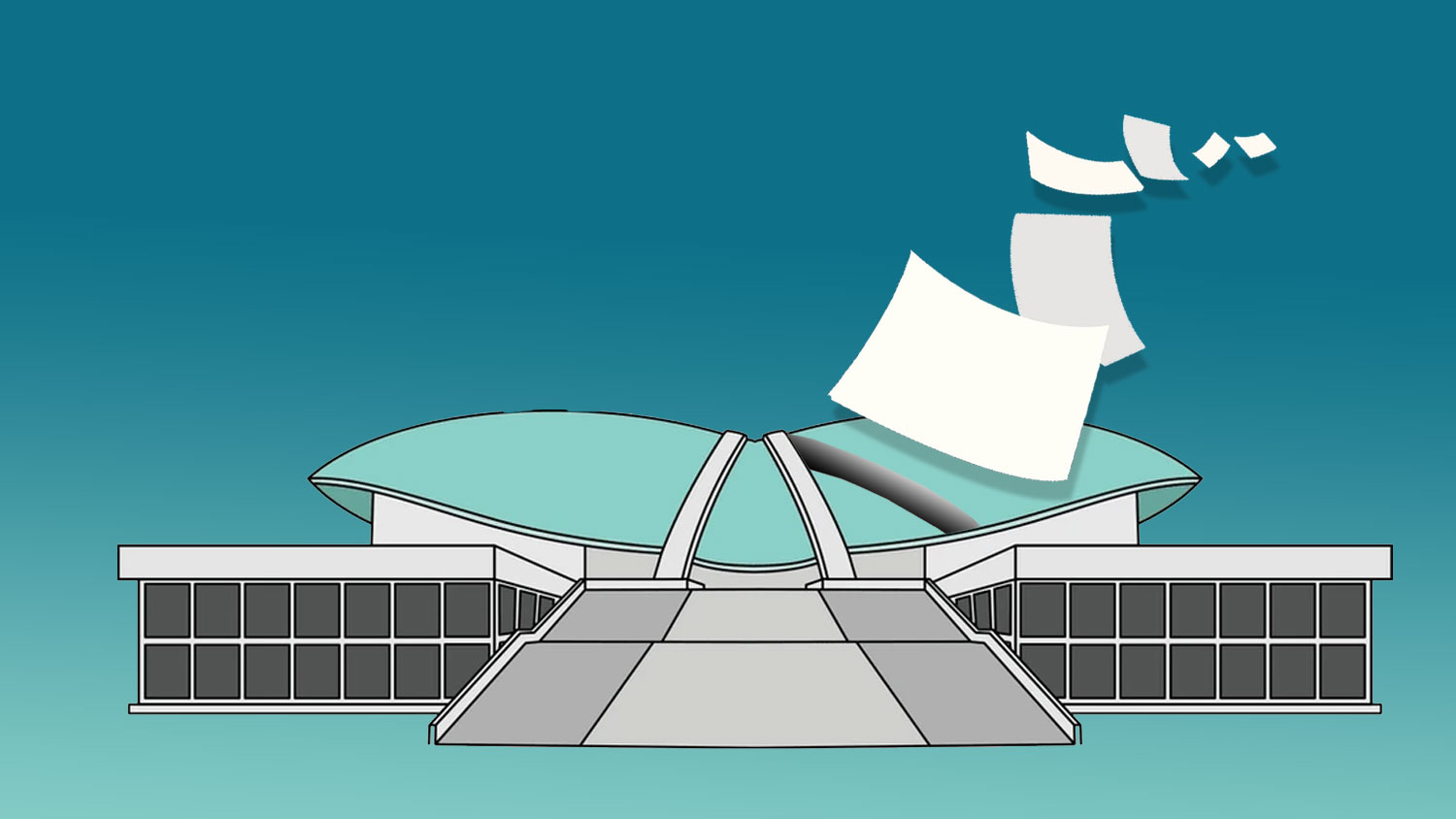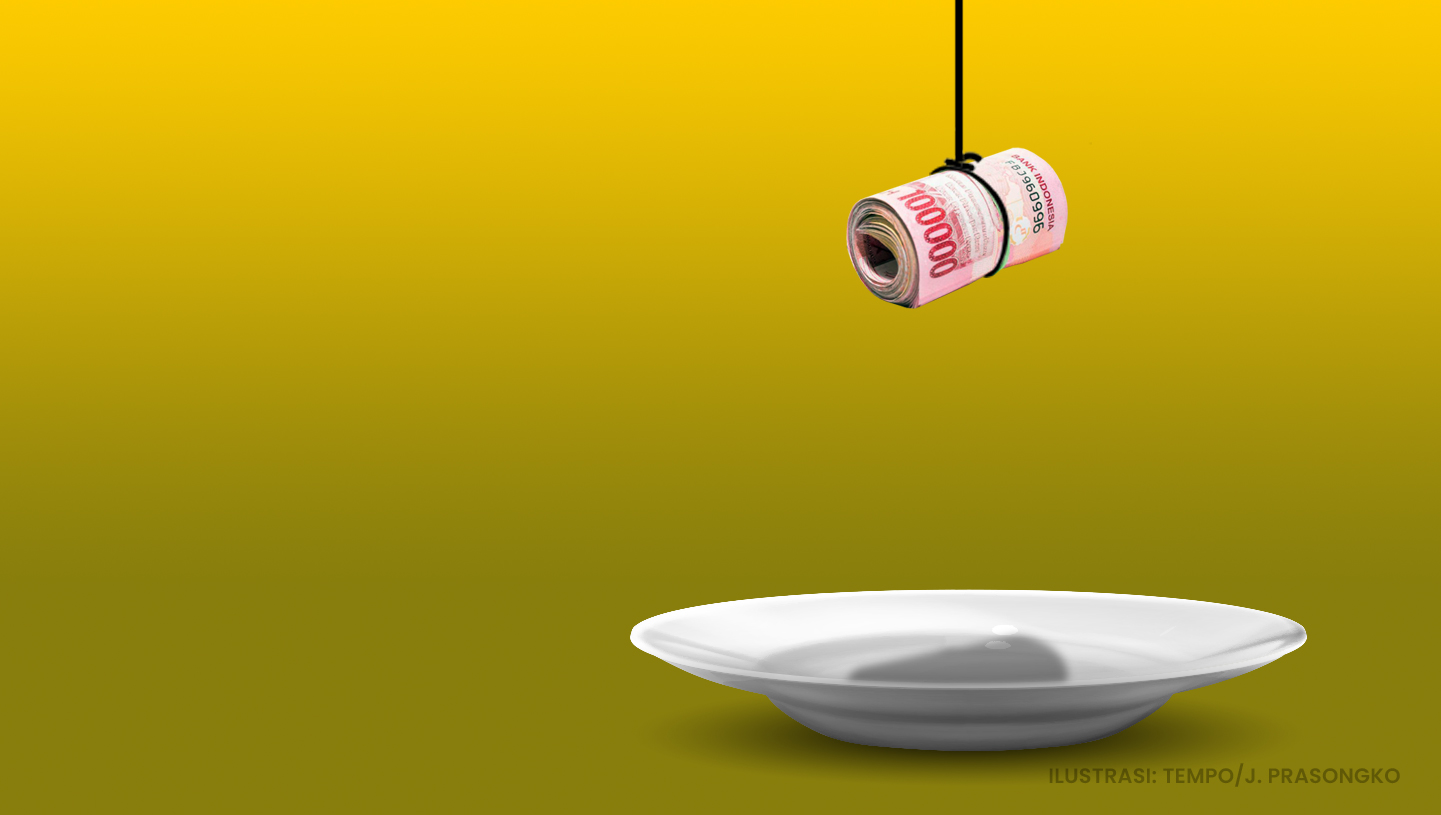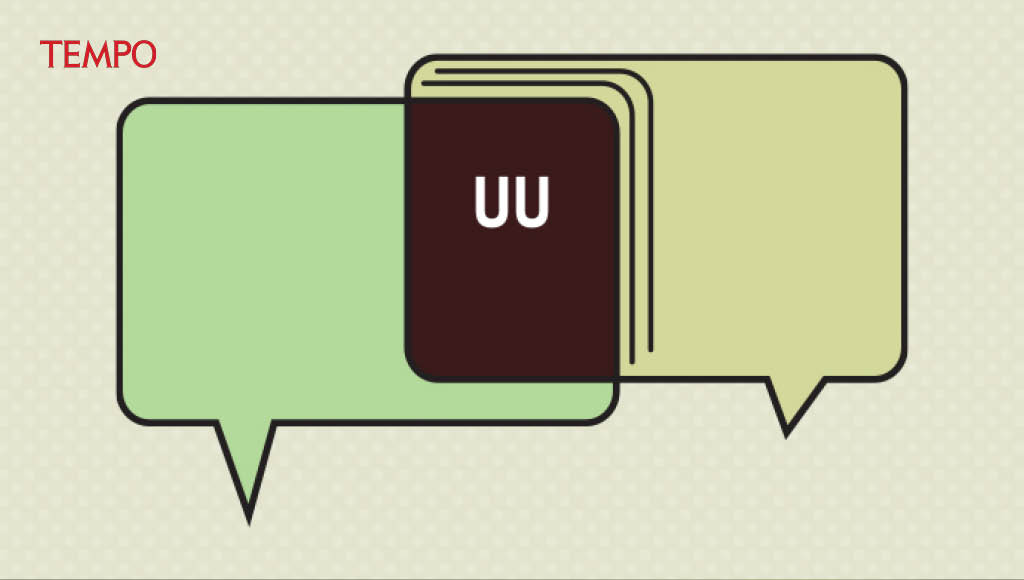Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ichlasul Amal
Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Banyak analis berpendapat bahwa nasionalisme kini adalah "something in the past". Benarkah nasionalisme tidak relevan lagi dalam perkembangan politik saat ini?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Yang jelas, nasionalisme sangat berfungsi bagi negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II. Demikianlah yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia, misalnya, merdeka atas Belanda melalui revolusi kemerdekaan pada 1945. Rakyat Malaya banyak meniru revolusi Indonesia dan merdeka pada 1959. Rakyat Burma di bawah pimpinan Aung San merdeka atas Inggris pada 1949.
Secara historis, nasionalisme terbentuk setelah Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri perang di Eropa dan membentuk negara-bangsa, yang berarti kedaulatan negara dengan batas-batas bangsa. Di Eropa mulai terbentuk batas negara dan bangsa atas dasar bahasa dan agama, seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Tapi, tentu saja, banyak tumpang-tindih antara bahasa dan agama serta batas negara yang satu dengan yang lain.
Namun nasionalisme Indonesia dari awal bukan atas dasar wilayah. Seperti kata Sukarno, "bangsa adalah keinginan untuk hidup bersama". Ini hampir sama dengan pernyataan Benedict Anderson tentang nasionalisme Indonesia sebagai imajinasi kelompok masyarakat.
Dalam perkembangannya, nasionalisme tidak lagi berkaitan dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara, melainkan dengan aspek sosial-ekonomi dan sosial-politik. Setelah Perang Dunia II, gerakan nasionalisme di sejumlah negara lebih berhubungan dengan demokrasi sehingga nilai-nilai otoritarianisme tidak dikehendaki sebagai sistem pemerintahan. Pilihan ini membuat negara menjadi liberal di bawah pengaruh Amerika Serikat.
Pada zaman Orde Baru, orang jarang membicarakan nasionalisme, walaupun Presiden Soeharto selalu menekankan Pancasila sebagai dasar pembangunan. Bahkan, dalam proses amendemen UUD 1945, yang saya terlibat di dalamnya, beberapa kelompok ekonom mengusulkan supaya Pasal 33, yang menjamin kedaulatan negara atas bumi, air, dan seisinya, dihilangkan karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Memang benar bahwa banyak hasil tambang yang besar, seperti minyak, gas, nikel, aluminium, emas, dan tembaga, telah dikuasai perusahaan asing, paling tidak melalui joint venture. Namun nasionalisme sangatlah kompleks dan tidak mungkin Pasal 33 diubah meski berbeda dengan kenyataan.
Pada waktu Sukarno menyusun konsep nasionalisme dalam Pancasila, mungkin yang dia maksudkan adalah patriotisme, dalam arti anti-dominasi ekonomi luar negeri. Nasionalisme dianggap bertentangan dengan liberalisme sehingga Sukarno berkali-kali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap demokrasi pada 1950-an yang dianggap sebagai demokrasi liberal.
Pada awalnya nasionalisme berpotensi melawan liberalisme. Tapi, pada era globalisasi sekarang ini, demokrasi liberal mengemuka. "Dalam periode ini, demokrasi liberal menjadi bentuk default pemerintahan di banyak negara di dunia, setidaknya dalam aspirasi jika bukan dalam praktiknya," demikian Francis Fukuyama menulis dalam pembukaan buku Identity. Semua negara memajukan ekonominya dengan membuka investasi asing, termasuk Indonesia.
Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia luar biasa. Jalan tol di mana-mana. Namun, harus diingat, pada periode pemerintahan Jokowi yang kedua, utang luar negeri kita mendekati Rp 5.000 triliun. Meskipun, menurut Bank Indonesia, kita masih aman dengan jumlah itu. Tapi, kalau utang semakin besar dan kita dinyatakan sebagai negara gagal karena tidak mampu lagi mengembalikan utang, apakah kita harus mengobral semua bahan tambang?
Meski demikian, liberalisme tak selamanya bertahan, seperti kesimpulan John J. Mearsheimer dalam buku terbarunya, Bound to Fail: The Rise and Fall of Liberal International Order: ’tatanan liberal’ hampir pasti jatuh di era ketika nasionalisme, dengan penekanan pada kedaulatan dan penentuan diri sendiri, bertahan sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa".
Persoalannya, negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, telah mengambil banyak keuntungan dari liberalisme. Namun sekarang mereka menjalankan kebijaksanaan nasionalis populis yang hanya menguntungkan rakyatnya.
Sebagai ideologi, nasionalisme sudah berubah. Banyak negara Barat yang tadinya penganut liberalisme kini cenderung menutup diri dan mengarah ke kanan. Mereka dikenal sebagai kelompok "populis". Di bidang ekonomi, mereka lebih mementingkan buruhnya dan mengurangi impor dari negara-negara berkembang. Mereka menjadi proteksionis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat atau turun.
Perbincangan ideologi dunia, seperti liberalisme, komunisme, dan nasionalisme, kini tidak relevan lagi. Yang berkembang, kata Fukuyama, adalah politik identitas.
Apakah pilihan kita? Bagaimana Majelis Permusyawaratan Rakyat akan merumuskan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)? Pengalaman saya tiga kali sebagai tim perumus GBHN pada masa Orde Baru, GBHN akhirnya hanya menghasilkan kalimat-kalimat jargon yang tidak ada artinya. Apakah ini akan berulang?