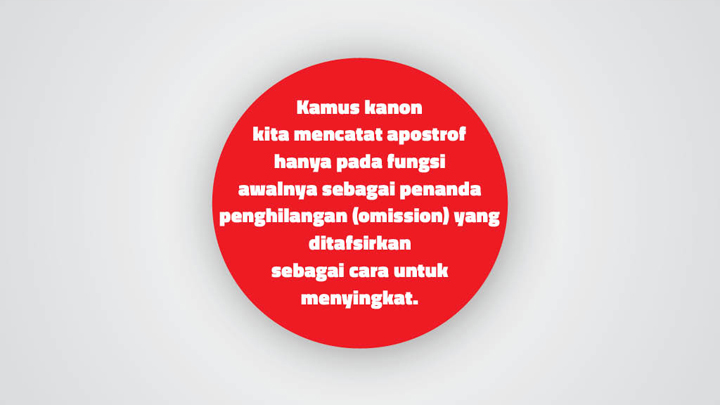Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asep Rahmat Hidayat*
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KONON, apostrof muncul untuk pertama kalinya pada 1559 dalam buku The Cosmographical Glasse karya William Cunningham. Apostrof digunakan untuk menandai huruf e yang dihilangkan dari kata the (we see the partes of th’ earth but moones age). Apostrof kemudian digunakan juga sebagai penanda kepemilikan (possession). Selain itu, dalam retorika, apostrof memiliki fungsi lain. Ia menjadi sebutan untuk bagian exclamatory dalam puisi dan pidato.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kamus kanon kita mencatat apostrof hanya pada fungsi awalnya sebagai penanda penghilangan (omission) yang ditafsirkan sebagai cara untuk menyingkat. Karena itu, kamus menyinonimkan apostrof dengan “tanda penyingkat”, sementara pedoman ejaan menggunakan istilah yang sama.
Dalam perkembangannya, apostrof menjadi tanda baca yang mendapat perhatian karena dua hal: banyak yang salah menggunakannya dan, bahkan, membuangnya sama sekali. Akibatnya, dua gerakan muncul di dua negara.
Di Amerika Serikat, seorang penulis dan seorang penjual buku membentuk Typo Eradication Advancement League. Berbekal spidol, kapur, dan cairan penghapus, mereka melakukan perjalanan untuk memperbaiki penulisan tanda baca, terutama apostrof, dalam tulisan-tulisan di ruang publik. Gerakan itu harus berurusan dengan masalah hukum. Kisah unik mereka dapat dibaca dalam buku The Great Typo Hunt, yang terbit pada 2010.
Di Inggris, Apostrophe Protection Society melakukan hal yang lebih lunak. Mereka berkirim surat untuk mengingatkan penutur bahasa akan kesalahannya ketika menggunakan apostrof dalam tulisan.
Di jagat bahasa Indonesia, perbincangan tentang apostrof juga menghangat. Hal itu dipicu bocoran surat tanggapan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terhadap surat Kementerian Agama yang kemudian dikonfirmasi melalui rilis informasi dari akun media sosial Badan Bahasa. Satu yang menjadi sorotan adalah digunakannya kembali apostrof pada nama diri: Al-Qur’an dan Ka’bah. Komentar dan tanggapan yang muncul beragam. Satu hal yang pasti, pedoman ejaan hanya mengatur apostrof dalam fungsinya sebagai penyingkat atau penanda penghilangan huruf dan angka. Lalu bagaimana riwayat penggunaannya? Apakah penyebutan tanda penyingkat untuk lambang itu tepat? Apakah lambang itu memang apostrof atau merujuk pada hal lain?
Bahasa Belanda sebagaimana bahasa Inggris mengenal apostrof untuk menandai omisi dan posesi. Ketika menuliskan kata Melayu, penulis-penulis Belanda menggunakan apostrof. Dalam Grondt Ofte Kort Bericht van de Maleysche Tale (1674) terdapat penulisan kata kardja’an, sementara dalam Kitab Indjil Soetji (1892) terdapat penulisan karadjaän dan Allah taäla. Dengan demikian, penulisan apostrof tersebut digunakan untuk menggantikan tanda trema (titik dua horizontal di atas vokal), bukan untuk menggantikan fonem tertentu.
Dalam Kitab Logat Melajoe, Ophuijsen menggunakan apostrof untuk fonem hamzah seperti pada moe’min dan ain seperti pada ma’na. Namun apakah “apostrof” itu merujuk pada apostrof seperti dalam bahasa Inggris dan Belanda?
Dalam Tata Bahasa Melayu (Maleische Spraakkunst), Ophuijsen memberikan penjelasan. Apostrof dalam aksara Latin disebut sebagai penanda spiritus lenis (embusan lembut) yang menandai tidak adanya frikatif glotal bersuara “h” di awal kata. Berbeda dengan bahasa Latin, dalam bahasa Arab spiritus lenis muncul pada awal dan akhir kata yang dilambangkan dengan hamzah (ء).
Dalam aksara Arab-Melayu, hamzah dilambangkan dengan huruf k atau q. Ophuijsen berinisiatif menyederhanakan bunyi hamzah ini dengan apostrof, merujuk pada lambang spiritus lenis tersebut. Jadi, kalaupun kita bersepakat tanda tersebut sebagai apostrof, fungsi apostrof telah bertambah dan sebutan tanda penyingkat menjadi kurang tepat.
Ophuijsen juga meminjam tanda diaeresis atau trema dari ejaan Belanda untuk menandai vokal yang memulai suku kata. Vokal a pada Quran mengawali suku kata, sehingga Ophuijsen menulis Quran dengan Koerän. Ia menegaskan: “Kata Koerän harus diucapkan koer-an dan bukan koe-ran (orang Eropa malah mengatakan koran).”
Dalam Ejaan Soewandi, bunyi hamzah atau yang mirip ditulis dengan k pada akhir suku kata, seperti makna. Nama diri dikecualikan dalam ejaan ini.
Dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi pertama, penulisan nama diri menjadi klausul tersendiri dan tanda baca apostrof tidak diatur. Namun, dalam edisi selanjutnya, penulisan nama diri menjadi keterangan dan menjadi bagian dari beberapa pasal berbeda, sementara penulisan tanda penyingkat (apostrof) diatur dalam klausul tersendiri. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia selanjutnya menguatkan aturan yang sama.
Walhasil, pemilik nama diri memang diakui haknya ketika menuliskan nama diri. Namun tanda baca memiliki aturan tersendiri, sementara rumpang dalam penulisan apostrof perlu dibenahi.
*) PENELITI DI BALAI BAHASA JAWA BARAT
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo