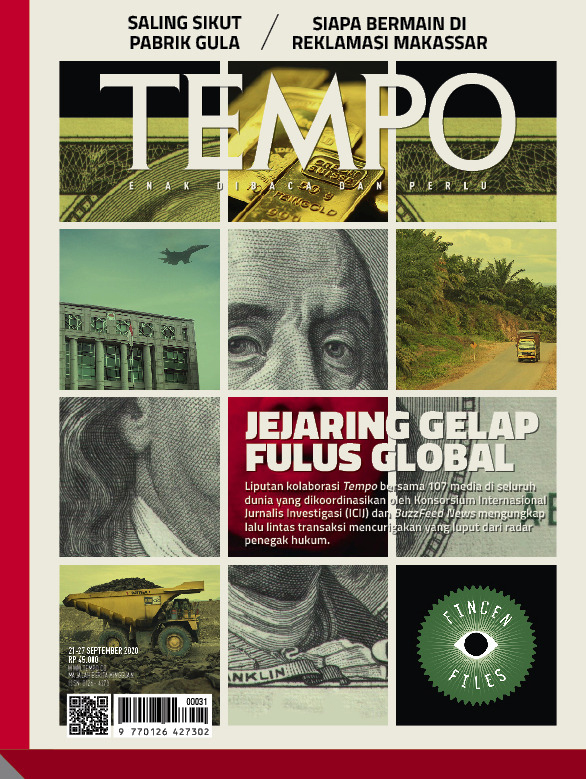Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anindita S. Thayf*
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ADA serombongan ibu yang viral setelah ditampilkan dalam film Tilik. Mereka tokoh perempuan yang mengobrol tanpa henti di sepanjang film. Seolah-olah hendak melampaui perannya sebagai pembesuk orang sakit—sebagaimana judul film itu, yang bermakna “menjenguk”—ibu-ibu ini ditonjolkan sebagai penggosip. Sebaliknya, tokoh laki-laki dibuat hanya berbicara seperlunya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gosip berarti “obrolan tentang orang-orang lain; cerita negatif tentang seseorang; pergunjingan”. Kata ini bermakna netral. Ironisnya, dalam film Tilik, pengertian yang netral ini menjadi bergender. Mengapa sebuah makna kata yang netral bisa menjadi bias gender, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun karya seni?
“Karena, begitu kita eksis,” kata Helene Cixous, “kita dilahirkan ke dalam bahasa dan bahasa berbicara kepada kita, mendiktekan hukumnya, hukum kematian.” Maka makna sebuah kata tidak lahir begitu saja. Ia muncul dalam konstruksi sosial tertentu, yaitu masyarakat patriarkal. Agar kata tersebut bermakna, menurut istilah Cixous, “Salah satu kata dalam pasangan itu dihancurkan untuk kepentingan yang lain.” Penghancuran tersebut bertujuan menunjukkan superioritas laki-laki dengan meletakkan perempuan sebagai inferior.
Dalam dunia maskulin, perempuan dipasangkan dengan laki-laki. Penyandingan ini bukan untuk mendudukkan perempuan sejajar, melainkan merendahkannya demi meninggikan yang lain (laki-laki). Jadilah perempuan, di hadapan sebuah kata yang maknanya didiktekan dan hukumnya disusun dunia maskulin, ibarat telah dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan demikian, pilihan perempuan, apakah menerima atau menolak, akan menentukan nilai akhirnya di mata laki-laki.
Perempuan dikonstruksikan pasif, sedangkan laki-laki aktif agresif. Sementara perempuan digambarkan emosional karena dianggap lebih menggunakan perasaannya dalam menjawab problem kehidupan, laki-laki diposisikan sebagai makhluk rasional karena bekerja dengan rasionya.
Pasangan-pasangan tersebut tidak bisa dipertukarkan. Bila tertukar, akan dianggap melenceng dari tertib sosial. Umpamanya, perempuan agresif akan dianggap menyimpang dari nilai-nilai keperempuanan yang telah ditetapkan dunia maskulin untuknya, yaitu berwatak pasif. Adapun jika seorang laki-laki bertingkah laku gemulai, cap negatif akan melekat padanya. Juga apabila seorang perempuan menjadi agresif sekaligus berpengetahuan dalam suatu bidang, seperti Calon Arang yang menguasai ilmu sihir, dia mesti lekas-lekas ditundukkan laki-laki karena dianggap berbahaya.
Bahkan, dalam menggunakan bahasa pun, sudah ada hukumnya. Perempuan, yang dikonstruksikan lemah lembut, terlarang bersuara keras, memaki, atau tertawa terbahak-bahak, kecuali dia mau dilabeli bukan perempuan baik-baik. Sebaliknya, hanya laki-laki yang boleh melakukannya karena semua itu merupakan tolok ukur maskulinitasnya.
Dalam konstruksi dunia maskulin inilah makna sebuah kata mudah menjadi bias gender. Salah satunya makna kata “gosip”. Perempuan dipaksa menerima peran sebagai penggosip yang rajin membicarakan dan membahas kejelekan orang lain. Peran ini kian mendiskreditkan perempuan ketika dihubungkan dengan pesan utama yang hendak disampaikan film Tilik, yaitu melawan penyebaran kabar palsu atau kebohongan lewat Internet.
Di tangan perempuan, pengetahuan dalam hal teknologi informasi seolah-olah mudah disalahgunakan hanya karena kecenderungan perempuan untuk mengobrol dan keterbatasannya berpikir rasional. Mengabaikan betapa riuh-rendahnya obrolan ngalor-ngidul para laki-laki di warung kopi, perempuan dipilih memainkan peran penggosip hanya karena laki-lakilah pemegang otoritas. Juga, lebih mudah menyalahkan perempuan sebagai makhluk yang hanya bisa menghasilkan sesuatu yang tidak berarti, termasuk kabar palsu dan kebohongan.
Pengekalan perempuan sebagai makhluk penggosip sungguh memprihatinkan. Bahasa Indonesia dibangun sebagai bahasa persatuan. Ia tidak hanya untuk menyatukan beragam suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing, tapi juga buat menyatukan semua gender yang ada. Sejatinya, yang berdiri di hadapan bahasa bukan lagi aku laki-laki atau aku perempuan, melainkan aku sebagai manusia yang memiliki kedudukan sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk berbahasa.
Usaha terus-menerus meletakkan perempuan sebagai makhluk penggosip, juga mempercayainya sebagai peran khusus perempuan hanya karena begitulah yang ditampilkan realitas, merupakan pengingat bahwa kesadaran gender masyarakat kita masih rendah. Bias gender yang terus bermunculan juga mesti terus dilawan agar bahasa Indonesia bisa menjadi rumah bagi siapa saja, tanpa diskriminasi.
*) NOVELIS DAN ESAIS
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo