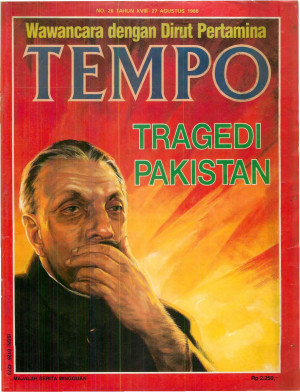KRITIK sesungguhnya tidak hanya ulasan yang menunjuk pada kelemahan atau kesalahan suatu pendapat. Kritik mestinya juga menunjuk pada kekuatan atau kebenaran pendapat tersebut. Karena kritik terutama ingin memusatkan pada kelemahan atau kesalahan, dengan demikian mendesak pengakuan akan kekuatan dan kebenaran pendapat tersebut ke pinggir, kritik jadi tampil "agresif". Mengkritik jadi tampil sebagai "menyerang". Yang ditunjuk kesalahan dan kelemahannya jadi merasa "diserang". Bagaimanapun sang pengritik berusaha menunjukkan kekuatan dan kebenaran pendapat tersebut. Tapi yang kena kritik sudah terlebih dahulu mengambil posisi "bertahan" atau bahkan bersiap untuk ganti "menyerang". Dalam bahasa silat ia akan "pasang kuda-kuda". Kritik-mengkritik adalah masalah bagaimana melantunkan bahasa. Seperti juga dalam sastra yang baik, kritik akan bergantung pada "bahasa pilihan". Bahasa ini adalah bahasa yang sangat pribadi, yang hanya sang penulis atau sang pengritik memilikinya. Begitu ia merasa pas dengan pilihannya, kritik itu akan siap dilancarkan. Kadar "menyerang" dari kritik akan tergantung bobot bahasa pilihan tersebut. Di lain pihak, bahasa adalah juga bahasa masyarakat. Ia berkembang dan dikembangkan, antara lain untuk menjaga sistem nilai. Masyarakat pertanian tradisional yang sangat mementingkan kerukunan dan harmoni akan mengembangkan penggunaan bahasa yang memperkukuh nilai-nilai tersebut. Bahasa yang dianggap cenderung merusakkan kerukunan dan harmoni akan dihindari dan dicegah. Pada waktu masyarakat pertanian itu berkembang menjadi masyarakat kerajaan yang lebih rumit, sistem nilai tersebut juga menjadi lebih rumit. Kerukunan dan harmoni itu "ditingkatkan" menjadi kerukunan dan harmoni dalam naungan hierarki kerajaan. Nilai kerukunan dan harmoni dalam masyarakat pertanian feodal itu adalah kerukunan dan harmoni dalam rangka menjaga kelestarian hierarki kekuasaan. Dalam masyarakat seperti itu, kritik diharapkan dilakukan dalam bahasa yang tidak akan merusakkan kerukunan dan harmoni. Tapi, kalau diingat bahwa esensi kritik adalah "menyerang", bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan dalam kondisi tuntutan sistem nilai demikian? Bahasa pilihan yang bagaimana akan dikembangkan sang pengritik ? * * * * * Budaya bangsa kita sering dikatakan sebagai "budaya malu". Saya akan menambahkan bahwa budaya bangsa kita juga sangat dikuasai oleh "budaya rikuh" atau "budaya segan" atau mungkin juga "budaya enggan". Nilai kerukunan dan harmoni yang begitu sentral dalam sistem budaya kita telah menciptakan berbagai sikap yang khas dalam masyarakat. Ia mendorong tumbuhnya keengganan untuk berkonfrontasi langsung atau memulai suatu konflik. Ia menganjurkan lebih baik menghindari pertengkaran daripada menyambutnya. Ia akan menekankan pada sikap peka terhadap kemungkinan munculnya rasa tersinggung pada orang lain. Maka, bisa dibayangkan bagaimana bangsa kita dalam perjalanan hidupnya selalu ditempatkan dalam kedudukan waspada terhadap kemungkinan pecahnya kerukunan atas keselarasan. Ia adalah beban budaya kita yang paling pokok dalam pengaturan hidup bermasyarakat. Karena hidup bermasyarakat adalah hidup dalam dunia hierarki yang bertakuk-takuk, maka kepekaan yang terus-meneru dilatih adalah kepekaan menjaga jarak yang lestari dalam hierarki. Orang Jawa sudah dianggap Jowo apabila telah menguasai juru kepekaan dalam konteks di atas. Ukuran "halus", "beradab", dan "tahu adat" akan sangat ditentukan oleh penguasaan jurus kepekaar ini. Rikuh dengan demikian juga kepekaan seperti itu. Maka euphemism, yang menurut Kamus Inggris-lndonesia oleh Echols dan Shadily diterjemahkan sebagai "ungkapan pelembut" menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Ia adalah penangka. terhadap kemungkinan konflik situasi yang sangat merikuhkan bagi bangsa kita. Dengan demikian, bahasa pergaulan, dengan sendirinya juga bahasa pilihan kritik yang mestinya "menyerang" itu, juga penuh bunga-bunga euphemism. Kritik-mengkritik menjadi ajang lantunan bahasa sanepa, bahasa semu, bahasa sindir, dan bahasa yang berbunga-bunga. Apakah dengan demikian tujuan kritik tercapai? Ini tergantung seberapa jauh sistem nilai tradisi kita masih kuat berakar dalam masyarakat. Bila akar sistem nilai tradisi tersebut masih kuat berakar mungkin kritik yang euphemistic justru lebih efektif daripada kritik lugas dan langsung. Yang dikritik masih mendudukkan dirinya dalam posisi hierarki masyarakat, sehingga kadar kepekaannya terhadap kritik masih akan berada dalam konteks posisi tersebut. * * * * * Apakah euphemism milik khas bangsa Indonesia? Monopoli bangsa yang sudah menciptakan Wedatama dan Wulangreh serta menggali Pancasila? Tentu tidak. Euphemism, seperti juga nilai "halus" dan "ikuh", ada di mana-mana. Juga bahasa sanepa, bahasa semu, dan ungkapan-ungkapan yang eloquent, yang elegant, yang micara dan jatmika serta canggih, dikenal dan dihargai di Eropa Barat, di Eropa Timur, maupun di Amerika. Semua itu sama-sama dibutuhkan sebagai pengikat, pemikat, serta bumbu-bumbu pergaulan antarmanusia. Mereka juga membutuhkan kerukunan dan keselarasan, karena tidak ingin jagat mereka berantakan dan berceral-berai. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Barangkali konteks orientasi budayanya. Mereka, masyarakat industri maju yang modern itu, hidup dalam masyarakat egaliter dan sistem yang sangat terbuka. Masyarakat sama derajat dan sama hak. Mereka menganggap itu semua sebagai suatu syarat mutlak. Kita, masyarakat pasca-pertanian, belum industri dan mau modern, hidup dalam masyarakat yang masih menganggap hierarki sosial sebagai konteks budaya sangat penting. Dahulu kita pernah menganggap itu sebagai syarat mutlak. Sekarang kita mulai mempertanyakan kemutlakan itu. Barangkali kita sekarang sedang bergerak mencari dan merumuskan bahasa baru yang tidak terlalu bergantung pada konteks nilai keselarasan hierarkis. Suatu bahasa yang cukup sopan, eloquent, dan elegant tetapi tanpa harus merunduk-runduk dan sering mendongak ke atas. Bahasa kritik yang sopan ? Saya jadi teringat guru bahasa Jawa saya di sekolah menengah. Seorang gentleman Jawa yang masih sangat menjunjung tinggi sistem nilai priyayi tetapi sekaligus juga berusaha dengan sekuat tenaga menjadi orang Indonesia baru yang baik. Nasihatnya: "Begitu ya begitu, Le. Tapi mbok jangan begitu ...."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini