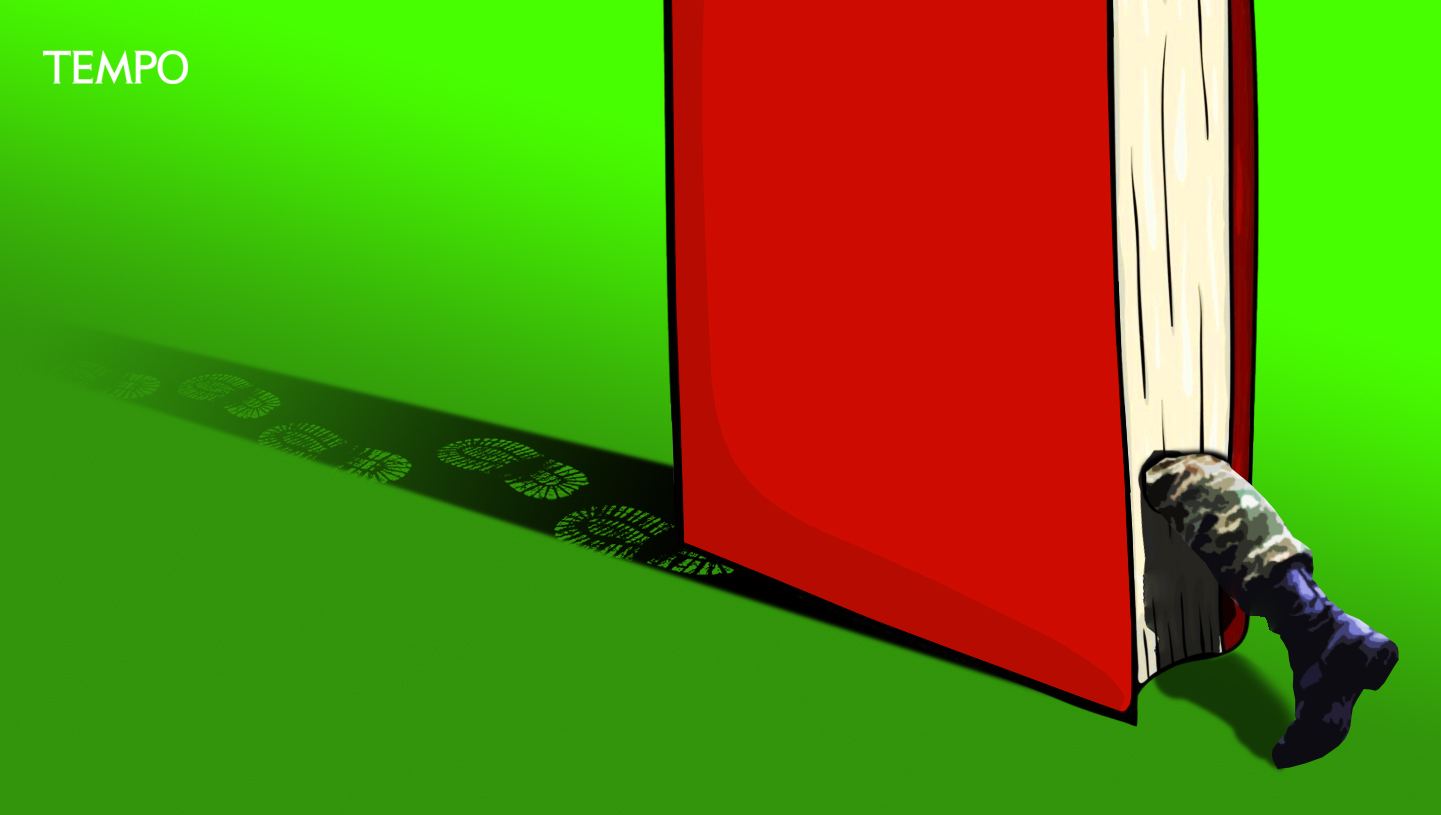Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miko Ginting
Pengajar STH Indonesia Jentera
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Putusan pemidanaan terhadap Baiq Nuril Maknun menuai reaksi negatif dari banyak kalangan. Baiq Nuril, perempuan pegawai honorer di sebuah sekolah menengah atas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, adalah korban pelecehan seksual oleh atasannya, seorang kepala sekolah. Logika hukum dan keadilan seakan runtuh ketika mendapati seorang korban berubah menjadi pelaku kejahatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nuril didakwa menyebarluaskan konten bermuatan kesusilaan, yang berisi percakapan cabul atasannya. Pada putusan tingkat pertama (pengadilan negeri), yang memeriksa fakta dan alat bukti secara langsung, hakim memutuskan Nuril terbukti bersalah melakukan delik yang dituduhkan. Putusan itu berbalik di tingkat kasasi di Mahkamah Agung: Nuril diputus bersalah.
Hingga hari ini, putusan kasasi belum diunggah di laman resmi Mahkamah sehingga belum terlacak apa alasan hakim membalikkan putusan pengadilan tingkat pertama itu. Namun, apabila melihat karakter kasasi, yang berfungsi memutus penerapan hukum (judex juris), dapat diduga kuat MA melakukan penafsiran terhadap unsur “penyebarluasan” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasal itu memuat unsur delik dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pemenuhan unsur pasal itu semata didasarkan pada perbuatan Nuril, yang menyerahkan rekaman percakapan dengan pelaku kepada orang lain. Dengan jalan pikiran ini, ia kemudian dipersalahkan atas “penyebarluasan” konten yang bermuatan kesusilaan.
Pemeriksaan yang hanya “hitam-putih” terhadap pemenuhan pasal itu akan menyingkirkan konteks materiilnya. Fakta bahwa Nuril adalah korban pelecehan seksual yang mendapat tekanan dari pelaku tidak bisa dikesampingkan. Fakta bahwa terdapat relasi kuasa yang tegas (pelaku adalah kepala sekolah dan korban adalah pegawai honorer) juga makin menguatkan bahwa kalaupun Nuril menyerahkan sejumlah informasi kepada orang lain, itu karena didasari tekanan psikologis.
Konteks dan fakta tersebut berhasil ditangkap Pengadilan Negeri Mataram. Karena itu, putusan MA yang membalikkan keadaan itu menjadi polemik.
Pertama, sistem pemeriksaan yang berjenjang dan terbagi antara pemeriksaan terhadap fakta (judex facti) dan pemeriksaan terhadap penerapan hukum (judex juris) punya konsekuensi pada konsistensi. Putusan berbeda dari pengadilan yang lebih tinggi dimungkinkan sepanjang memuat argumentasi yang kuat dan beralasan. Dalam kasus Nuril, putusan MA tidak mendapat landasan argumentasi yang kuat. Penafsiran terhadap unsur “penyebarluasan”, yang dimaknai secara sempit dan lepas dari konteks, menjadikan putusan MA itu dipertanyakan.
Kedua, MA terikat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Peraturan itu adalah “paksaan” bagi hakim agar melihat konteks yang lebih luas dalam kasus-kasus berdimensi perempuan, seperti ketimpangan gender dan relasi kuasa. Dalam kasus Nuril, peraturan ini seakan-akan diabaikan.
Selain itu, terdapat permasalahan lain berupa norma dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal itu tampaknya ditujukan kepada kesengajaan penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan. Namun perumusan yang longgar berdampak pada pemaknaan yang luas, bahwa seakan-akan perbuatan tanpa kesengajaan juga dapat dijerat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya melakukan evaluasi mendalam terhadap semua norma dalam Undang-Undang ITE yang bermasalah dan kerap ditafsirkan tidak tepat.
Jalan keluar yang tersedia kini melalui dua jalur, yaitu Nuril mengajukan peninjauan kembali atau Presiden memberikan amnesti. Namun amnesti biasanya diberikan dalam perkara politik. Sedangkan jalur peninjauan kembali diduga berisiko karena terdapat “benturan kepentingan” di antara sesama hakim agung yang melakukan pemeriksaan. Meskipun, dalam beberapa kasus, jalur peninjauan kembali sengaja dibuka sebagai solusi.
Namun poin pentingnya jelas. Semua upaya untuk mencegah Nuril dan korban-korban lain terjerat pemidanaan yang dipaksakan harus dilakukan. Sikap Presiden dan Ketua Mahkamah Agung penting untuk diuji. Nuril adalah korban, dan korban tidak seharusnya disalahkan.