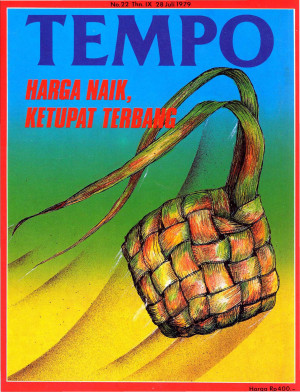BERAPA kali dalam sehari anda makan nasi? Tiga kali? Bagus, dan
selamat. Itu menunjukkan bahwa anda mungkin sudah dapat
dimasukkan ke dalam golongan mereka yang tidak berada di bawah
"garis kemiskinan". Dan mungkin juga telah memasuki taraf "hidup
bergizi dan bermutu".
Tetapi, dulu waktu masih kecil seringkah anda mengamati pola
konsumsi nasi" kakek dan nenek kita? Kalau anda orang Jawa kakek
dan nenek itu mungkin suka tirakat, nglakoni, suka mengurangi
kwantitas dan kwalitas makannya.
Kadang mereka hanya makan ubi-ubian dan sayuran tanpa garam --
nganyep dan ngrowot. Kadang ditambah dengan puasa Senin dan
Kamis. Dan kalau kita tanya buat apa mereka berbuat begitu,
mungkin mereka akan berkata: buat kalian, cucuku, supaya kalian
bisa berpangkat tinggi dan bisa naik mobil besar.
Waktu berkata begitu, kepala mereka manggut-manggut, tersenyum,
matanya bersinar bahagia. Kebahagiaan seorang masochist, yang
bahagia karena penyiksaan dirinya sendiri?
Masochist atau bukan mungkin sekali nganyep atau ngrowot itu
konsep "mistik" nenek-moyang orang Jawa yang nrimo dan pasrah
tentang penghematan dan penyimpanan persediaan pangan. Sebab
siapa tahu konsep ini baru berkembang sesudah Jawa dihajar dan
dikuras habis oleh Cultuurstelsel -- itu sistem tanam paksa yang
edan dari Van den Bosch. Yakni, sesudah orang-orang Jawa dan
Sunda tinggal tulang dan kulit .....
Dan para petani kecil kita yang merupakan mayoritas itu,
pernahkah mereka makan nasi tiga kali dalam sehari juga dalam
keadaan makmur mereka? Sekali-sekali pernah, tetapi tidak
selalu. Makan nasi dalam kwantitas besar saya kira cuma sekali
dalam sehari, yakni pada waktu siang atau sore hari. Selebihnya
yang mereka makan adalah ubi-ubian, kacang-kacangan dan
buah-buahan.
Juga di sini petani itu di samping memang melarat juga punya
konsep menghemat dan menyimpan. Sebab tanpa konsep demikian
bagaimana mereka akan masih bisa bertahan terus, dengan involusi
pertanian Jawa, seperti dikemukakan Clifford Geertz
(Agricultural Involution) itu?
Lantas, siapa dong, yang makan nasi tiga kali dalam sehari? Wah,
tinggal orang-orang kota! Dan tentulah kota-kota itu kebanyakan
kota-kota di Jawa.
Kota, tangan-panjang dari desa yang makin membengkak saja itu
mengangakan mulutnya lebar-lebar melahap nasi yang ditanak dari
beras yang diimpor tidak hanya dari desa-desa kita sendiri,
tetapi juga dari negara-negara asing yang akan makin banyak saja
jumlahnya.
* * * *
Tetapi belum sampai setahun yang lalu, bukankah massmedia kita
telah mencanangkan kekhawatiran para pengamat konsumsi beras
tentang pola kita melahap nasi itu? Kata mereka: bila begini
terus cara orang Indonesia melahap nasi (sambil terus melahirkan
bayi-bayi), ditanggung pada tahun 1985 seluruh, sekali lagi
seluruh, ekspor di seluruh dunia harus ditumpahkan ke Indonesia.
Wah, itu tinggal enam tahun lagi! Sementara itu sudah akan
memadaikah usaha perluasan persawahan kita di luar Jawa? Sudah
akan naikkah, dengan sangat mengesankan, produktivitas per
kapita petani kita? Masih akan cukupkah dana-dana yang kita
tumpuk lewat kenaikan harga minyak OPEC dan pemungutan pajak
yang lebih getol pada tahun 1985 untuk membayar beras dari
ekspor seluruh dunia itu?
Tapi sementara itu pula, nasi terus dilahap dengan penuh oisesi
dan gusto. Nasi adalah simbol status dan simbol kenikmatan
karbohidrat yang dianggap sangat penting di negeri ini. Makan
nasi tiga kali (yang enak lagi) adalah untuk mengukuhkan citra
kemakmuran kita dalam komunitas. Kurang sreg jika cuma makan
nasi pembagian, PB atau IRI. Kalau bisa, Cianjur, Rojolele,
Mandi .,, (Dalam ruang advertensi majalah kita ini, umpamanya,
sebuah rumah-makan Ayam-Goreng bahkan menjajakan dengan
bangganya bahwa nasi yang disuguhkan adalah nasi rojolele yang
spesial didatangkan dari Delanggu . . .)
Konsep empat sehat, lima sempurna juga ditafsirkan demgan
lauk-pauk lengkap plus nasi!
Sementara itu dilaporkan bahwa produksi sagu, ubi-ubian dan
jagung di kawasan lain di negeri kita melimpah, setidaknya dapat
diusahakan dengan gampang untuk melimpah.
Tidak tahukah kita tentang berbagai informasi di atas itu? Tidak
tahukah kita bahwa "makan nasi" sudah menjadi isyu nasional yang
gawat dan kritis?
Oh, kita tahu, dong! Informasi itu meski sepotong-sepotong
disampaikan di media massa. Kita diberi tahu, umpamanya,
keluarga Presiden sekarang makan nasi diseling dengan kentang
dan ubi-ubian. Menteri Ali Murtopo menganjurkan kita makan roti,
Masri Singarimbun melancarkan kampanye sagu, seorang menteri
mengumpat mereka yang makam nasi rojolele sebagai orang-orang
yang mementingkan diri sendiri, ahli ini atau itu berkata bahwa
kita masih terlalu "padi sentris" kurang perhatian buat palawija
dan sebagainya lagi.
Lantas, mengapa kita masih adem ayem seakan kita sudah berada
lagi dalam negeri yang tata tentrem kertaraharja seperti duluuu
waktu kita masih membayangkan hidup di kerajaan Ngamarta atau
Hastinapura?
***
Herbert Feith pernah berbicara tentang gaya pengelolaan politik
yang disebutnya sebagai solidarity-making approach. Yakni suatu
pendekatan yang mengandalkan pada penggalangan solidaritas-massa
lewat teknik pengerahan opini massa yang digerakkan secara luas
dan intensif. Gaya Bung Karno disebutnya sebagai gaya
solidarity-making ini.
Saya tidak tahu apakah pendekatan begini akan tepat buat
mengguncang-guncang ketidak-acuhan kita terhadap "krisis makan
nasi" sebagai isyu nasional yang kritis. Tapi mungkin perlu satu
gerakan kampanye besar-besaran yang dibarengi dengan contoh dari
para bapak pemimpin tentang perubahan radikal, sekali lagi
radikal, dalam pola makan nasi kita.
Makan nasi yang cukup satu kali dalam sehari. Selebihnya,
kreatiflah menyeling dengan makanan lain. Dan berbaren dengan
itu juga sekaligus kampanye penelitian, penanaman dan pemasaran
besar-besaran: sagu, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan,
jali-jalian ....
Bagian terbesar dari rakyat kita sudah selalu makan nas sekali
saja dalam sehari. Mereka sudah cukup "kreatif" menyelingnya
dengan makanan lain. Tinggal kita-kita yang di kota saja yang
belum. Bisa?
Mungkin pada waktu puasa begini kita bisa mulai dengan tekad
itu. Mungkin pada waktu kita nanti berziarah di kuburan kakek
dan nenek kita perlu berbisik pada batu nisan mereka: Nyuwun
sewu, meskipun pangkat dan montor sudah di tangan, nampaknya
kita masih akan harus tirakat ngrowo lagi ..........
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini