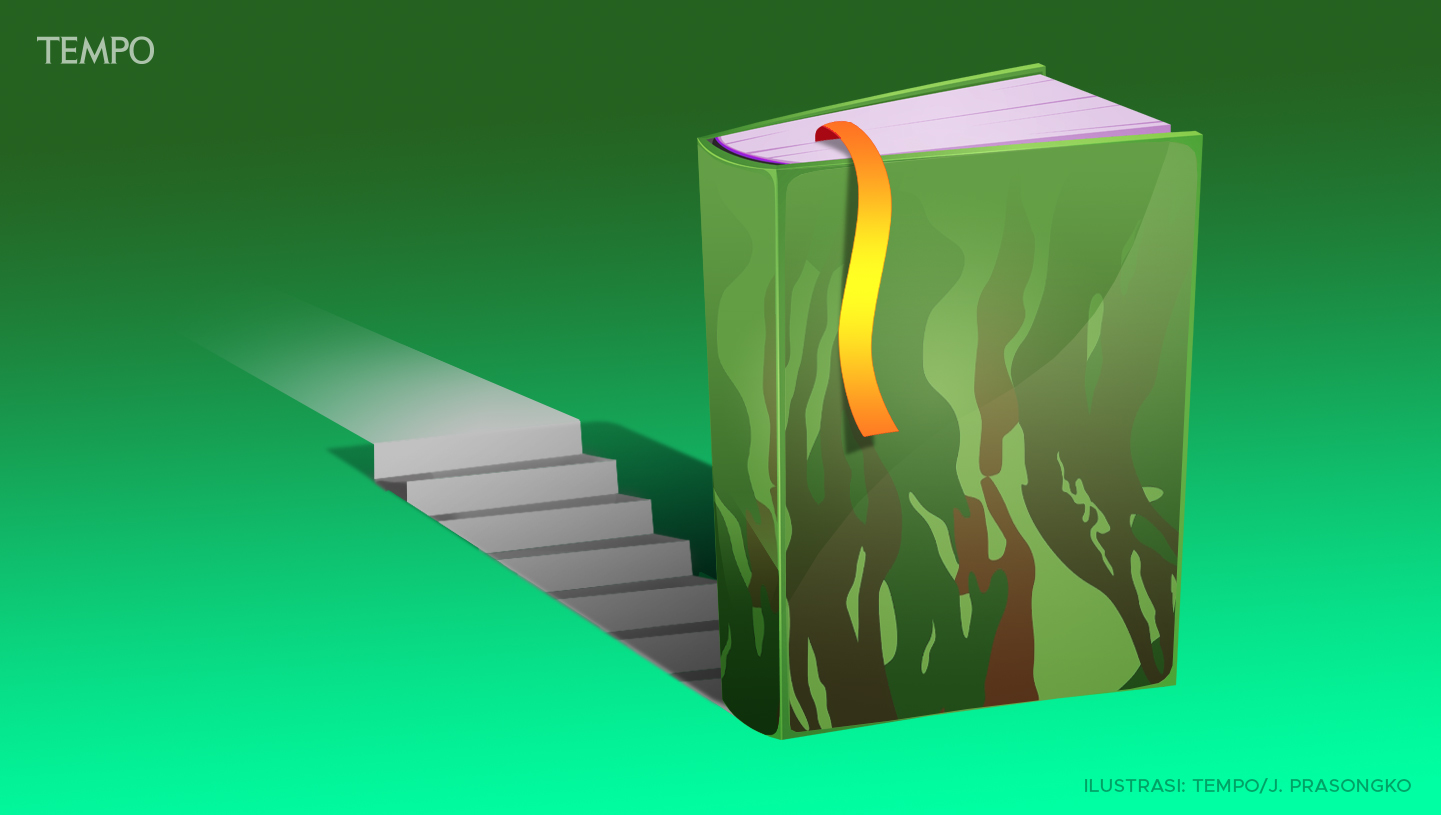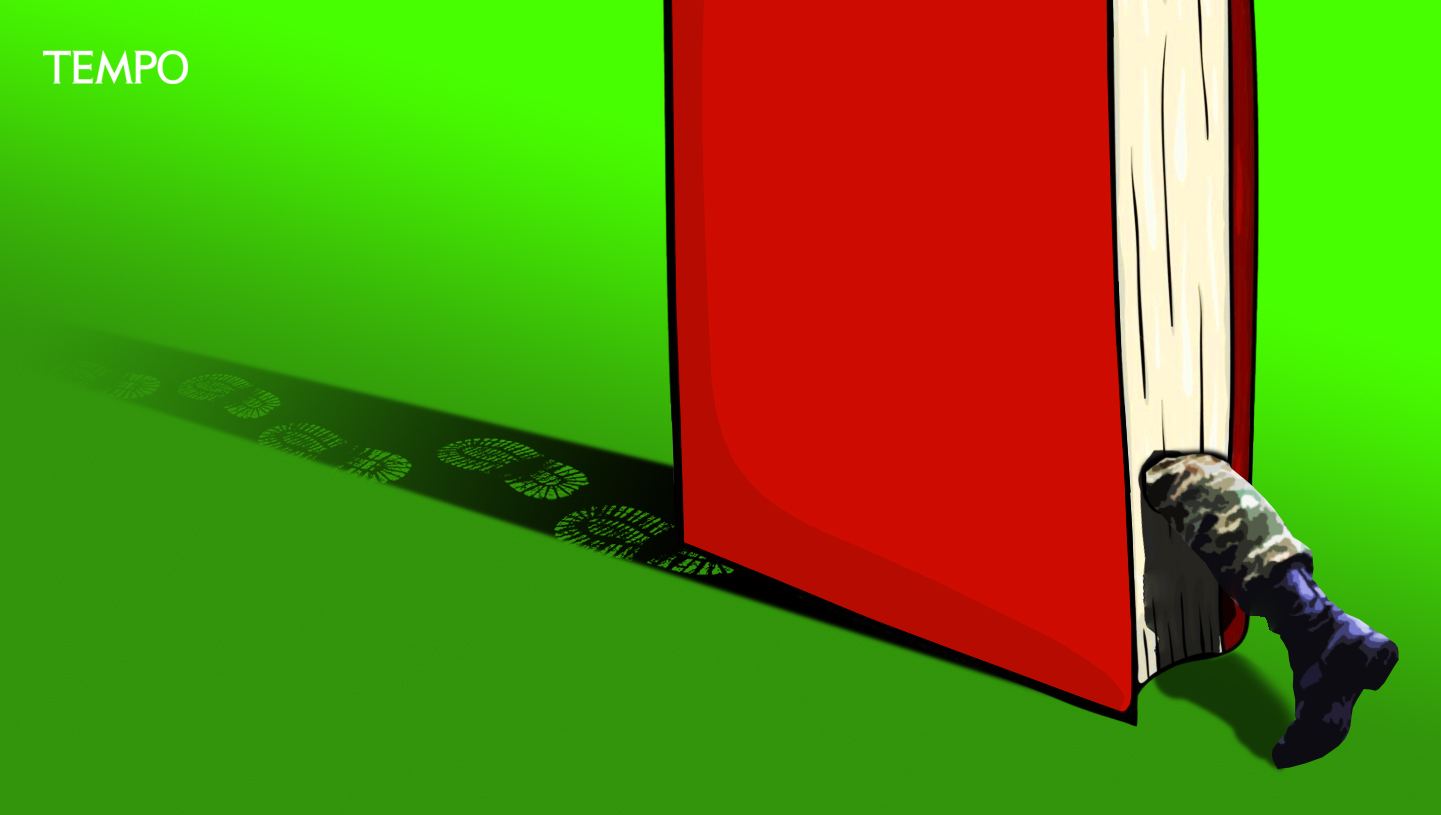Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miko Ginting
Pengajar Hukum Pidana di STH Indonesia Jentera
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perdebatan mengenai hukuman mati semakin hari semakin bergerak ke arah penghapusan atau paling tidak secara gamblang: kompromi. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sebuah representasi sikap pemerintah dan DPR menunjukkan wacana kompromistis ihwal hukuman berupa perampasan hak hidup ini. Wacana itu diakui dan dibicarakan secara terbuka dalam pembahasan Rancangan KUHP yang sudah menuju tahap akhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perdebatannya bukan lagi soal efektivitas hukuman mati dalam upaya pemberantasan kejahatan. Hukuman mati sudah diakui secara terbuka, terutama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak berkorelasi dengan upaya untuk menekan angka kejahatan.
Dalam pembahasan Rancangan KUHP, sikap kompromistis itu disandarkan pada alasan moralitas agama. Dengan demikian, perdebatan sesungguhnya berada pada kutub yang sama sekali berbeda dengan konteks penegakan hukum.
Pada aras yang sama, diakui bahwa hukuman mati sangat perlu dihindari di tengah sistem peradilan pidana yang rapuh. Untuk itu, para perumus Rancangan KUHP menyiapkan beberapa lapis prasyarat sebelum hukuman mati dilakukan. Selama ini, hukuman mati kerap dijatuhkan tanpa mekanisme pemeriksaan yang tuntas dan utuh serta didasari prinsip uji tertentu. Padahal, hukuman mati bersifat non-return, yang sekali dijatuhkan tidak dapat diulang kembali, pun apabila ada kesalahan dalam penerapannya.
Kasusnya banyak. Yusman Telambanua sempat dijatuhi hukuman mati meski ia seorang anak di bawah umur. Rodrigo Gularte divonis pidana mati padahal mengidap gangguan jiwa. Zulfikar Ali meninggal dengan status terpidana mati padahal nyaris diberi grasi oleh presiden. Dan, Mary Jane Veloso, yang hampir saja direnggut nyawanya, padahal kemudian terbukti sebagai korban sindikat perdagangan manusia. Sekian banyak contoh ini menegaskan rapuhnya sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penerapan hukuman mati.
Rancangan KUHP mengatur bahwa hukuman mati tetap diakui, tapi bukan lagi sebagai pidana pokok. Hal ini diposisikan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Ketentuan ini bermakna pembentuk Rancangan KUHP memberi arah bahwa pidana mati merupakan upaya paling terakhir.
Dalam Rancangan KUHP, setelah vonis pidana mati, seorang terpidana tidak serta-merta dieksekusi. Eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden. Setelah itu, dia juga harus masuk masa penundaan selama 10 tahun.
Ini selangkah lebih maju dibanding KUHP sekarang. Tapi masih ada masalah soal tidak adanya kepastian setelah masa penundaan 10 tahun. Situasi ini berpotensi mendorong naiknya angka daftar tunggu eksekusi mati (death row).
Daftar tunggu ini merupakan bentuk penyiksaan, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa studi menunjukkan hal tersebut. William Schabas (1996), misalnya, menyatakan bahwa penundaan hukuman mati menambah efek psikologis ketercerabutan seseorang, tidak hanya dari masyarakat, tapi bahkan sesama narapidana. Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa bahkan mengeluarkan keputusan penting soal ini melalui kasus Soering vs The United Kingdom (1989). Pengadilan menyatakan bahwa penundaan hukuman merupakan pemenjaraan berkepanjangan dengan situasi penekanan dan kesengsaraan terus-menerus.
Rancangan KUHP seharusnya mengatur hal ini. Selain itu, hukuman mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif harus dihapus dari ancaman dalam rumusan pasal per pasal Rancangan. Jika tetap dicantumkan, tujuan kompromistis yang didambakan perumus Rancangan KUHP tidak akan tercapai. Hukuman mati berpotensi tetap diposisikan sebagai pidana pokok yang diancamkan.
Selanjutnya, penghapusan ancaman pidana mati dari rumusan pasal per pasal harus diikuti dengan reformulasi pedoman. Di sini, pilihan untuk melakukan moratorium penuntutan akan lebih menjamin terhindarkannya fenomena daftar tunggu eksekusi. Dengan demikian, moratorium berpindah dari moratorium eksekusi menjadi moratorium penuntutan.
Apabila strategi ini berhasil ditempuh, bukan hanya cita perumus Rancangan KUHP akan tercapai, tapi juga cita pendirian bangsa, yaitu menghargai hak hidup dan kemanusiaan, akan turut terpenuhi. Cita ini tidak akan pernah terpenuhi apabila hukuman mati masih diterapkan, terutama dengan sistem peradilan pidana yang rapuh dan tidak sepenuhnya bersih dari penyimpangan.