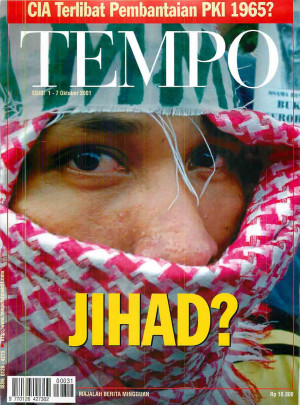Dan kematian makin akrab.” Hari-hari ini sebaris sajak Soebagio Sastrowardojo itu kembali ke ruang kepala saya berkali-kali: sebuah eulogia untuk seseorang yang dibunuh, atau sebuah kata penyerahan terhadap sebuah kepastian, yakni mati, yang menyembunyikan ketakpastian?
Hari-hari ini saya sering membayangkan bagaimana sejumlah orang datang, tenang dan teratur, untuk membunuh diri, untuk membunuh orang lain…. Benar, saya membayangkan Muhammad Atta—atau siapa pun namanya—beserta teman-temannya, yang pada pagi 11 September 2001 itu datang ke Bandara Logan, Boston. Saya membayangkan mereka naik, di antara puluhan penumpang lain, ke dalam dua pesawat Boeing 767, dan duduk. Saya bayangkan mereka menunggu, membisu.
Apa gerangan yang mereka pikirkan, sebelum mereka masuk ke dalam kokpit dan dengan paksa mengambil alih kemudi, memilih arah baru, dan dengan kecepatan 640 kilometer per jam berturut-turut menabrakkan dua pesawat seberat 160 ribu kilogram itu ke gedung raksasa kembar yang menjulang tinggi di bagian selatan New York?
Sebuah dokumen berbahasa Arab kemudian ditemukan. Jika benar itu berasal dari apa yang mereka bawa pada hari yang mengerikan itu, teks itu sederet petunjuk yang rinci ke jalan kematian. Pada malam menjelang 11 September itu, demikian di sana disebut, kau harus bersumpah untuk mati. Cukurlah rambut yang berlebihan. Gunakan minyak pewangi tubuh. Mandi. Baca dua surah dalam Quran (dan ”ingat semua hal yang dijanjikan Allah untuk para syuhada”). Salat. Murnikan sukmamu dari semua hal yang najis. Lepaskan seluruhnya sesuatu yang disebut ”dunia ini”. Asahlah pisaumu. Jika membunuh, jangan sampai si korban kesakitan. Menjelang naik ke pesawat, eratkan tali sepatumu. Kau harus tenang secara penuh, sebab ”saat antara kamu dan perkawinan kamu [di surga] sangat pendek. Setelah itu, akan mulai hidup yang berbahagia….”
Dan kematian makin akrab, dan juga, dengan jalan itu, mungkin sebagian ibadah. Teror itu sebuah perang suci.
Tapi tentu saja tidak demikian bagi 6.333 manusia lain, yang tewas dan terkubur, hampir sekaligus, dalam waktu hanya beberapa menit, di ujung bawah daerah Tribeca pagi itu. Bagi ribuan manusia yang terbakar pelan-pelan atau mendadak luluh-lantak dalam kedua gedung itu—apa kematian bagi mereka? Saya mencoba membayangkan. Di sebuah majalah saya pernah melihat sebuah gambar: orang-orang yang putus asa, bergantung-gantung di sederet jendela tinggi di sebuah lantai atas dari salah satu gedung World Trade Center. Asap tebal mengepul dari lantai di bawah. Mereka tak punya tempat untuk lari.
Hari-hari ini sanak keluarga para korban berduyun-duyun berziarah. Di area itu itu kini 90 ribu ton puing-puing yang jadi sebuah makam besar tak bertanda, tak terduga-duga, tersembunyi. Dari arah Vesey Street, memandang beberapa sisa bangunan yang terhantar seperti rangka ikan pari raksasa yang terjemur, saya teringat seorang raja abad ke-20 yang berkata, ”Perlu waktu 20 tahun masa damai untuk menjadikan manusia; hanya perlu waktu 20 menit peperangan untuk menghancurkannya.”
Peperangan? Atau pembantaian? Apa pula bedanya, bagi mereka yang tak hadir untuk angkat senjata: penduduk sipil Hiroshima dan Nagasaki yang binasa oleh bom atom, orang dusun Vietnam di May Lai yang ditembaki tentara Amerika, orang Aceh yang dibunuhi TNI, orang Aceh yang ditembak GAM, orang Palestina yang diberondong peluru di Masjid Ibrahim oleh seorang Yahudi, orang Israel yang mati di sebuah restoran karena bom orang Palestina, dan seterusnya, dan seterusnya—juga 2.593 orang bukan Amerika, yang datang dari 65 negeri, yang hari itu hilang atau mati di World Trade Center. Termasuk seorang Indonesia yang ada di pesawat yang ditabrakkan itu.
”Dan kematian makin akrab.” Dari carik kertas berbahasa Arab yang ditemukan itu disediakan cara untuk mati yang salih dan ikhlas. Penyerahan, bahwa semuanya karena Allah? Sebagian begitu. Tapi ini penyerahan dengan sebuah paradoks. Pembunuhan besar hari itu adalah sebuah misi yang terencana, dengan tujuan yang bisa diukur hasilnya. Pada jam-jam itu manusia meletakkan diri sebagai pengendali, penakluk, pencapai sukses, seperti yang diproyeksikan oleh humanisme—yang melahirkan banyak prestasi dan banyak tragedi. Dalam instruksi berbahasa Arab itu, terbaca perintah untuk bergeming dalam membunuh, menguasai, dan menang. ”Salatlah malam harinya, dan memohonlah kepada Allah agar diberikan kepadamu kemenangan, kontrol, dan penaklukan.”
Dalam penaklukan itu, hidup dan mati memang dikalahkan, juga duka cita mereka yang di dunia. Dari sinilah para martir lahir, juga para algojo. Ada yang mengharapkan Taman Firdaus, ada yang memimpikan kekekalan nama sebagai pahlawan, ada yang meyakini masyarakat baru yang lebih baik. Ada yang untuk Tuhan, ada yang untuk Raja, ada yang untuk tanah air. ”Aku seorang Amerika,” seru orang Arizona yang menembak mati seorang Sheikh yang disangkanya seorang Islam beberapa hari setelah 11 September. ”Aku segera akan pergi keluar, untuk membentuk hari esok yang bernyanyi,” tulis Gabriel Péri, pemimpin komunis Prancis, dalam sepucuk surat pada bulan Juli 1942, sebelum ia mati di depan regu tembak Jerman.
Komunisme yang atheistis, agama yang menyembah Tuhan, keyakinan para prajurit kamikaze Jepang yang memuja Tenno, semangat seorang patriot Amerika, dengan jenis eskatologi masing-masing, memang menampik masa sekarang. Masa depan yang sempurna menghalalkan apa pun yang dibuat hari ini. Tuhan, atau Sejarah, menjanjikan, dan menentukan.
Mengagumkan memang iman yang seperti itu. Tapi, bagi yang yakin akan Tuhan dan surga, menggabungkan eskatologi dengan penghancuran adalah sebuah kontradiksi. Seseorang yang menafikan dunia seharusnya seorang yang membiarkan dunia dalam cacatnya. Bumi, ”dunia ini”, telah diabaikan. Maka, ganjil bila orang itu pada saat yang sama juga ingin meluluh-lantakkan apa yang buruk sekarang, seakan yakin bahwa dunia layak diperbaiki. Ganjil pula bila ia percaya kepada Tuhan yang mengatakan bahwa membunuh seseorang sama artinya dengan membinasakan seluruh umat manusia, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang tak menyesali apa yang Ia ciptakan sendiri.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini