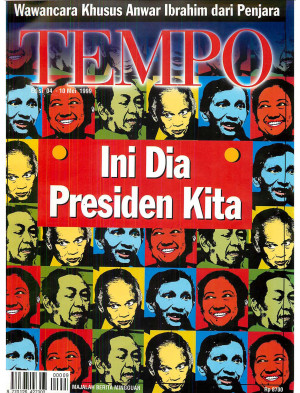Gairah untuk menyambut pemilihan umum punya jalan pikirannya sendiri. Ada kepentingan yang hendak dicapai, yaitu kesempatan untuk ikut berkuasa melalui cara demokratis. Tetapi, di samping itu?masih berhubungan dengan pemilu?terdapat juga pilihan rasional lain, yang menghasilkan sikap yang berbeda. Titik tolaknya adalah kepentingan juga, tetapi yang sifatnya langsung dan merupakan kebutuhan hidup yang lebih utama, yaitu keselamatan diri pribadi dan keluarga. Dari sudut ini, peristiwa pemilu lebih dilihat sebagai risiko keamanan, bukan pembawa kesempatan berdemokrasi. Karena itu, ramai-ramailah orang hengkang mencari tempat lebih aman, sampai ke luar negeri pun jadi.
Mengapa menghindari pemilu dengan mengeluarkan ongkos mahal itu termasuk pilihan rasional? Pada asasnya, tiap putusan yang diambil untuk lepas dari ancaman maut sudah pasti didasari pertimbangan akal. Kalau seseorang memperhitungkan bahwa kemungkinan pecah huru-hara cukup besar, dan dia yakin akan tergolong jadi korban sasaran, apa yang harus dilakukannya untuk menghindari itu? Pengalaman menunjukkan, aparat keamanan tidak berdaya melindungi warganya di saat keguncangan terjadi. Rumah terbakar, harta benda musnah, nyawa melayang: tak ada ketentuan bilamana serta di mana munculnya, dan siapa yang akan dapat giliran jadi korban berikutnya.
Perlindungan dan bantuan? Sedikit yang bisa diharapkan selain yang diusahakan sendiri. Dan jangan pura-pura tidak tahu, dalam hampir setiap kekacauan masal dengan kekerasan, warga keturunan Tionghoa berada di urutan pertama sasaran brutalitas para pengamuk. Kalau memang tergolong jadi calon korban, dalam kondisi tak bisa mengharapkan perlindungan keamanan, pilihan apa yang lebih baik kecuali menjauh?
Apa yang harus ditimbang? Di satu sisi, nyawa yang dipertaruhkan. Di sebelah lainnya, ada risiko biaya, sambil menanggung rugi karena menutup usaha, ditambah biaya nonmaterial lainnya, seperti dicap tak punya rasa kebersamaan, dituduh kurang rasa peduli bernegara karena tidak berpartisipasi dalam pemilu. Mana yang lebih berat? Apabila akhirnya pilihan jatuh pada penyelamatan jiwa raga, itu memang hasil pertimbangan yang bisa diterima akal.
Kalau ditanya, tak seorang pun bisa memastikan seberapa besar ancaman fisik itu nyata ada. Namun, setelah Banyuwangi, Ketapang, Ambon, Sambas, Ciamis, Lhokseumawe, Jepara, belum lagi tragedi 14-15 Mei 1998, yang tak kunjung diusut tuntas, siapa sudi percaya pada jaminan yang cuma didasarkan pada kira-kira saja? Berandai-andai tentang kemampuan polisi dan tentara untuk mencegah atau mengatasi kerusuhan terlalu tinggi risikonya. Tak ada bukti yang menenteramkan mengenai hal itu.
Sebenarnya agak berlebihan untuk memakai istilah eksodus bagi gelombang penduduk yang keluar menghindari masa kampanye pemilu ini. Dari sudut jumlah dan sifat perpindahannya yang sementara, kejadian ini belum termasuk ''migrasi paksaan" dalam arti sebenarnya. Memang, dikabarkan puluhan ribu, mungkin di atas seratus ribu, warga kota-kota besar, terutama kaum peranakan Tionghoa, akan menuju Singapura, Australia, bahkan ke Amerika Serikat dan Eropa, atau sekadar ke pulau Bali (lihat halaman 18), terutama mulai minggu ketiga bulan Mei ini. Cukup banyak untuk dijadikan berita.
Tetapi tak ada pemandangan seperti barisan panjang penduduk etnis Albania di jalan-jalan Kosovo, atau geladak kapal laut yang dijejali warga suku Bugis dan Buton di pelabuhan Ambon, atau sekoci penuh sesak penduduk suku Madura yang berlayar ke luar Pontianak, atau kepanikan ribuan penduduk yang mengungsi dari Cot Murong di Lhokseumawe. Derajat keterpaksaan hengkang pemilu ini sama sekali tidak sebanding dengan urgensi eksodus di tempat-tempat itu. Namun, ancaman yang dibayangkan itu ternyata hampir sama efek gertaknya dengan ancaman yang sudah di depan mata. Ada rasa tidak aman yang tak teratasi, sehingga orang lari.
Rasa takut ini tak dapat dikatakan hanya mengada-ada. Banyak warga asing, swasta maupun anggota kedutaan dan keluarganya, yang akan terbang ke luar Indonesia semasa kampanye, yang dimulai pekan depan. Selain terjadi pemborosan devisa dan inefisiensi ekonomi, yang lebih penting ialah kesan yang ditimbulkan oleh kabur berbondong-bondong ini. Ini merupakan pertanda pemerintah tak dipercaya mampu menjaga kestabilan dan menjamin keamanan.
Tetapi, harus disadari, ketidakpercayaan juga ada yang dialamatkan pada masyarakat Indonesia sendiri, yaitu pada ketidakmampuannya untuk mengorganisasi diri, membangun kepatuhan pada ketertiban dengan sukarela. Padahal, sangat banyak partai-partai politik yang telah didirikan, yang seharusnya bisa jadi penyalur dan pengarah tingkah laku warga masyarakat. Alasan ketidakpercayaan lainnya ialah karena masyarakat masih belum berhasil mengurangi, kalau tidak menghapus, prasangka etnis terhadap keturunan Tionghoa.
Arus keluar menghindari kerusuhan sudah melewati batas untuk mungkin dibalikkan lagi. Kemungkinan yang masih ada ialah membuktikan bahwa kerusuhan massal, dengan banyak korban, bisa dicegah. Sukar untuk mengharap pemerintah akan bisa kreatif, tetapi jalan untuk itu bukan tidak ada. Sebenarnya, yang lebih ditantang ialah partai-partai politik untuk membuktikan kompetensinya berorganisasi. Apakah pengorganisasian vertikal, dari tingkat pusat sampai ke cabang dan ranting, benar punya arti untuk mengatur anggotanya?
Jika benar, tentu tidak sukar untuk berkonsensus antarpartai, lalu melaksanakan apa yang dimufakati. Jadi, bila semua sepakat menghindari kekerasan, pemilu yang damai bukan mustahil untuk diselenggarakan bersama. Tinggal soal organisasi dan kepemimpinan. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Kalau berhasil, arus balik dari mereka yang menyingkir pun akan diisi dengan perasaan yang lebih tenteram.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini