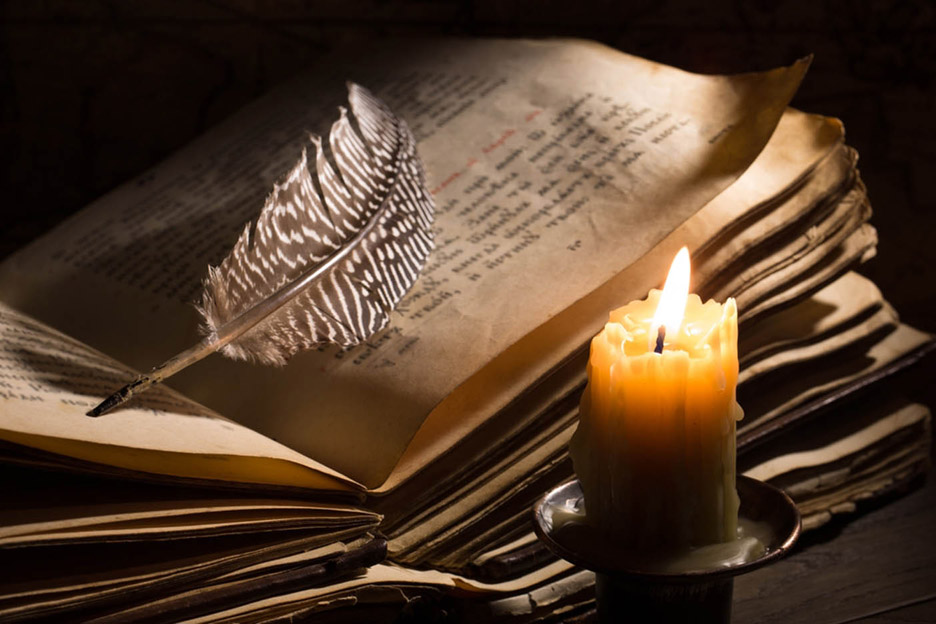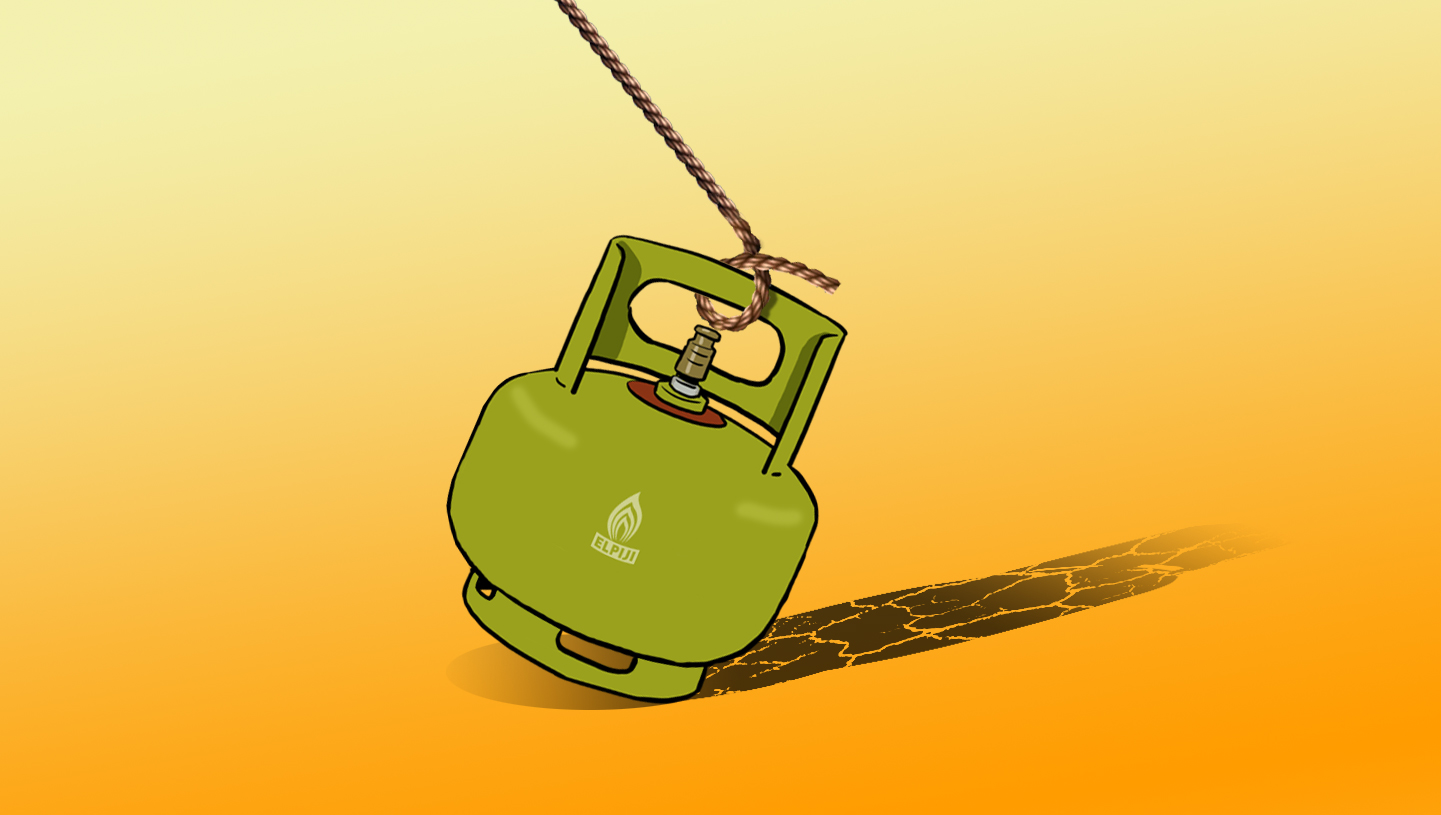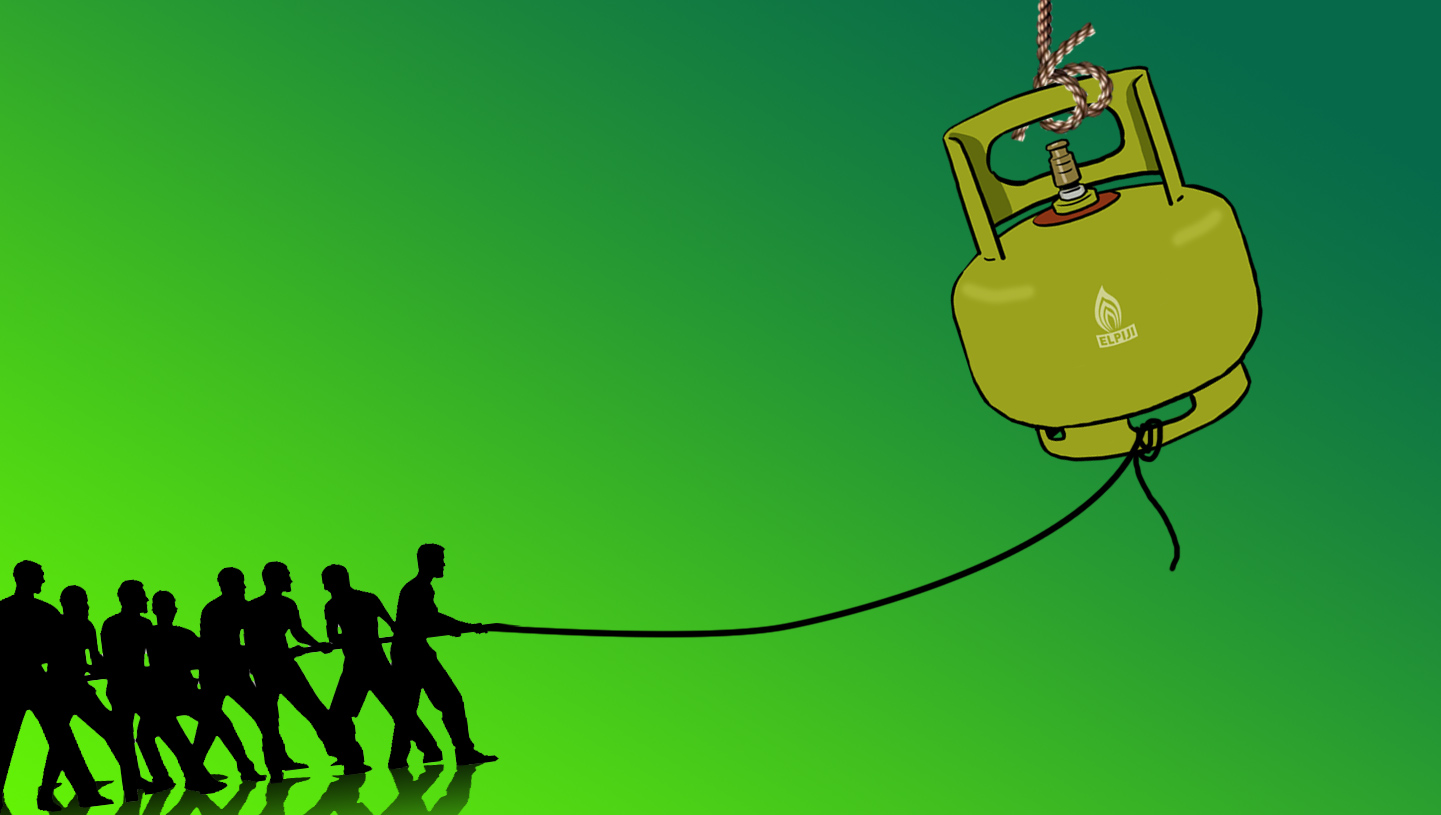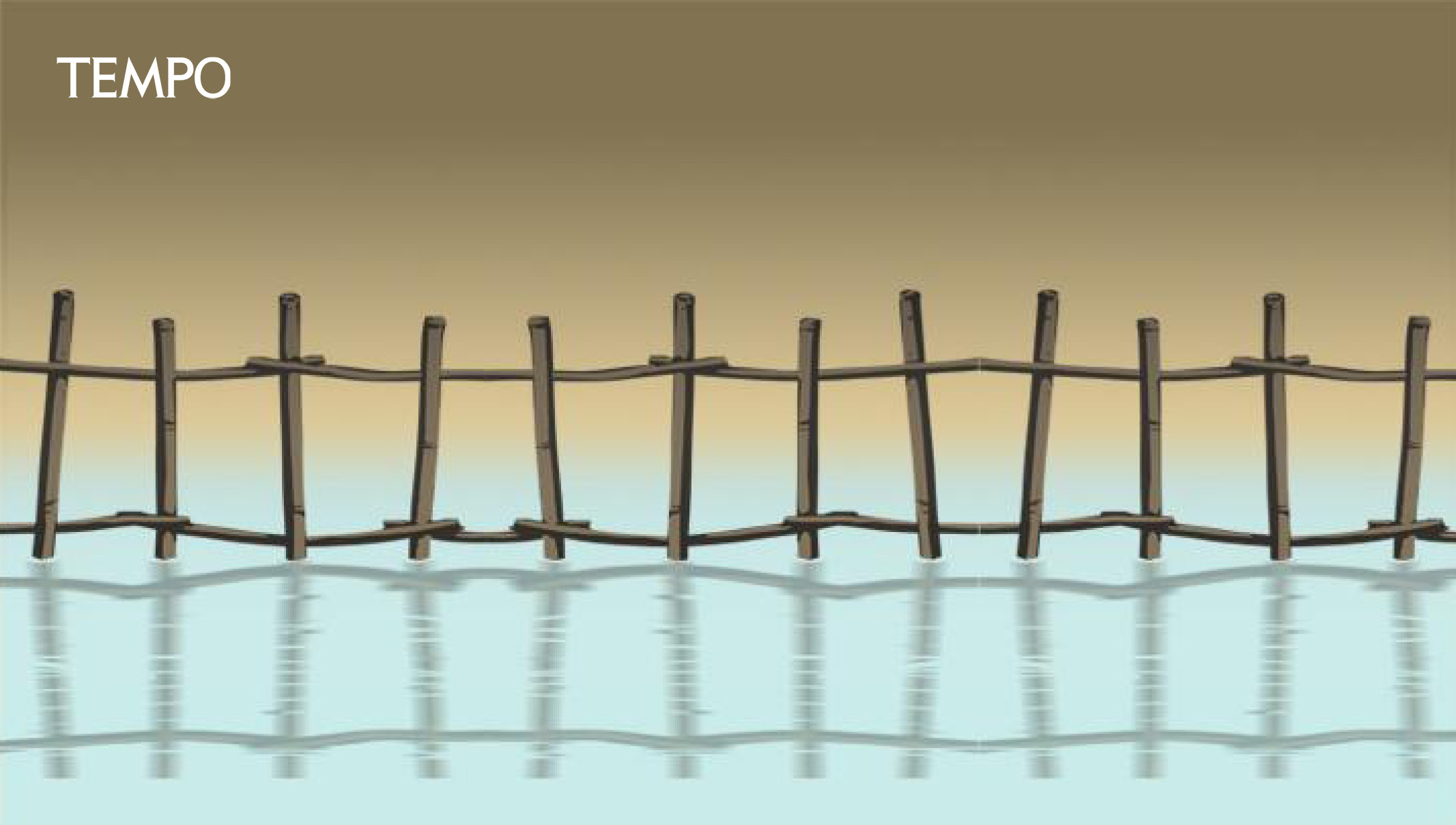Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Tragedi Kanjuruhan merupakan hari tergelap dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Kerusuhan suporter sepak bola dapat dicegah dengan kontrol sosial.
Sejumlah penelitian telah menunjukkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan.
Bagong Suyanto
Dekan FISIP Universitas Airlangga
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kerusuhan yang pecah di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu, 1 Oktober lalu, disebut-sebut sebagai "hari tergelap sepanjang sejarah sepak bola Indonesia". Kesimpulan itu bukan tanpa alasan. Dalam tragedi di akhir pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu dilaporkan sedikitnya 187 suporter dan dua polisi tewas. Bukan tidak mungkin jumlah korban yang tewas akan bertambah, mengingat sebagian korban masih dalam kondisi kritis di rumah sakit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jumlah korban tewas dalam kasus kerusuhan di Kanjuruhan itu termasuk yang terbanyak dalam sejarah sepak bola Indonesia. Menurut data Save Our Soccer (SOS), sebelum tragedi Kanjuruhan, total ada 86 suporter sepak bola Indonesia yang meninggal selama 1995-2022. Dengan demikian, jumlah korban tewas di Malang ini jauh melampaui total korban tewas dalam sejarah sepak bola Indonesia selama hampir tiga dekade sebelumnya.
Pengendalian Sosial
Apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mencegah kerusuhan seperti ini tidak terjadi lagi? Secara teoretis, untuk mencegah ulah suporter yang ingin dan telah melanggar tertib sosial tidak berkembang lebih parah, aparat dan masyarakat perlu menjalankan pengendalian sosial (social control) terhadap individu-individu anggotanya.
Menurut Peter L. Berger (1978), yang dimaksudkan dengan pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan aparat keamanan dan masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang. Adapun menurut Roucek (1965), pengendalian sosial merupakan istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak terencana untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal.
Dalam setiap pertandingan, aparat dan pengurus suporter sudah barang tentu tidak sekali-dua kali mensosialisasi untuk mengajak suporter tidak bertindak anarkistis. Tapi sosialisasi yang berkali-kali tidak menjamin hal itu bakal diikuti perilaku tertib suporter sebagaimana diinginkan.
Berbicara idealnya, ketika sosialisasi sudah dilakukan dan suporter dianggap telah memahami bagaimana harus bertingkah laku, norma-norma sosial bisa dikatakan telah dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri (self-enforcing). Namun, dalam kenyataannya, bagi suporter tertentu atau pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu, daya self-enforcing dari norma-norma itu sering kali melemah atau bahkan hilang sama sekali.
Para suporter pada saat situasi tertentu mungkin saja merasa bahwa mengikuti norma tertentu itu justru tidak bermanfaat (rewarding) dan bahkan, sebaliknya, mengalami kerugian. Seorang suporter, yang merasa harus membela tim kesayangannya, bukan tidak mungkin akan bertindak membabi buta dengan melakukan apa pun agar tim kesayangannya menang. Secara garis besar, dua faktor yang menyebabkan suporter kemudian berperilaku anarkistis dan menyimpang dari norma yang berlaku adalah sebagai berikut.
Pertama, berkaitan dengan fanatisme suporter terhadap tim kesayangannya. Suporter yang merupakan penggemar fanatik pada sebuah kesebelasan tentu tidak akan mudah menerima keadaan ketika timnya kalah. Dalam kasus suporter Arema di Kanjuruhan, sebagian suporter dilaporkan tidak hanya mengejar tim kesebelasan lawan, tapi juga melampiaskan kekesalan mereka kepada tim kesayangannya sendiri karena kalah. Suporter yang fanatik niscaya tidak akan bersikap rasional karena yang berkecamuk di benaknya adalah dorongan untuk selalu memperjuangkan kemenangan timnya dalam segala situasi.
Kedua, berkaitan dengan berkembangnya mentalitas "sok jagoan", yang biasanya menjadi acuan bagi suporter dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Seorang suporter niscaya akan merasa bukan suporter sejati kalau hanya bersikap lembek ketika membela nama baik tim kesayangannya. Sudah lazim terjadi, seorang suporter akan terdorong melakukan aksi yang ekstrem dan anarkistis untuk mendemonstrasikan siapa mereka di hadapan teman-teman sesama suporter.
Bagi suporter yang "sok jagoan", tidak penting apakah mereka tengah berhadapan dengan suporter lawan atau tidak. Sebab, yang terpenting adalah bagaimana mereka memperlihatkan bahwa dirinya lebih nekat atau lebih ekstrem dibanding teman-temannya sendiri. Kontestasi yang dihadapi suporter tidak harus diperlihatkan ketika menghadapi suporter lawan, tapi juga kontestasi mereka dengan sesama suporter dalam kelompoknya.
Deteksi Dini
Untuk mencegah agar kasus kerusuhan seperti tragedi Kanjuruhan tidak terulang, salah satu upaya kunci yang perlu dikembangkan adalah bagaimana merancang dan melaksanakan mekanisme deteksi dini. Ketika ulah suporter sudah keburu beringas, niscaya akan membutuhkan energi dan sumber daya yang jauh lebih besar dari aparat keamanan untuk mengatasinya.
"Mencegah api keburu besar" harus menjadi prinsip utama dalam upaya penanganan ulah suporter. Belajar dari sejumlah hasil yang telah dilakukan para ahli, seperti Clary (1977) serta Horton dan Hunt (1984), ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah kerusuhan suporter. Pertama, tindak kekerasan dalam pertandingan olahraga lebih cenderung terjadi pada malam hari daripada siang atau sore hari. Pada malam hari, pencandu sepak bola atau suporter yang fanatik biasanya memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk meminum minuman keras dan melakukan aksi yang anarkistis.
Kedua, potensi kerusuhan umumnya lebih besar terjadi ketika tim yang bertanding adalah musuh bebuyutan yang sudah bertahun-tahun diwarnai konflik. Rekam jejak siapa saja tim yang bertanding niscaya harus menjadi pertimbangan untuk menentukan kekuatan aparat yang berjaga selama pertandingan berlangsung.
Ketiga, kerusuhan dan ulah anarkistis suporter cenderung lebih sering terjadi setelah pertandingan usai daripada sebelum pertandingan dimulai. Bagi suporter yang tim kesebelasannya kalah, mereka umumnya lebih mudah terpancing melakukan kerusuhan untuk melampiaskan kekecewaannya sehingga penjagaan aparat seyogianya lebih dikonsentrasikan pada wilayah tempat suporter tim kesebelasan yang kalah berada.
Di Negeri Abang Sam, Bryan dan Horton (1978) memberikan saran agar lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner, diputar setelah pertandingan berakhir. Saran ini ada baiknya juga dicoba dilakukan dalam laga sepak bola di Indonesia.
PENGUMUMAN
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo