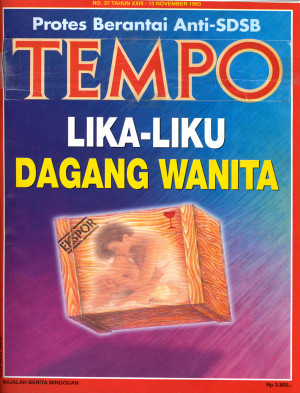GOLKAR nampaknya selalu bisa memberikan harapan, tapi benarkah kita butuh demokrasi? Di tahun 1971 ada pemilihan umum: itu yang kedua sejak Republik Indonesia berdiri. Yang pertama diadakan di tahun 1955, dan sejak itu tak ada apa-apa, sampai terjadi ledakan besar yang menumpahkan darah di tahun 1965. Lalu lahir ''Orde Baru''. ''Orde Baru'' membutuhkan legitimasi yang tak cuma teriakan massal anti-PKI. Ia tak hanya menoleh ke masa lampau yang buruk, tetapi juga menggagas: apa yang harus dilakukan untuk Indonesia, dengan cara yang lebih baik. Untuk itulah diadakan pemilihan umum 1971, dan untuk itulah Golkar dibangun. Maka, Golkar nampaknya selalu bisa memberikan harapan, terutama di masa peralihan, tapi sebenarnya tak jelas apakah kita berpikir tentang demokrasi. Sebuah contoh. Di hari Jumat 4 Juni 1971, Dewan Pers yang baru dilantik di Jakarta. Ketika jeda, dalam suasana di sekitar hari pemilihan umum itu, salah seorang anggota Dewan Pers yang baru, Mochtar Lubis, berbicara kepada wartawan. Katanya (sebagaimana dikutip dalam buku Sedjarah Pergerakan Pemuda Indonesia yang disusun oleh Peter Tomasoa dan ejaannya saya perbarui): ''Satu-satunya jalan untuk memperbaiki negara ini ialah dengan memenangkan Golkar.'' Mochtar Lubis, tokoh dunia wartawan yang tersohor itu, bahkan dikutip mengatakan, ''Semua partai harus dibunuh.'' Sebab, ujar Mochtar Lubis pula, selama 25 tahun ini (ia berbicara di tahun 1971), apa yang telah diperbuat partai? Maka, Golkar yang tak dianggap sebagai partai model lama jadi satu-satunya harapan. Saya belum tahu pasti sejauh mana kutipan itu akurat. Tapi tidak mengherankan bila kita dengar sikap seperti itu: di kalangan sebagian cendekiawan Indonesia yang bersuara sejak tahun 1966, suatu perubahan besar, terutama dengan semangat modernisasi, memang dicita-citakan, tetapi demokrasi tak selamanya masuk dalam agenda. ''Negara kita ini masih feodal. Jadi, untuk perbaikan perlu kekerasan,'' kata Mochtar Lubis dalam kutipan di buku Peter Tomasoa itu pula. Modernisasi, apa boleh buat, memang mengandung paradoks. Di satu pihak, semangatnya adalah untuk meninggalkan suatu keadaan mandek yang terasa tenteram, tapi menurut anggapan kaum modernis juga suatu keadaan tua dan abai. ''Telah kutinggalkan kau, teluk yang tenang tiada beriak,'' tulis S. Takdir Alisjahbana, pemikir pelopor modernisasi Indonesia yang tak pernah lekang itu, di dalam sebuah sajak di tahun 1930-an. ''Teluk yang tenang'' itu, kehidupan masyarakat yang dikeloni tradisi, lelap, tapi juga lalai itu harus ditaruh di masa lampau, lantaran ia tak bergerak oleh datangnya tantangan sebuah zaman yang berubah. Zaman modern harus dijelang, untuk membebaskan orang Indonesia dari takhayul, dari ketidakmampuannya berpikir rasionil, bersikap lugas, menghargai waktu dan materi dan segala sifat ''manusia Indonesia'' yang sering dicapkan kepada kita oleh sebagian kaum ''Orientalis'' Barat dan kaum ''Orientalis'' dalam negeri. Di lain pihak, modernisasi menuntut semangat baru, terkadang ketidaksabaran baru yang sebenarnya tak ada hubungannya dengan pembebasan. Modernisasi memang melahirkan organisasi pemerintahan dan hukum yang konsisten, rapi, dengan asas yang universal, yang bisa mengatasi pelbagai ragam budaya, manusia, kasus. Modernisasi membutuhkan apa yang disebut Weber sebagai Zweckrationalitat, yang merancang cara-cara yang efisien untuk memperoleh hasil. Maka, yang berkibar adalah gairah kepada faedah dan kepastian. Yang nampak tak berguna, yang nampak tak efisien, yang ganjil-ganjil dan tak bisa diatur dalam rencana dan kalkulasi, harus dimarjinalkan. Atau akan terpaksa minggir. Partai politik, yang di awal tahun 1960-an dianggap merupakan macam-macam ikatan kesetiaan yang ''tak rasionil'' (di masa itu kata ''irrationil'' dianggap berbau ''Orde Lama''), sebab itu merupakan centang-perenang yang mengganggu. Golkar adalah harapan. Maka, dalam diri Golkar juga ada paradoks, seperti dalam setiap proyek modernisasi. Kita mengharapkan pembaruan, tapi juga kita menghendaki sesuatu yang bisa diprediksikan. Maka, kita prioritaskan hasil dan faedah, dan kita desakkan kerapian. Kita pun menggandrungi perencanaan dan teknik, merindukan kepastian dalam iman, menyukai keseragaman dalam doktrin dan baju dan mencurigai apa yang berbeda, apalagi berbeda secara ramai: kita menganggapnya ganjil, suatu ''kelainan'' yang juga berarti anomali atau disorder. Artinya: harus dibereskan, kalau perlu (dalam hiperbola ala Mochtar Lubis): ''dibunuh''. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini