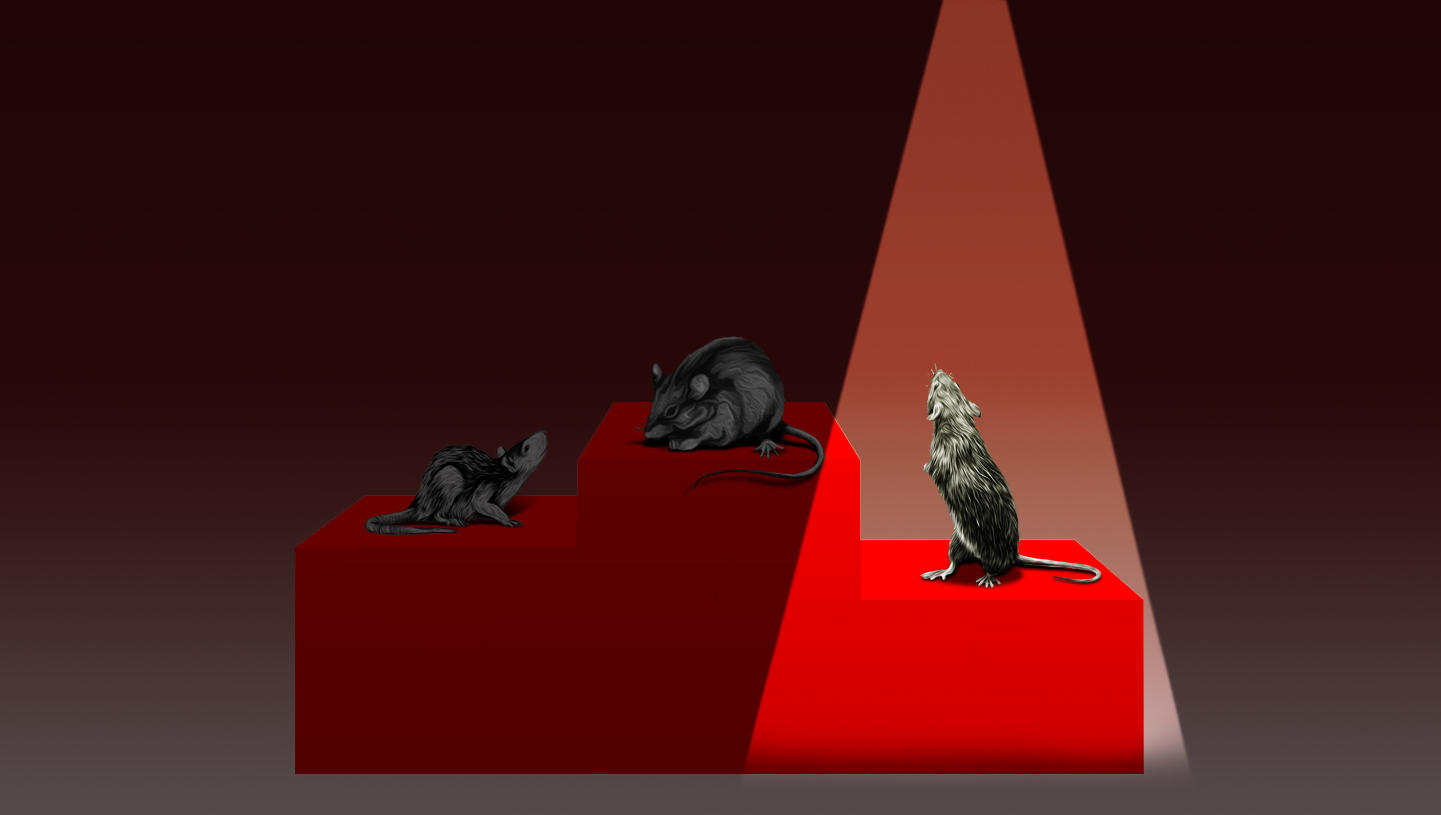Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEJAK Sabtu dinihari dua pekan lalu, Paris bukan lagi sekadar nama kota. Metropolitan dengan tiga juta penduduk itu berubah menjadi simbol keteraniayaan kemanusiaan—dengan segala duka dan kepedihannya.
Tiga gerombolan bersenjata melakukan serangan animalistik di tiga lokasi yang penuh manusia. Total 132 korban jiwa jatuh dan setidaknya 350 orang terluka. Presiden Prancis Francois Hollande, yang berada di salah satu lokasi penyerbuan—dan mungkin sekali merupakan sasaran utama para teroris—luput dari maut. Inilah serangan teroris terburuk di Prancis setelah Perang Dunia II.
Hanya dalam hitungan jam, dan tak jauh dari perkiraan, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Pengakuan ini mengiris perasaan keberadaban kita karena, untuk kesekian kalinya, simbol-simbol keberagamaan digunakan untuk sepak terjang yang berlawanan dengan ajaran agama apa pun. Bisa dimaklumi ketika Hollande langsung mengumumkan perang terhadap ISIS dan meminta persetujuan parlemen memberlakukan keadaan darurat untuk tiga bulan ke depan.
Menarik sekali pernyataan seorang mantan anggota Badan Intelijen Antiteror Prancis (DGSE): aparat intelijen sesungguhnya tidak pernah siap betul menghadapi serangan teroris. Keterlibatan Prancis menggempur sarang ISIS di Suriah tidak disertai kewaspadaan terhadap tindakan "balas dendam" yang mungkin terjadi di dalam negeri. Pada awal tahun ini, misalnya, tiga pria bersenjata menyerbu kantor redaksi mingguan Charlie Hebdo dan membunuh 12 orang. Dua hari kemudian, sepasang suami-istri asal Aljazair menyandera pengunjung toko khusus kaum Yahudi dan menewaskan empat orang. Kedua peristiwa itu terjadi di Paris.
Eropa memang sedang diguncang ISIS. Beberapa hari sebelum teror Paris, sebuah pesawat penumpang milik Rusia jatuh di Sinai, dan ISIS mengaku bertanggung jawab. Sebaliknya, ditengarai sekitar 6.000 warga negara Eropa menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok militan di Timur Tengah. Sebagian besar bisa melakukan perjalanan ulang-alik dari dan ke Eropa. Lebih dari 500 warga negara Prancis bergabung dengan ISIS. Separuh di antaranya sudah pulang ke Prancis.
"Perang melawan terorisme", seperti yang dicanangkan Francois Hollande—dan didukung penuh Barack Obama dan Vladimir Putin—merupakan sesuatu yang niscaya. Tapi lebih penting dari itu adalah "perang melawan akar terorisme". Tindakan "balas dendam", apalagi secara membabi-buta, tidak akan menyelesaikan masalah. Serangan "balas dendam" Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak, pada Maret 2003, justru memicu perang berkepanjangan. Teror Paris juga tak bisa digunakan sebagai dalih menolak imigran yang sebagian besar berasal dari wilayah perang yang melibatkan pula negara-negara Eropa—dan Amerika Serikat.
Dua di antara "akar terorisme" adalah kebodohan dan kelumpuhan komunikasi. Diperlukan gerakan yang meyakinkan bahwa terorisme, apa pun bentuknya, berasal dari "ideologi sesat" yang sangat berbahaya. Karena itu, pertanyaan penting yang harus dijawab: mengapa "ideolog sesat"—dan terbelakang—itu masih laku dijual justru di dunia yang seyogianya makin beradab dan makin berkemanusiaan.
Teror Paris membangkitkan kebersamaan global dunia beradab. Kebersamaan itu juga harus menggalang kewaspadaan karena terorisme bisa muncul di sekitar kita. Apalagi, menurut Kepala Kepolisian Daerah Jakarta, satu di antara pelaku teror Paris pernah tinggal di sini, di Bandung, selama tak kurang dari tiga tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo