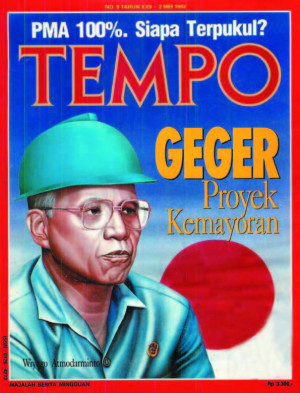JIKA salah satu elemen penting demokrasi adalah pemilihan umum, sistem politik yang sering dicap sebagai produk Barat itu lebih tua umurnya di pedesaan daripada di tingkat nasional. Pada masa pemerintahan (Barat) Belanda, yang umurnya lebih panjang dari kemerdekaan Indonesia, tak ada satu pun catatan yang menunjukkan pemilihan umum pernah dilaksanakan. Dan pada masa Indonesia merdeka, pemilu baru dilaksanakan pada tahun 1955. Tapi di pedesaan, seperti yang terjadi di Ciledug, Cirebon, sistem yang begitu maju ini ternyata telah dilaksanakan setidak-tidaknya pada 1916. Pada hari "H"nya -- demikianlah dicatat oleh Sewaka, seorang amtenar jebolan OSVIA pada 1915, yang kelak (1951) menjadi Menteri Pertahanan RI -- para jago calon kepala desa telah duduk di kursi masing-masing di hadapan panitia pemilu dan massa rakyat. Seraya memegang simbolnya masing-masing -- bendera dengan warna tertentu atau dedaunan atau buah-buahan -- dengan rasa berdebar menatap bumbungan yang berfungsi sebagai kotak suara. Ke dalam bumbungan yang di atasnya telah diletakkan simbol masing-masing jago itulah biting (lidi), alat penghitung suara, dimasukkan rakyat pemilih. Seperti di Amerika, para calon kades ini bukan saja harus terdiri dari orang kaya -- karena ia harus mampu menyediakan dana untuk membujuk rakyat -- tetapi juga banyak pihak berkepentingan terhadap pemilihan itu. Di sini, seperti disebut Sewaka, para jagoan atau pedagang-pedagang Cina, bahkan pabrik gula setempat, menaruh kepentingan politik dan ekonominya terhadap jagonya masing-masing. Desa-desa Jawa awal abad ke-20 dengan demikian telah terlibat dalam sistem pemilu yang bersifat "kapitalistis", ketika faktor-faktor ekonomi telah dipertaruhkan untuk memperebutkan kekuasaan politik. Dengan sedikit melebih-lebihkan, bisalah dikatakan bahwa sistem pemilu ini mengandung selera "demokrasi liberal". Dilihat dari sudut ekonomi, Ciledug memang telah mengalami proses "kapitalisasi". Gejala ini hampir menjadi gambaran umum desa-desa Jawa masa itu. Setidak-tidaknya, itulah yang terlihat pada Desa Ngablak, Pati. Di desa terakhir ini proses kapitalisasi bahkan tercatat dengan rapi dari urutan tahun 1869 sampai 1929, berkat penelitian D.H. Burger pada awal tahun 1930-an. Bayangkan, sistem tebasan, suatu ciri kapitalisme desa yang meruyak pada 1970-an seperti dilihat William Collier awal Orde Baru, telah terlihat tanda-tandanya justru pada 1869 di Desa Ngablak. Struktur patronclient relationship yang merupakan ciri nonkapitalistik desa telah mulai digerogoti sejak akhir abad ke-19 itu. Ciri kapitalistik Ciledug terutama ditandai oleh kehadiran pabrik gula. Produk gula di Jawa merupakan salah satu hal terpenting bagi perekonomian kolonial. Bukan saja karena ia merupakan "industri pelopor" kedua setelah kopi -- ekspornya mulai menyusut pada 1880. Tapi juga karena komoditi itu merupakan 10 persen dari produksi dunia pada 1920 dan menghasilkan pajak ekspor -- seperti dicatat Furnivall pada tahun 1944 -- lebih dari satu juta gulden. Gula dengan demikian telah menjadi "tambang emas", karena hasil ekonominya melebihi produksi lainnya, termasuk mineral. Bagi massa tani Ciledug, seperti juga massa tani Jawa lainnya, produksi gula punya arti tersendiri. Bukan saja melalui produksi itu sistem ekonomi uang telah diciptakan, juga secara tak langsung telah mengaitkan para petani itu ke dalam jaringan kapitalisme dunia. Massa yang parochial yang hidup di "sudut-sudut dunia" itu justru menjadi rentan terhadap dinamika ekonomi internasional. Depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, misalnya, telah melahirkan kemiskinan masal desa-desa Jawa. Yang terpenting adalah pengaruh kapitalisme gula ini terhadap tingkah laku politik dan birokrasi kolonial. Ia sedikit banyak telah menciptakan selera "liberal" dalam pemilu tingkat desa seperti yang terlihat di Ciledug. Tapi di atas itu sang industri juga telah menciptakan sejenis sistem kontrol politik tertentu terhadap kaum birokrat (asisten wedana atau wedana). Inilah -- kita kembali kepada coratcoret Sewaka ketika ia bekerja di sebuah kantor controleur industri tebu -- yang terjadi di Sindanglaut, Cirebon. Dalam posisinya sebagai "industri pelopor", komoditi gula telah menjadi "anak emas" kolonial. Karena itu, kaum birokrat harus menanganinya secara ekstrahati-hati. Setiap waktu harus diketahui berapa lembar yang ditanam, berapa yang sedang dan telah dipotong. Setiap pelanggaran atau pencurian haruslah dicatat dengan seksama. Dalam posisinya sebagai staf controleur, Sewaka bahkan harus menelepon para administrateur pabrik gula setiap pagi, untuk mengetahui mrnit-menit perkembangan industri itu. Suatu sistem birokrasi ketat yang bertumpu pada kapitalisme gula telah dikembangkan secara sistematis. Di bawah kontrol langsung birokrasi negara kolonial modern pada birokrat yang berhubungan dengan industri gula ini memang layak berdebardebar. Mereka telah menjadi tumpuan atas keberlangsungan jalannya sistem perekonomian itu. Maka, kedudukan mereka sangat bergantung pada bekerja atau tidaknya perekonomian gula tersebut. Tinggi rendahnya tingkat pencurian atau kebakaran atau besar kecilnya jumlah kuli yang datang ke pabrik gula secara langsung menentukan konduite mereka. Jika kita mengaitkan persoalan historis itu kepada masa kini melalui pepatah Prancis, l'histoire se repete (sejarah berulang), kita memang tak melihat penjelmaan selera "liberal" pada pemilu Ciledug awal abad ke-20 itu dalam pentas pemilu nasional masa Orde Baru. Setidak-tidaknya, sisa-sisa bentuk kontrol birokrasi ekonomi gula yang telah terpatrikan dalam sejarah itu sedikit masih menjelma di masa kini. Para pejabat biasanya akan berdebar-debar setiap menjelang pemilu. Karena, seperti tertera di TEMPO, 14 Maret 1992, konduite mereka sangat ditentukan oleh berapa banyak sumbangan suara yang diasalkan dari wilayahnya masing-masing untuk kontestan tertentu. "Sensus politik" yang disinyalir berlangsung di beberapa tempat belakangan ini mungkin bisa kita baca sebagai penjelmaan-penjelmaan tak resmi dari gaya birokrasi gula masa lalu, ketika konduite para pejabat pemerintahan dipertaruhkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini