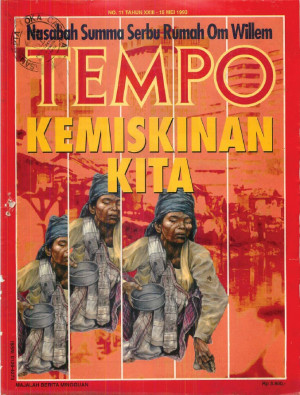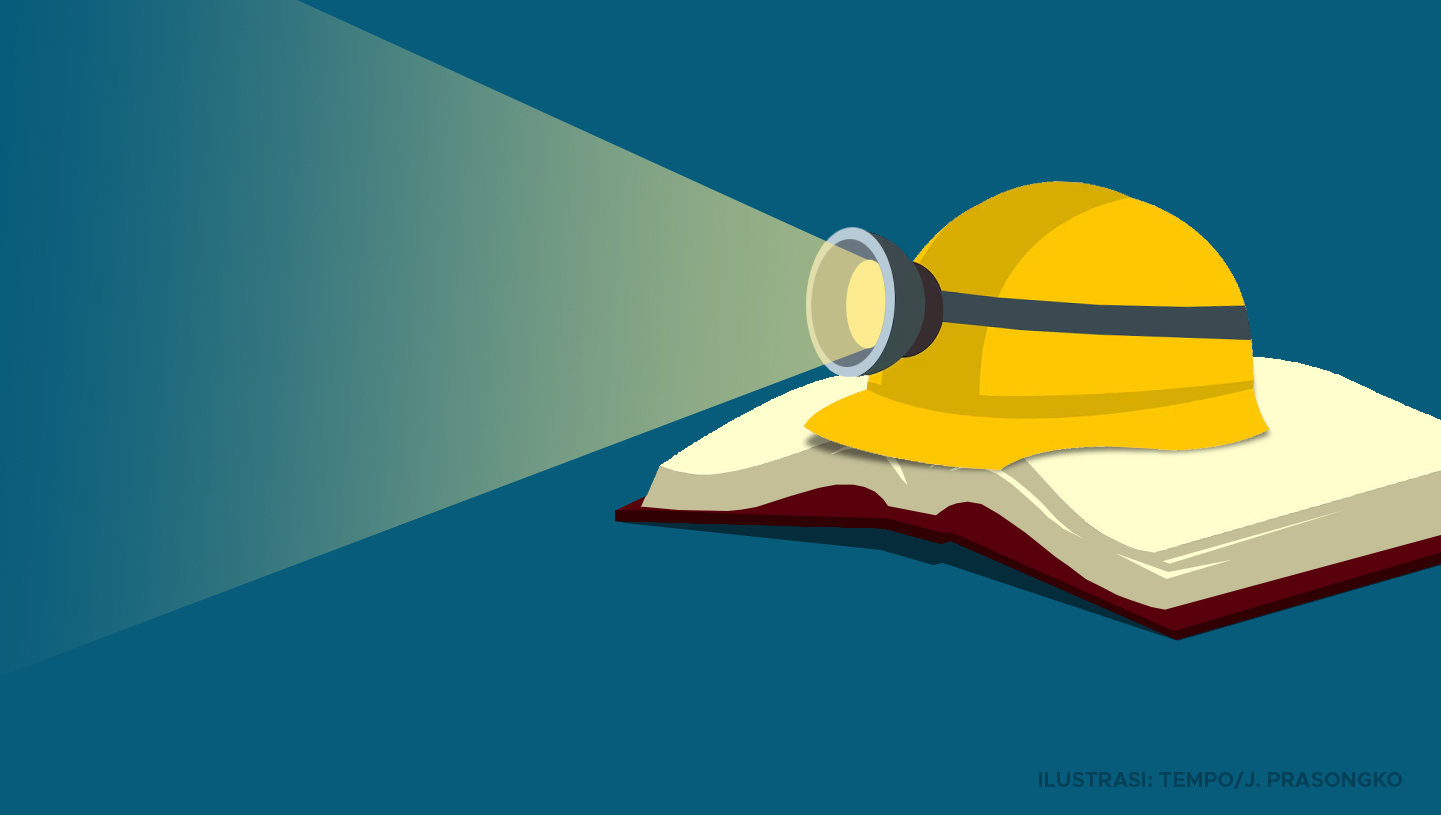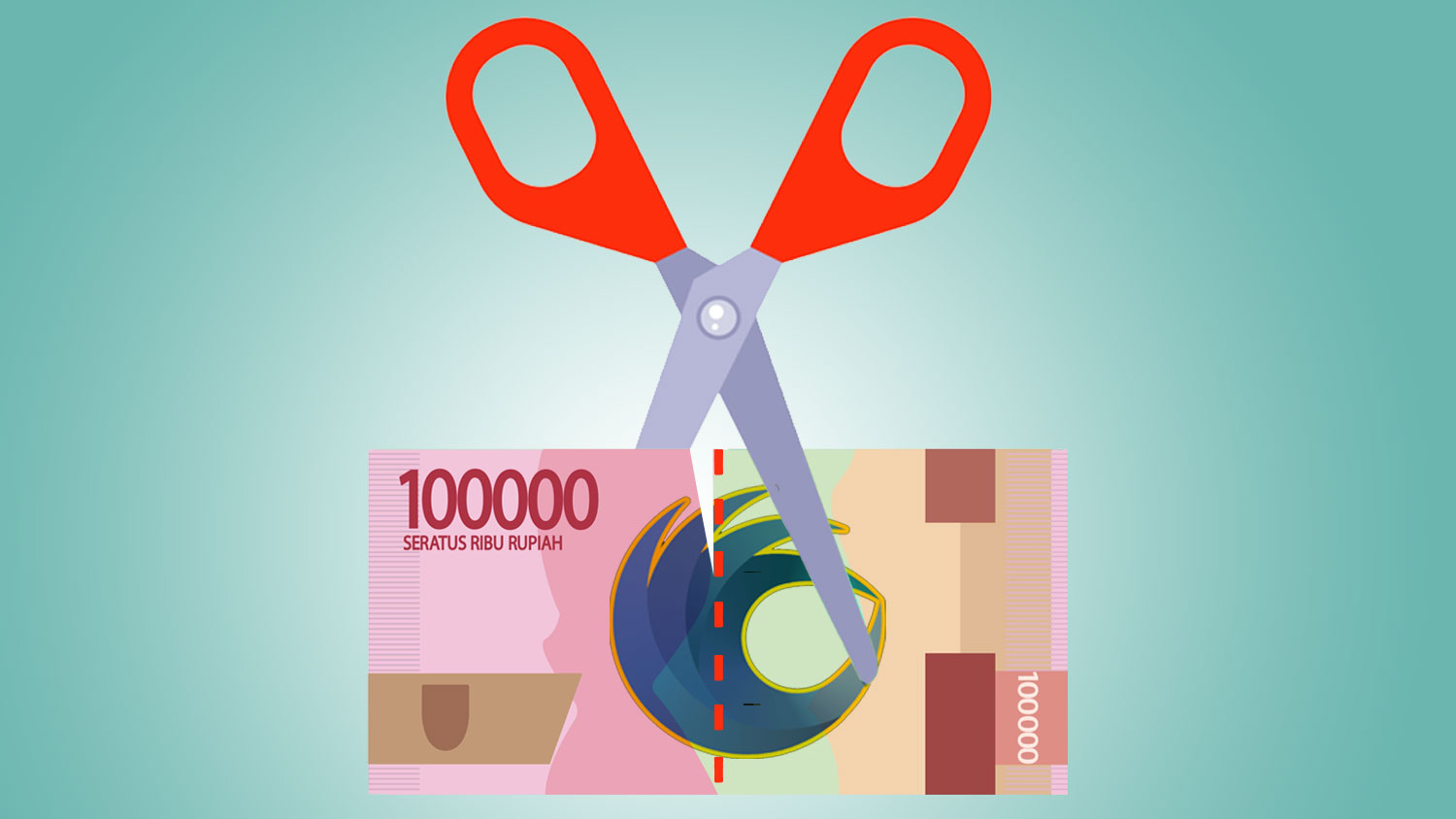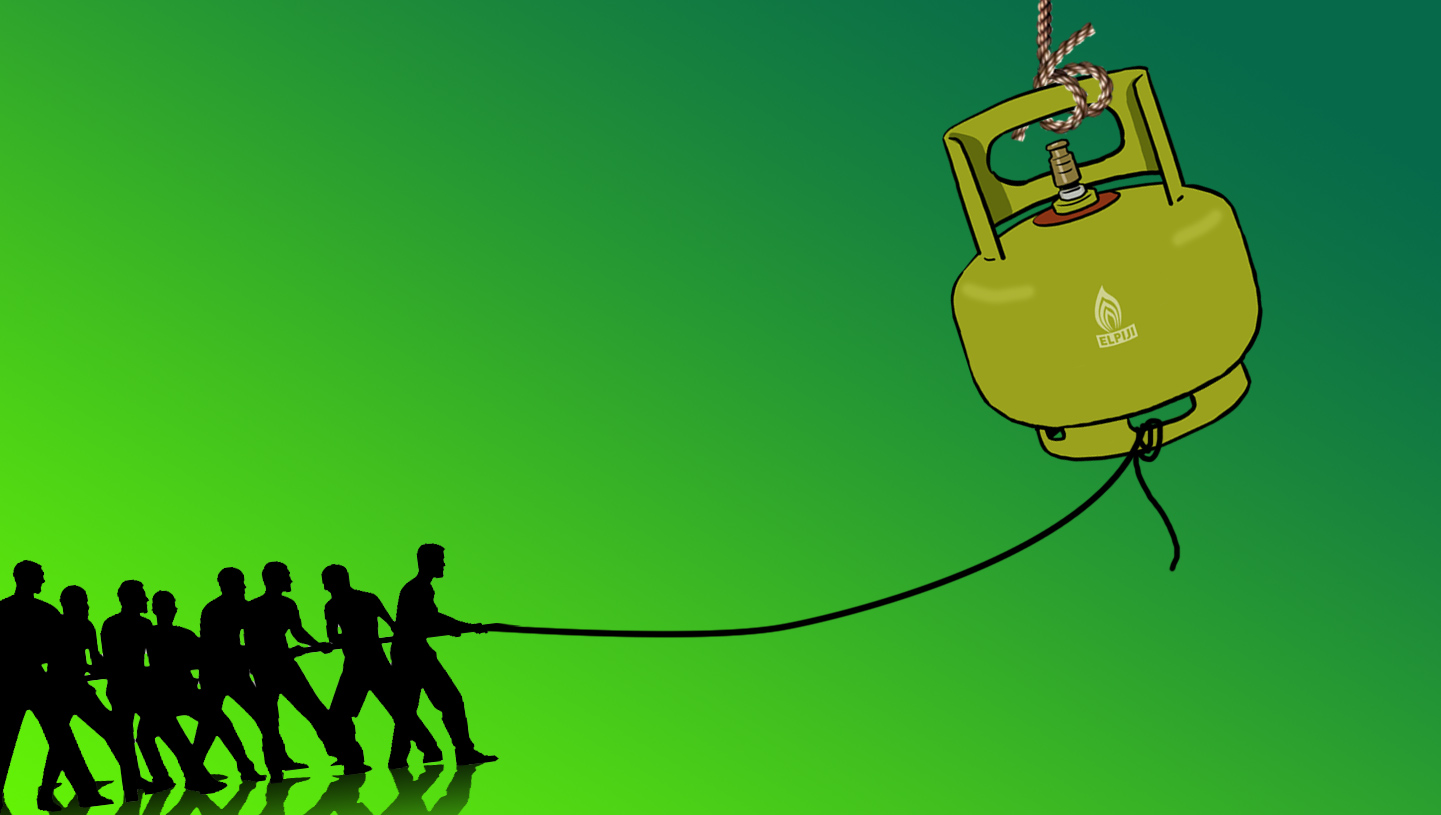KETIKA Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita mengumumkan peta kemiskinan Indonesia, orang memberi reaksi yang beraneka ragam. Tetapi reaksi itu umumnya terkesan buru-buru. Mereka berkomentar sebelum mengetahui data dasar yang digunakan untuk membuat peta tematik tentang kemiskinan itu. Apakah data dasar itu berkaitan dengan distribusi banyaknya orang miskin menurut kecamatan? Ataukah data dasar yang digunakan itu berkaitan dengan potensi dan fasilitas desa-desa yang ada di kecamatan? Peta kemiskinan memang cenderung dikaitkan dengan data tentang kemiskinan di Indonesia, yang diumumkan Pemerintah menurun terus dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 1990 tinggal 15% atau 27 juta saja penduduk miskin di Indonesia. Orang mengasosiasikan peta tematik kemiskinan yang diumumkan Bappenas itu dengan program dan fokus kegiatan untuk mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan. Peta itu diduga digambar berdasarkan data tentang banyaknya penduduk miskin di tiap desa dan kecamatan. Orang menduga pula, data dasar yang digunakan untuk pemetaan itu merinci desa-desa mana saja yang dihuni oleh banyak penduduk miskin. Tetapi Ketua Bappenas juga mengumumkan, peta kemiskinan itu disusun berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik. Wakil Kepala BPS, Soegito, M.A., menerangkan bahwa statistik yang diberikan ke Bappenas untuk keperluan itu diturunkan dan diolah berdasarkan survei potensi desa (disingkat Podes). Survei ini penyelenggaraannya dititipkan pada pelaksanaan Sensus Penduduk 1990, tiga tahun yang lalu. Memang tradisi BPS selama ini, demi efisiensi, mengumpulkan keterangan dasar tentang desa-desa secara lengkap ketika sedang ada kerja penyelenggaraan sensus apakah itu sensus penduduk, sensus pertanian, atau sensus ekonomi. Pertimbangannya, itulah kesempatan menitip yang paling murah dan mudah. Bisa mencakup semua desa, setiap tiga tahun sekali. Kalau benar statistik Podes yang digunakan sebagai data dasar guna menyusun peta kemiskinan, peta itu tidak berkaitan dengan gambaran tentang banyaknya orang miskin di suatu desa atau kecamatan. Karena data Podes tidak memuat statistik tentang banyaknya keluarga miskis di suatu desa! Inilah dilema yang dihadapi oleh instansi yang bertugas utama untuk menyediakan segala macam data. Survei diselenggarakan dengan sikap dasar agar hasilnya sebisa-bisa berguna untuk banyak keperluan. Memang pendekatan itu sepintas tampak murah, tetapi ketajaman konsep dan definisi, yang lazimnya dirumuskan berdasarkan tujuan survei, bisa tidak cukup tajam dan sensitivitasnya sebagai instrumen pengukuran menjadi berkurang. Semula penyusunan statistik tentang potensi desa itu dikembangkan dari survei fasilitas desa (disingkat Fasdes). Tujuannya adalah untuk menyajikan baseline data tentang keadaan serta fasilitas fisik desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Titik beratnya untuk mencatat statistik tentang prasarana ekonomi dan prasarana sosialnya. Kemudian data baseline itu dirasa perlu disempurnakan. Karena, pada tahap pembangunan daerah selanjutnya, titik beratnya tidak lagi semata-mata pada prasarana, tetapi juga pembangunan kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya, bahkan mental spiritual! Karena itu, ragam data yang dikumpulkan dari setiap desa perlu dikembangkan dan disempurnakan. Selain prasarana, kemudian juga dicakup data tentang kependudukan, organisasi sosial, dan kelembagaan. Itulah sebabnya ia perlu ganti nama menjadi survei potensi desa, Podes. Kini tiba-tiba ada keperluan mendesak untuk membuat peta kemiskinan. Maka, dari data baseline itu, data Podes diolah ulang, dianalisa, dan dikategorikan dengan dibuat skoring untuk 29 variabel yang dinilai relevan di antara sekitar 92 data yang ada di dalamnya. Maksudnya, agar pada batas tertentu, dari situ bisa digambarkan penggolongan potensi desa untuk bisa disebut desa miskin sekali, desa miskin, dan desa tidak miskin. Kalau benar data Podes yang dipakai dasar utama untuk menyusun peta tematik tentang kemiskinan, di situ timbul masalah yang sangat mendasar. Desa miskin (potensinya) di satu pihak, dan desa yang dihuni oleh bagian besar penduduk miskin di pihak lain, adalah dua hal yang berbeda. Kalau dasarnya data Podes, peta itu bukan menggambarkan mana saja daerah yang banyak dihuni dan tempat atau lokasi penduduk miskin. Peta kemiskinan yang ada itu hanyalah menerangkan mana di antara kecamatan itu yang berisi desa-desa yang berdasarkan skor potensinya dinilai desa miskin sekali, desa miskin, dan desa tidak miskin. Yang dibuat skornya adalah data tentang tipe LKMD, jalan utama desa, potensi desa, rata-rata tanah pertanian yang diusahakan per rumah tangga tani, jarak dari kelurahan ke ibu kota kecamatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang tinggal di desa, sarana komunikasi, pasar, kepadatan penduduk, sumber air minum, wabah penyakit, bahan bakar, pembuangan sampah, jamban, penerangan, tempat ibadah, tingkat kelahiran kasar, tingkat kematian kasar, enrollment ratio, persentase rumah tangga pertanian, rata-rata banyaknya ternak per rumah tangga, persentase rumah tangga yang mempunyai TV, persentase rumah tangga yang memiliki telepon, angkutan penduduk, dan data fasilitas dan kelembagaan sosial budaya. Itu semua tidak langsung berkaitan dengan rumah tangga atau penduduk miskin. Inilah dilema suatu studi yang tidak terlebih dahulu menyelesaikan kesepakatan tentang konsep dan definisi sasaran penelitian. Kalau karena keterbatasan dana dan hendak menggunakan secara optimum informasi yang ada, rekonsiliasi konsep yang semula digunakan dengan konsep yang sedianya hendak dituju perlu dipecahkan atau disepakati terlebih dahulu. Kesan saya, yang utama hendak diperoleh gambarannya dari peta kemiskinan ini adalah di manakah gerangan tempat keberadaan penduduk miskin itu secara geografis dan administratif. Bukan desa-desa yang potensinya masih tergolong desa miskin sekali, desa miskin, dan desa tidak miskin. Pengetahuan lokasi penduduk miskin, sebagai kelanjutan pengetahuan tentang gambaran agregat banyaknya penduduk miskin sebanyak 27 juta itu, akan mempermudah komunikasi teknis program dan anggaran antara Bappenas dan pemerintah daerah. Kini peta itu sudah ada dan sudah dikomunikasikan. Duduk perkara sudah kita ketahui. Maka, kalau boleh, tinggal dinilai seberapa relevan peta kemiskinan yang disusun utamanya berdasarkan data potensi desa itu bisa menggambarkan lokasi penduduk miskin. Memperhatikan reaksi kepala daerah yang tulus, yang intinya menyampaikan ketidaksesuaian peta dengan keadaan sebenarnya, saya mempunyai tiga catatan. Pertama, saya merisaukan kualitas data yang ada di dalam isian daftar pertanyaan tentang potensi desa itu. Saya tahu, sebagian penting jajaran teknis BPS enggan menyajikan data hasil survei potensi desa itu. Alasannya, mutu data yang dapat dihimpun di situ sangat rendah. Hanya kepada peneliti senior kaliber Prof. Sayogya atau Prof. Mubyarto data itu ''rela'' diperlihatkan. Kepada tiap pemakai data itu diingatkan agar hati-hati dan bersikap kritis tatkala hendak menggunakannya. Kedua, data-data yang kemudian dipilih untuk keperluan kriteria desa miskin sekali, desa miskin, atau desa tidak miskin seperti tertera di atas, sangatlah superfisial dan bias ke desa atau kelurahan yang terletak di kota. Misalnya, kelompok data tentang potensi dan fasilitas desa yang diambil selain tipe LKMD, ada atau tidaknya SLTA, dokter, telepon umum/terpasang, dan pasar. Kelompok data tentang perumahan dan lingkungan, antara lain ada pertanyaan tentang sumber air minum apakah dari PAM/pompa listrik, selain sumur, mata air, dan air hujan. Untuk bahan bakar digunakan kriteria tinggi listrik atau gas, kemudian minyak tanah dan kayu bakar. Bukankah itu semua bias ke keadaan desa atau kelurahan-kelurahan di kota? Begitu juga kelompok data tentang keadaan penduduk, ada tingkat kelahiran kasar, tingkat kematian kasar. Apakah hubungan angka tingkat kematian dan kelahiran begitu linier dan sederhana? Lagi pula, untuk penduduk satu desa yang jumlahnya di luar Jawa banyak yang kurang dari 1.000 orang dan di Jawa pedesaan hanya 1.000 sampai 3.000 orang, menurut kaidah statistik demografi sangat tidak sahih hasil hitungan CDR dan CBR-nya. Lalu ada lagi tentang persentase rumah tangga yang ada teleponnya, ada atau tidaknya koperasi dan lain-lain, semuanya itu sedikit sekali berkorelasi dengan banyak orang miskin atau tidak di desa itu. Data itu memang menggambarkan tingkat ''kemajuan'' desa menurut kriteria yang bias ke fasilitas urban. Catatan saya yang ketiga, yang menurut pendapat saya serius secara teknis statistik, adalah pemberian skor secara arbitrer, sangat sederhana tetapi sungguh mengecohkan. Beberapa contoh saja: skor tinggi diberikan pada desa-desa yang tidak padat (4), kurang padat (3), baru yang terendah yang padat (1). Bukankah desa yang makmur biasanya lebih padat daripada desa miskin yang umumnya terisolasi? Skor tinggi diberikan pada desa-desa yang ada dokternya (3), menengah yang ada paramediknya (2), baru yang rendah yang ada dukun bayinya (1). Ini bias untuk desa kota, sehingga untuk desa-desa pertanian yang makmur terpaksa ''tertekan rendah skornya'' karena tidak ada dokter atau paramedik. Begitu juga urusan telepon dan pasar. Yang lebih ''merugikan'' desa maju karena pembangunan pertaniannya adalah skoring arbitrer yang dikenakan pada pekerjaan penduduk. Kalau desanya sebagian besar berpenduduk yang bergantung dari usaha perdagangan dan jasa, skornya 3, kalau industri kerajinan 2, tetapi kalau pertanian 1. Maka jangan heran kalau hasil pemetaan ini menggambarkan bahwa desa-desa miskin di kota hanyalah 2,56%, sedang desa-desa miskin di pedesaan sampai 37,51%. Ini tidak konsisten dengan statistik kemiskinan sebelumnya yang dengan bangga menyajikan bahwa proporsi penduduk miskin di desa (tahun 1990, 14%), lebih rendah ketimbang penduduk miskin di kota (tahun 1990, 16%). Usul saya, kembalikan peta tematik kemiskinan itu sesuai dengan tujuan, yaitu peta yang secara geografis dan administratif bisa mengidentifikasi lokasi penduduk miskin. Dasarkan peta itu dari data banyaknya penduduk yang tergolong miskin. Kriteria sederhana untuk itu bisa dikembangkan bersama. Data statistik yang dipakai untuk dasar pengukuran tidak perlu terlalu banyak. Kalau tidak bisa pendapatan atau pengeluaran rumah tangga, cukup dengan fokus pada pekerjaan kepala rumah tangga, apakah ia nelayan, buruh tani, petani lahan kering, pekerja sektor in formal, atau menganggur. Bisa juga digunakan keadaan rumah sebagai proxy, ditengok kualitas atapnya injuk, lantainya tanah, dindingnya gedek, luas lantainya per kepala apakah kurang dari lima meter itu misal saja. Atau mungkin dipilih tiga atau empat variabel berdasarkan analisa principle component. Atau sebelum diterapkan dites dulu korelasinya dengan garis kemiskinan, yang sekarang ini telah digunakan. Setelah itu lalu diterapkan di tiap desa, untuk mengetahui berapa persen di antara penduduknya yang berada di bawah garis kemiskinan. Antara 0-5% baik sekali, Antara 5-10% baik, B. Antara 10-25% cukup, C. Antara 25-50% kurang, D. Dan lebih dari 50% yang sangat kurang, Itu usul yang sangat tentatif dan bersifat sederhana. Yang teknis seyogyanya dirundingkan dengan ahli-ahli yang kompeten, instansi terkait, dan Bappeda tingkat provinsi dan beberapa Bappeda kabupaten/kota madya. Tujuannya, untuk menghimpun masukan dan mempertinggi peluang bisa diterima dengan baik, karena sudah memperhatikan suara mereka. Karena ini upaya serius, saya mengusulkan hendaknya data dasarnya betul-betul disusun dengan tingkat validitas dan kecermatan yang tinggi. Bukan menumpang data yang seadanya, apalagi Podes, yang sudah dikenal rendah mutunya itu. Selamat bekerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini