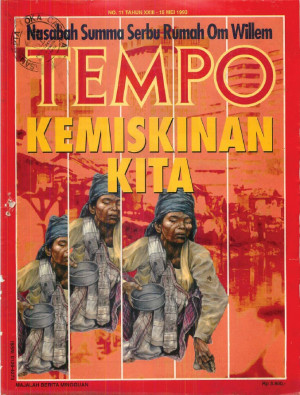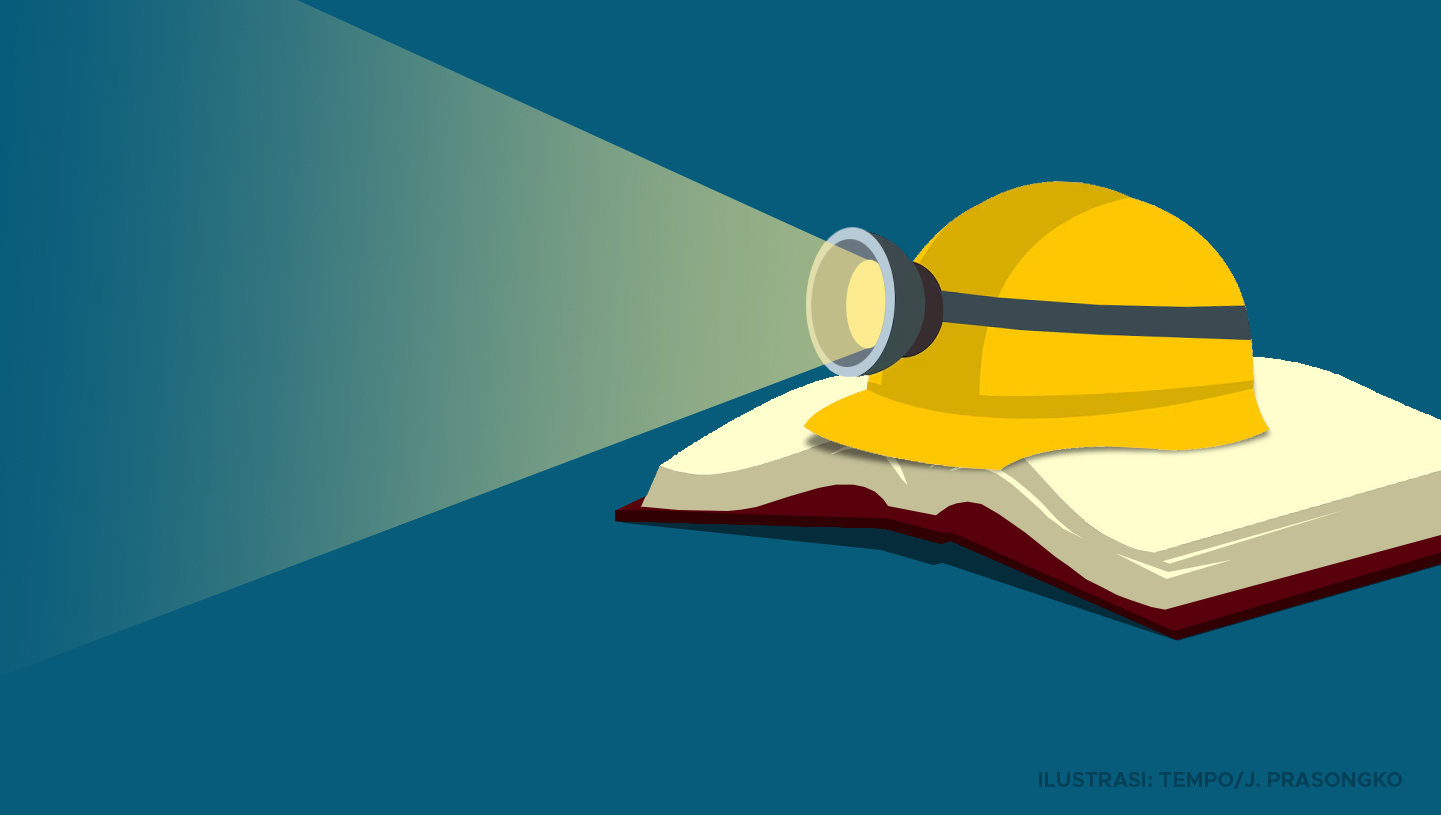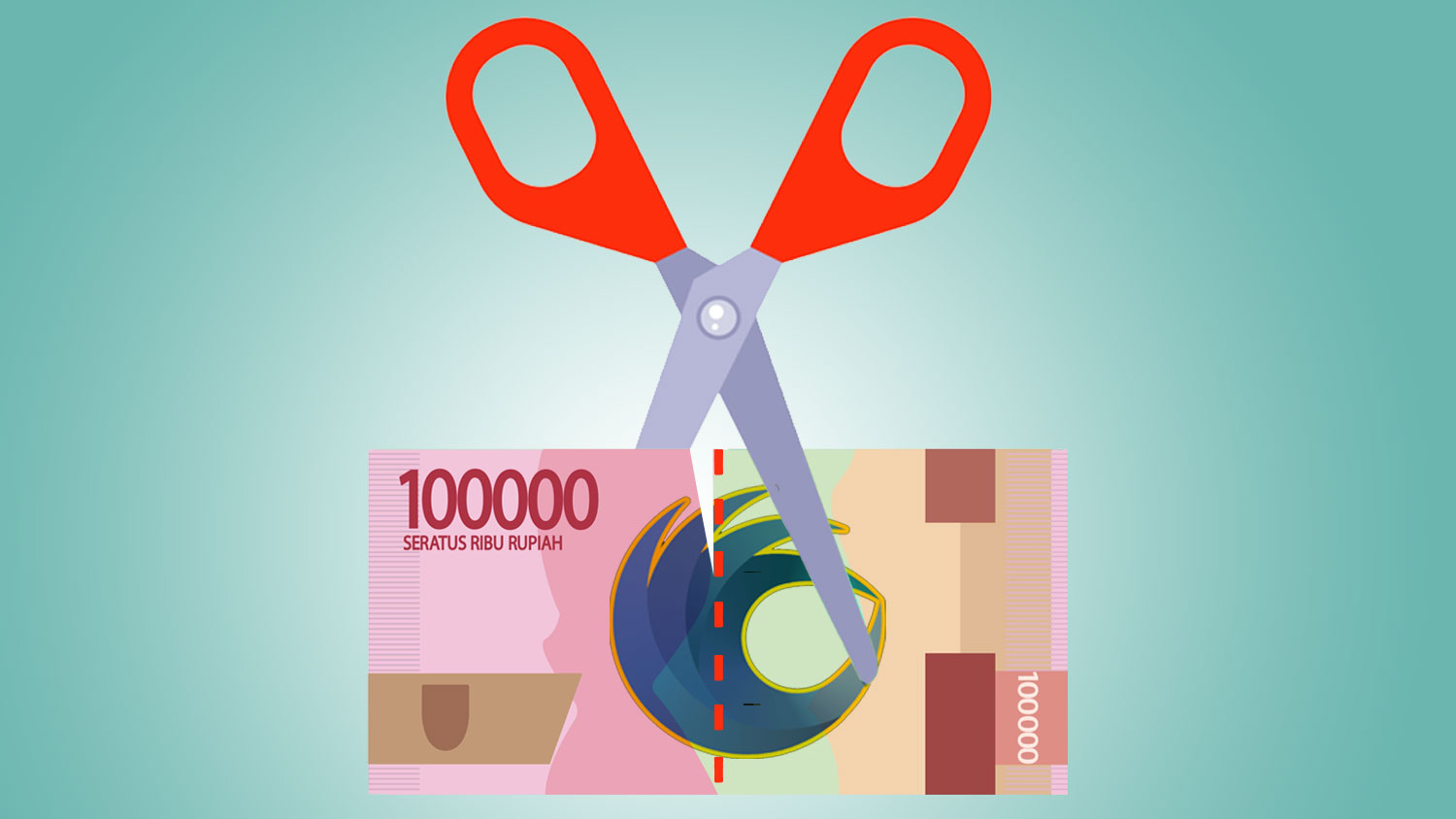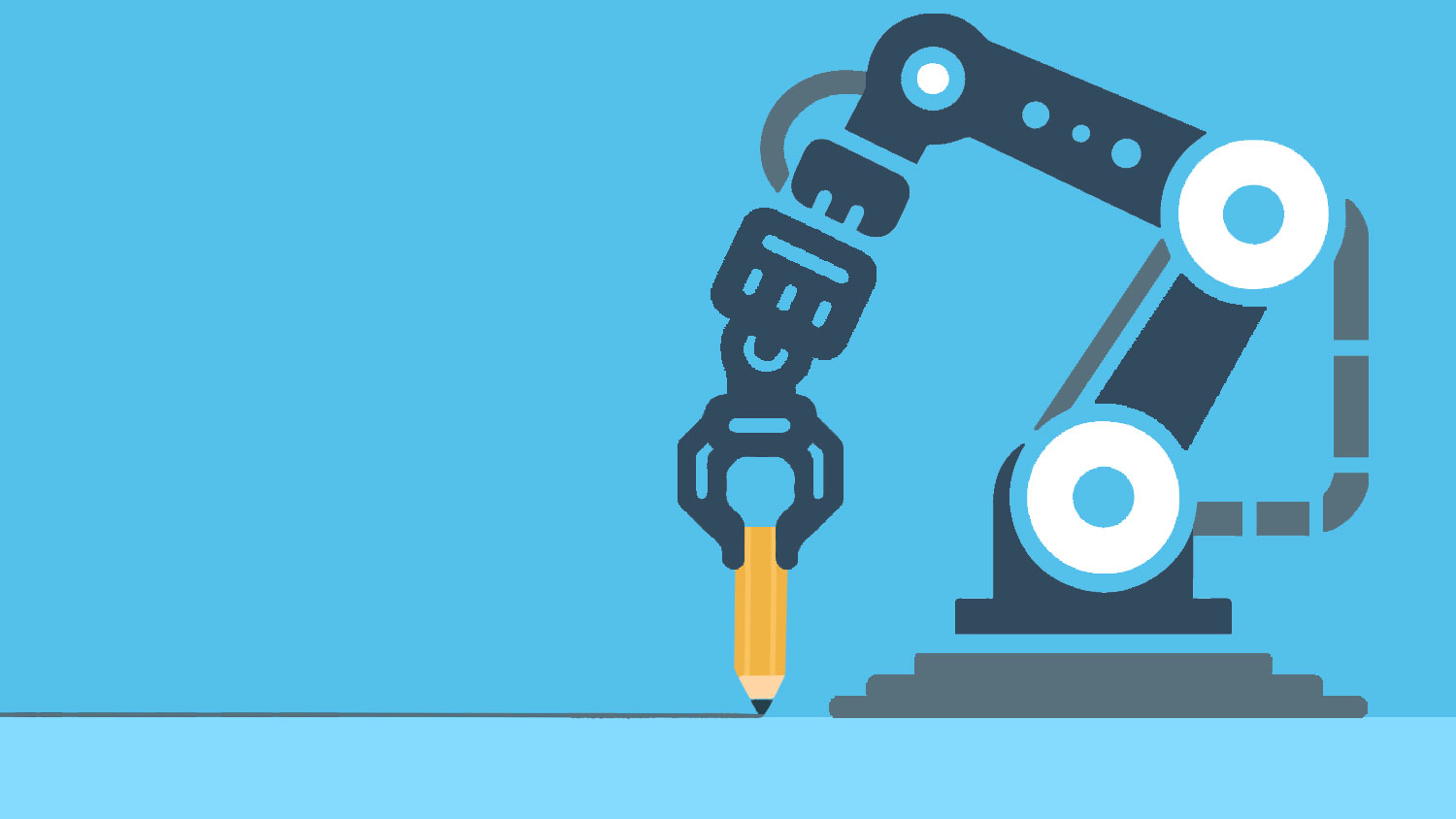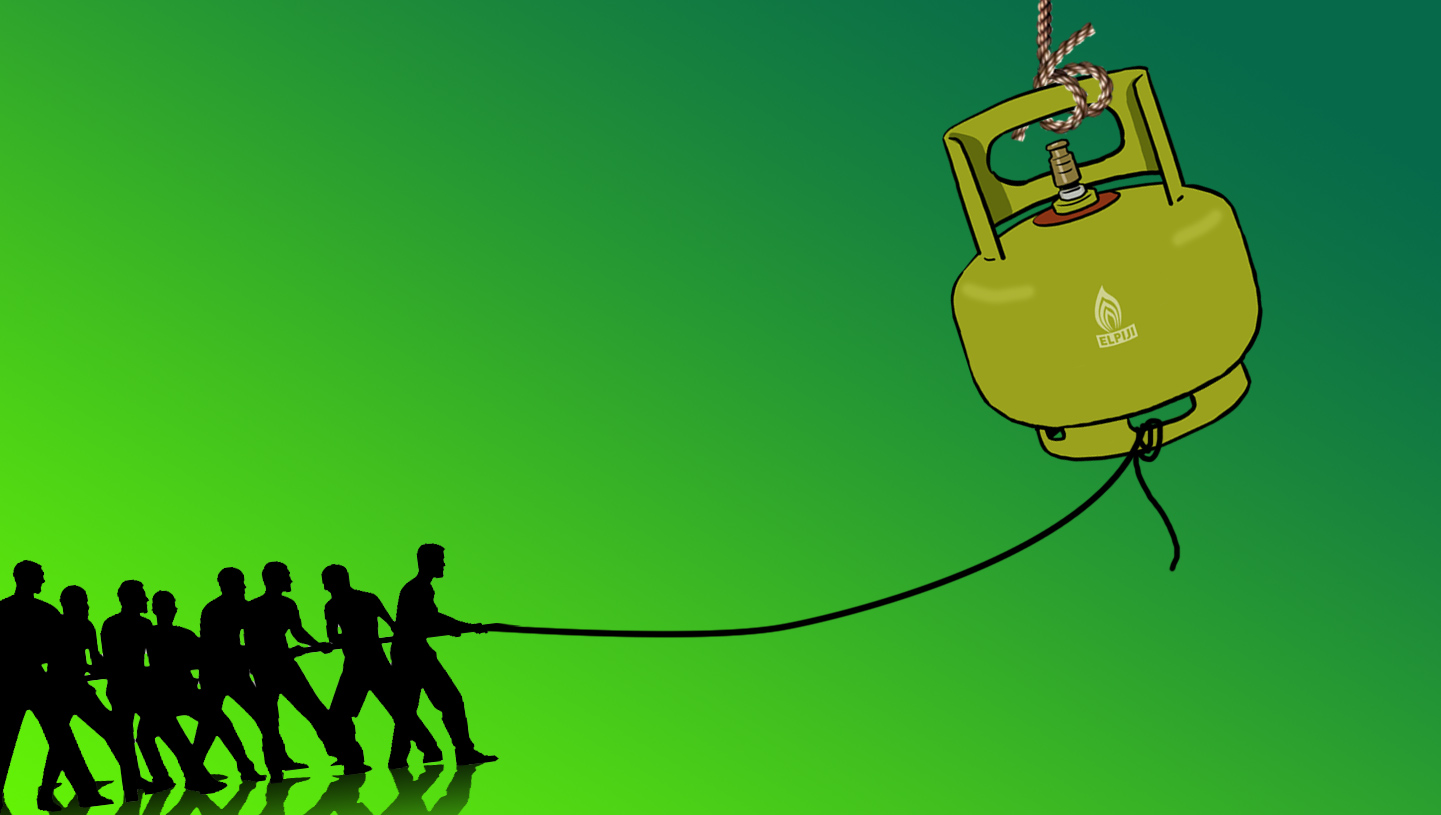KOTA-KOTA berbicara tentang kemiskinan dengan cara yang paling menikam. Ada seorang pendatang dari Amerika yang menuliskan kesannya tentang sebuah kota yang baru mencorong oleh industrialisasi, yang dengan cepat menjadi pusat kemegahan tapi juga pusat kesengsaraan: ''Di tengah keserba-melimpahan yang luar biasa itu, ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mati kelaparan. Seiring dengan kereta kuda yang gilang-gemilang, yang berlapiskan emas, yang berwiru sutera, yang diiringi pelayan berseragam, mereka yang miskin, sendirian, tanpa harap, telanjang ....'' Orang Amerika itu berbicara tentang London, pada tahun 1849. Tapi bagaimana kemiskinan itu secara tajam menusuk bisa dibaca dari sebuah laporan lain dari pertengahan abad ke-19 itu. Seorang penulis menuliskan kesaksiannya melihat hidup sekelompok orang miskin yang bekerja sebagai para pemungut tulang: ''Saya telah melihat mereka mengambil sekerat tulang dari seunggun kotoran, dan menggerogotnya sementara masih panas oleh proses meragi dan membasi ....'' Rupanya suatu nasib yang universal: kota-kota berbicara tentang kemiskinan dengan cara yang menikam, bukan karena sejumlah orang hidup serba kurang atau pas-pasan, melainkan karena kontras di sana yang menganga tajam. ''Kemelaratan yang paling nyata adalah yang terdapat di kota-kota, karena di sanalah ekses-ekses saling bertetangga,'' kata Andre Gide. Kita tahu ini karena Jakarta, tahun 1993, seperti London, tahun 1849, adalah contoh tentang ekses yang berdampingan dengan ekses sedemikian rupa jelasnya hingga praktis sudah menjadi klise: Rumah-rumah real estate dengan kolam renang (dan listrik ribuan watt) berhimpun bagaikan para anggota sebuah klub yang mahal tidak jauh dari bedeng-bedeng yang kumal dan termangu di tepi selokan cemar yang mati. Lapangan golf luas yang segar bugar membentang di dekat kampung-kampung yang tak berpekarangan. Orang-orang yang bisa menghabiskan uang Rp 3 juta untuk sekali bertaruh di lapangan tenis berpapasan dengan orang-orang yang harus hidup dengan Rp 1.000 sehari. Itulah sebabnya nasib si miskin rasanya tak cukup didendangkan dalam lagu kroncong ciptaan Maladi, Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Kita telah lama berteriak dengan marah tentang mereka yang hidup dalam kemiskinan: kita telah bicara dengan kata ''marhaen'' atau ''proletar'' pada masa penjajahan. Kita telah bertubi-tubi mendesak, dan berbuat, untuk zakat bagi yang fakir dan papa. Kita telah membikin sejumlah besar proyek pemerataan. Persoalannya, apa sebenarnya yang hendak kita capai: menghabisi kemelaratan atau menghilangkan ketimpangan? Hampir satu abad sebelum seorang pengunjung dari Amerika melihat London sebagai kota tempat sejumlah orang miskin ''tanpa harap, telanjang'', seorang pengunjung Amerika lain punya kesan lain. Pada tahun 1766, orang Amerika yang terkesan itu, Benjamin Franklin, menulis tentang Inggris: ''Tak ada negeri di dunia ini yang membangun sebanyak itu perlengkapan bagi orang miskin. Begitu banyak rumah sakit untuk menerima mereka bila mereka sakit atau lumpuh, semuanya dibangun dan dirawat oleh organisasi amal sukarela. Begitu banyak rumah derma untuk orang tua dari kedua jenis, dan ada sebuah undang-undang yang khidmat dibuat oleh orang kaya untuk menjadikan tanah mereka kena pajak yang tinggi guna mendukung orang melarat ....'' Jarak waktu antara 1766 dan 1849 begitu panjang, tapi tak ada tanda bahwa kemiskinan menyusut. Kita termangu. Jalan rupanya rumit. Menghabisi kemelaratan saja dengan memberi banyak dana dan kemudahan bagi si papa ternyata tak memperbaiki keadaan. Benjamin Franklin sendiri pada tahun 1766 itu sudah melihat bahwa kedermawanan yang melimpah-ruah yang disaksikannya di Inggris itu hanya merupakan ''suatu hadiah untuk menggalakkan kemalasan''. Tak mengherankan, kata Franklin pula, bahwa akibatnya ialah ''bertambahnya kemiskinan''. Kritik Benjamin Franklin itu kemudian, pada zaman kita, menjadi kritik utama terhadap sistem welfare state dan, lebih tegas lagi, sistem sosialisme, di mana orang hidup dari kemudahan yang diatur oleh pemerintah, dan etos kerja menjadi merosot. Tapi bukan hanya itu. Akibat lain ialah berlanjutnya ketimpangan sosial. Bagaimanapun juga, gagasan kedermawanan mengandung suatu keniscayaan adanya ''sang pemberi derma'' dan ''sang penerima derma''. Keduanya berbeda dalam derajat dan kekuasaan. Kedermawanan hanya akan membuat si miskin kian tak berdaya. Filantropi bisa dianggap sebagai cara terselubung untuk mempertahankan ketimpangan. Maka, agaknya kedermawanan yang sesungguhnya harus berangkat dengan niat bahwa ketimpangan itulah yang mesti ditiadakan. Tapi di kota-kota besar, di kantor penguasa-penguasa besar, orang akan mendengar kalimat itu dengan senyum yang besar. ''Lihat,'' mereka akan berkata, ''tanpa ketimpangan, tak akan ada kami. Tanpa ketimpangan, tak akan ada persaingan, tak akan ada niat untuk menang. Dan bukankah kitab suci dan sejarah telah mengajarkan bahwa si miskin akan selalu bersama kita?'' Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini