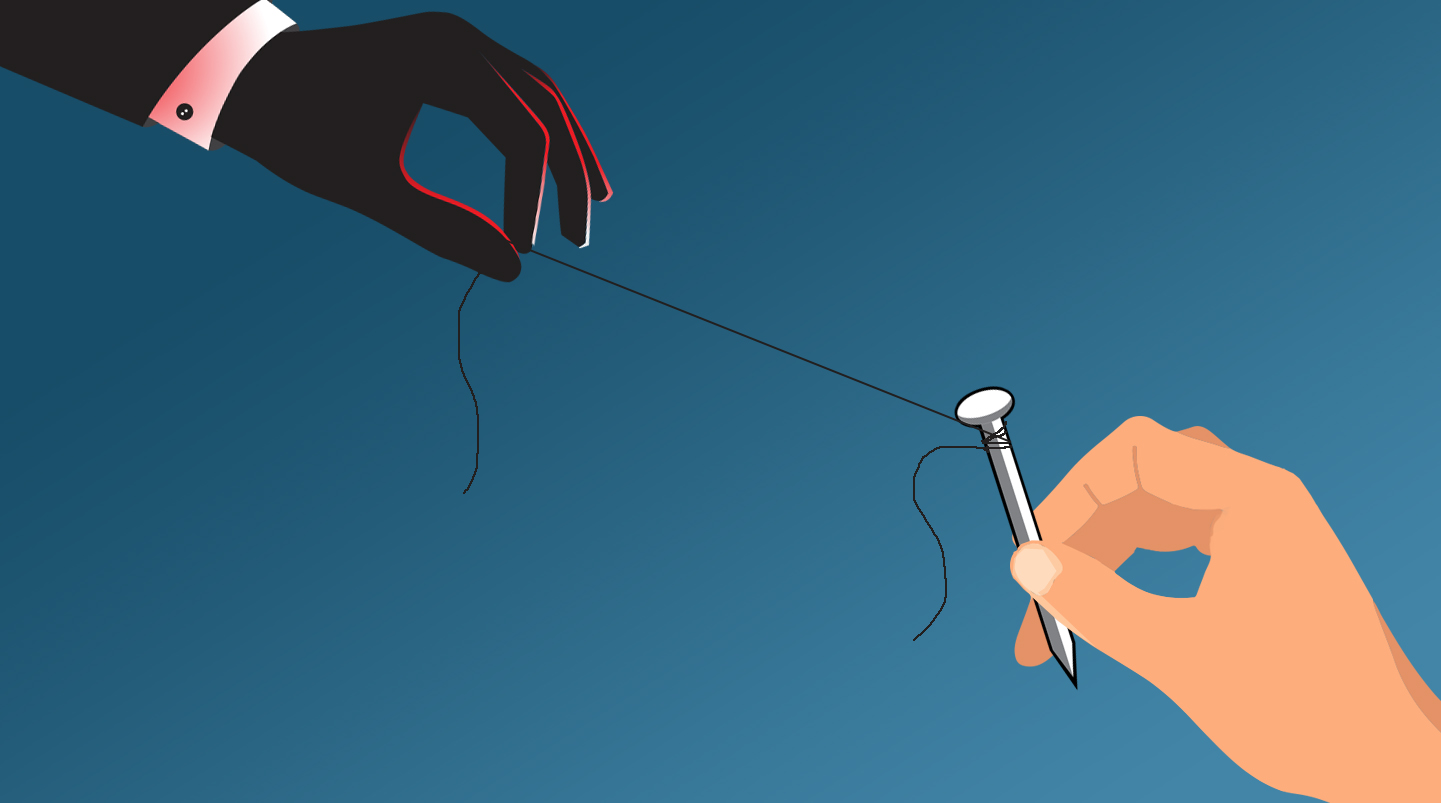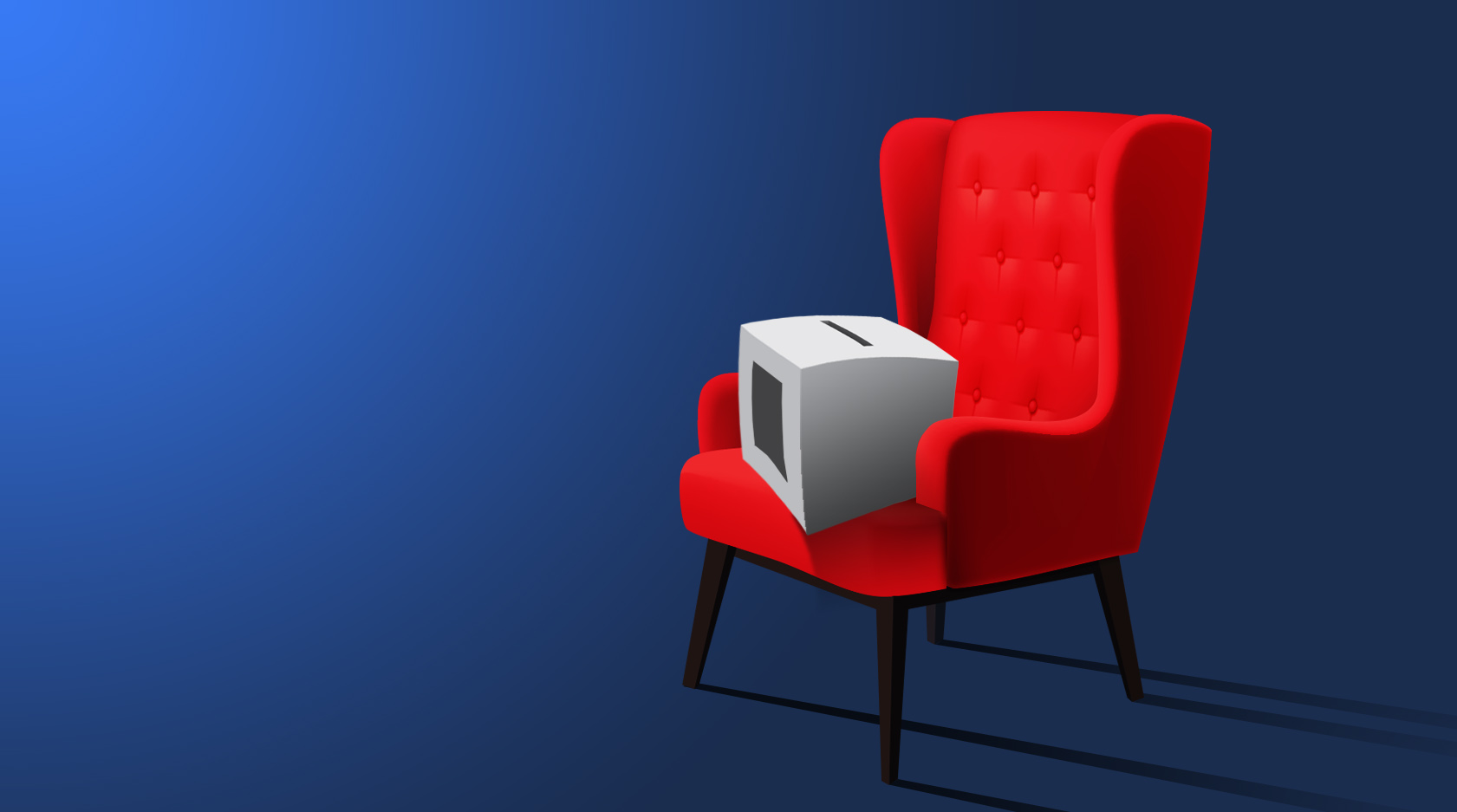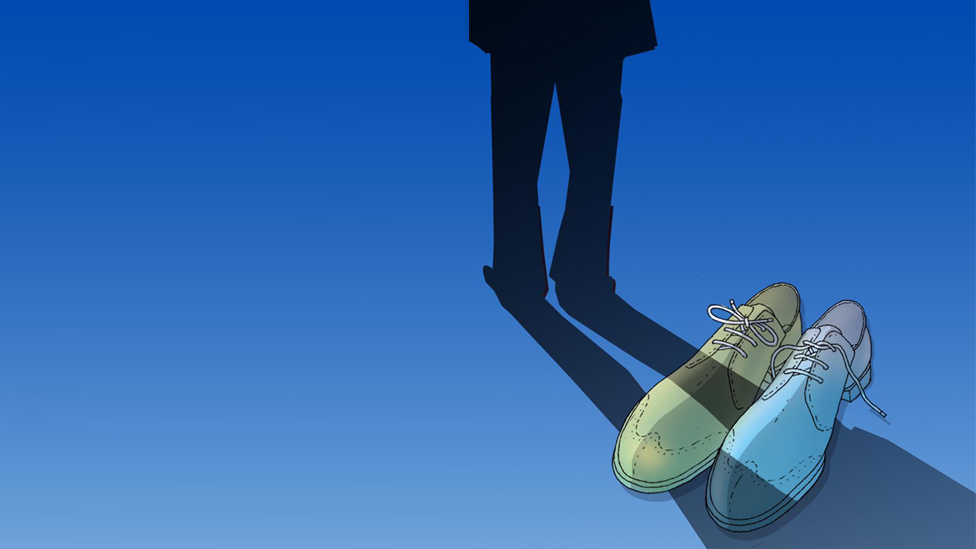Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seno Gumira Ajidarma
Panajournal.com
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertemuan dengan Juwono Sudarsono yang sedang berobat membuat saya teringat kembali pada buku yang disuntingnya, Pembangunan Politik dan Perubahan Politik (1976). Mengingat tahun terbitnya, satu dekade setelah 1966, yakni masa Orde Baru yang kini sudah 21 tahun ditinggalkan, menarik untuk menengok konteks buku itu dalam perspektif politik kontemporer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam pengantarnya, Juwono mengulas sistem politik Indonesia pada 1950-an, yang kabinet demi kabinetnya jatuh-bangun, koalisi terbentuk dan pecah, dalam aturan main dan semangat zaman, yang konstitusional dan sah. Pandangan kritisnya: Gaya berpolitik demikian hanya menyangkut elite politik "yang berkelahi mempertaruhkan nama dan ideologinya masing-masing atas nama kepentingan nasional".
Juwono menyebut politik demokrasi konstitusional gaya Barat borjuis tidak sesuai dengan kesinambungan sejarah, yang mendasari kehidupan rakyat "yang bergolak di bawah aturan permainan sopan yang berlaku di kalangan elite politik". Situasi ini meredup pada akhir 1950-an, ketika Sukarno berangsur meruntuhkan struktur palsu yang tidak relevan itu. Mobilisasi politik dilakukan, menggunakan bentuk, prosedur, dan upacara berpolitik yang "digali" dari kebudayaan tradisional. Solidaritas bangsa dikembangkan, dan politik adalah panglima, bahkan berperan di lingkungan akademik.
Reaksi dari sistem politik semacam itu, setelah 1 Oktober 1965, adalah berkembangnya semangat baru: penyederhanaan struktur politik, yang ditandai dengan besarnya peranan militer, khususnya Angkatan Darat, yang disebut sebagai sumbu utama kehidupan politik Indonesia. Selain itu, kekuatan pasar dalam ekonomi Indonesia secara terbuka dihadirkan dalam perumusan konsep politik. Bagaimanapun, semangat zaman barunya Orde Baru itu tidak terhindar dari masalah yang lazim menimpa negara kebangsaan baru, sesuai dengan keberagaman struktur sosial-budaya khalayaknya (Sudarsono, 1976: 8-10).
Dari lima pemikir yang dihadirkan untuk menunjukkan masalahnya, pemikiran Clifford Geertz (1926-2006) tampak urgen untuk hari ini. Geertz menyebutnya sebagai sentimen primordial, ketika hubungan kesetiaan komunal dan kesetiaan politik menjadi masalah karena kaburnya konsep bangsa, kebangsaan, dan nasionalisme.
Terdapat enam titik pusat keguncangan primordial yang mengancam utuhnya kedaulatan nasional. Pertama, hubungan darah atau kesukuan. Pengertian hubungan darah di sini lebih bersifat kuasi-kekeluargaan tapi tidak mengancam kedaulatan nasional, kecuali diperluas secara sosiologis menjadi hubungan kesukuan. Ikatan primordial kesukuan berkontestasi dengan ikatan kebangsaan.
Kedua, jenis bangsa atau ras. Secara etno-biologis terdapat kemiripan konsep dengan kesukuan, tapi ciri utama jenis bangsa adalah bentuk fisik fenotipe (warna kulit, bentuk muka, tinggi badan, bentuk rambut), bukan persamaan keturunan.
Ketiga, bahasa. Bahasa adalah faktor primordial yang keberbedaannya tidak dianggap membawa perpecahan, meski memang bisa membingungkan. Konflik primordial pada kenyataannya bisa terjadi pada khalayak berbahasa sama.
Keempat, kedaerahan atau regionalisme. Kedaerahan menjadi rawan di daerah geografis heterogen, seperti negara kepulauan Indonesia, yang secara teritorial tidak bersambungan. Kedaerahan adalah faktor primordial dalam politik nasional. Secara spesifik, di samping contoh-contoh lain, Geertz menyebut Jawa lawan luar Jawa.
Kelima, perbedaan agama. Kuatnya ikatan keagamaan disebut menghambat ataupun menggagalkan perasaan kebangsaan yang lebih luas. Di antara berbagai contoh, Geertz menyebut tiga suku di Indonesia dengan ikatan keagamaan dominan.
Keenam, kebiasaan. Ada kalanya suatu kelompok secara intelektual dan estetis terbiasa merasa dirinya membawa "peradaban" ke tengah penduduk lain, yang dianggap kasar serta mesti berpedoman kepada golongan yang "unggul". Perbedaan dalam kebiasaan seperti ini disebut sebagai dasar perpecahan nasional. Contohnya adalah orang Jawa. Namun, meski orang Jawa dan Sunda adalah golongan yang berbeda, mereka dapat menjalankan gaya hidup yang sama. Adapun orang Bali, yang berpola kebiasaan dengan ragam terbanyak, belum pernah menunjukkan tanda-tanda keguncangan (Geertz [1963] dalam Sudarsono, 1976: 15, 20-2).
Geertz masih melanjutkan perbincangannya dengan kombinasi berbagai variabel dari titik-titik keguncangan primordial ini, dan tetap saja Jawa dan luar Jawa menjadi faktor tetap. Sebagai antropolog spesialis Islam dan Jawa, sebetulnya Geertz menjadi bulan-bulanan kritik. Namun, jika geografi pembagian suara Pemilihan Umum 2019 dalam majalah Tempo edisi 8 April 2019 diperhatikan, sentimen primordial dalam politik Indonesia rupanya memang bekerja dan dipekerjakan kaum politikus.