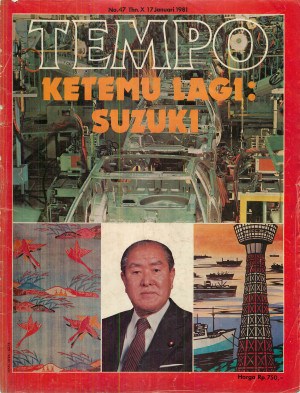SETELAH Jenderal van den Bosch yang arsitek Tanam Paksa
diturunkan dari tahta dengan paksa dan Tanam Paksa lambat laun
diakhiri pada tahun 1870-an maka sinyo-sinyo dari golongan
liberal pun menggantikannya sebagai penguasa tanah Jawa. Sejak
lama sebenarnya sinyo-sinyo liberal ini mengungkapkan
kejengkelannya terhadap teori dan praktek cultuurstelsel.
Sebagai anak kandung dari revolusi borjuasi maka mereka amat
peka terhadap segala bentuk monopoli pemerintah. Kdtik mereka
terhadap cultuurstelsel adalah kritik mereka terhadap monopoli
pemerintah, yang tak memberi kesempatan kepada pihak swasta,
yang hampir selalu dicemoohkan sebagai 'pencari untung pribadi
yang mata duitan'. Pada tahun 1970-an maka kaum liberal inilah
yang ganti berkuasa di tanah Jawa.
Sinyo Liberal dan Pendidikan
Dengan gayanya yang amat sarkastis, Multatuli mengatakan bahwa
beda yang amat asasi antara golongan konservatif (yang mendukung
proyek Tanam Paksa) dengan golongan liberal adalah: 'Kaum
konservatif menginginkan dari Hindia semua keuntungan yang bisa
diambil, sedangkan kaum liberal menginginkan semua keuntungan
yang bisa diambil dari Hindia'. 'Beda' yang secara amat tajam
dilukiskan oleh Multatuli itu bagi kalangan rakyat petani tanah
Jawa memang terbukti. Orang Olanda baik sesudah maupun sebelum
tahun 1870-an tetap saja mereka kenal sebagai 'Kumpeni Olanda'.
Namun lepas dari sarkasme Multatuli, kita dapati ciri-ciri yang
benar-benar membedakan kedua kelompok pencari untung tersebut.
Beda yang dalam jangka panjang memberikan pengaruh besar. Yaitu
ketika pada tahun 1870-an pemerintahan liberal Olanda mulai
menyisihkan sedikit uangnya untuk membiayai pos pendidikan bagi
kaum pribumi.
Pada masa cultuurstelsel tidak ada pendidikan. Karena yang
dibutuhkan saat itu adalah tanah dan otot orang Jawa semata.
Ilmu, ketrampilan, teknologi dan keberuntungan, semuanya
merupakan hak khas kolonial. Berbeda dengan kaum konservatif,
golongan liberal yang berkuasa menganggap bahwa seluruh lapisan
masyarakat pribumi harus dididik. Kemampuan intelektual kaum
pribumi perlu dipelihara dan ditingkatkan. Telah tersedia
alasan-alasan politis maupun ekonomis untuk mendidik orang
pribumi tersebut. Muka untuk pendidikan khusus pribumi saja
tahun 1870 pemerintah kolonial telah menyediakan uang 300 ribu
gulden, sedang tahun 1900 meningkat menjadi 1.409.000 gulden.
Dalam kamus golongan liberal tidak dikenal 'kerja paksa' dengan
alasan apapun juga. Sebab itu pula mereka tidak menyetujui Tanam
Paksa karena di dalamnya terkandung unsur yang memperlakukan
petani sebagai tenaga yang dipaksa bekerja. Para petani itu
bukan hanya dipaksa untuk menanam tanaman ekspor yang ditentukan
pemerintah, akan tetapi sekaligus diperlukan sebagai tenaga
paksa forced, compulsory-labor). Dalam pemikiran kaum liberal
para petani/pekerja dianggap sebagai tenaga yang bebas. Dengan
demikian mereka dapat dihubungi secara langsung di tempat di
mana mereka berada. Sebagai akibatnya perantaraan kaum feodal
atau bangsawan Jawa menjadi tersisih. Para penguasa pribumi
dalam hubungan ini tidak lagi menjadi perantara yang vital
antara para pemilik modal dengan rakyat petani-pekerja. Apa lagi
dengan masuknya alat-alat mekanisasi (misalnya pabrik gula) di
paruh kedua abad 19 telah menyebabkan pengerahan tenaga kerja
yang tak terdidik menjadi kurang relevan. Pengelolaan kolonial
yang efektif bukan lagi pertama-tama soal pengerahan tenaga
kerja. Hubungan langsung antara para pekerja/petani Jawa dan
pemilik modal swasta ini pada gilirannya akan menimbulkan dilema
pelik di kalangan para bupati.
Dilema Para Bupati
Ditinjau dari segi pendidikan maupun peran politik di masa
pemerintahan kaum liberal telah yata bahwa para bupati banyak
kehilangan pamor-pamornya yang gemerlap di masa lampau. Mereka
tak bisa lagi mengandalkan keningratannya, sebab keningratan
tidak dengan sendirinya dianggap penting oleh penguasa kolonial.
Pemerintah merasa bisa berhubungan langsung dengan rakyat tanpa
terlalu tergantung pada jasa-jasa baik para bangsawan. Tingkat
pendidikan serta intelektualitas mereka pun boleh dikatakan
rendah. Bahkan di tahun 1902 di seluruh Jawa dan Madura hanya
ada 4 (empat) orang bupati yang bisa menu]is dan bercakap-cakap
dalam bahasa Olanda. Beberapa bupati lainnya hanya mendapat
pendidikan yang amat tak memadai. Pendidikan formal yang mulai
dijalankan oleh pemerintah agaknya telah menggoyahkan akar-akar
kemasyarakatan yang saat itu bertumpu pada adat dan agama.
Kultur dan pengajaran yang mereka terima dari akar-akar adat dan
agama agaknya tak cocok lagi dengan keadaan yang mulai berubah.
Kaum bangsawan mulai merasa inferior di hadapan orang Olanda.
Dalam konteks semacam inilah para bangsawan Jawa merasa
kehilangan status dan peranan yang selama berabad-abad mereka
nikmati. Semakin meluasnya pendidikan yang diberikan oleh
pemerintah kolonial khususnya pada masa berlakunya Politik Etik,
maka serta-merta muncullah kesadaran di kalangan mereka akan
pendidikan. Agar prestise mereka di tengah masyarakat dapat
dipulihkan. Dan tak kurang dari Pangeran Ario Condronegoro
sendiri (Bupati Demak, kakek Raden Ajeng Kartini) berpetuah:
'Anak-anakku, jika tidak mendapat pelajaran. engkau tidak akan
mendapat kesenangan, turunan kita akan mundur, ingatlah!' Di
Jawa, adakah selalu hubungan antara pendidikan dan
kebangsawanan?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini