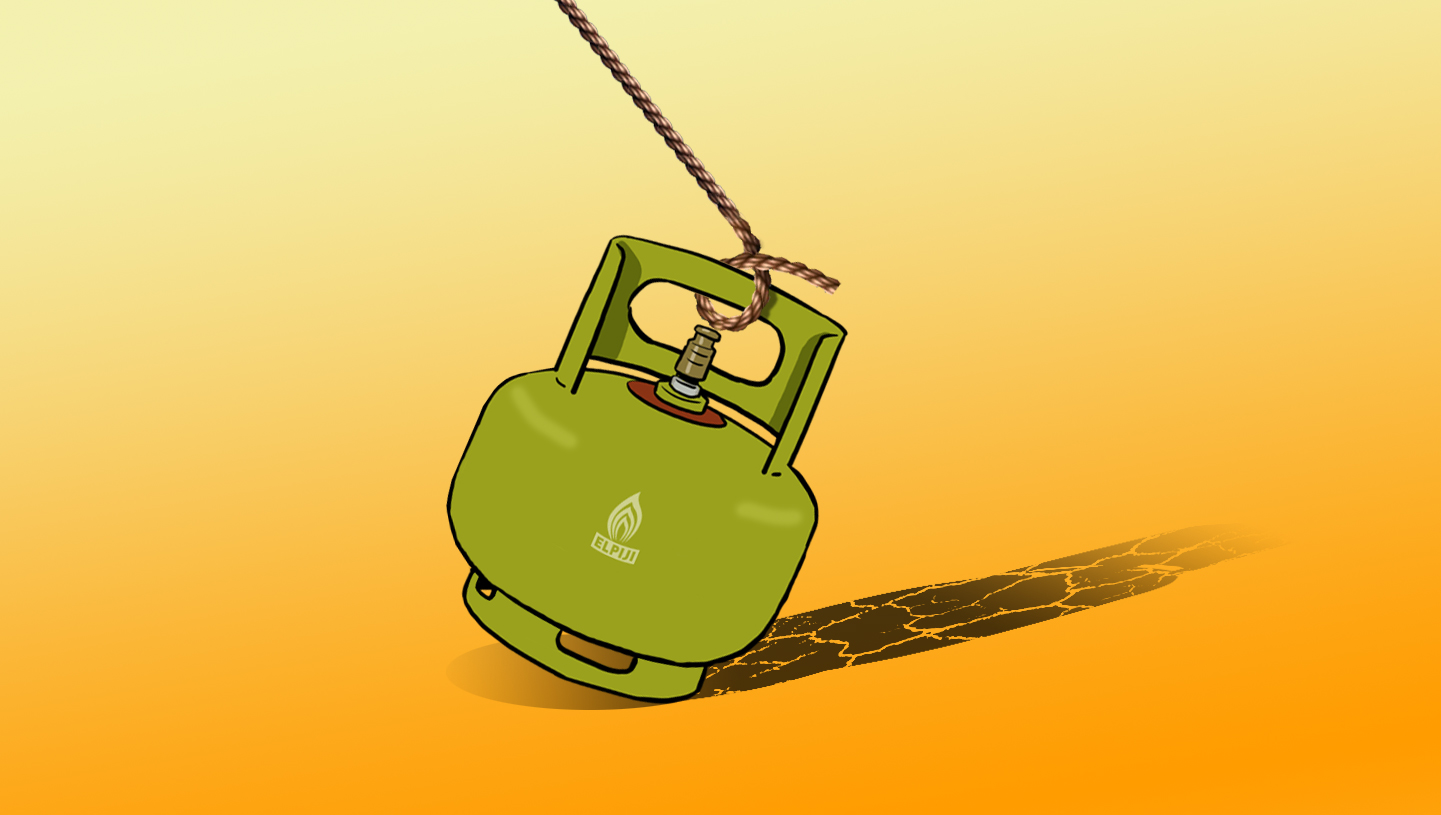Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain bahwa kekerasan di Wamena baru-baru ini bukan merupakan konflik etnis (Tempo.co, 30 September 2019) tidak hanya menyembunyikan persoalan sesungguhnya, tapi juga berpotensi membuat pemerintah lamban dan salah langkah dalam mengelola gejolak sosial di Papua. Pemberitaan media nasional dengan framing kacamata kuda “kerusuhan” yang dibarengi dengan narasi “kebaikan hati” orang Papua melindungi penduduk non-Papua juga memberi kesan seolah-olah tidak ada ketegangan antarsuku atau ras dan agama di Papua.
Banyak tokoh Papua, seperti diangkat sejumlah peneliti, sudah lama mengingatkan adanya perluasan masalah di Papua, dari masalah vertikal (antara orang Papua dan negara) ke arah ketegangan horizontal antara orang Papua dan penduduk yang disebut pendatang. Mereka juga mendesak pemerintah berhenti memakai strategi demografi untuk menguasai Papua. Selain itu, aparat keamanan diingatkan untuk tidak bermain api dengan melibatkan masyarakat pendatang dalam meredam aspirasi politik orang Papua karena hal tersebut menyebabkan eskalasi konflik komunal.
Bagaimana sesungguhnya dimensi etnis atau rasial dan agama dari kerumitan persoalan sosial, politik, dan ekonomi di Papua dewasa ini? Bagaimana seharusnya langkah pemerintah Indonesia?
Dari Vertikal ke Horizontal
Ketegangan laten antarsuku atau ras dan agama di Papua terkait erat dengan—di satu sisi—ekspansi kekuasaan politik, ekonomi, dan militer Indonesia sejak 1960-an dan di sisi lain gerakan emansipasi dan dekolonisasi orang Papua. Sebagaimana kita tahu, integrasi Papua ke dalam Indonesia disertai dengan pendudukan (settler occupation). Pada masa Orde Baru, Papua dijadikan wilayah huni penduduk dari luar Papua melalui transmigrasi dan ekspansi birokrasi sipil dan militer. Selama masa otonomi khusus, migrasi ke Papua terus meningkat bersamaan dengan pemekaran dan akselerasi pembangunan di kota-kota dan daerah otonomi baru. Di kota-kota utama Papua, seperti di beberapa kabupaten, misalnya Merauke, Keerom, Timika, dan Nabire, jumlah penduduk pendatang sudah melampaui penduduk asli. Dalam komposisi demografi semacam itu, orang Papua tidak hanya harus berhadapan dengan kontrol otoritas militer dan sipil Indonesia, tapi juga dengan penduduk pendatang yang dominan dalam jumlah dan pengaruh.
Situasi ini sudah berlangsung lama, ibarat api dalam sekam. Pada 2011, saya menulis tentang ketegangan demografis yang menjadi semacam bom waktu (Jakarta Post, 2 Februari 2011, “Demographic Tensions in Papua: a time bomb?”). Pertumbuhan jumlah pendatang yang cepat disertai dengan model pembangunan, yang oleh antropolog Benny Giay disebut “pembangunan berbias pendatang”, memicu sentimen rasial/etnis dan agama. Setahun setelahnya, dalam artikel lain saya mengingatkan situasi yang mengarah ke darurat kekerasan yang oleh Thomas Hobbes disebut bellum omnium contra omnes, kekerasan semua melawan semua.
Saya mencatat, selain kekerasan oleh aparat dan kelompok bersenjata, kekerasan antarsuku dan agama telah menjadi dimensi baru dalam konflik di Papua. Bukan hanya kekerasan fisik, berkembang juga kekerasan struktural, seperti penguasaan ekonomi-politik lewat konsolidasi etnis dan agama melawan kelompok lain serta kekerasan kultural, misalnya rasisme di satu sisi dan sentimen anti-pendatang di sisi lain (Kompas, 29 Desember 2012, “Darurat Kekerasan di Papua”).
Apa yang terjadi beberapa waktu belakangan tidak hanya mengafirmasi kebenaran analisis itu, tapi juga menunjukkan bahwa kondisi makin parah. Kota-kota utama di Papua, termasuk di pedalaman, makin didominasi pendatang. Kendati otonomi khusus mengatur bahwa posisi gubernur dan bupati adalah hak eksklusif orang Papua, posisi-posisi strategis di pemerintahan dan di sektor ekonomi terus dikuasai penduduk luar. Elite politik Papua juga terkondisikan untuk membangun aliansi dengan paguyuban suku-suku Nusantara, sebuah aliansi yang pada gilirannya memperkokoh posisi tawar dari paguyuban-paguyuban itu. Proyek-proyek afirmatif, seperti gedung pasar bagi mama-mama asli Papua, sangat insignifikan dari segi skala sehingga tidak mampu secara riil mendongkrak keadilan ekonomi.
Sementara itu, penguasaan tanah atas nama pembangunan terus meningkat. Ekspansi tambang, industri kayu, dan perkebunan yang paling rakus mengambil alih sumber daya penduduk asli. Pemekaran kabupaten dan provinsi baru serta pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bandar udara, dan pelabuhan, yang merangsek ke pedalaman justru memperluas dominasi pendatang dan eksploitasi oleh korporasi.
Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya aliansi strategis antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok ultranasionalis, seperti Barisan Merah-Putih dan Paguyuban Nusantara. Ketika kelompok masa bergesekan, (oknum) aparat keamanan pun tidak bertindak netral dan profesional. Sepanjang peristiwa demonstrasi di Jayapura, Wamena, dan Manokwari beberapa waktu lalu, misalnya, kita menyaksikan bagaimana aparat berada bersama warga Nusantara berhadapan dengan orang asli Papua.
Yang lebih parah, pemerintah terkesan tidak mencegah kelompok radikal atas nama Islam membangun basis di Papua. Kasus yang paling kontroversial adalah kelompok Jafar Umar Thalib di wilayah Keerom dan Koya. Di Indonesia, berbagai kelompok di kota seperti Solo, Jawa Tengah, dan Poso, Sulawesi Tengah, menyerukan mobilisasi jihad ke Papua atas nama Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masalah rumit seperti itulah yang merupakan basis material bagi sisi horizontal dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Kendati masyarakat akar rumput seperti di Wamena masih berusaha mengontrol diri agar tidak terperangkap dalam lingkaran setan kekerasan komunal dengan pendatang, sesungguhnya telah terjadi perkembangan ketegangan Papua dari oposisi vertikal ke arah horizontal antara orang Papua dan penduduk suku-suku Nusantara.
Pada saat yang sama terjadi konsolidasi aliansi strategis antara nasionalisme Indonesia di kalangan aparat dan pendatang versus Papua dan sentimen suku/etnis yang juga berdimensi agama dan kelas. Berkembangnya milisi dan kelompok radikal yang memainkan isu nasionalisme dan islamisme kian merumitkan situasi. Celakanya, aparat keamanan makin sulit diharapkan sebagai penegak rule of law dan jembatan perdamaian karena merupakan bagian dari masalah.
Tanggung Jawab Pemerintah
Perlu langkah-langkah strategis dan sistematis dalam rangka mencegah terulangnya kekerasan komunal sekaligus menangani akar kekerasan politik, ekonomi, dan kultural di Papua.
Pertama, pemerintah Indonesia perlu mengakui dan bersama memahami adanya dimensi rasial dan agama dari persoalan di Papua. Hanya dengan pemahaman dan pengakuan itu, pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat dalam mencegah kekerasan dan tidak melakukan kebijakan yang memperparah situasi.
Kedua, pemerintah mengoreksi kebijakan demografi yang selama ini membuat orang Papua menjadi minoritas dan marginal di tanah mereka sendiri. Selain harus menghentikan transmigrasi (terbuka ataupun terselubung), ekspansi pendatang ke kota dan wilayah pemekaran harus dikontrol. Dalam kaitan dengan itu, pemekaran provinsi atau kabupaten baru serta pembangunan Jalan Trans Papua di pedalaman jangan dijadikan sarana untuk ekspansi koloni pendatang serta kontrol militer seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Masyarakat Papua membutuhkan ruang aman untuk bertumbuh dan meng-urus diri mereka sendiri tanpa dipaksa bersaing dengan atau diurus kelompok lain.
Ketiga, pemerintah tidak boleh mencampuradukkan konflik politik dengan konflik sosial antarkelompok. Konkretnya, aparat harus berhenti bermain api dengan mengkonsolidasi penduduk sipil sebagai alat untuk meredam Gerakan Papua Merdeka. Pendekatan keamanan (pengerahan pasukan) juga perlu dievaluasi efektivitas dan dampaknya.
Keempat, untuk mengatasi ketegangan antarkelompok, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha transformasi konflik dan membangun perdamaian. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin komunitas Papua dan Nusantara, lembaga-lembaga agama, serta organisasi kemasyarakatan sipil mencegah mobilisasi kekerasan dan membangun interaksi positif sebagai jejaring transformasi konflik.
Kelima, pemerintah segera menjalankan dialog yang komprehensif dengan elemen-elemen kunci masyarakat Papua, bukan dengan kelompok pro-pemerintah atau kelompok binaan aparat. Selain masalah status politik Papua, agenda mendesak dalam dialog itu adalah bagaimana menangani realitas ke-beragaman ras atau etnis dan agama di Papua sekarang.
Bahwa banyak orang Papua merasa dijajah dan menuntut kemerdekaan adalah kenyataan politik yang mau tidak mau harus dihadapi pemerintah Indonesia hari ini. Ketegangan etnis atau ras dan agama adalah salah satu dimensi dari realitas itu. Semuanya menuntut penyelesaian yang segera dan sungguh-sungguh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo