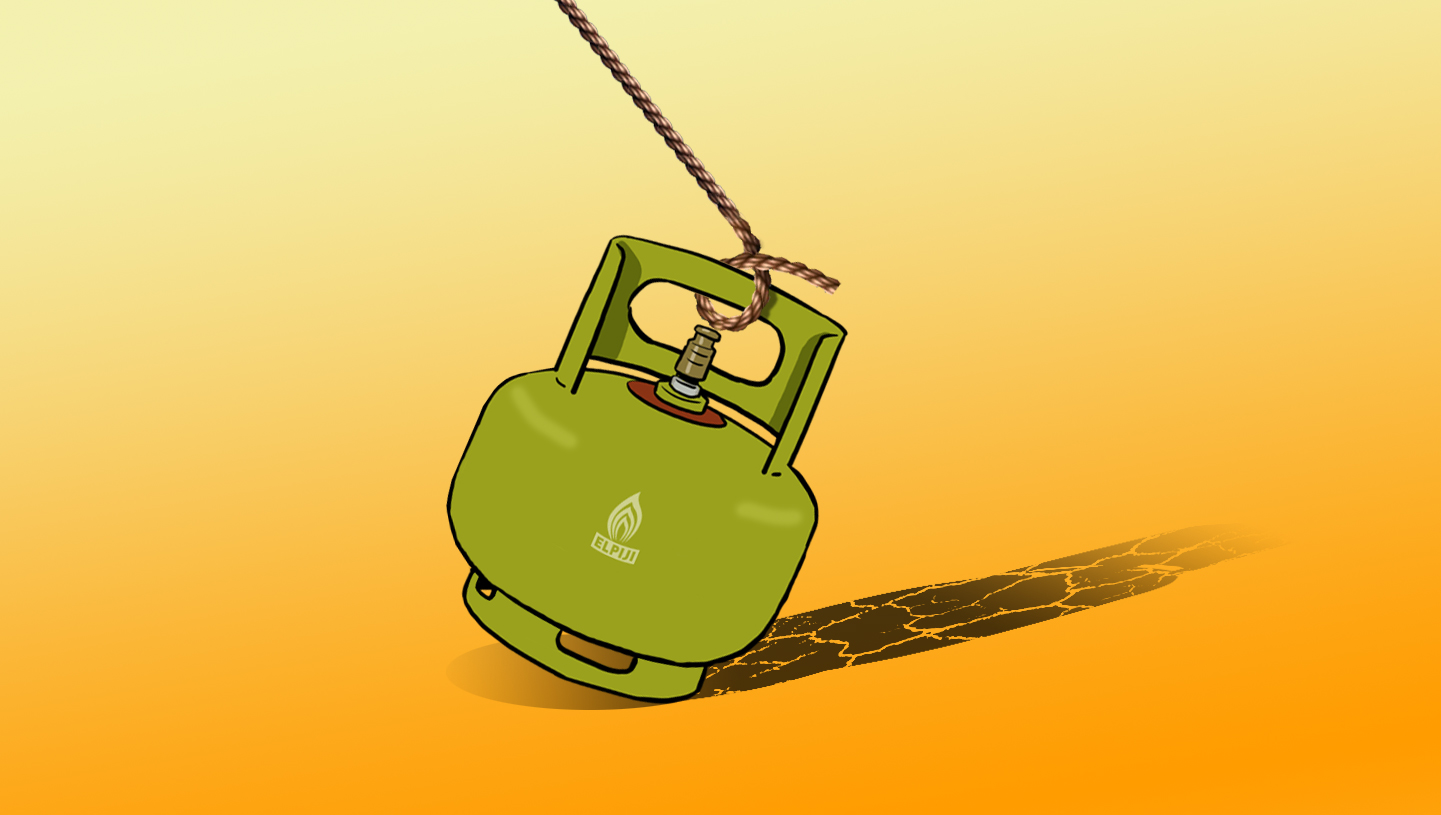Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setidaknya saya berbicara tentang Sherlock Holmes, detektif termasyhur dalam cerita-cerita Arthur Conan Doyle. Juga tentang Romo Brown, pastor Katholik yang memecahkan kasus-kasus kejahatan dalam fiksi G.K. Chesterton.
Ceritanya mengasyikkan karena ia bukan (dan tanpa) petunjuk agama. Agama menyatakan diri punya semua jawab; cerita detektif justru berangkat dengan pertanyaan: siapa yang melakukan X? Bagaimana caranya? Apa motifnya?
Dan lahirlah suspens. Pembaca diletakkan atau meletakkan diri dalam posisi “aku-belum-tahu” dan bergerak ke dalam “aku-ingin-tahu” tentang apa yang berikutnya. Suspens adalah ketegangan yang mendorong cerita ke masa depan yang entah apa nanti.
Ia membuat kita betah. Bayangkan kita baca sebuah cerita yang langsung mengungkapkan siapa sang pencuri dan bagaimana perbuatan itu dilakukan—berbeda dengan misalnya yang dengan memikat dikisahkan Suman Hs. dalam Mencari Pencuri Anak Perawan. Novel ini jelas bukan narasi yang mengikuti model ajaran yang memberitahukan masa depan yang tanpa entah, yang akan membuat kita berhenti sebelum halaman ke-10. Tak ada kejutan lagi.
Itu sebabnya hampir tiap cerita detektif yang tamat kita baca tak akan menarik dinikmati ulang: toh kita sudah tahu siapa pembunuh di dalam kereta api Orient Express dalam cerita Agatha Christie. Kecuali jika narasi yang kita ikuti tiap kali segar kembali, seperti Tinker, Tailor, Soldier, Spy, novel spionase John le Carre. Di ujungnya terungkap siapa agen Soviet yang ditanam jauh di dalam dinas rahasia Inggris, tapi kita akan tetap senang membalik-balik halamannya lagi (atau menonton versi filmnya): Tinker tak hanya melukiskan proses bagaimana misteri dipecahkan, tapi juga, dengan gaya bertutur yang nyaman dan sesekali menyentuh, ini kisah manusia yang lemah tapi tegak karena kewajiban dan yang bercita-cita luhur tapi siap berkhianat.
Kisah spionase Le Carre, seperti cerita detektif Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, atau G.K. Chesterton, memukau karena sepenuhnya tentang kejatuhan dan kemampuan manusia tanpa intervensi Tuhan. Kalaupun ada iman, semua di dasar yang lamat-lamat, atau dalam pigura rasionalitas. Dalam The Blue Cross, Romo Brown mengecam Flambeau: “Kamu menyerang akal. Itu theologi yang buruk.” Dalam fiksi Chesterton, seorang Katholik yang yakin, Romo Brown beberapa kali mengejek orang yang menerima begitu saja penjelasan supernatural.
Di akhir 1920-an, ketika cerita detektif mulai berkembang, di Inggris ada sebuah perhimpunan penulis cerita detektif, London Detection Club. Anggotanya antara lain Agatha Christie dan Chesterton. Di sana ada sejenis sumpah: mereka tak akan menulis cerita dengan memakai “wahyu ilahi”, “sihir dan sulap”(Mumbo-Jumbo), atau “tindakan Tuhan”.
Bahkan tak boleh dipakai “intuisi feminin”. Kita ingat Sherlock Holmes. Ia, yang hidup tanpa menikah dan tak pernah tertarik perempuan, dengan bangga menyatakan keyakinannya kepada kekuatan intelek, bukan intuisi. Dalam The Adventure of the Mazarin Stone ia berkata, “Aku ini sebongkah otak, Watson. Selebihnya hanya tambahan.” Ia bahkan pernah mengatakan, dalam The Naval Treaty, seraya mengagumi indahnya setangkai mawar, bahwa “agama dapat dibangun sebagai sebuah ilmu pasti bagi orang yang menggunakan akal” (the reasoner).
Cerita detektif adalah sebuah indeks datangnya dunia modern dan rasionalisme. Novel termasyhur Il nome della rosa Umberto Eco, yang membenturkan fanatisme agama dengan sikap ilmiah dalam kisah pembunuhan di biara abad ke-12, juga menandai datangnya semangat yang “sekuler”.
Di Indonesia abad ke-20, tokoh utama Mencari Pencuri Anak Perawan (terbit 1932) adalah orang yang pintar yang disebut “Sir Jon”; kata “Sir” itu dipasang karena ia sering menggunakan kata Inggris. Ia lelaki lajang yang tinggal sendiri, hanya bersama seorang pembantunya, di sebuah kota pantai, bukan dusun pedalaman. Di sana berbagai etnis dan agama hidup berbaur dan sesekali dipererat pertandingan sepak bola. Sir Jon berani mengabaikan kekuasaan orang tua kepada anak angkatnya, seorang gadis yang disebut “Nona”: dengan siasat yang amat rapi, Jon menculiknya.
Tiga tahun sebelumnya, di Surabaya terbit dua jilid novel karya Ong Hap Djin, Kang Lam Yau?... atawa Si Boeroeng Walet dari Kang Lam. Saya memperoleh bahan tentang cerita detektif ini dari Doris Jedamski, yang menulis dengan menarik dalam -Clearing A Space: Postcolonial Readings of Modern Indonesian Literature (ed. Keith Foulcher & Tony Day, 2002). Tokohnya, Wat Song, disebut sebagai “Sherlock Holmes dari Timur”. Ia, seperti detektif London itu, didampingi seorang teman dan pembantu, Pouw Long. Wat Song menyadari hidupnya sebagai detektif “partikelir” meniru-niru orang di Eropa. Tapi ia tahu dalam proses penyidikan ada hal yang berbeda yang harus diperhatikan seorang detektif Surabaya, misalnya dalam hal “sepatoe jang bangsa kita pake”. Meskipun demikian, ia tetap mengatakan, “Peladjaran, pendapetan, pengetahoean dan laen-laen sebaginya jang modern, ampir semoeanja dateng dari djoeroesan koelon—Europa—…Ilmoe detective adalah sala satoe diantara itoe pengetahoean modern.”
Pengakuan seperti ini langka di Indonesia awal abad ke-20—juga sekarang. Tapi siapa yang menggemari cerita detektif akan tahu, Wat Song bukan omong kosong. Di dasar tiap penyidikan, asumsinya adalah tak ada kegaiban; bekalnya adalah tak gentar pertanyaan. Detektif Wat Song: sebuah sikap tanpa dogma.
GOENAWAN MOHAMAD
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo