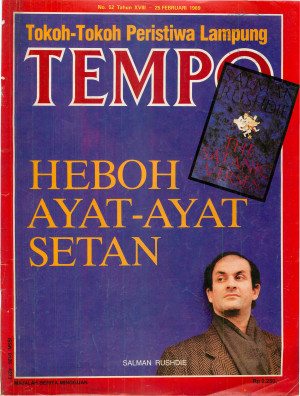SETIDAKNYA tiga puluhan tubuh saudara kita terbaring sudah di pelukan bumi. Inilah "duka sejarah bangsa Indonesia" entah untuk yang keberapa kalinya. Tapi di manakah ruh mereka? Sekelompok hamba Allah sambil meneriakkan "Allahu Akbar!" berperang melawan sekelompok hamba Allah yang juga memekikkan "Allahu Akbar". Tersentakkah para malaikat mendengar ironi itu? Ruh siapa dari mereka gerangan yang langsung bersemayam di surga -- sepertl yang Ia janjikan mengenai para syuhada? Dan ruh siapa yang melayang-layang tak menentu, yang menunggu dan termangu-mangu? Kita punya kebiasaan untuk memperdebatkan pertanyaan semacam itu, seolah kita memiliki wewenang dan kesanggupan. Tidak sekadar memperdebatkannya dalam perspektif meta-hidup, tapi juga sebagai ideologi, filsafat, atau dalam konteks ilmu pengetahuan biasa. Maka, perdebatan itu biasanya sampai ke ada tidaknya sharing kekuasaan, pembagian beras dan masa depan, juga senjata dan kematian. Kita membagi sejarah menjadi fragmen-fragmen yang didasarkan pada keyakinan akan "kebenaran sendiri". Tatkala kemudian kita mendominasi kekuatan, kita angkatlah "kebenaran sendiri" itu menjadi "kebenaran konvensional", "kebenaran konstitusional", yang kita beri baju "kebenaran orang banyak". Kita tidak sanggup memelihara kerendahan hati untuk saling memafhumi bahwa kita sama-sama berada di tengah proses panjang menelusuri "kebenaran yang sejati". Ketika seorang saudara kita sendiri menancapkan anak panah ke ulu hati, ketika demi membela diri kita terpaksa mencabik-cabik nyawa para saudara kita yang lain, tiba-tiba kita pun tersadarkan bahwa kita telah terlalu banyak mengisi sejarah tidak dengan rasa haus akan kebenaran, melainkan dengan gairah keunggulan, kemenangan, dan keperkasaan. Di dalam egoisme "kebenaran sendiri", amat cepat kita menuding: "Kafir". Atau di posisi lain kata kafir itu kita modifikasi secara politis menjadi "Ekstremis", atau "Sempalan". Substansi ketiga tudingan itu sama: kekufuran, keingkaran, khianat. Di atas batu berbongkah-bongkah jalanan sejarah, kereta pembangunan kita tidaklah berjalan semulus yang kita impikan. Kita sering terpaksa menunda kemampuan untuk mengatasi suatu masalah secara obyektif, sehingga untuk menutupi rasa sedih atau menghapus rasa gagal, kita mencoba bersitenang dalam keadaan itu dengan cara mendayagunakan subyektivisme. Kalau sesudah kerja keras bertahun-tahun tak juga bisa kaya, kita manipulasilah kearifan "kaya tanpa harta". Penduduk suku Mandar yang tak bisa naik haji, naik ke puncak Bukit Bawakaraeng untuk memperoleh rasa haji. Kalau kita amat susah rajin salat Jumat, kita bilang kepada tetangga bahwa kita Jumatan langsung di Mekkah. Pelacur sudah kita lenyapkan, kini yang ada tinggal wanita tunasusila. Klta tak pernah menaikkan harga karena kita sanggup menyesuaikan harga. Kita basah kuyup oleh eufimisme. Kesulitan sosial ekonomi yang tak bisa kita atasi secara sosial ekonomi obyektif kita tabiri dengan subyektivisme budaya. Demikian pulalah yang terjadi pada kaum muslimin kita. Inferioritas sosial ekonomi dan keterpinggiran politik mereka -- juga inkonfidensi kultural mereka -- rasanya terlalu jauh untuk mereka jawab secara obyektif. Kaki mereka mengambang di atas permukaan sejarah, tangan mereka gamang untuk begitu saja berpegang pada pilar-pilar nilai di sekitarnya. Bahkan mulut mereka harus mengucapkan kata-kata yang sering bertentangan dengan realitas yang mereka alami. Mereka harus memakan roti basi -- dan itu tak cukup -- mereka masih harus mengucapkan bahwa roti itu enak. Mereka wajib menyatakan bahwa kaki telah mapan berpijak dan tangan telah gamblang berpegangan. Kebanyakan dari mereka menempuh jalan pragmatis dengan mencoba menemukan analogi dan perbesaran-perbesaran dari "ideologi si Boy" di berbagai bidang hidup. Tapi sebagian kecil dari mereka berlari masuk ke dalam gua subyektivismenya masing-masing. Apa yang ada dalam gua itu adalah tingkat pemahaman keislaman yang sektarianistis, dengan fanatisme yang overdosis. Muncullah lingkaran-lingkaran kecil puritanisme, neokonservatisme, formalisme wantah. Kedangkalan pemahaman keislaman -- yang begitu sering diumumkan oleh para pemimpin negara maupun oleh para cendekiawan muslim sendiri -- itu sungguh lumrah. Karena ruang untuk memperkembangkan proses internalisasi nilai Islam justru bukan hal yang cukup disuka oleh para penentu sejarah. Sekat-sekat didirikan dengan cat sekuriti, sebab gumpalan-gumpalan semacam itu memang tampak seperti kumparan rapat gelap. Dan karena gelap, tentulah ia sub dari versi, tentulah ia garis ekstrem dari bagan lumrah, tentulah ia sempalan dari bangunan badan tertentu yang sudah dimapankan. Kalau anak-anak di kelas menjadi sumpek karena begitu banyaknya sekal yang mengkotak mereka masing-masing, maka Segala sesuatu di balik sekat hanyalah kegelapan. Mereka meneriaki kegelapan itu: "Kafir!". Dan kalau kepengapan kelas itu sungguh-sungguh tanpa ventilasi, satu dua anak di kelas itu akan mendobrak sekat di sisinya -- tanpa sempat menakar apa beda antara kesucian dan ketololan. Anak-anak di kelas itu membutuhkan Guru atau Wali Kelas yang -- kalau bisa -- jangan hanya pintar mengutuk. Tapi juga bisa memperluas pandang dari jengkal peristiwa "Anak itu mendobrak sekat" menuju sejarah panjang "Kenapa ia mendobrak". Syukur Guru dan Wali Kelas itu bersedia juga menimbang kembali apa benar diperlukan sekat-sekat serekat dan seketat itu. Anak-anak bingung adakah yang mereka hadapi ini kekuatan ataukah kecemasan. Semua itu saudara-saudara kita sendiri, yang kita kasihi. Mereka pergi, dengan duka, namun entah untuk apa. Barangkali kita tak akan pernah sungguh-sungguh memahaminya. Mereka pergi meninggalkan dunia yang membutuhkan seribu kali kekerasan hati dan takaran daya juang mereka semua. Mereka pergi meninggalkan kita yang dahaga akan manusia-manusia berani mati, bukan manusia-manusia ingin mati. Mereka pergi memasuki sepi, untuk -- barangkali -- kaget sendiri. Subyektivisme memperanakkan subyektivisme, untuk ditampar, dikubur, dan dikutuk oleh subycktivisme. Klenik melahirkan bayi klenik, untuk dicekik dan disumpahserapahi klenik. Berdukakah kita? Kalau menangis, kok cengeng. Kalau tidak, sudah sedemikian dinginkah kumanusiaan kita?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini