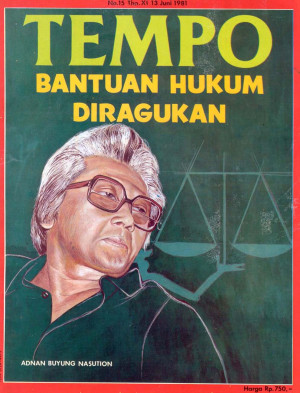MEMBERIKAN ceramah kependudukan di Jawa, Bali dan Lombok cukup
enak dan mudah. Dari sudut mana saja masalahnya bisa
disingkapkan dengan meyakinkan. Semua dimensinya mencuat.
Imajinasi yang dangkal sekalipun sanggup menjamah persoalan
kependudukan secara memadai.
Kalau mau sedikit dramatis, bisa disodorkan kisah tragis di
Lombok. Bisa dicuplik cerita Putu Arya Tirtawirya yang
melukiskan betapa maut menggerayangi Lombok Selatan di musim
paceklik. Dalam cerita Seekor gagak menggarisnya dari arah
kampung, berkata Putu perihal gadis Rini yang kelaparan:
"Kemarin ibunya, selang sehari dengan adik laki enam tahun.
Kehilangan yang berturutan: beras - jagung ubi - dedaunan -
bungkil pisang - umbi gadung yang memabukkan - ibu dan adik.
Esok lusa ayah? Sang ayah mengerang."
Lain ceritanya kalau ceramah diberikan di Banda Aceh, Padang
atau Pakanbaru. Tidak mudah ditangani. Memang mereka sudah
dengar perihal Pulau Harapan yang bakal karam mengikuti jejak
Pulau Jawa, sebab pertumbuhan penduduk yang ngetop. Tapi
kedengarannya seperti dongeng, karena bukankah hutan Sumatera
begitu luas? Malah masalah gangguan gajah dan harimau biasanya
menjadi perbincangan yang lebih menarik daripada bahaya
pertambahan penduduk.
Dan tidak jarang penceramah kewalahan sebab orang Sumatera suka
tanya macam-macam.
-- Kami diajak berkabe. Kami diajak berpancawarga, stop setelah
tiga anak. Kami diajak bercaturwarga, stop setelah dua anak.
Mengapa kami disuruh membatasi jumlah anak, membatasi jumlah
penduduk? Sedangkan di pihak lain didatangkan transmigran ke
daerah kami. Mengapa begitu? Minta penjelasan.
Gawat. Kalau dikatakan transmigran itu petani maju, lebih maju
dari petani Sumatera, buktinya kurang lengkap. Apalagi kalau
yang datang itu bekas gelandangan, yang nyata lebih mahir
mengolah puntung rokok daripada mengolah tanah. Maka terpaksalah
dijawab dengan samar-smar: itu kebijaksanaan Pemerintah maksud
Pemerintah meningkatkan kesejahteraan bangsa, meratakan
pembangunan, meningkatkan asimilasi, meningkatkan ketahanan
nasional.
Namun, pembaca yang budiman, kalau kita maklum liku-liku
kehidupan suku terasing Sakai di Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau, persoalan penduduk Sumatera menjadi jernih, sejernih
Sungai Siak. Seperti orang Sumatera lainnya, orang Sakai seperti
balam, mata lepas badan terkurung. Mereka tinggal di hutan atau
di pinggir hutan tapi dilarang menebang pohon. Kalau mau
selamat, sesungguhnya mereka perlu berkabe, stop setelah dua
anak.
Orang-orang Sakai yang sudah dimukimkan di suatu tempat, di
pinggir hutan 110 km dari Pakanbaru, punya kisah begini. Tiap
keluarga dapat rumah dari Pemerintah, tambah tanah kering satu
HA, tambah alat rumah tangga, tambah kapak dan cangkul. Di
samping itu beras empat kilogram per jiwa per bulan, dan garam.
-- Kami di sini seperti masuk perangkap, Pak. Dulu kami menerima
janji yang muluk-muluk, kami akan dimajukan, pendidikan dan
kesehatan akan diperbaiki, katanya kesejahteraan akan
ditingkatkan. Tapi nyatanya ....
Niat Pemerintah memang jelas terurai dalam kata dan gambar yang
ditempelkan dengan rapi di dinding: "Mari Belajar", "Mari Hidup
Sehat", "Mari Membangun Bersama." Tapi masih jauh rupanya, jauh
sekali.
-- Bagaimana bisa sejahtera, Pak. Uang masuk tidak ada.
Pekerjaan tidak ada. Entah mengapa, pekerjaan upahan tidak
diberikan kepada kami.
-- Misalnya?
-- Misalnya, kontraktor tidak mau memberikan pekerjaan apa pun.
Sebodoh-bodohnya kami, paling tidak jaga malam kan sanggup. Kami
biasa di hutan, kan bisa jaga malam? Itu pun tidak. Pekerja
didatangkan dari luar.
Beberapa kali diulanginya: masuk perangkap. Dia merasa getir.
Getir karena hutan pun ternyata sudah dimiliki orang. Dan mereka
pun ditakut-takuti. Awas, kalau mengganggu hutan. Awas, kalau
mengambil kayu dari hutan milik pemegang HPH. Dilarang mengambil
kayu gelondongan. Dan kepada mereka dijelaskan peran poster yang
berbunyi: "Selamatkan Hutan, Air dan Tanah Kita."
Tanah kering yang mereka terima satu HA jauh lebih kecil
daripada jatah para transmigran. Mengapa mereka, yang jumlah
jiwanya tak seberapa ini, tidak bisa disamakan dengan
transmigran, wallahualam. Sulit diterangkan memang. Karena
bukankah kita sudah sepakat meningkatkan harkat mereka sebagai
manusia, diintegrasikan seutuhnya dalam kehidupan bangsa?
Dengan asumsi begitu jauh tercecer dalam proses perubahan dan
kemajuan, persoalan etika yang begitu mendasar tidak kita
perdebatkan lagi, seperti halnya kita tidak mempertanyakan
Proyek Koteka dan yang sejenisnya. Tidak dipertanyakan: apakah
bijaksana membongkar kehidupan dan kebudayaan suku terasing
sampai ke akar-akarnya? Katakan lah tindakan itu bisa
dibenarkan, tetapi apakah sudah dilakukan semua daya upaya agar
mereka tidak tercecer lagi? Dan apakah mereka tidak semakin
tercecer lantaran terkatung-katung antara dua dunia?
Apa makna tanah kering satu HA? Dari segi masalah kependudukan
seyogyanya orang Sakai tidak lagi memecah-mecah tanah satu HA
itu. Demi keselamatan petak tanah itu dan demi kelangsungan
hidup mereka sendiri, mereka perlu konsekuen beranak dua. Tidak
peduli hutan Riau begitu luas, tidak peduli berapa prosen hutan
di tangan pemegang HPH, tidak peduli gajah banyak atau sedikit,
suku Sakai memerlukan caturwarga. Mereka memerlukan pamflet
caturwarga di samping pamflet lainnya yang sudah beredar:
"Mari Belajar", "Mari Hidup Sehat", Mari Membangun Bersama",
"Selamatkan Hutan, Air dan Tanah Kita."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini