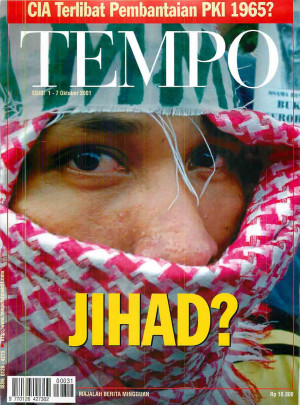Binny Buchori *)
*) Sekretaris Eksekutif INFID
SALAH satu agenda mendesak yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Megawati adalah beban utang yang amat berat. Beban itu terdiri atas beban utang pemerintah dan swasta, dalam negeri dan luar negeri.
Total utang pemerintah Indonesia, luar negeri dan dalam negeri, kurang-lebih US$ 150 miliar atau 100 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dampak langsung dari beban utang yang sedemikian besar itu adalah mengecilnya anggaran pembangunan, terutama untuk kesehatan dan pendidikan, yang anggarannya lebih kecil 40 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 1995/1996.
Jelasnya, adanya beban berat bagi pemerintah dalam membayar utang dan cicilannya menyebabkan setiap rakyat Indonesia membayar US$ 45 per tahun kepada kreditor dan hanya mendapatkan US$ 2 untuk anggaran kesehatan.
Kecilnya anggaran kesehatan itu menyebabkan UNICEF mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia sesungguhnya secara nyata menghadapi "generasi yang hilang" karena malnutrisi, buruknya status kesehatan, dan tidak terjangkaunya pendidikan. UNICEF juga mengungkapkan, dari 11 ribu bayi yang dilahirkan di Indonesia setiap hari, 800 di antaranya meninggal karena kekurangan gizi dan penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah.
Apakah usaha yang ditempuh pemerintah Indonesia—baik Habibie, Abdurrahman Wahid, maupun Megawati—untuk mengatasi hal ini? Mereka meminta pengunduran waktu pembayaran utang luar negeri (penjadwalan kembali atau rescheduling) kepada kreditor melalui Paris Club. Artinya, untuk sementara Indonesia tidak perlu membayar, tapi pada saat jatuh tempo, Indonesia bersedia dan harus membayar utangnya.
Pada September 2001 lalu, sedianya pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan Paris Club untuk kedua kalinya (Paris Club I pada 1998). Namun, penandatanganan ini untuk sementara ditunda karena peristiwa penyerangan World Trade Center, yang menyebabkan Amerika Serikat berhalangan hadir. Dalam skema ini, pemerintah Indonesia mendapatkan penundaan sekitar US$ 10 miliar yang akan jatuh tempo pada Maret 2002. Apabila Indonesia tidak mendapatkan penjadwalan kembali, pada April 2002 Indonesia harus membayar utang kepada kreditor sebesar US$ 10 miliar.
Meskipun belum ada keterangan resmi, sudah tampak dari sekarang bahwa pemerintah Indonesia akan kembali meminta penjadwalan utang pada Maret 2002 alias masuk ke Paris Club III. Ini terlihat dari permintaan yang disampaikan Megawati dalam kunjungannya ke Jepang dan juga Amerika.
Pertanyaan yang timbul: apakah penjadwalan ulang utang merupakan solusi yang komprehensif atas persoalan utang luar negeri pemerintah Indonesia yang sekarang berjumlah sekitar US$ 70 miliar itu serta meletakkan Indonesia dalam jebakan utang alias debt trap? Apa saja yang akan dikorbankan oleh pemerintah untuk "menghormati perjanjian" dengan para kreditor? Sampai berapa lama Indonesia akan menunda pembayaran utangnya? Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Ekuador, yang keluar-masuk Paris Club selama 9 kali dan tetap saja memiliki beban utang yang sama sekali tidak sustainable?
Data dari Bank Indonesia tahun 2000 menyebutkan bahwa Indonesia harus membayar kepada kreditor luar negeri uang sejumlah US$ 7,5 miliar pada tahun 2001, dan empat tahun berikutnya masing-masing US$ 10,97, US$ 9,32, US$ 8,3, dan US$ 8,2 miliar.
Melihat begitu besarnya beban utang, baik dalam jumlah maupun persentase, jelas bahwa Indonesia tidak akan mampu membayar utangnya. Penjadwalan kembali yang didapatkan Indonesia dari Paris Club hanya memberikan kesempatan bernapas selama dua tahun dan menunda pembayaran cicilan sebesar US$ 5 miliar setiap tahunnya. Di pihak lain, tim ekonomi Megawati juga harus menyadari bahwa apabila mereka memilih keluar-masuk Paris Club, sesungguhnya mereka juga memilih mengorbankan belanja sosial dengan akibat makin buruknya status kesehatan dan layanan pendidikan.
Dengan demikian, sebenarnya tidak ada pilihan bagi tim ekonomi Megawati selain meminta pemotongan utang. Argumen yang selama ini disampaikan bahwa Indonesia tidak termasuk sebagai highly indebted poor country sebenarnya bisa dengan mudah dipatahkan karena struktur utang Indonesia, menurut laporan Bank Dunia yang dimuat dalam Global Development Finance tahun 2000, menempatkan Indonesia dalam kategori severely indebted low income country (SILIC). Sebagai SILIC, Indonesia berada dalam satu golongan dengan Mali, Malawi, bahkan Etiopia. Alasan lain yang selalu diajukan, apabila Indonesia meminta pengurangan utang, hal ini akan menurunkan creditworthiness dan menyebabkan investor lari. Kenyataannya, saat ini, tanpa ada permintaan pemotongan utang pun, Indonesia terus mengalami capital flight dan credit rating Indonesia terus menurun.
Ada beberapa argumen yang bisa diajukan oleh tim ekonomi kita untuk meminta pemotongan utang. Pertama, adanya kewajiban negara untuk melindungi penduduknya serta menjamin hak sosial dan ekonomi warganya melalui anggaran yang cukup untuk belanja sosial. Kedua, utang yang ditanggung oleh pemerintah saat ini di-wariskan oleh pemerintahan Soeharto yang korup, otoriter, dan tidak melakukan persetujuan dengan rakyatnya tentang berbagai perjanjian pinjaman—istilah yang sering digunakan adalah odious debt atau utang najis. Ketiga, para kreditor pada 1971 memberikan pengurangan utang kepada Soeharto karena adanya Perang Dingin. Dengan demikian, apa yang bisa didapatkan oleh Soeharto juga bisa didapatkan oleh Megawati.
Dengan argumen ini, pemerintah Indonesia bisa maju ke meja perundingan melalui sebuah konsultasi internasional yang dipimpin oleh pihak ketiga yang independen. Konsultasi ini akan menghasilkan diskusi tentang kemampuan pembayaran pemerintah Indonesia tanpa mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Untuk mencapai persetujuan ini, tentu saja pemerintahan Megawati harus menunjukkan kesungguhannya dalam memberantas korupsi dan menanggulangi kemiskinan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini