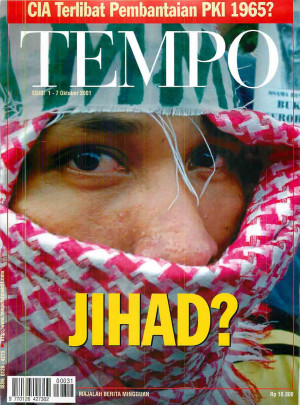J.E. Sahetapy *)
*) Guru besar emeritus Universitas Airlangga dan anggota DPR-RI
DI zaman Soeharto berkuasa, sepanjang yang diketahui, tidak ada yang memiliki keberanian untuk secara transparan mempersoalkan "raison d'etre" adanya kepolisian dalam ABRI. Pada waktu konferensi hukum pidana dan kriminologi di Yogyakarta, lebih-kurang dua dasawarsa lalu, saya untuk pertama kali mempersoalkan keberadaan institusi kepolisian dalam ABRI. Saat itu, saya ditentang bahkan antara lain oleh jenderal senior dalam kepolisian. Tentu dari ABRI pun ikut menolaknya. Itu tidak mengherankan.
Namun, akhirnya, memiliki mimpi yang indah tentang kepolisian seperti menjadi kenyataan ketika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi dipisahkan dari ABRI. Ini memang seperti mimpi indah karena selama ini Polri telah tercemar berbagai penyakit yang menakutkan yang hingga kini belum juga dibenahi dan disembuhkan. Harapan itu makin membubung dengan adanya Undang-Undang Kepolisian, yang kini sedang dibahas di DPR. Diharapkan, dari rencana itu Polri akan menjadi Polri yang profesional, bersih, berwibawa, dan adil.
Nyatanya, apa lacur. Tiba-tiba saja muncul berita di surat kabar bahwa ada beberapa Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) yang menginginkan agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang sekarang dipertahankan. Ini menyebabkan mimpi yang indah tentang Polri yang profesional tiba-tiba menjadi buram. Para Kapolda tersebut tampaknya mulai kehilangan "elan" atau semangat profesionalisme dan seperti sedang bermain akrobat politik. Permainan seperti ini amat berbahaya dan membuat aparat polisi jadi terombang-ambing di antara kekuasaan, ibarat dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Dalam soal ini, benarlah apa yang ditulis John Stott: "Morality can not be legislated, but behaviour can be regulated."
Polisi adalah orang sipil berbaju polisi, bukan berbaju tentara. Falsafah, visi, dan misi Polri berbeda secara "diametral" dari tentara. Itulah sebabnya diharapkan, melalui Undang-Undang Kepolisian yang baru, bisa terbentuk Polri yang profesional, yang bukan saja policing the community, tetapi juga dan terutama communicating with the community. Mengapa polisi harus bersikap demikian? Contoh saja kepolisian di Inggris, yang bisa berhasil—tanpa senjata, tanpa kekerasan, dan jelas tanpa pemerasan dan pungli—menjamin keamanan dan ketertiban, disukai dan disayangi oleh masyarakat Inggris.
Lalu, bagaimana dengan polisi kita? Banyak berita-berita di media massa tentang kepolisian yang negatif. Ada oknum polisi digebuk, kantor kepolisian diserbu, dirusak, atau dibakar. Ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Polri. Dan, sebagaimana ungkapan "ikan yang busuk bukan berbau di ekornya, melainkan di kepala ikan busuklah bercokol bau busuk itu", secara "mutatis mutandis" hal itu memberi kesan serupa pada institusi kepolisian kita.
Bagaimanapun, mimpi agar polisi Indonesia bisa jadi baik masih tetap ada, dan saat ini mimpi itu sedang diperdebatkan di DPR melalui RUU Kepolisian. Namun, dari konsep pemerintah q.q. Polri semula, masih terlihat betapa polisi masih "endemis" dengan berbagai penyakit. Ada kesan Polri masih ingin berkuasa (secara mutlak). Belum terlihat keinginan mereka untuk melayani, seperti yang terjadi sekarang melalui pungutan, pemerasan, dan cara-cara yang hanya mungkin bisa terjadi di zaman perang atau di era kekacauan atau seperti di masa lalu.
Kerja polisi kerap dipertanyakan. Mereka menggilas dan menangkap nyamuk kecil, tapi serangga besar dengan enak saja menerobos jaring kepolisian. Terlalu banyak retorika bombastis dari pimpinan dalam institusi kepolisian. Kritik intern tidak ditoleransi, malahan ditindas secara tidak manusiawi agar yang lain-lain menjadi takut. Kenaikan pangkat, mutasi, dan penempatan belum didasarkan atas merit system. Yang tampak seolah-olah nepotisme angkatan dan faktor like and dislike.
Perjudian tampaknya seperti terus dipelihara. Penindakan seperti sudah terencana dan diketahui sebelumnya. Belum terlihat doktrin equality before the law. SP3 seperti komoditi dagang di bursa efek. Hardikan kepada bawahan untuk bekerja, dan terutama berkelakuan yang baik agar "kami bisa bertemu kalian" di surga, ternyata hanya suatu mimpi kosong belaka. Sebab, ketika para bawahan tiba di surga, ternyata atasan yang memberi wejangan telah terdampar di neraka. Quo vadis? Jawabannya: que sera-sera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini