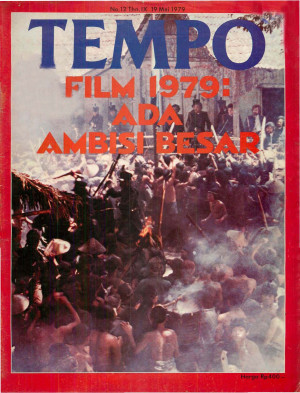PADA suatu hari Gareng, Petruk dan Bagong begitu saja --
mendapatkan diri mereka berada di alam sonya ruri, alam-antara
yang tidak kenal siang atau malam, alam yang hanya dihuni oleh
para lelembut. Di depan mereka duduk bagaikan batu-karang ayah
mereka, Semar.
Dengan bingung ketiga panakawan itu bertanya kepala ayah mereka
apa yang sedang terjadi. Semar menjelaskan bahwa dia sedang
memisahkan diri dari para ksatria yang biasa mereka ikuti, para
pemimpin yang di atas itu. Semar ingin melihat dapatkah mereka
itu hidup tanpa para panakawan. Dapatkah mereka hidup terpisah
dari orang-kecil yang biasa mengikuti mereka.
Maka Semar memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menemui
Arjuna mempertanyakan hal itu. Bila Arjuna berpendapat bahwa
sebagai seorang ksatria-raja dia tidak dapat hidup tanpa
panakawan maka dia musti berusaha mencari di mana Semar sekarang
sedang berada. Siapa yang dapat menemukan Semar dan dapat
berbicara dengan dia akan mendapat wejangan Wahyu
Toh-Jali-Abadi. Toh berarti tanda, jali berarti bibit dan abadi
. . . ya, abadi. Alkisah, demikian Semar bersabda, mereka yang
mendapatkan wahyu itu akan mampu menguasai wahyu kerajaan yang
sebenarnya . . .
Sementara itu Batara Ismoyo, dewa tertua yang mengendon di dalam
badan-kasar Semar berangkat ke Suralaya, markas-besar para dewa,
ingin mengusulkan kepada Batara Guru agar dia segera menurunkan
Wahyu Toh-Jali-Abadi ke dunia karena dunia sedang dalam keadaan
krisis yang gawat. Para staf dewa di markas-besar dewa itu tentu
saja menganggap kedatangan Ismoyo yang begitu saja tanpa belet
terlebih dahulu, kurang ajar. Dewa itu ada di lapisan tertinggi
birokrasi, dus kudu dihormati. Maka para dewa itu beramai-ramai
mengeroyok Batara Ismoyo untuk mengusirnya kembali ke bumi.
Dewa-dewa itu kalah. Mereka lupa bahwa Ismoyo sebagai dewa yang
tertua yang ditugaskan untuk berada di tengah manusia akan
selalu berada dalam kondisi yang paling sakti bila sekali-sekali
dia naik ke Suralaya untuk mempertanyakan kepentingan yang
mendesak dari para manusia biasa di bumi. Batara Guru-pun,
presiden dari para dewa itu, tak akan mampu mengalahkannya . . .
***
Orang yang bercerita bagaikan memberikan penataran hubungan
antara, pemegang kekuasaan dengan rakyat itu bukanlah seorang
pujonggo ulung yang mumpuni olah-sastra dan filsafatnya. Bukan
pula seorang dalang dengan mutu virtuoso seorang Nartosabdo atau
Anom Suroto yang terkenal itu. Bukan pula seorang yang baru
lulus dari kursus penatar P4 di Jakarta.
Dia adalah seorang dalang desa yang sederhana. Tua, sedikit
kisut dan ompong, usianya merangkak mendekati 65 tahun.
Dibandingkan dengan para dalang superstars honorariumnya yang
cuma Rp 25.000, termasuk gamelan, pemukul gamelan dan pesinden
itu pastilah hanya peanuts alias kacang-cina saja.
Suaranya sudah serak dalam mengejar nada yang tinggi seringkali
tidak sampai. Bahasanya tidak selalu halus dan kaya akan
metaphora. Karakterisasi suara dari para tokoh yang
ditampilkannya tidak selalu pas bahkan seringkali kacau suara
siapa mewakili siapa. Sabetan wayangnya juga sedang-sedang saja.
Itulah pak Kiat dalang desa yang beberapa waktu yang lalu
sempat saya lihat dalam satu pesta sunatan di suatu desa kecil
di kabupaten Klaten. Konon dalang ini termasuk dalang yang laris
yang ditanggap orang dari desa ke desa.
Apa yang membuat dalang ini menarik dan populer? Ciri-ciri
kwalitas seperti tersebut di atas pastilah bukan merupakan daya
tarik yang mempesona. Mungkin sekali pada kepolosannya, pada
keunikan konsep cerita carangan yang dilemparkannya, pada
kejituan wawasannya tentang keadaan yang aktuil, pada rasa
humornya yang tajam.
Di tengah suasana panca-roba dari desa-desa kita sekarang (hama
wereng, korupsi bimas, kredit bank rakyat yang tidak terbayar
kembali, pengganti bibit padi baru ke bibit padi baru yang
lain), mungkin sekali cerita carangan a la Kiat itu mempunyai
daya-tariknya sendiri. Di desa-desa itu mungkin rakyat yang
menonton wayang pak Kiat mengenal kembali "batara guru-batara
guru." "semar-semar" atau "ismoyo-ismoyo" mereka. Dan sekali
begitu rakyat itu mungkin sekali juga membayangkan
"wahyu-wahyu"-nya sendiri yang bakalan turun.
Apakah ini gejala eskapisme? Gejala mencari hiburan untuk lari
dari kenyataan pahit dari kehidupan sehari-hari seperti pada
mereka yang pada melihat film komersial baik Indonesia atau
asing? Mungkin. Mungkin juga tidak.
Setidaknya menonton wayang di komunitas desa begitu masih ada
unsur ritusnya. Yakni ritus peneguhan kembali solidaritas mereka
menjadi warga satu komunitas.
Bukan satu kebetulan -- saya kira -- bila pada jam 1 pagi itu,
sesudah nasi gule selesai disantap, sesudah Semar dan Ismoyo
selesai mendudukkan persoalan antara rakyat dan pemegang
kekuasaan dan bisa ditarik kesimpulan bahwa hanya Arjuna yang
bisa mendapatkan wahyu, tamu-tamu itu hampir serentak berdiri
minta pamit pulang ke rumah masing-masing. Ritus solidaritas
selesai, pesan ki dalang sudah tertangkap. Adakah roso begini
pada penonton di gedung bioskop?
* * *
Mungkin sekali dalang-dalang desa seperti pak Kiat itu lehih
penting buat masyarakat pedesaan Jawa ketimbang para dalang
superstars dengan honor ratusan-ribu rupiah yang seringkali
ditanggap demi untuk menjaga gengsi sosial para elite desa.
Tanpa disadari -- karena dia seniman yang baik -- orang seperti
dalang Kiat itu adalah justru "semar-semar" kecil yang berada di
alam "sonya ruri"-nya sendiri yang harus kita cari untuk
membimbing kita, memberi tahu kita tentang kearifan hidup.
Dan orang seperti dia itu -- saya kira -- tidak membutuhkan
tingkat virtuoso yang bagaimanapun juga. Format sosial dan
ekonomi desa beserta khalayaknya, audience-nya, tidak
membutuhkan virtuoso seperti itu.
Kalau katharsis kecil-kecilan bisa dicapai di desa sono dengan
sikap sederhana yang dibarengi dengan intuisi tajam, mau apa
lagi sih . . .
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini