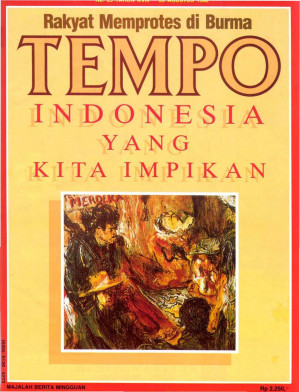SETIAP bangsa bermimpi. Tapi tak semua bangsa sama. Konon, hanya mereka yang sudah cukup usia di dalam sejarah biasa bermimpi di malam hari. Seseorang yang arif pernah menulis, mereka yang bermimpi di malam hari tahu bahwa mimpi sering hanya sebuah angan-angan yang sombong: ketika matahari terbit, dan jendela jadi terang, apa yang yang semalam dilamunkan ternyata akhirnya tak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Mereka yang bermimpi di siang hari sebaliknya bisa salah sangka. Mereka rancu membedakan mana yang Dichtung dan mana yang Warheit, mana yang khayalan dan mana yang bukan, mana pengharapan yang terlampau muluk dan mana yang sewajarnya. Dan mimpi di siang hari bolong itulah yang umumnya terjadi pada bangsa yang belum lama dilahirkan bangsa yang belum sempat banyak mengenal malam. Hari ini Indonesia berumur 43 tahun. Kita masih teramat muda dalam ukuran sejarah manusia, tapi kita juga bukan bangsa kemarin sore. Kita sudah mulai tahu apa artinya kecewa. Kita sudah mulai mengenal harapan yang hanya terpenuhi sebagian. Tapi kita masih kaya dengan angan-angan yang panjang. Tidak apa. Cukup sah sebuah mimpi yang dipendam, karena perjuangan selalu dimulai dari sana: dalam lakon Bebasan Roestam Effendi, sang pemuda berangkat melawan Sang Angkara Murka setelah mimpi itu datang padanya. Pada akhirnya memang tak ada bangsa yang berhenti memasang lamunan: mimpi, bagaimanapun, lahir dari keinginan dan penderitaan. *** LEBIH dari 43 tahun yang lalu, setiap hari sebelum 17 Agustus 1945, kita bermimpi tentang kemerdekaan. Kita bermimpi tentang sebuah hidup yang tidak lagi dimiliki bangsa lain. Kita bermimpi tentang sebuah ruang tempat kita tak cuma menumpang. Sebab, bertahun-tahun lamanya, kita berdiri di luar sebuah gedung yang tak pernah boleh kita masuki -- karena kita cuma inlader. Di luar itu kita pun mendambakan suatu saat ketika titah yang sewenang-wenang itu tak ada lagi. Dalam sebuah sajak Multatuli, pemuda dusun yang sedih dan bernama Saijah itu membandingkan dirinya dengan bajing dan rama-rama. Ia tahu ia tak sebebas tupai serta kupu-kupu yang bergerak dari pohon ke pohon. Ia tahu ia dipaksa pergi, dan merasakan sembilu yang memisahkan dirinya. Ia tahu ia tak boleh berada di tanah kelahirannya lagi: di kampungnya nun di Badur itu ia hanya seekor rusa luka yang diburu. Ia adalah seorang yang kerbaunya telah direbut dan ayahnya telah dibunuh, dan ia melawan. Itu tidak diperkenankan. Kekuasaan Belanda memang kemudian membunuhnya. "Aku tak tahu di mana aku akan mati," demikianlah Multatuli menuliskan nyanyian Saijah yang tak terucapkan. Dan orang-orang sekampung Saijah, orang-orang sebangsanya -- yakni kita semua sebelum 17 Agustus 1945 itu dengan tajam merasakan betapa benarnya nyanyian itu: kita tak bisa menentukan nasib kita sendiri. Kita bahkan tak bisa mendesain masa depan kita sendiri. Masa depan itu, oleh penjajahan, telah dilambangkan dengan pintu-pintu di depan gedung societet yang nyaman: di gerbangnya tertulis peringatan "dilarang masuk", khusus bagi kita yang datang dari jalan kampung yang busuk. Sementara itu, kita tahu: tanah larangan itu adalah ruang hidup tempat kita dibesarkan. "Aku tak tahu di mana aku akan mati," kata Saijah. Tanpa kemerdekaan, kita bahkan tak tahu di mana sebenarnya kita hidup. *** KARENA itulah kita bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Karena itu kita berseru, agar "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya" ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Tapi kita terkadang lupa, bangsa yang bagaimanakah yang bangun jiwa dan badannya itu. Kita terkadang tak teringat bahwa kita pernah mengharapkan akan datangnya sebuah masyarakat yang lain dari yang kita saksikan dalam penghambaan kolonial dulu. Kita mengharapkan orang-orang yang tak merundukkan tubuhnya karena digertak dan orang-orang yang tak gentar hatinya untuk berpikir. Dengan kata lain, bangsa yang bangun jiwa dan badannya adalah bangsa yang tidak terdiri atas anjing-anjing kurus, yang berjalan dengan ekor yang tersembunyi di selangkangan. Anjing yang semacam itu tidak bisa mengalami kemerdekaan. Anjing yang semacam itu adalah ibarat seorang petani Badur yang telah dikuras harta dan keberaniannya, terbongkok-bongkok membisu di hadapan demang Parang-Kujang. Ia tahu penguasa itu merampok milik dan kebanggaannya, tapi ia hanya merunduk. Ia bahkan tidak berani meragukan, apa hak Tuan Demang yang berkuasa itu dan apa yang bukan haknya. Di dalam badan yang terantai dan jiwa yang terpenjara, kita diperlakukan sewenang-wenang tapi kita tidak memprotes. Kita bahkan tak berani bertanya. Di luar dan di dalam ruang sunyi, yang ada hanya rasa takut. Maka, ketika kita bermimpi tentang sebuah negeri yang merdeka, kita sebenarnya mengharapkan sebuah bangsa yang tak dirundung oleh takut. Dengan itulah sebuah bangsa berdiri tegak dan tersenyum lega. Dengan itulah kita selalu akan bisa bernyanyi yakin dan berseru jernih, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ...." *** ADA seorang ahli sejarah yang mengatakan bahwa di antara bahasa-bahasa Asia, hanya dalam bahasa Indonesia dan Melayu terdapat kata yang dapat menerjemahkan konsep "freedom". Kata itu adalah "merdeka". Asalnya dari suatu pengertian Sanskerta tentang orang yang memiliki kekuasaan spiritual atau kekayaan yang besar, yang disebut mahardika. Kata itu nampaknya telah dipakai dalam abad ke-7, di Sriwijaya, dan tersebar jauh sampai Filipina. Ketika kota-kota berbahasa Melayu di abad ke-15 mengembangkan suatu konsep hukum yang jelas tentang individu-individu yang bukan budak, maka kata "merdehika" itulah yang dipergunakan. Ketika di abad ke-18 orang Bugis dan Makasar membuat klasifikasi penduduk, mereka juga sudah mengenal beda antara ata (budak) dan maradeka. Orang Belanda kemudian memungutnya, ketika mereka menyebut mardijkers -- yang tak lain adalah budak-budak yang telah dibebaskan. Dalam arti tertentu, kita juga mardijkers. Tapi bila para mardijkers tetap membiarkan perbudakan berlangsung di sekitar mereka, kita tidak. Kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa -- bukan sebuah pemberian seorang dermawan. Yang menjadi persoalan adalah bahwa sebuah bangsa yang telah diakui kemerdekaan negerinya tidak dengan sendirinya tahu apa maknanya berdiri sebagai orang-orang "merdehika" yang bukan budak. Karena itulah kita tahu mengapa kita mengenang riwayat mimpi itu lagi: di suatu masa kelak, akan ada sebuah Indonesia yang badan dan jiwanya selalu tegak. Goenawan Mohamad Aku bertanya: Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi orang asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, tehnologi, kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya. ketika pulang ke daerahnya, lalu berkata: "Di sini aku merasa asing dan sepi" (RENDRA. Seonggok Jagung di Kamar) Pergi ke dunia luas, anakku sayang pergi ke dunia bebas! Selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinari daun-daunan dalam rimba dan padang hijau Pergi ke laut lepas, anakku sayang pergi ke alam bebas! Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan menutup pintu waktu lampau Jika bayang telah pudar dan elang laut telah pulang ke sarang angin bertiup ke benua Tiang-tiang akan kering sendiri dan nakhoda sudah tahu pedoman boleh engkau datang padaku! .. ............................ (ASRUL SANI. Surat dari Ibu) Siapa cinta anak, jangan jual tanah sejengkal. Siapa cinta tanah, jangan lupakan bunda meninggal Siapa ingat hari esok mesti sekarang mulai menerjang. .................... (RAMADHAN K.H. Priangan si Jelita) Hari depan Indonesia adalah duaratus juta mulut yang menganga Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu l5 wat, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam karena seratus juta penduduknya Kembalikan Indonesia padaku ............................................. (TAUFIQ ISMAIL. Kembalikan Indonesia Padaku) Kami telah meninggalkan engkau tasik yang tenang, tiada beriak, diteduhi gunung yang rimbun dari angin dan topan. Sebab sekali kami terbangun dari mimpi yang nikmat: "Ombak ria berkejar-kejaran di gelanggang biru bertepi langit. Pasir rata berulang dikecup, tebing curam ditantang diserang, dalam bergurau bersama angin, dalam berlomba bersama mega". Sejak itu jiwa gelisah, Selalu berjuang, tiada reda, Ketenangan lama rasa beku, gunung pelindung rasa pengalang. Berontak hati hendak bebas, menyerang segala apa mengadang. (S. TAKDIR ALISJAHBANA. Menuju ke Laut) Ada tanganku sekali akan jemu terkulai, Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut, Dan suara yang kucintai 'kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita -- anjing diburu- hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang Tidak tahu Romeo & Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu Keduanya harus dicatet, keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu Kita memburu arti atau diserahkan pada anak lahir sempat. Karena itu jangan mengerdip, tatap dan penamu asah, Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau basah! (CHAIRIL ANWAR. Catetan Th. 1946)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini