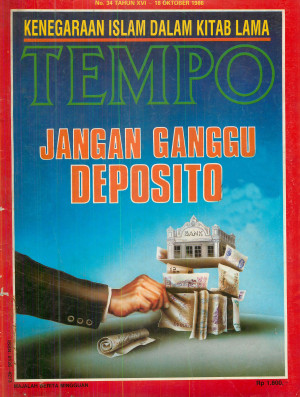SEPERTI tiba-tiba keluar dari simpanan lama, buku tua itu dibentang dan dikaji kembali. Ruang gedung Pengurus Besar Nahdatul Ulama yang sempit dan panas itu penuh Jumat malam pekan lalu. Ada Menteri Agama, memang, yang bertindak sebagai pribadi dan menjadi pembicara utama. Tapi juga tampak keinginan hadirin untuk, katakanlah, menemukan kembali basis dari satu masa yang jauh silam: sebuah kitab pemerintahan yang dikarang di abad ke-5 Hijri atau ke-10 Masehi. Tak heran: minat orang kepada pustaka kuno itu, kitab Al-Ahkamus Sulthaniyah wal-Wilayatud Diniyah (Hukum-Hukum Pemerintahan dan Pengaturan-Pengaturan Keagamaan), di tahun-tahun terakhir memang seperti dibangkitkan kalangan NU sendiri: ajaran sekitar politik dan pemerintahan dalam Islam, yang "lebih absah" bahkan, yang bukan dari jenis "panas" seperti yang pernah mendominasi kesan tentang Islam itu. Itu terserak dalam berbagai kitab (yang, memang, tidak dalam segala butir bersepakat), tapi terutama dalam kitab Al-Ahkam itu. Bukan, karya Imam Mawardi ini bukan sebuah buku politik. Ia kitab fiqh -- hukum atau yurisprudensi Islam. Akrom Malibary, M.A., ilmuwan muda NU yang turut membawa makalah, bahkan menunjukkan tidak adanya konsep filosofis tentang negara di situ -- arti, ruang lingkup, wewenang hukum, tanggung jawab dan kewajiban negara. Juga tidak konsep kedaulatan. Atau teori konstitusi. Seorang pembicara di antara hadirin, Aswab Mahasin, Direktur LP3ES, lebih dari itu menyatakan kesimpulannya bahwa Ahkam bukanlah sebuah teori politik, melainkan teori legitimasi. Dengan kata lain, pembenaran kekuasaan. Dan di sinilah soalnya. Kitab ini, yang dikarang di Baghdad pada periode kedua Dinasti Abbasiah, memang membahas pembentukan keimaman alias khalifah, aturan penggantiannya yang mengiringi kematiannya, hak-hak istimewanya, tugas-tugasnya, dan kemungkinan pemecatannya. Tapi yang terasa menonjol memang kesan peneguhan kekuasaan itu. Pembentukan keimaman, misalnya, dinyatakan -- sebagaimana umumnya pendapat Ahlus Sunnah alias Sunni -- sebagai wajib syar'i (berdasar syariat). Kesimpulan yang berlandaskan hanya ijma' (konsensus ulama) ini memang berbeda dari pendapat aliran Mu'tazilah atau kalangan filosof, yang memandangnya sebagai semata-mata wajib 'aqli, berdasar akal. Dan pewajiban berdasar agama itu memang searah dengan aspirasi Sunni yang menekankan faktor stabilitas masyarakat dan, dengan demikian, pemerintahan. Untuk stabilitas itu pula Al-Mawardi menyatakan, selain dapat dipilih oleh sebuah dewan, imam juga dapat ditunjuk oleh imam pendahulunya. Praktis, ini adalal pengangkatan seorang (bahkan bisa lebih) putra atau pangeran mahkota. Dan, baik dipilih maupun ditunjuk, imam tidak harus dari calon yang terbaik, meski harus memenuhi sejumlah persyaratan -- sebuah teori yang, kata Malibary, menjadi tempat berlindung sebagian besar khalifah yang buruk akhlak. Pemilihan itu sendiri bisa saja dilakukan oleh mayoritas anggota dewan di setiap kota. Tapi juga bisa hanya di satu tempat. Bahkan sebagian ulama (kitab ini merekam berbagai kesimpulan ulama terdahulu) menyatakan, lima pemilih cukup sudah. Sebagian yang lain: tiga, Al-Mawardi sendiri? Seperti juga Imam Asy'ari: kalau perlu, satu orang pun boleh. Semua itu berdasar berbagai preseden, khususnya pada pengangkatan Khalifah-khalifah Abubakar, Umar, Usman, dan Ali, lepas dari apakah penafsiran preseden-preseden tersebut -- watak atau motivasi dari peristiwa-peristiwa itu -- bisa dianggap cocok. Dan, baik ditunjuk maupun dipilih, imam punya hak -- berdasar agama -- untuk ditaati secara mutlak. Ia tak harus bermusyawarah atau minta pendapat rakyat dalam masalah kenegaraan, dan rakyat berkewajiban turut menjaga kekuasaannya sepanjang ia tidak punya alasan untuk dipecat. Pemecatan itu sendiri (yang dalam praktek tak pernah terjadi), juga keberhentian lain di luar sebab kematian, punya persyaratan yang menyangkut baik masalah moral (tiba-tiba si imam menjadi penganut hawa nafsu, atau memeluk kepercayaan yang menyeleweng), masalah jasmani (menjadi cacat, yang menghalanginya melakukan tugas kenegaraan) maupun faktor kecakapan atau kemungkinan melakukan tugas. Yang terakhir itu menarik. Seorang imam, bila dikuasai seorang pembantu atau penasihat -- yang praktis mengambil alih kekuasaan, tapi tidak terang-terangan menentang -- dinyatakan tetap menduduki jabatannya, dengan syarat: si perampas itu memerintah sesuai dengan syariat dan norma-norma keadilan. Ini agar rakyat "terhindar dari situasi faudha (kacau)". Namun, bila peri laku si perampas berlawanan dengan prinsip-prinsip tadi, imam wajib mencari bantuan untuk mengenyahkannya. Itu pertama. Kedua, bila ia ditawan musuh yang kafir (dan seluruh umat wajib membebaskannya) tapi masih punya harapan pulang, ia tetap dianggap imam, dengan tugas-tugas yang dilaksanakan seorang wakil. Bila tak ada harapan lagi, ia dinyatakan berhenti. Begitu juga bila ia ditawan pemberantak Muslim. Bedanya: bila pihak pemberontak sudah mengangkat imam baru, imam tertawan itu kehilangan haknya -- dan dewan pemilih bekerja dengan calon baru. Diktum-diktum terakhir itu barangkali yang paling jelas menunjukkan situasi lingkungan dan periode sejarah di sekitar penulisan kitab ini. Seperti dituliskan dalam makalah pengantar K.H. Ali Yafie, ulama yang juga mustasyar Syuriah NU dan anggota DPR-MPR, abad ke-5 Hijri adalah era meningkatnya otonomi para penguasa daerah dalam kekhalifahan Abbasiah. Kedudukan khalifah hanya semacam lambang kesatuan unsur Turki dominan di bidang pemerintahan, menggantikan unsur Persia yang"merajalela" sebelumnya. Bisa dipahami bila, seperti dikatakan Malibary, Al-Mawardi "barangkali sangat berkepentingan untuk menyelamatkan kekhalifahan Bani Abbas" -- khususnya, di zaman itu, dari tangan-tangan Bani Buwaih yang Syiah, meski ia sendiri dihormati baik di istana maupun di kalangan Buwaih. Pengemukaannya tentang prinsip pemilihan khalifah itu betapapun semacam pembedaan dari prinsip Syiah yang, dalam kekhalifahan, bersandar pada wasiat imam-imam keturunan Ali. Bahkan, bahwa Mawardi menekankan faktor keturunan Quraisy -- kabilah Nabi Muhammad -- sebagai syarat seorang calon imam, bisa pula dihubungkan dengan pembentengan terhadap ambisi Turki maupun Persia ke arah tahta khalifah. Paling tidak, itulah gambaran situasi politik yang labil -- sehingga, selain ada klausul penawanan seorang khalifah oleh pemberontak dalam Al-Ahkam, juga timbul -- seperti diingatkan Ali Yafie -- teori imarah istila' (kekuasaan rebutan) yang disahkan dengag 'aqd idhthirar (akad darurat). Yang terakhir ini bukan dari Mawardi. Tampak bahwa teori politik Islam -- yang menjadi serius karena bersanksi syariat hanyalah sekumpulan besar preseden yang kemudian dicarikan legalitasnya. Tapi bila itu dihubungkan dengan faktor integritas ilmiah dan konsistensi keagamaan sang teoretikus, semua pembicara utama malam itu -- paling tidak Ali Yafie, Munawir Sjadzali, Rodhi Soleh -- akan dengan senang hati berusaha menghindarkan segala kesan yang mungkin negatif. Cukup mengharukan, sebenarnya, bila kita baca bagian kalimat dalam kata pengantar kitab setebal 264 halaman ini. "Untuk itu, aku tulis kitab ini," kata sang hakim agung pada alinea kedua, "memenuhi permintaan orang tempat aku terikat loyalitas dengan dirinya" -- alias Khalifah. Tapi yang berdiri di belakang itu jelas bukan sepenuhnya semangat kompromi bila cendekiawan ini menyambung kata-katanya dengan, "agar ia mengetahui aliran-aliran pendapat para fakih mengenai hak-haknya (sebagai khalifah) sehingga ia bisa mengambilnya, dan mengenai segala kewajibannya sehingga ia bisa menunaikannya, dengan dambaan pada keadilan dalam penetapannya dan pelaksanaannya .... " Dengan kata lain, dialah pejabat tinggi dari jenis yang tetap melihat kesempatan menyuarakan keyakinannya yang "jujur namun luwes" -- "mengingat kondisi politik di zamannya," kata Ali Yafie, yakni di masa ketika "pembicaraan tentang hukum-hukum pemerintahan menyrempet-nyrempet bahaya." Dan, kesejajarannya dengan para fakih lain bukan tak gampang dilihat. Masalah khalifah yang keturunan Quraisy itu, misalnya. Munawir Sjadzali, yang menjadi penanggap, mengingatkan bahwa faktor Quraisy -- yang berdasar hadis "Para imam adalah dari Quraisy" -- itu bukan hanya milik Mawardi. Tapi juga Imam Syafi'i, dan di belakang hari Ibn Taimiah dan, samar-samar, Ibn Khaldun. Bahkan juga Al-Ghazali yang orang Persianitu yang, bahkan, menetapkan bahwa para menteri pun harus Arab. Hanya Ibn Abi tabi' yang tidak memakai hadis tersebut apalagi embel-embelnya. Juga Mawardi tidak berlebihan memandang jabatan khalifah. Ghazali, kata sarjana ilmu politik Georgetown University ini, sampai-sampai memberikan gelar muqad!as (yang suci) kepada pemegang jabatan itu -- meski lebih kabur pengertiannya dibanding ma'shum (terpelihara dari dosa), gelar yang diberikan Syiah kepada imam mereka. Ibn Taimiah, meski hanya menyangkut hal yang lebih rendah dari itu, mengajarkan bahwa seorang pemimpin zalim (jenis khalifah yang selalu ia kritik, dan yang menyebabkannya enam kali masuk penjara dan meninggal di penjara) tetap lebih baik dibanding keadaan faudha alias chaos alias anarki. Demikian "fanatik"-nya guru besar kaum Wahabi (Arab Saudi) dari abad ke-13 masehi itu, dan anutan Muhammadiyah ini, dalam hal stabilitas, sampai-sampai -- ditambahkan oleh Nurcholish Madjid menganggap Husain ibn Ali, cucu Muhammad saw. sebagai bughat (pemberontak yang berhak diperangi) karena menandingi pemerintah Yazid bin Mu'awiah yang sudah duluan ada. Nah. Kelemahan Mawardi, menurut Nurcholish, adalah luputnya faktor musyawarah dari pikirannya -- barangkali karena sudah diambil oleh kaum Khawarij, lawan Sunni dulu. Ini jugalah yang ditekankan berkali-kali oleh Malibary. Menurut jalan pikiran ini, betapapun rupanya bentuk-bentuk pengangkatan Abubakar, Umar, dan seterusnya itu sebagai khalifah, prinsip syura yang termaktub dalam Quran itu jelas di zaman para sahabat Nabi itu tapi tidak pada sistem khalifah belakangan yang dilegitimasikan itu. Masalahnya barangkali justru -- sebagian -- berada pada sifat kitab Ahkam sendiri. Berukuran tebal -- pada edisi modern hanya 264 halaman, karangan 20 bab ini sebenarnya hanya dua bab pertama membicarakan tema yang riuh itu. Selebihnya: masing-masing dua bab tentang pemerintahan daerah (sipil maupun militer) dan pengaturan pelaksanaan ibadat yang menyangkut kepentingan umum masing-masing satu bab untuk kamtibmas, kekuasaan kehakiman, kekuasaan pemerintahan umum dan pengawasan, catatan sipil, administrasi pemerintahan, undang-undang pidana, dan pengendalian, serta pembinaan masyarakat tiga bab untuk kekuasaan keuangan dan biaya kepentingan umum dan empat bab untuk masalah-masalah agraria. Dengan kata lain, ini sebenarnya kitab hukum tentang penjabaran kekuasaan serta tugas-tugas kepala negara dan administrasi pemerintahan, dan bukan (terutama) karya filosofis tentang negara dan politik -- tidak seperti yang ditulis dalam Encyclopaedia Britannica, Micropaedia VI (1977), yang secara keliru menyatakan sebaliknya. Betapapun, seperti dikatakan Ali Yafie, Mawardi -- yang masih punya peninggalan lima kitab lain -- adalah orang pertama dalam Islam yang merangkum seluruh butir hukum di wilayah pemerintahan, yang selama itu terserak di ribuan kitab fiqh klasik. Bagi Munawir Sjadzali, ia bahkan seorang reformis. Jangan lupa, katanya, dialah yang pertama kali -- di dunia, bahkan -- berani menyebut soal pemecatan kepala negara. Itu baru yang pertama. Yang kedua: judul bab pertama Al-Ahkam sendiri adalah 'Aqdul Imamah (Akad Keimaman) -- alias kontrak. Di Eropa, teori pemerintahan sebagai kontrak ini baru lahir di abad ke-17. Bahkan Thomas Hobbes bilang, kontrak hanya berlaku antara rakyat dan rakyat, sementara raja berada di luar -- tidak terjamah, absolut. Herankah kita, bila Ahkamus Sulthaniyah kemudian begitu berpengaruh, dan abad demi abad menjadi rujukan, setidaknya bandingan, bagi pemikiran hukum sekitar pemerintahan ? Bahkan terkadang ia terasa lebih monumental -- karena kunonya, tentu -- dibanding beberapa buku tentang negara Islam yang ditulis sebagai respons pemikiran kenegaraan Barat sesudah masa Jamaluddin Afghani. Z.A. Nuh, pembicara dari floor, menuturkan bahwa sistem pengangkatan para sultan di Jawa, sekadar contoh -- dengan bai'at oleh penghulu keraton, "mewakili dewan pemilih", dan dengan gelar khalifatullah (yang sebetulnya khalifatur rasut) -- bukanlah warisan Majapahit, melainkan bukti dipeganginya ajaran Ahkam. Kitab ini memang sebuah cerita sukses -- dan itu mungkin karena ia, seperti dibilang Nurcholish, "mewakili pandangan Ahlus Sunnah yang selalu memilih jalan tengah". Jalan tengah model Mawardi, betapapun, tidak berdalil langsung dari Quran dan Hadis. Tapi demikian juga dengan jalan pinggir para penulis modern -- meski yang terakhir ini bisa tampak lebih dulu ingin menangkap ruh -- dan tiba-tiba, ternyata, lebih memperjuangkan tubuh. Apa daya, bila ketentuannya yang jelas tidak dimaksud ada -- dalam sumber pertama. Syu'bah Asa, Laporan Musthafa Helmy
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini