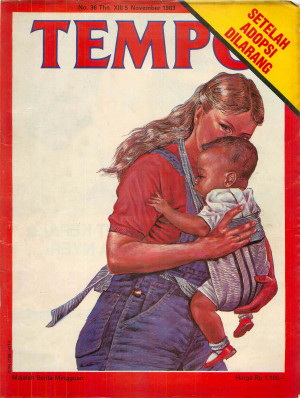KALAU jadi, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka,
sekolah menengah atas (SMA) tidak akan dikotak-kotakkan.
Diharapkan tak akan ada lagi siswa yang bingung karena harus
duduk di kelas yang pelajarannya tidak diminatinya, misalnya.
Menurut Keputusan Menteri P&K 22 Oktober lalu, Kurikulum 1975
yang mengenal Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa itu akan diubah.
Kelak hanya akan ada kurikulum inti dan sejumlah mata pelajaran
pilihan.
Bagi SMA, itu berarti hilangnya pembagian jurusan yang diwarisi
dari zaman kolonial.
Menurut Teuku Jacob rektor UGM, pembagian jurusan di SMA
"mencontoh kurikulum sekolah Eropa zaman dulu, yang kini sudah
tak dipakai lagi." Dan, sebenarnya, dengan terus terang
Setijadi, pembantu dekan II Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta,
mengakui, perubahan-perubahan kurikulum selama ini tak mengubah
esensinya "Mata pelajarannya ity-itu saja, tak banyak berubah,"
kata orang yang terlibat dengan penyusunan Kurikulum 1975 ini.
Kalau toh lulusan SMA gaya lama, cerita Setijadi pula,
mengesankan lebih berkualitas daripada lulusan SMA sekarang,
penyebabnya tidak pada kurikulum. "Dulu, jumlah siswa terbatas,
proses belajar-mengajar lebih intensif," katanya. Untuk sekadar
perbandingan, pada 1970, ketika Kurikulum 1968 baru berjalan
setahun, SMA punya 165 ribu siswa. Menjelang penyusunan
Kurikulum 1975, pada 1974, jumlah itu sudah berlipat sekitar dua
kali menjadi 320 ribu. Empat tahun kemudian, 1978, siswa SMA
melonjak menjadi 600 ribu, sebelum menjadi sekitar dua juta pada
tahun 1983 ini. "Membengkaknya siswa itu yang merepotkan," tutur
Setijadi.
Tapi itu tak berarti kurikulum selama ini, yang menjadikan siswa
SMA terkotak-kotak, tak mengandung hal-hal yang perlu
diluruskan. Sebab, menurut Munandir, dosen IKIP Malang yang dulu
juga terlibat penyusunan Kurikulum 1975, "perubahan kurikulum
tidak selalu mengingat soal pendidikan, tapi juga soal di luar
pendidikan, misalnya politik." Sependapat dengan Setijadi, ia
melihat pembagian jurusan di SMA yang berubah-ubah itu
manfaatnya kurang jelas. Bahkan bisa mengaburkan posisi mata
pelajaran tertentu (lihat: Mengambang diAntara Mayor dan Minor).
Lebih tegas adalah Teuku Jacob. Bagi ahli antropologi ini,
pembagian jurusan di SMA tidak manusiawi. "Membagi bakat manusia
ke dalam kotak-kotak adalah pekerjaan sukar," katanya. "Sebab,
hanya sedikit orang yang bakatnya tampak menonjol hingga gampang
dikenali."
Lebih lagi, ternyata pembagian Jurusan itu tidak
mengetistensikan jumlah mata pelajaran. Baik SMA model gaya lama
yang mengenal jurusan A, B, C, maupun kurikulum yang disebut
Gaya Baru Tahun 1964, yang merupakan hasil perubahan kurikulum
sebelumnya, dengan jurusan-jurusan Pasti, Pengetahuan Alam,
Sosial, dan Budaya. Atau Kurikulum 1968, hasil perubahan
berikutnya yang cuma mengenal jurusan Paspal dan Sosbud, dan
akhirnya Kurikulum 1975. Menurut Teuku Jacob, dalam empat macam
kurikulum itu tetap saja siswa harus menekuni 15 sampai 21 mata
pelajaran. "Padahal, tidak semua mata pelajaran itu diperlukan
di perguruan tinggi," kata rektor yang pada tahun 1950-an jadi
asisten ahli antropologi di UGM ini.
Jacob memang tak menyebutkan apa saja pelajaran SMA yang mubazir
itu. Tapi yang dipikirkannya ialah, "SMA cukup dengan pelajaran
pokok yang mantap, hingga siswa mudah mengembangkan diri di
perguruan tinggi di Jurusan mana pun." Sewaktu masih menjadi
dekan Fakultas Kedokteran UGM, 1970-an, ia melontarkan gagasan
untuk menerima mahasiswa kedokteran dari lulusan SMA jurusan
IPS. "Yang penting 'kan bingkainya. Mengisi lubang-lubang
bingkai itu gampang," katanya. Maka, ia sangat mendukung rencana
mengubah kurikulum menjadi kurikulum inti dan pilihan.
Cuma, yang tidak gampang, memilih mana yang inti, mana yang
pilihan. Harsja, untuk sementara menyebut Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Sejarah, dan
Agama sebagai kurikulum inti. Teuku Jacob baru berani memastikan
bahasa Inggris-lah yang pokok dibutuhkan di perguruan tinggi,
di samping bisa menjadi modal lulusan SMA mengembangkan ilmu
secara mandiri. Dan, bagi rektor UGM ini, yang tak kurang
pentingnya ialah kebijaksanaan pelaksanaan kurikulum baru
nantinya.
Agar tiap SMA bisa mengonsentrasikan pada kurikulum inti, hingga
kualitas lulusan terjamin, Teuku Jacob berpendapat, "sebaiknya
kurikulum baru tidak dipaksakan berlaku bagi semua SMA."
Jelasnya, SMA yang besar, yang punya banyak guru, boleh
memberikan kurikulum pilihan yang beraneka. Bagi SMA yang,
pas-pasan, cukup pilihan terbatas. "SMA di jakarta 'kan tidak
harus sama dengan yang di Irian Jaya," ujarnya. "Yang penting,
kurikulum intinya, bingkainya itu." Biar konsentrasi tidak
buyar, waktu tak terbuang. Leburnya kotak-kotak jurusan, justru
lebih memungkinkan siswa memilih dan menentukan apa mau
mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini