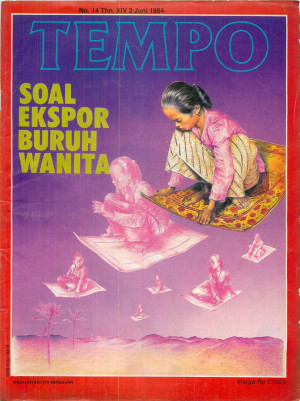ADA sebuah seminar, yang temanya berbunyi: "Siapakah Manusia". Memangnya siapa? Seminar itu - yang diselengggarakan oleh Sekolah Tinggi Theologia Jakarta (STT-J), Selasa pekan lalu, dalam menyambut HUT-nya yang ke-50 - sebenarnya membahas problem pendidikan theologi dalam hubungannya dengan "manusia di dalam proses pembangunan masyarakat", seperti tertulis sebagai subtema. Dr. P.D. Latuihamallo, misalnya, ketua umum Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), mengakui bahwa STT-J lebih banyak menghasilkan calon-calon pemimpin gereja yang "elitis sekali". Elitis bukan berarti tak praktis. Malahan, para mahasiswanya, yang umumnya mendapat beasiswa dari Gereja, setelah lulus pada kembali ke Gereja dan kemudian tenggelam dalam kegiatan rutin yang bersifat pelayanan ibadat. Masalahnya, mereka itu semata-mata "berada dalam lipatan-lipatan Alkitab", katakanlah begitu. Jangankan bergumul dengan berbagai masalah masvarakat. Dalam khotbah pun para pendeta sering terasa kurang "menggali", kurang beryikir tentang lingkungan. Warna itu agaknya tak lepas dari seiarah pendidikan pendeta di Indonesia, apa boleh buat. Dr. Liem Khim Yang, rektor STT-J, mengungkapkan hal itu. Pada masa penjajahan, seperti dikatakannya dalam tulisannya, STT-J dan pendidikan Teologi di Indonesta, yang rencananya akan dlterbitkan, ada semacam pendapat bahwa studi teologi hanya dapat dilaksanakan secara murni di Negeri Belanda. Memang begitu. Karena itu sejak sekolah pendeta pertama kali didirikan di Batavia pada 1754, sampai tahun 1934 sesungguhnya tak ada sekolah sejenis di Indonesia. Yang ada hanya sekolah pembantu pendeta - yang bertugas membantu pendeta menyebarkan agama, selain menyelenggarakan upacara peribadatan. Bahkan ketika pada tahun 1934 dibangun Hogere Theologische School (embrio STT-J) di Bogor, pola pikiran itu tak sepenuhnya lenyap. Pendidikan terasa sekadar memberikan pelajaran teologi untuk keperluan "dalam ruangan gereja" dan warna itu sampai kini masih juga terlihat. Itu bukan tak disadari pihak STT-J sendiri. Selama setengah abad bertarung melawan pola pikiran yang rupanya mengakar itu, lembaga ini terpaksa mengubah kurikulumnya berulang kali. Sampai-sampai pernah dengan jalan memperbanyak jumlah mata kuliah yang diberikan - pada tahun 1960-an. Setelah "dipangkas" pada tahun 1970 karena dianggap berlebihan - kurikulum STT-J dianggap stabil setelah direvisi pada 1980. Ini disebut Dr. Liem sebagai kurikulum yang lebih memperkenalkan masyarakat dan mendekati "teologi dalam arti sebenarnya". Yakni yang tidak hanya selingkar peribadatan. Begitulah secara umum. Toh, rektor ini mengakui, para lulusan yang umumnya memang menjadi pendeta, dan hanya sedikit yang tidak - tetap belum mencerminkan target STT-J. Mereka masih dinilai kurang tanggap terhadap masalah sosial, juga belum akrab dengan teologi yang dimaksudkan. Eka Dharmaputra, juga alumnus STT-J, dalam hal itu menilai bahwa para alumnus almamaternya itu kurang dibekali "alat analisa" untuk melihat baik masyarakat maupun teologi. "Kalau ada gejala, senantiasa mereka lihat dengan kaca mata Kristen. Bukan mereka lihat sebagai gejala itu sendiri," ujar pendeta yang mengambil gelar doktornya di Amerika Serikat itu. Dengan kata lain, mereka tidak berangkat dari obyek, dari kenyataan. "Pada akhirnya, mereka tidak bisa mengatakan apa pun kecuali yang telah dikatakan orang lain." Padahal, menurut pendapatnya, seorang teolog mestinya mampu membangun pendirian yang khas, yang kreatif, berdasarkan penghayatan imannya. Dan STT harusnya menjadi laboratorium "pencarian dan pembaruan teologi". Entah pembaharuan barangkali memang sudah bisa diharapkan di STT-J. Tapi, menurut Eka, Gereja-Gereja di Indonesia sebenarnya ikut mendesak STT-J menjadi "pabrik pendeta" - dalam pengertian pemimpin ibadat itu. Malah, sulit dihilangkan kesan bahwa kalangan gereja sendiri sebenarnya kurang menyukai pendeta yang aktif di masyarakat. "Saya tidak tahu mengapa," katanya. Sepertl menJawab pertanyaan Dharmaputra, lulusan STT-J yang lain, Th. Sumartana, melihat latar belakang yang lebih jauh. Katanya, Protestantisme di Indonesia pada dasarnya"apolitis". Kolomnis itu menyebutkan, keterlibatan masyarakat Kristen dalam berbagai pergolakan masyarakat sebenarnya ada. Lihat saja perjuangan Pattimura atau Sadrach Suropranoto - yang secara unik dikenal sebagai Kiai Ibrahim Tunggul Wulung - yang menggerakkan pemberontakan di pesisir Jawa pada 1870. Hanya, "Sayangnya, aspirasi-aspirasi itu tidak mendapat tempat dalam Protestantisme di Indonesia." Khususnya di STT-J, ketika politik Kristen menurut Sumartana - terlalu bertopang pada pendapat Dr. J. Verkuyl, bekas guru besarnya yang berkebangsaan Belanda, yang dianggapnya tidak relevan dengan kondisi politik Indonesia. Verkuyl memang datang dari latar belakang yang konservatif tadi. Di tengah Protestantisme yang "beku" itu, para lulusan lalu seperti menyelaraskan diri, menjadi birokrat-birokrat gereja. Padahal, katanya, "Mereka seharusnya menjadi teknokrat gereja."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini