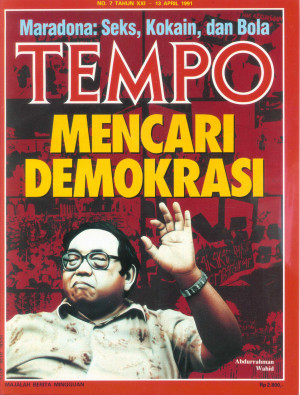DEMOKRASI itu makan ongkos besar. Itu tulis Bung Hatta di tahun 1932. Padahal, ketika itu belum dibayangkan biaya kampanye pemilu. Alasan Hatta sederhana saja: keputusan yang demokratis menuntut keterlibatan lebih banyak orang, demi menyenangkan lebih banyak orang. Toh Hatta tak takut demokrasi. Hatta menghendaki jaminan agar, antara lain, rakyat bebas dari penindasan, punya hak menolak peraturan yang dianggap kurang adil, punya kemerdekaan bergerak dan berkumpul. Menurut Hatta, akar demokrasi ada di banyak desa di Indonesia. Pemilihan kepala desa, umpamanya, dilakukan oleh rakyat. Sulitnya, menurut Hatta, di atas desa tak ada demokrasi. "Yang ada hanya autokrasi," tulis Hatta: para bangsawan dulu setiap keinginannya harus dijawab dengan "daulat tuanku". Maka, kata Hatta, "Daulat tuanku harus diganti dengan daulat rakyat." Bung Karno agak lain. Ia lebih menekankan penolakan kepada demokrasi liberal. Demokrasi liberal, menurut Soekarno seperti yang ditulisnya dalam koran Pikiran Ra'jat 1932, hanya akan menguntungkan kaum kapitalis, sementara kaum proletar ditindas, dan dilempar ke jalanan sebagai penganggur -- satu argumen yang memang lazim bagi para pemikir Marxis. Pilihan bagi Indonesia, menurut Soekarno, adalah sosio-demokrasi, yang punya dua kaki. Satu kaki membela demokrasi, kaki yang lain kepentingan sosial. Bagaimana struktur pemerintahan dalam "sosio-demokrasi" itu tak dijelaskan. Pada masa itu, seperti juga keadaan sekarang, cita-cita demokrasi itu sering kabur. Tapi umumnya para pemimpin memang cemas kepada demokrasi Barat. Tokoh Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, misalnya, memilih demokrasi terpimpin untuk Indonesia. Di situ tak ada pemilihan langsung bagi ketua. Yang ada, pemimpin di antara tokoh-tokoh yang punya sifat bijaksana, dan dipilih orang-orang bijaksana. Secara halus sistem demokrasi terpimpin itu oleh Ki Hajar disebut sistem kekeluargaan. Istilah ini, kata Ki Hajar, ditarik dari konsep kawula yang wajib melayani kepentingan warga. Di situ ada suasana kebersamaan, tapi jelas: kepemimpinan dibangun atas dasar konsep paternalistik. Tapi bagaimana menentukan lebih dahulu siapa yang berhak dan bijaksana, dan siapa yang tidak? Soal ini juga tak sepenuhnya terjawab sampai menjelang kemerdekaan. BPPKI (Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia) dibentuk 29 April 1945. Dalam sidang-sidangnya yang dilakukan di gedung Volksraad, Pejambon, Jakarta Pusat, tokoh yang terkemuka adalah Prof. Soepomo, seorang ahli hukum adat. Ia menawarkan konsep kenegaraan, yang baginya sesuai dengan corak-ragam masyarakat Indonesia: "harus beraliran integralistik," kata Soepomo. Ia bahkan menggunakan kata "totaliter" untuk konsep negaranya itu. (Lihat juga Catatan Pinggir). Bung Hatta tak begitu setuju kepada Soepomo, tapi pada umumnya Soepomo didukung. Juga oleh Bung Karno, yang menolak dicantumkannya hak-hak asasi manusia (yang menurut dia " individualistis"). Waktu itu memang belum disadari bahwa negara dalam konsep Soepomo bisa menimbulkan kekuasaan para pemimpin yang terlalu besar. Soalnya, para pemimpin dianggap tak punya pamrih pribadi. Akibatnya, menurut Frans Magnis, ahli filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, "Kontrol terhadap pemimpin kurang." Negara jadi kuat di hadapan rakyat. Hanya Hatta yang waktu itu sudah melihat kemungkinan itu. Ia menyarankan adanya perangkat untuk menghindari kemungkinan kekuasaan negara yang tak terbatas. Ia didukung beberapa anggota BPPKI antara lain M. Yamin dan Sukirman. Bahkan ada pula usul agar kebebasan pers dilindungi oleh UUD. Sebagai kompromi muncul pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Konstitusi integralistik berlaku sampai 1949. Setahun berikutnya berlaku UUD Republik Indonesia Serikat. Lalu, sejak 1950 berlaku UUD Sementara, menunggu hasil Pemilu 1955, yang akan membentuk dewan Konstituante. Namun, sampai awal 1959, dewan itu tanpa hasil. Maka, Presiden Soekarno mengeluarkan "amanat" agar kembali ke UUD 45. Banyak yang mendukung. Tapi ada anggota Konstituante yang menolak, dan itu adalah Mr. Yap Thiam Hien, yang menginginkan pencantuman hak-hak asasi. Ada yang setuju asal ada penyempurnaan di beberapa pasal. Salah satunya adalah A. Syaifuddin, anggota dari kelompok Islam. Syaifuddin menyebut perlunya jaminan hak mogok bagi buruh. Dia juga meminta agar hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pikiran, seperti dimaksudkan pada Pasal 28, ditetapkan secara tegas dalam UUD. Namun usul itu gagal. Bung Karno memberlakukan dekrit 5 Juli 1959: kembali kepada UUD 1945. Ia memaklumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin. Ini dikecam oleh Hatta, yang sudah mengundurkan diri dari pemerintahan. Hatta melihat tindakan Bung Karno itu "kudeta terhadap demokrasi". Demokrasi Terpimpin Bung Karno yang membubarkan beberapa partai antikomunis kemudian membuka peluang bagi PKI. Lalu terjadi Peristiwa G30S. Demokrasi Terpimpin pun runtuh, dan Orde Baru muncul di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sejak itu istilah Demokrasi Pancasila mulai populer. Demokrasi Pancasila, seperti dikatakan Pak Harto dalam buku Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, bukan ditentukan oleh paksaan kekuatan, melainkan lewat mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmat kebijaksanaan. "Jelas di dalamnya menolak diktator, baik diktator perorangan, diktator golongan, diktator kelas, atau diktator militer. Jelas pula di dalamnya menolak liberalisme, menolak diktator mayoritas terhadap minoritas." Putut Trihusodo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini