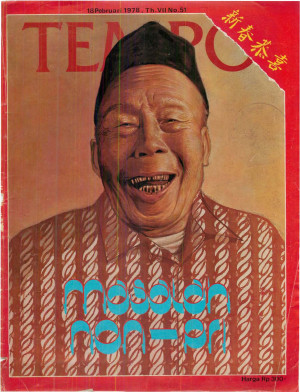KELENTENG-KELENTENG sejak Minggu malam 5 Pebruari sudah
dibanjiri masyarakat yang beragama Kong Hu Cu dan Buddha.
Sementara itu di depan meja abu leluhur di rumah masing-masing,
setiap keluarga membakar hio (lidi dupa) sambil mengucapkan
syukur atas rezeki yang telah dilimpahkan Thian, dewa langit
pencipta bumi, selama tahun silam. Sekalian mohon hokki (rezeki)
dan peng an (keselamatan) untuk tahun mendatang.
Di Jakarta, sepanjang jalan menuju rumah ibadah Wihara Dharma
Bhakti milik tiga agama Tri Dharma (Kong Hu Cu, Taoisme, dan
Buddhisme) di malam tahun baru itu pun penuh mobil, motor dan
becak. Engko-engko dan enci-enci dengan pakaian yang masih
berbau toko antri untuk masuk kelenteng di Petak Sembilan,
Jakarta Kota. Setelah membeli sebungkal hio serta lilin merah
mereka berdoa di muka patung Dewi Kwan Im (dewi welas asih),
Jenderal Kwan Te Kun yang jujur, Dewa Hok Tek Tjeng Sin (dewa
kesuburan) dan Dewa Hian Tan Kong (dewa pengobatan). Kebanyakan
pengunjung kelenteng basah matanya. Asap dupa yang
mengepul-ngepul memang memedihkan.
Beberapa bahan makanan yang biasanya digunakan dalam
sembahyangan Shincia, juga tercatat naik harga di Jakarta. Para
penjual blmga, buah-buahan dan kue juga panen. Setangkai sedap
malam harganya naik 5 x lipat. Seaang kue keranjang--yang hanya
muncul pada waktu Shincia--tahun ini harganya sampai Rp 650
sekilo.
Namun sementara itu, penduduk Jakarta yang hari Senin dan Selasa
itu mau ke pasar justru jadi kapiran. Toko-toko yang biasanya
berdagang tanpa mengenal hari libur awal minggu lalu tutup. Di
Pusat perdagangan lodok dan Senen, Jakarta, suasana sepi
seperti tanpa manusia.
Seperti halnya Jakarta, Medan, yang punya masyarakat keturunan
Cina lebih dari 200 ribu (dri 1,2 juta penduduk) juga senyap.
"Pribumi" yang buka toko boleh dihitung dengan jari. Ada
beberapa bank milik "non-pribumi" yang buka, tapi kerjanya
aplusan. Bahkan ikan asin pun nyaris tak ada yang menjualnya.
Toh abang-abang becak tak begitu beruntung, sebab banyak yang
berimlek ke Parapat di tepi Danau Toba, atau tempat-tempat
peristirahatan lainnya.
PERAYAAN Imlek di Medan sendiri tak menyolok, sebab,
barongsay dan liong tak lagi diarak keliling kota. Tapi ada satu
panitia yang tak kalah akal. Dengan biaya Rp 8 juta, mereka
mendatangkan penari barong dari Bali. Hanya dalam iklan mereka
sebutkan "barong berikut barongsay." Sampai akhir minggu lalu,
rombongan barong Bali itu sudah keliling beberapa tempat di
Sumatera iJtara. Termasuk beberapa malam main di Medan.
Barongsay (singa Cina) dan liong (naga) itu memang sudah lama
dilarang dipertunjukkan di Medan karena dianggap "tak
berkepribadian Indonesia." Begitu pula di Cirebon. Sejak
meletusnya G-30-S/PKI, hari raya Imlek alias Shincia yang
menandai mulainya musim seni di Tiongkok maupun hari raya Cap
Go Meh (15 hari sesudah Shincia) dilarang diramaikan dengan
barongsy dan liong, maupun arak-arakan toa pekong
(patung-patung di kelenteng).
Namun walaupun diizinkan, masyarakat keturunan Cina di sana
memilih suasana sederhana saja. Kata seorang sesepuh Kong Hu Cu
Cirebon, Suryanatadiredja: "Situasi tahun ini kurang
menguntungkan bagi perayaan semacam itu. Sedapat mungkin
menjelang sidang umum MPR, suasananya harus stabil."
Selain itu, dia berpendapat "situasi Cirebon berbeda dengan
kota-kota lain." Menurut kepercayaan masyarakat Cirebon, sebagai
pusat pengembangan agama Islam--setidak-tidaknya bagi Jawa
Barat--kota Cirebon dianggap merupakan "puser"nya bumi. Jadi
"kalau puser (pusat) ini merasa sakit, seluruh anggota tubuh
akan sakit," ujar Surya. Sebagai ontoh disebutnya bentroka
antara pemuda pribumi dengan keturunan Cina di Cirebon, 7 Maret
1963 "yang meluas hampir ke seluruh Indonesia."
Di Pontianak, suasana Imlek jauh lebih terasa. Sejak subuh 7
Pebruari, jantung kota Pontianak tiba-tiba berhenti berdenyut.
Meskipun hari itu perana non-pribumi tiba-tiba diambil oper oleh
pedagang pribumi, masyarakat agak dengan membeli dari "tauke"
pribumi. Soalnya, mereka main genjot harga. Cabe yang sebelum
Imlek cuma Rp 700, 5 hari sebelum Imlek sudah naik 2 x lipat.
Makanya beberapa toko di tempat ia yang ikut buka di hari kedua
dan ketiga hanya menguakkan pintunya selebar dua jari tangan.
"Tak sampai hati mendengar langganan mengetok pintu
terus-menerus," kata seorang di antaranya. Berarti formilnya,
toko masih tetap tutup guna menghormati datangnya musim semi (di
Tiongkok, tentunya).
Shincia di Semarang terasa paling sepi tahun ini. Pasar malam
Imlek yang sudah tradisi di Gang Baru, hanya dibanjiri
orang-orang tua yang membeli benda sesaji sembahyangan. Tak ada
pertunjukan liang-liong. "Larangannya memang belum dicabut,"
kata I. Soeparjo Kepala Kantor P & K Semarang. Meskipun harus
dicatat, bahwa Juli 1977 pernah berlangsung festival liang-liong
se Jawa di depan kelenteng Gedung Batu-kabarnya dengan izin
langsung dari Jakarta.
Sekolah-sekolah Katolik yang banyak siswa peranakan Cina, tak
ada yang libur. Kata Buntoro, seorang pengusaha Tionghoa yang
punya nama di sana kepada Hamid S. Darminto dari TEMPO: "Tak ada
undangan makan-makan buat saya. Saya pun tak mengundang para
sejawat seperti Shincia tahun-tahun lalu." Sejumlah tokoh
peranakan lainnya yang dihubungi, umumnya menyatakan "scdang
prihatin". Prihatin apa? Suasana ekonomi? Atau politik?
Rata-rata menjawab: "prihatin suasana politik". ,da semacam
was-was menyelubungi mereka.
Apakah semua itu tanda, bahwa usaha pembauran antara "pribumi"
dengan masyarakat keturunan Cina belum seluruhnya berhasil?
Mungkin itu pula sebabnya, sejak sebelum Pemilu 1977 kabarnya
sudah terkandung niat di kalangan pemerintah menghidupkan
kembali gerakan asimilasi, yang agak melempem setelah Orde Baru.
Toh rencana itu -- yang jadi tugas Departemen Dalam Negeri--baru
dapat diwujudkan, setelah Pemilu usai. Bertempat di Hotel Sahid
Jaya, Jakarta, minggu ketiga Juli 1977 Dirjen Sospol Depdagri
mengundang para tokoh keturunan Cina dari 26 propinsi untuk
berdialog dengan tokoh-tokoh pribumi dalam Pekan Komunikasi
Penghayatan Kesatuan Bangsa.
GAYUNG bersambut, kata berù jawab. Di Jakarta, ide asimilasi itu
sudah lama tetap membara dalam para tokoh peranakan Cina
eks-LPKB, ditambah sejumlah cendekiawan pribumi yang tergabung
dalam Badan Pembina Kesatuan Bangsa-DKI. Para tokoh swasta itu
terus mengejar gagasan pemerintah itu, sehingga terbentuklah
Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB) yang
berlingkup nasional, dengan ketua drs K. Sindhunatha, veteran
LPKB (lihat: Gong Kedua Telah Berbunyi).
Apa yang merisaukan para veteran LPKB ini bukan cuma keengganan
sebagian masyarakat keturunan Cina larut dalam kehidupan
masyarakat pribumi. Tapi juga, seperti dikeluhkan seorang
anggota pengurus Bakom-PKB kepada TEMPO: "diskriminasi masih
berjalan terhadap golongan minoritas ini, walaupun mereka sudah
lama menjadi warganegara Indonesia sekalipun." Di bidang
perbankan misalnya, non-pribumi kabarnya paling top dapat
menjabat posisi Direktur Muda di bank-bank pemerintah.
Akibatnya, banyak yang lari ke bank swasta asing dan nasional.
Di bidang pendidikan, mahasiswa pribumi dikenakan semacam
"jatah", sehingga mereka lari ke perguruan tinggi swasta. Itu
semua mengurangi ide pembauran.
Di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut perkreditan, tak
ada policy yang tegas. Kadang-kadang digunakan istilah ekonomi
kuat versus ekonomi lemah, kadang-kadang "pribumi dan
nonpribumi." Sementara kalangan "nonpribumi," biasanya otomatis
dimasukkan dalam kotak "ekonomi kuat."
Alasan "diskriminasi" itu tentu ada. Posisi ekonomi kaangan
keturunan Cina sudah kuat sejak abad-abad yang lalu (lihat:
halaman 10). Meskipun tak semua keturunan Cina punya kesempatan
itu tapi posisi "pribumi" perlu diperbaiki.
Tentu saja harus dicatat bahwa "diskriminasi" itu bisa berlanjut
terlalu jauh. Pernah dalam sidang perampokan di jalan Kereta
Api, Medan, terjadi perdebatan yang sengit dalam ruang
pengadilan gara-gara sebutan "Cina". Korban perampokan, Paulus
Marjuni Cukrono wartawan koran Analisa di Medan, sampai naik
pitam dan berteriak: "Saya bukan Cina. Saya orang Indonesia.
Saya besar di sini, makan juga di sini."
Protes Paulus timbul, karena sebelumnya hakim bertanya kepada si
perampok: "Kenapa kau rampok dia?" Dijawab oleh siperampok:
"Karena dia Cina."
Di Medan memang prasangka ras terhadap golongan Cina menonjol
sekali.
Mungkin lebih dari keadaan di Jawa atau di Sumatera Barat.
Barangkali karena banyak yang lebih suka berbahasa Tionghoa
daripada bahasa Indonesia. Sampai-sampai banyak orang pribumi
bertanya-tanya: "Kenapa keturunan Tionghoa di Jawa bisa lebih
lugas bergaul dan malah tak tahu berbahasa Tionghoa?"
Kendati demikian, prasangka yang diawetkan melalui kecenderungan
generalisasi itu memang sangat menghambat penyempitan jurang
"pribumi-non-pribumi." Seperti dikemukakan dr KS Gani, rektor
Atma Jaya Jakarta yang punya ibu Nias dan ayah Tionghoa: "Orang
mungkin sudah lupa, bahwa Rudy Hartono atau peloncat indah Lanny
Gumulya adalah keturunan Cina. Tapi kalau ada penyelundup yang
namanya Cina, di bawah sadar pun orang kemudian akan
menggeneralisir persoalan."
Walhasil, tantangan yang dihadapi Bakom PKB begitu kompleks.
Lantas apa sasaran yang paling dekat? Salah satu sasaran itu
menurut drs Lo S.H. Ginting, sekretaris umum badan itu:
"Mendesak Mendagri, yang merupakan pelindung kami, untuk
menghapuskan kewajiban mengisi kolom 'keturunan' dalam formulir
sensus penduduk bulan depan."
Di Jakarta, formulir sensus penduduk yang tadinya sudah
beredar, ada mencantumkan kolom 'WNA/WNI' itu. Namun setelah
Ketua Bidang Kenegaraan & Hukum Bakom PKB, drs Ridwan Saidi
bertemu dengan Gubernur untuk mnanyakan masalah itu, minggu
lalu formulir itu dicabut dari peredaran.
BOKS
OEI TJOE TAT
Bekas Menteri di Zaman Orde Lama dan tokoh Baperkini umurnya
sudah 15 tahun. Meski lama ditahan di penjara Nirbaya (dia
dibebaskan hampir berbarengan dengan Hariman, setelah melewati
proses peradilan), wajahnya tetap kelihatan tegar dengan
rambutnya yang ubanan. Tapi badannya nampak kurus ketika
dijumpai oleh wartawan TEMPO minggu lalu.
Oei Tjoe Tat lahir di Sala. Isterinya di Salatiga. Ibu-bapaknya
juga kelahiran Sala. Malah "salah seorang nenek moyang saya
puteri bupati Mageiang," kata Tjoe Tat. Itulah sebabnya dia tak
enam merasa sebagai keturunan Cina. antas, kenapa tak ganti
nama?
"Apa sih artinya nama?", tanyanya kembali, meniru Shakespeare.
Baginya, nama itu pemberian orang tua, habis perkara. "Yang
penting jiwa patriotnya," katanya. Waktu diangkat Bung Karno
menjadi Menteri, dia iseng-iseng tanya, apa perlu ganti nama.
Jawab Bung Karno: "Buat apa? Salah satu sebab kamu saya pakai,
justru karena tidak ganti nama."
Pengetahuan Oei Tjoe Tat tentang bahasa Cina terbatas
mengartikan namanya saja. Tjoe itu sendiri, Tapi artinya
mencapai. Jadi "saya disuruh berdikari," katanya. Di Sala, ia
memang besar dalam lingkungan Jawa. Ibunya yang buta huruf itu
tiap malam Jumat kliwon selalu hanya memakai kemben, dengan
rambut terurai. Lalu dengan tungku kecil berisi dupa, keliling
rumah. Kalau Tjoe Tat sakit, ibunya menanggap wayang klitik di
klenteng. "Apa ini bukan gado-gado?" katanya sambil ketawa. Ahli
hukum itu tampaknya gembira sekali mengingat masa kecilnya.
Mungkin memang gado-gado Jawa berbumbu Cina. Sebab pada waktu
orangtuanya masih hidup. pada hari raya Imlek ia sowan kepada
orangtuanya untuk soja. Setelah orangtuanya meninggal ia soja di
depan potret ibubapanya di rumah kakaknya yang jadi dokter.
"Tapi sekarang sudah tidak lagi. Hari Raya saya sekarang, ya
Tahun Baru 1 Januari," katanya.
Kawan anak-anaknya sendiri 90% pribumi. "Padahal saya tak pernah
menyuruh mereka berbuat itu. Saya tak pernah peduli siapa kawan
mereka," tuturnya. Tapi omong-omong, kenapa dulu masuk Baperki?
Karena menurut keyakinan Tjoe Tat, "dengan Baperki itu
pengindonesiaan orang Cina akan berhasil." Paling tidak, dia
benar-benar merasakan itu pada tahun 1963.
NAKIM
"Owe sih pengin ngikut Shincia, tapi kalo nggak punya duit yah
mau ape?" Itu komentar Nakim, 32 tahun, yang dulunya bernama Oei
Tek Lim. Lahir Dari keluarga petani Tionghoa miskin di daerah
Bekasi, umur 12 tahun sudah bekerja sebagai kernet kopelet milik
salah seorang tetangganya. Ketika berumur 18 tahun, bekerja jadi
centeng (penjaga malam) pada anemer Asnawi, di mana dia juga
menumpang tinggal. "Rupanya Pak Asnawi ngeliat owe kerja bener,
dikawinin ame anaknye yang bernama Enin," kata Nakim yang belum
pernah merasakan pendidikan resmi, dengan logat Betawinya yang
tebal.
Menikah secara Islam, sekarang Enin yang baru 27 tahun itu
telah punya lima anak. Yang terbesar 12 tahun. Kenapa tidak ikut
KB? Sahut Nakim: "Bini owe takut. Kata orang kalo nggak cocok
nanti sakit. Kalo sakit kan repot biaya lagi buat dokter."
lumahnya berukuran 2 x 2 meter, disewa Rp 200 per bulan.
Terbuat dari papan dan dibagi dua tingkat, bagian baah
dijadikan dapur merangkap ruang tamu yang hanya bensi dua kurs
panjang dari papan. Di bagian atas, suami isteri itu tidur
dengan kelima anaknya. Letaknya di daerah Gunung Sahari XI.
Tek Lim yang sekarang kerjanya jadi tukang cat, dulu pernah
menarik becak. Kalau lagi ada kerja, sehari bisa dapat seribu
perak. "Tapi kalau kayak sekarang, ya nganggur," kata Tek Lim.
Menjelang Imlek, dia ketiban durian runtuh. Seorang dermawan
yang baik hati meminjamkan uang Rp 10 ribu untuk modal dagang
ayam goreng dan nasi uduk. "Malamnya nggak bisa tidur mikirin
utang sebesar itu, gimana gantinya," kata Oei Tek Lim alias
Nakim. Soalnya, setelah dibelikan kompor, petromaks dan beberapa
peralatan lainnya, modalnya habis sehingga niat tersebut batal
di tengah jalan.
MULIA TAN
Di kampungnya di Desa Gerendang Karawaci, Tangerang, dia dikenal
dengan julukan "encek letnan." Dan memang, Mulia Tan alias
Yohannes Fransiscus Tan Bun Tjao, 52 tahun seorang pumawirawan
Kesatuan Angkutan Kodam VI/Siliwangi dengan pangkat terakhir
Pembantu Letnan Satu (Peltu). Nrp: 248082.
Dengan uang pensiun Rp 26 ribu sebulan dia menghidupi seorang
isteri dengan 7 anaknya. Orangtua kakeknya berasal dari propinsi
Hok-kian, Tiongkok Selatan, tetapi Tan lebih merasa Indonesia
sebagai tanah airnya sendiri. "Habis, kita kan dilahirkan
anak-beranak di sini," katanya. Kendati demikian, sebagai
Tionghoa Peranakan dia masih memakai tatacara Cina seperti
memuja abu leluhur. Ikut perayaan Shincia, Ceng Beng, Tang Ce.
Tan pernah mendapat Satya Lencana Penegak Kemerdekaan tahun
1967. Tentang ganti nama, dia berpendapat: "Biar bagaimana kita
disebut Cina juga. Mana bisa kita ganti kulit mata-mata sipit?
Tapi bagi owe, soal ganti nama sih boleh aja. Yang penting hati
orang yang bersangkutan." Dia juga sangat setuju pernikahan
campuran. Asal suka sama suka. Tinggal di rumah beratap rumbia
berlantai tanah dan berdinding bilik bambu, untuk menambah
penghasilannya seminggu 2 x dia mengajar reparasi mobil di
Tangerang.
ABDUL KARIM
Ketua PITI (Pembina Iman Tauhid Islam d/h Persatuan Islam
Tionghoa Indonesia) ini, terlahir sebagai Oei Tjeng Hien.
Asalnya dari Sumatera Barat, di mana dia lama berdakwah sebagai
tokoh Muhammadiah. Menurut dia, "Islam dapat mempercepat proses
asimilasi." Tapi repotnya, orang Tionghoa memandang Islam
sebagai milik suatu bangsa dengan kebudayaan dan peradaban yang
dipantulkannya. Sehingga pekerjaan mengislamkan orang Tionghoa
tak gampang.
Di zaman Jepang, dia pernah berhasil mendamaikan golongan
pribumi dengan golongan keturunan Cina di Padang. Soalnya,
dulunya Cina dimanjakan oleh Belanda di sana. Sehingga ada rasa
kurang senang terhadap orang Cina. Datang Jepang, orang Cina
digencet oleh musuhnya yang sama-sama kulit kuning. Nah,
memasuki periode perebutan kemerdekaan, timbul bentrokan antara
pribumi dan non-pribumi di sana. Toko-toko Cina dibakar dan
dirampok. Untung Abdul Karim sendiri keturunan Cina, tapi tokoh
Muhammadiah. Sehingga kedua golongan masyarakat yang sedang
berseteru itu sama-sama punya rasa hormat terhadapnya.
Menyinggung soal pengusaha Cina yang mendapat fasilitas
berlebihan, dia menganggapnya lebih "soal kepribadian, soal
watak seseorang." Pengusaha yang berdagang secara tak wajar itu,
"jangankan Cina, yang non-Cina pun ada." Yang penting menurut
dia, "kita harus sama-sama memperkecil jurang antara pri dan
non-pri, agar tak membuat si pribumi tersinggung karena si
non-pri mendapat uang secara tak wajar." Dia juga menyebutkan,
bahwa ada Rp 60 juta dana yang terkumpul dari tokoh-tokoh
semacam Liem Sioe Liong, Njoo Han Siang dan beberapa tokoh Cina
lainnya, untuk membantu pribumi yang lemah.
Dari tiga anaknya yang sudah kawin, dua di antaranya kawin
dengan pribumi. Abdul Karim sendiri masuk ke Jakarta tahun 1952.
Seperti juga dalam perubahan kepanjangan organisasi yang
dipimpinnya, Abdul Karim memang lebih menyukai nama Indonesia
daripada nama Cina, karena "identitas nasionalnya menjadi
jelas." Dia sendiri menyebut dirinya, "orang Indonesia yang
beragama Islam."
TJIAM DJOE KIAM
Tahun 1960, Tjiam Djoe Kiam adaah orang pertama yang mendapat
surat kewarganegaraan Indonesia. Waktu itu, dia nyaris
dilangkahi oleh Oyong P.K., wartawan yang sekarang jadi pe
mimpin umum Kompas. Oyong P.K., minta kepada hakim agar ia
diberi nomer 1. Tapi karena yang paling lengkap keterangannya
adalah Tjiam, maka Tjiam-lah yang diberi nomer 1. Sedang Oyong
mendapat nomer 3.
Pengacara terkenal ini, agaknya anti ganti-nama. "Mengapa harus
ganti nama? Toh itu hanya anjuran," katanya. Ganti nama, tak
menjamin seorang keturunan menjadi warganera yang baik. Malah
"banyak orang ganti nama cuma untuk melakukan kejahatan," kata
Tjiam. Berdasarkan pengalamannya di pengadilan, ia sering
melihat orang yang ganti nama hanya untuk melakukan kejahatan.
Termasuk Robby Cahyadi yang pernah dibela Tjiam.
Tjiam merasa masih ada diskriminasi tentang penyebutan "WNI".
"Mengapa WNI keturunan Indonesia, Belanda atau asing lainnya
tidak disebut? WNI selalu berarti keturunan Cina," ujarnya
dengan jengkel. Dia juga punya seorang kemanakan yang gagal
masuk UI. Padahal anak itu bintang pelajar dari Semarang.
Kerikilnya hanyalah karena waktu itu (1960), setiap calon
mahasiswa harus membawa kartu kewarganegaraannya yang
menyebutkan nama Cina dan Indonesia. Dan si kemanakan itu
rupanya tak lagi punya dua nama. Untunglah bernilai-nilai
ujian akhir SMA-nya yang begitu menyolok, tanpa ditest
kenalkan Tjiam itu berhasil masuk ITB. Bhkan dalam setahun
langsung menjadi sekretaris profesor atom.
Saya sih sudah tujuh turunan di Indonesia. Nggak tahu apa ada
famili di RRT " tutur Tjiam. Leluhur Tjiam datang ke Indonesia,
tutur Tjiam. Leluhur Tjiam datang ke Indonesia, mendarat
di Lasem, Jawa Tengah. Langsung saja kawin dengan wanita
Indonesia, karena di tahun 1700-an itu orang Cina yang datang ke
Indonesia umumnya tak membawa isteri.
SURYANATADIREJA
"Kenapa asimilasi baru digembargemborican sekarang? Sejak nenek
moyang saya, asimilasi sudah dijalankan. Dan bukan hanya
terbatas pada perkawinan antara keturunan Tionghoa dengan
ibumi." Yang bilang begini, orangnya sudah 74 tahun. Tampak
awet muda berkat kemahirannya berolahraga kuntao,
Suryanatadiredja (d/h Kho Sin Swan) adalah bekas "Lurah Cina"
(Chineesche Wijkmeester) di Cirebon, antara 1948-1951. Sekarang
dia sesepuh agama Kong Hu Cu di sana.
Menurut Surya, asimilasi sudah dan masih tetap harus dijalankan
di segala bidang. Suatu contoh, penduduk pribumi kini mengenal
upacara tiga hari, tujuh malam, 40 hari dan seterusnya tatkala
memperingati arwah yang baru meninggal. Konon itu asalnya dari
tradisi Cina. Lalu. "anda kan kenal mi bakso, tahu, dan
lain-lain Inasakan Tionghoa apa itu bukan asimilasi?" tanyanya
kepada Aris Amiris dari TEMPO.
Meski demikian Surya juga kurang menyenangi oknum-oknum pribumi
yang menutup masuknya keturunan Cina dalam lingkungan mereka.
Juga masih banyak keturunan Cina di negeri ini yang menganggap
dirinya "superior", lebih tinggi dari pribumi. Menyangkut yang
ganti narna, Surya mengecam keenganan menghilangkan nama she
(marga). Seperti she Tan diteruskan menjadi Tanuwijaya. "Ini
nggak benar," ujar Surya.
Suryanatadireja sudah keturunan kelima sejak nenek moyangnya 300
tahun lalu menetap di Cirebon. "Saya bukan orang Cina tapi
bangsa Indonesia asli. Nama Suryanatadireja adalah pemberian
Raden Partasudjana tahun 1951, sebelum ada anjuran pemerintah
untuk ganti nama," katanya.
NYOO HAN SIANG
Lahir dari ibu-bapak berdarah Cina asli di Yogya, 48 tahun
silam, Nyoo Han Siang mendapatkan pendidikan dasar di sekolah
Cina di Yogya pula. Tahun 1946, melanjutkan pelajaran di Amoy,
Cina Selatan. Tapi hanya tiga tahun berada di daratan Tiongkok,
Nyoo terpaksa angkat kaki karena Komunis merebut kekuasaan di
negeri itu (1949). Hampir setahun mampir di Hongkong tahun 1950
dia kembali ke Indonesia.
Karenakesulitan bahasa dan macam macam, Nyoo cuma dapat
melanjutkan pelajaran di Akademi Wartawan pimpinan Parada
Harahap. Setanun belajar jurnalistik, dia kemudian bekerja
sebagai wartawan foto pada majalah Sunday Couner. Hanya dua
tahun menjadi wartawan, dia kemudian pindah lagi bekerja di
perusahaan perkapalan. Tak betah, ia kembali ke Semarang
"menunggui" perusahaan kakaknya. Setelah itu ia mulai mapan
sebagai pedagang hasil bumi, ternak. Bisnis bank mulai
dimasukinya tahun 1968 setelan hijrah ke Jakarta, yakni dengan
mengambil oper Bank Umum Nasional yang dulunya dipegang
orang-orang PNI.
Tapi Bunas yang dipimpinnya, tampaknya kalah bersaing dengan
bank Tenglang (keturunan Cina) seperti Panin Bank serta bank
asing dan bank pemerintah.
Setiap Imlek, Nyoo selalu pulang berkumpul dengan keluarganya di
Semarang. Meskipun menolak ganti nama, dia sangat setuju
pembauran. Di Semarang, dia mempelopori pengalihan bekas sekolah
Cina yang diduduki tentara menjadi sekolah umum di mana siswa
pri dan non-pri dapat belajar bersama. Namun dalam soal
pembauran itu, Nyoo masih menyayangkan ketidaktegasan
pemerintah. "Kita sudah pegang paspor Indonesia, tapi segala
macam dipersoalkan," katanya.
Banyak anak yang sejak lahir sudah tak punya nama Cina, tapi di
sekolah masih juga ditanyai nama aslinya sebelum ganti nama.
"Kan repot?" tanya Nyoo. Anak-anak yang tadinya tak sadar lagi
bahwa ia keturunan Cina, jadi bertanya-tanya kepada orangtuanya.
"Dalam posisi terdesak seperti itu, anakanak itu akhirnya ingin
tahu banyak mengenai orang Cina. Orangtuanya terpaksa
mengajarkannya," tutur Nyoo.
Nyoo juga membenarkan kesan umum, bahwa pengusaha Cina di sini
selalu dekat dengan yang berkuasa. "Tapi harus dilihat
sejarahnya," kata dia. Orang Cina yang datang ke mari kebanyakan
berasal dari suku Hok-kian dan Kanton. Mereka lari dari
negerinya karena mau dipaksa jadi tentara oleh para warlord.
Mereka lari meninggalkan orangtua mereka di sana. Saking
rindunya pada orangtua, di sini mereka selalu mencari orangtua
angkat. "Dan pemerintah mereka anggap sebagai semacam orangtua
angkat yang bisa memberikan perlindungan pada mereka," begitu
argumentasi Nyoo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini