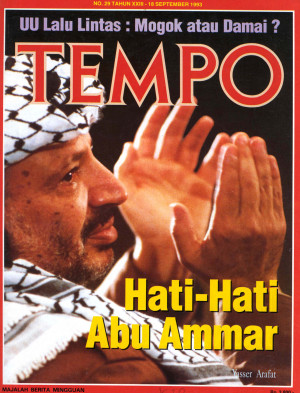KOMENTAR saya tentang pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas baru? Saya dengar sopir-sopir pada mau mogok tanggal 17 September nanti. Supaya pemerintah tahu,'' ucap Yasirwan, sopir President Taxi, kepada Joewarno dari TEMPO, Rabu pekan silam. Ayah dua anak ini melihat UU baru itu akan membuat pekerjaannya sebagai sopir taksi semakin terancam. Ia lalu membandingkan penghasilannya setiap hari, dan itu pun setelah bekerja keras sejak pukul 6.00 hingga pukul 22.00, yang hanya Rp 10.000 sampai Rp 20.000, dengan ancaman denda yang sampai jutaan rupiah. ''Nggak mungkin saya mampu membayar denda sebesar itu,'' tambahnya. Kecemasan Yasirwan mengenai sopir-sopir angkutan umum bakal sering dijaring polisi bukan tak berdasar. Pengalamannya sebagai sopir taksi menunjukkan bahwa angkutan kota, seperti bus, metro mini, mikrolet, dan taksi, lebih sering disetop polisi dibandingkan dengan mobil pribadi. ''Biar sudah hati- hati, tetap saja ada yang salah,'' katanya. Tak mengherankan bila Trisno, sopir bus mini Kopaja, bertekad untuk meninggalkan pekerjaan itu yang sudah digelutinya selama dua tahun mulai 17 September. ''Pemerintah tidak adil,'' katanya. ''Nasib nelayan dan petani diperhatikan. Tapi, nasib sopir tidak.'' Trisno, yang berpenghasilan sebagai sopir Rp 5.000 sampai Rp 7.000 sehari, khawatir dengan UU yang baru itu, polisi akan menaikkan tarif ''denda damai''. ''Sekarang aja, kalau nyupir perasaan saya waswas, tidak tenang. Kalau diprit, biasanya polisi mau dikasih Rp 5.000, kayaknya nanti pasti minta lebih besar lagi,'' katanya. Pria lulusan STM itu mengaku mungkin akan alih profesi. ''Mungkin jadi kuli. Yang penting, anak-anak bisa makan,'' tambahnya. Sikap Yasirwan dan Trisno adalah sepenggal potret ketidakpuasan para sopir angkutan umum (yang belum tentu sepenuhnya benar) terhadap pelaksanaan UU Lalu Lintas yang baru. Untuk mencari gambaran yang lebih luas tentang sikap dan pandangan mereka yang duduk di belakang kemudi terhadap UU ini, TEMPO membuat pol yang melibatkan hampir 1.000 orang sebagai responden. Mereka terdiri dari para sopir berbagai lapisan dan golongan. Ada sopir truk, sopir bus, sopir mikrolet, sopir taksi, pengemudi bemo, pengemudi bajaj, dan pengendara sepeda motor termasuk di dalamnya para eksekutif yang mengemudikan mobil sendiri. Sebagian besar responden, sekitar 90%, berasal dari Jakarta. Sisanya adalah responden dari berbagai kota besar, seperti Medan, Bandung, dan Surabaya. Tingkat keterpercayaan pol ini adalah 95% ini dihitung berdasarkan standar deviasi dalam penarikan sampel yang bernilai 1,36. Penggarapan pol ini dilakukan TEMPO dengan Kelompok Peneliti dan Pengkaji Masalah-Masalah Kriminologi (KP2MK) Universitas Indonesia. Pengumpulan data dilakukan sejak pertengahan Juli hingga Agustus lalu. ''Semula banyak yang mengira kami ini intel,'' kata Reza Edwin, Koordinator KP2MK. Akibatnya, sejumlah sopir sempat melakukan gerakan tutup mulut. Maklum, menurut kacamata politis, soal ini memang sensitif. Sejak tahun lalu aparat keamanan sudah dikerahkan untuk melicinkan pelaksanaan UU yang sempat mengundang kontroversi itu. Baru setelah para responden itu tahu bahwa lembaga yang melakukan pol ini adalah TEMPO (dibantu KP2MK) suasana jadi berbalik. ''Mereka malah jadi bersemangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan,'' tambahnya. Pol ini memang dimaksudkan untuk menjaring sikap para sopir terhadap pelaksanaan UU Lalu Lintas baru ini. Berapa hukuman denda yang pantas, menurut mereka tentunya, untuk beberapa pelanggaran: lupa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), lalai membawa kendaraan tanpa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan sebagainya. Selain itu, juga untuk melihat sikap dan perilaku responden. Ternyata sebagian besar para sopir itu memilih membayar ''denda damai'' ketimbang berurusan dengan bank (sebagai tempat penitipan uang denda) dan pengadilan. Mungkin karena dunia jalanan identik dengan kehidupan yang keras, maka tak mengherankan kalau sebagian besar responden (lebih dari 90%) berkelamin pria. Sedangkan pengemudi wanita kurang dari 10%. Dari sudut umur, responden termuda berusia 18 tahun (usia minimal untuk memperoleh SIM) dan yang tertua 68 tahun. Namun, responden terbanyak adalah mereka yang berusia 30-55 tahun (ada 60%). Ini memang usia yang dikategorikan sebagai usia produktif. Alhasil, jika terdapat perubahan atau ketidakstabilan dalam kehidupan di jalan, maka kaum pria juga yang terkena dampak terbesar. Berhubung di kebanyakan pundak pria terpikul beban pendapatan rumah tangga, maka perubahan yang meresahkan, sebagaimana yang mereka khawatirkan akan timbul karena UU yang baru ini, hampir pasti berwarna emosi. ''Kalau tak sanggup bayar denda, ya, saya pilih masuk penjara saja. Biar penjara nanti penuh dengan sopir-sopir,'' kata seorang responden. Penghasilan responden juga bervariasi. Kelompok terbesar adalah mereka yang pengeluarannya Rp 10.000 sampai Rp 20.000 per hari. Bisa ditebak, mereka adalah responden yang profesinya sebagai sopir, baik sopir angkutan umum maupun sopir kendaraan pribadi. Tentu saja ada yang pengeluarannya jauh di atas itu. Umumnya mereka adalah kalangan pemilik mobil atau motor yang berpenghasilan di atas Rp 1 juta per bulan. Adalah kebetulan semata kalau tiga perempat dari total responden ternyata mengaku pernah berurusan dengan polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Ketika ditanyakan bagaimana mekanisme penyelesaiannya, sebagian besar, hampir 60% responden, menjawab: bayar ''denda damai'' alias tidak ditilang. Hanya seperempat responden yang mau menyelesaikan urusannya lewat tilang. Sedangkan sisanya dibebaskan dengan peringatan. Tanpa ditilang, dan tanpa membayar ''denda damai'', mereka yang bebas ini mungkin karena polisi yang bertugas sedang mengutamakan pekerjaan tertentu, misalnya pengamanan jalan untuk pejabat tinggi negara. Atau kebetulan kesalahannya terlalu ringan sehingga polisi tak melakukan tilang, dan responden hanya diperingatkan setelah mengakui kesalahannya. Tampaknya pengalaman ini mempengaruhi responden yang sebagian besar tetap akan melakukan jurus ''bayar denda damai'' ketimbang ditilang, kendatipun UU yang baru ini diterapkan nantinya. Maka, tak mengherankan kalau sebagian besar responden, sekitar 60%, menginginkan ''damai'' dengan petugas. Sedangkan sisanya mencoba untuk menyelesaikannya lewat tilang (Lihat diagram: Siapa Mau Ditilang, Siapa Mau Damai?). Kenapa mereka lebih suka memilih ''denda damai''? Buat para sopir yang mengandalkan penghasilannya di jalan, memilih ditilang sama artinya dengan tak bekerja. Dengan kata lain, asap dapur bisa tak mengepul. Siapa pun tahu, sidang pengadilan dengan gaya lama makan waktu hampir sehari penuh. ''Coba pikir, melanggar leter S (rambu dilarang setop), kalau damai bayarnya cuma Rp 3.000. Kalau ditilang, bayar di pengadilan, keluar Rp 10.000. Nah, sehari saya bisa tiga kali kena di leter S. Kan mending damai daripada bayar tiga kali Rp 10.000,'' ujar Siregar (tanpa mau menyebutkan nama depannya), seorang pengemudi bus Metro Mini rute Pasar Minggu-Blok M. Begitu juga pengalaman seorang eksekutif muda yang berkantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Ia mengaku kapok tak mau lagi ditilang gara-gara melanggar rambu beberapa waktu lalu. Ayah tiga anak tadi, sejak pagi harus menunggu di kantor pengadilan lebih dari lima jam sebelum namanya dipanggil. ''Kalau tahu begitu, kan lebih baik damai saja sama polisi,'' cerita eksekutif muda itu. Para responden yang nanti memilih tak mau ditilang itu juga diajak urun-rembuk soal berapa besar ''denda damai'' yang mereka relakan untuk diberikan kepada polisi yang menangkap mereka (Lihat diagram: Berapa Besar Denda Damai?). Untuk jenis pelanggaran, misalnya kelupaan mengantongi SIM, lebih dari separuh responden yang memilih ''denda damai'' hanya mau membayar kurang dari Rp 5.000. Sisanya rela merogoh koceknya lebih dari Rp 5.000, namun tak lebih dari Rp 50.000. Begitu juga untuk pelanggaran karena lalai membawa STNK. Hampir separuh menyatakan hanya ikhlas membayar ''denda damai'' kurang dari Rp 5.000 untuk kesalahan itu. Sedangkan separuh lagi bersedia membayar Rp 5.000 sampai Rp 50.000. Banyaknya responden yang hanya mau membayar ''denda damai'' di bawah Rp 5.000 itu disebabkan mereka berang gapan kesalahannya sepele: lupa membawa SIM atau STNK. Sedangkan uang damai yang dipatok maksimal Rp 50.000, sesuai dengan isi kantong responden sehari-hari. Lain hal kalau kesalahannya karena tak memiliki SIM. Hampir 60% responden menyatakan uang damai yang pantas antara Rp 5.000 dan Rp 50.000. Bahkan ada juga responden yang menyatakan pelanggaran itu pantas dikenai sanksi ''denda damai'' di atas Rp 50.000. Sedangkan pasaran ''denda damai' untuk pelanggaran rambu, kurang dari tiga perempat responden bersedia membayar kurang dari Rp 5.000. Sisanya, mungkin ka rena latar belakang responden dari kalangan eksekutif, tak terlalu pusing mengeluarkan duit Rp 5.000 sampai Rp 50.000. Tak terelakkan lagi bahwa ''denda damai'', seperti yang dilihat Satjipto Rahardjo, ahli sosiologi hukum, tampaknya memang sudah menjadi institusi di jalan- jalan. Menurut Satjipto, dengan pisau analisa sosiologi hukum, ''denda damai'' itu bisa dilihat sebagai suatu ''denda informal'' yang berhadapan dengan ''denda formal dan legal'' dalam UU. Pengalaman tadi tampaknya memang besar pengaruhnya terhadap sikap responden (Lihat diagram: Sikap Terhadap UU Lalu Lintas yang baru). Lebih dari setengah merasa ragu-ragu alias bingung menjawab soal efektivitas pelaksanaan UU ini nantinya. Apakah lalu lintas akan semakin tertib, apakah praktek ''denda damai'' juga akan terkikis. Sikap mereka mendekati seperti yang digambarkan Wahyu, sopir angkutan kota di Bandung. ''Bagaimana nanti sajalah,'' ujarnya dengan nada pasrah kepada Ida Farida dari TEMPO. Sekalipun UU yang baru ini berisi ancaman hukuman denda sampai jutaan rupiah, toh para sopir tampaknya masih lebih suka memilih proses ''denda damai'' ketimbang ditilang. Sedangkan responden yang bersikap negatif kurang dari sepertiga. Mereka yang bersikap sinis ini barangkali, seperti tergambar dalam sosok Yasirwan atau Trisno, melihat ancaman hukuman denda dalam UU itu sangat memberatkan. Apalagi, menurut mereka, ada dampak yang bikin peluang buat polisi untuk menaikkan tarif ''denda damai''. Dan hanya sedikit, sekitar 20% responden, yang sikapnya positif melihat UU Lalu Lintas yang baru ini. Maka sebagian besar responden yang masih bingung itu tentu saja menjawab ''tak setuju'' (ada 80%) ketika disodorkan pernyataan: Pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan dengan baik besarnya denda dan sanksi hukum dalam UU Lalu Lintas Nomor 14/1992 itu. Ironis, hanya 20% responden yang menyatakan akur dengan pernyataan di atas (Lihat diagram: Opini Terhadap UU Lalu Lintas yang baru). Reaksi responden ini tampaknya seiring dengan jawaban mereka yang sebagian besar memang tak setuju terhadap pernyataan bahwa ''berat atau tidaknya sanksi (yang diatur dalam UU yang baru ini) amat relatif''. Rupanya, mereka masih melihat ancaman sanksi sebagai suatu hal yang absolut. Itu sebabnya banyak juga yang sangat berharap pelaksanaan sanksi maksimal ini akan jarang sekali diberlakukan. Apakah harapan mereka ini akan dipenuhi? Para responden pun rupanya pesimistis. Ini terlihat dari reaksi mereka yang hanya sedikit orang yang percaya bahwa polisi dan aparat penegak hukum lainnya telah siap melaksanakan UU yang baru ini dengan baik. Sedangkan sisanya, 75% responden, menyatakan sebaliknya. Walaupun diragukan kesiapannya, polisi tampaknya semakin disegani bila dipersenjatai dengan UU yang baru ini. Hanya 40% responden yang menyatakan tak setuju kalau polisi akan semakin disegani oleh pengguna jalan. Mungkin perlu diamati sejauh mana kata ''segan'' punya makna kewibawaan terhadap polisi. Di tengah rimba pendapat bernada pesimistis itu masih ada juga harapan yang bernada positif. Ternyata masih banyak, lebih dari 75% responden, yang percaya bahwa UU baru ini memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seluruh pengguna jalan. Alhamdullilah. Ahmed Kurnia Soeriawidjaja --------------------------------------------
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini