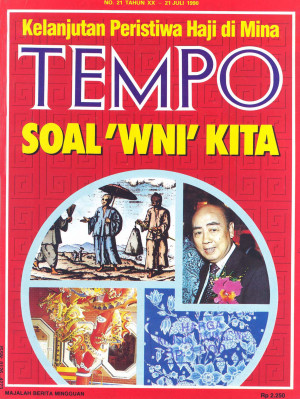TAK banyak orang membayangkan, seorang keturunan Cina hidup paspasan, sebagai petani miskin, kuli kebun, atau pemilik warung kecil. Apalagi sebagai tukang parkir, meski dulunya pernah ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Keturunan Cina telah tenggelam dalam anggapan bahwa mereka itu mesti makmur dan kaya. Penyamarataan yang tak sepenuhnya benar. Pada awalnya ada keturunan Cina yang datang ke Indonesia sebagai buruh, bukan pedagang. Rusman Nasution, dalam skripsinya "Perkembangan Agama Islam di Lingkungan Masyarakat Cina di Medan", menulis bahwa kedatangan warga Cina pertama kali ke Sumatera Utara justru sebagai buruh kebun pada awal abad ke-19. Saat itu Jakobus Nienhuys, seorang Belanda, membuka perkebunan tembakau di Titipapan di sebelah utara Sungai Deli. Karena tenaga kerja ternyata sulit, terpaksa Nienhuys mendatangkan 88 orang Cina dari Penang, Malaysia. Mungkin angka 88 itu hoki buat orang Cina, perkebunan itu pun sukses. Maka, gelombang TKC alias tenaga kerja Cina itu makin deras. Meledaknya kebutuhan ini mengakibatkan impor tak cuma diambil dari Semenanjung Melayu. Para tenaga kerja kemudian didatangkan pula dari tanah leluhurnya Daratan Cina. Muncul pula calo pengerah tenaga kerja yang ketika itu dikerjakan oleh Firma Lauts Haselop, milik seorang Jerman. Dari sekitar 4.000 orang pada 1872, jumlah orang Cina di Deli mencapai 27.000 jiwa pada 1926. Ketika Jepang masuk, pertumbuhan itu baru berhenti. Tak cuma di zaman Belanda, saat ini pun masih banyak warga Cina yang hidup dari kebun buah atau bertani. Salah satu contohnya, Cina dari kawasan Kampung Parit, di pinggiran Kota Pelaihari, ibu kota Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Letak areal ini kira-kira 60 km dari Banjarmasin. Di kawasan seluas sekitar 50 ha itu, hidup 472 jiwa yang seluruhnya keturunan Cina. Hampir semuanya hidup dari berkebun buah-buahan, rambutan, nangka. Sebagian kecil bertani padi. Mereka rata-rata berekonomi lemah. Kampung Parit sekarang boleh dibilang hanyalah sisa-sisa. Masuk ke sana ibarat memasuki panti jompo. Pukul rata mereka berusia di atas 50 tahun. Kawula mudanya sudah menyebar ke mana-mana. Tak tahan lagi hidup di situ. "Kalau mereka pulang ke sini semua, Kampung Parit tak akan mampu menampung semuanya," kata Oey Gwan In, 64 tahun, yang dianggap tetua di sana. Cuma mereka masih punya sedikit kebanggaan. Orang Cina Kampung Parit ini mengaku dirinya sebagai cikal-bakal keturunan Cina yang ada di Indonesia. Menurut Gwan In, sekitar 700 tahun lalu kerajaan Banjar meminta penguasa Cina saat itu mengirim tenaga ahli pembuatan perhiasan emas, keramik, dan ahli dalam soal pertanian. Permintaan itu lantas dipenuhi dengan mengirim 11 orang yang seluruhnya dari Hainan. Mereka semua berasal dari marga yang berlainan: Tan, Liem, Nyoo, Hong, Kiu, Go, Gwan, Tjong, Tjiaw, Law, dan Oey. "Kesebelasan" Hainan ini lantas menikah dengan gadis Dayak. "Tapi cuma sekali itu, lalu mereka menikah di antara mereka sendiri yang berlainan marga," tutur Gwan In. Kesebelas orang ini sangat diyakini oleh penduduk sebagai nenek moyang mereka. Bahkan, "Merekalah leluhur sebagian besar orang Cina yang ada di Indonesia sekarang," katanya lagi. Kehidupan keturunan Cina yang tergolong kelas bawah di kota-kota besar pun tak kalah muramnya. Agen To, 45 tahun bisa dijadikan contoh. Ia cuma hidup di rumah tua yang berukuran 3 x 8 meter di Kampung Balong, Solo. Di ruang sempit berdinding papan dan berlantai plesteran semen itulah Agen To tidur, makan, memasak, dan sekaligus bekerja membuka warung. Dagangannya barang-barang kecil: sabun, teh, gula, juga minyak. Kampung tempat To tinggal memang kawasan Pecinan. Jalanan sempit, rumah berimpitan, penduduknya berjubel. Untungnya, jalan itu sudah diperkeras dengan semen lewat program perbaikan kampung. Di jalan sempit itu pula mereka bekerja. Ada yang membuat bingkai sablon untuk kain batik, berjualan nasi, atau apa saja, bercampur-baur dengan anak-anak yang tak punya tempat untuk bermain. Enaknya, dalam suasana seperti itu kekerabatan dengan penduduk asli menjadi kental. Bahkan kampung ini selamat dari amukan massa ketika huru-hara anti-Cina meletus di Solo, 1980 lalu. Lebih lagi, banyak di antara orang Cina di situ akhirnya kawin dengan orang Jawa. Seperti Yun We, 37 tahun, yang kemudian beralih nama menjadi Jumadi. Pria yang hidup dari membuat roti pia-pia ini menikahi Yayuk Purwanti, 30 tahun, yang asli Jawa. "Soal Cina, ya, tak terasa lagi. Ya, karena sudah kulino (terbiasa)," kata Yayuk, yang sekarang punya dua putra itu. Cerita menarik juga bisa dilihat pada Bin Wat alias Kuwat. Dalam usia yang cukup lanjut, 70 tahun, ia masih harus membanting tulang menjadi tukang parkir di depan rumah makan Gudeg Bu Djuminten, Yogyakarta. Ayah lima anak ini termasuk asli Cina, hanya saja dia lahir di Yogya. Masa muda Bin Wat juga ramai. Ia pernah ikut berperang melawan Belanda. Dengan pangkat prajurit satu, ia bergabung di Kompi Angkutan Divisi III. "Pengalaman perang itulah yang membuat saya akrab dengan pribumi," tuturnya. Tetapi terus menjadi tentara rupanya tak menarik buat Bin Wat. Ia pun berhenti setelah perang usai. Ia mencoba buka warung kecil-kecilan. Ternyata lulusan SD ini gagal. Si kakek ini pernah jadi sopir, lalu pesuruh, dan akhirnya pasrah sebagai tukang parkir. Sebagai bekas pejuang, Bin Wat bukannya tak pernah mengurus status veteran yang menjadi haknya. Sayang, ia terpental gara-gara duit. "Saya mengurus status untuk mendapatkan pensiun, kok malah dimintai duit," katanya memelas. Sekarang ia harus mencukupkan diri dengan hanya Rp 2.000 sehari plus makan siang dan bekal makan sore gratis dari rumah makan Bu Djuminten. "Kalau tak ada makanan gratis itu, saya tak tahu harus bagaimana menghidupi keluarga saya," kata kakek ini, yang menikah secara Islam dengan Supiah, gadis Cirebon asli. Irwan E. Siregar, Kastoyo Ramelan, Almin Hatta, R. Fadjri, dan YH
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini