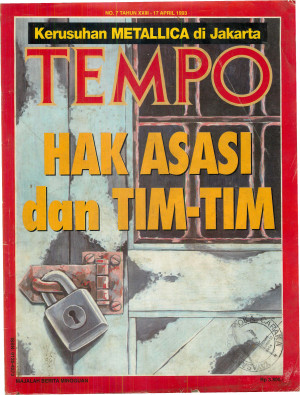KOMITMEN Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia pernah terungkap di forum internasional. Tepatnya di sidang Majelis Umum PBB, September tahun lalu, ketika Presiden Soeharto berpidato selaku Ketua Gerakan Nonblok. Salah satu hal penting yang ditekankan Pak Harto adalah bahwa Gerakan Nonblok siap bekerja sama untuk memajukan hak asasi manusia. Caranya tentu bukan sekadar mengumumkan pernyataan menerima Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Presiden Soeharto melontarkan konsep ''baru'' penerapan hak asasi manusia negara berkembang yang dirumuskan dalam KTT Nonblok tahun lalu di Jakarta: bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai andil yang sangat penting bagi peningkatan martabat manusia atau hak asasi manusia itu. Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembebasan manusia dari kemiskinan, keterbelakangan, serta kebodohan merupakan langkah- langkah nyata mewujudkan penghormatan atas hak asasi manusia. Hal ini kembali ditegaskan dalam konperensi hak asasi manusia di Bangkok pekan lalu. Konperensi Asia Pasifik yang dihadiri utusan dari 49 negara dan 110 lembaga nonpemerintah itu bahkan menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia akan terjamin jika pembangunan ekonomi berhasil. Artinya, pembangunan bidang ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama. Deklarasi Bangkok itu juga menyebutkan bahwa penerapan hak asasi harus disesuaikan pula dengan kondisi budaya dan politik, juga nilai-nilai yang berlaku di negara masing-masing. ''Kerja sama internasional didasarkan pada prinsip kesamaan dan penghargaan atas kedaulatan nasional,'' demikian antara lain isi deklarasi tersebut. Dan negara berkembang pun tampaknya lantas kompak mengecam serangan negara maju yang dinilainya sering memolitisasi pelaksanaan hak asasi itu. Bantuan ekonomi negara maju, misalnya, sering dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia tentunya menurut konsep penerapan negeri asal dana itu di negara berkembang. Syarat pemberian bantuan itu mungkin yang sering disebut ''tak sesuai dengan nilai dan budaya negara berkembang''. Sebab, negara maju dianggap terlalu menonjolkan hak sipil dan politik perorangan. Dirjen Politik Departemen Luar Negeri Wirjono Sastrohandojo, yang memimpin delegasi Indonesia ke Bangkok, juga menegaskan kembali konsep Indonesia, yang juga diadopsi negara Nonblok itu. Jadi, ''Hargailah usaha Indonesia membangun kehidupan sosial dan ekonominya,'' katanya. Dan konsep penghormatan hak asasi manusia yang disebut dengan indivisibility atau tak terpisahkan itulah tampaknya yang kemudian disepakati oleh negara Asia Pasifik di Bangkok. Dalam hal ini, seperti diamanatkan PBB pula, hak sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sipil berkaitan satu sama lain tanpa dipisah-pisahkan. Sikap negara Asia Pasifik yang disepakati di Bangkok itu tampaknya penting karena hal itu akan menjadi konsep bersama negara berkembang yang akan dibawa ke konperensi internasional hak asasi manusia di Wina, Austria, bulan Juni mendatang. Munculnya konsep bersama negara berkembang itu tampaknya tak lepas dari konsep penerapan hak asasi manusia yang selama ini didominasi oleh warna tata nilai di dunia Barat. Dan tak jarang nilai-nilai itu dipaksakan untuk mengukur tingkat penerapan hak asasi di negara berkembang yang belum tentu cocok. Seperti disebut di atas, negara maju terlalu menekankan hak sipil dan individu, dengan mengesampingkan hak komunal. ''Anda sudah mulai membicarakan hak asasi kaum homoseksual yang mungkin belum tentu sesuai atau diperlukan di negara berkembang,'' kata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhamad, yang ditujukan kepada negara maju di KTT G-15 Caracas, tahun 1991. Untuk mengompakkan negara Asia Pasifik atau Nonblok, konsep Indonesia itu tampaknya sudah cukup lama disiapkan. Selain dalam dua lokakarya internasional tentang hak asasi manusia, termasuk misalnya Lokakarya Asia Pasifik akhir Januari lalu, Indonesia juga menugasi Wanhankamnas untuk menyusun konsep penerapan hak asasi yang sesuai dengan tata nilai Indonesia itu. Menurut Profesor Ismail Sunny, yang ikut menyusun konsep bersama Wanhankamnas, konsep itu pada prinsipnya tak jauh beranjak dari apa yang termuat dalam UUD 1945. ''Ini suatu penguraian dari pandangan hidup bangsa Indonesia,'' katanya. Disebutkan, misalnya, kepentingan individu tak boleh melebihi kepentingan umum. Tentang penahanan dan perlindungan hukum, itu pun sudah terinci seperti yang disebutkan dalam KUHAP. Dalam UUD 1945 memang disebutkan delapan pasal tentang hak asasi, misalnya Pasal 27 dan 28: kedudukan warga negara itu sama dalam hukum, dan terjaminnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. UUD 1945 memang tak memuat secara rinci Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang lahir tiga tahun setelah konstitusi Indonesia itu berlaku. Namun, menurut almarhum Suardi Tasrif dalam makalahnya mengenai hak asasi manusia, seluruh isi deklarasi hak asasi PBB itu sudah terdapat secara tersebar dalam UUD 1945 dan berbagai perundangan yang ada. Suardi Tasrif mengambil contoh larangan penangkapan atau pembuangan seseorang secara sewenang-wenang yang termuat dalam Pasal 9 deklarasi PBB itu. Itu, tulisnya, sudah tercantum dalam Pasal 7 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14/1970. Dan juga, tentunya, KUHAP yang kini berlaku, yakni tidak ada orang yang dikenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah. Dan tentang jaminan bahwa seseorang yang dituduh melakukan pidana harus dibuktikan dalam sidang pengadilan, hal itu pun sudah dijelaskan dalam UU yang sama dalam tiga pasal. Karena itu, pada prinsipnya Indonesia telah menganut sepenuhnya deklarasi PBB itu (lihat Dari Konstitusi ke Konstitusi). Penjabaran dalam undang-undang atau hukum positif mungkin sudah memadai. Namun yang sering dipersoalkan adalah tak dilaksanakannya secara penuh hukum positif yang didasarkan pada deklarasi itu. Namun, dari sudut lain, tata nilai dan budaya setempat juga punya andil dalam perbedaan penilaian atas penerapan hak asasi manusia itu. Itu pula tampaknya yang sering menimbulkan konflik penilaian hak asasi antara negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Untuk sekadar memberikan gambaran perbedaan tata nilai itu, ambillah misalnya ada sekelompok transmigran yang berhasil di Aceh. Mereka, yang kebanyakan berasal dari petani miskin dan mungkin tak terpelajar di Jawa, ternyata rajin mengolah tanah, beberapa kali panen, dan memperbaiki rumah jatahnya menjadi bagus, atau mungkin punya sepeda motor. Ini bisa saja mengundang kecemburuan sosial di kalangan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan, misalnya, lokasi transmigran itu diserbu. Polisi pun lantas menangkapi para penyerbu. ''Kaca mata Barat'' sering melihatnya sebagai upaya penindasan dari orang Jawa yang ingin memusnahkan budaya Aceh. Demikian pula serangan sejumlah negara Barat di Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa bulan lalu, yang mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Tim-Tim. Menurut Wirjono, mereka tampaknya tak menghargai tindakan Indonesia yang memperlakukan para tahanan anggota Fretilin dengan baik. Juga, langkah Indonesia dalam menindak sejumlah anggota ABRI, termasuk, yang terakhir, pemberhentian Brigjen S. Warouw sebagai anggota ABRI. Sebagai perbandingan, ia memungut contoh peristiwa Mailai tahun 1968. Letnan Kelly cuma dihukum 3 tahun penjara, padahal perwira Amerika Serikat itu telah memberondong penduduk satu desa (lihat Ali Menjawab Hak Asasi/). Jadi, ''Janganlah setiap tindakan kita dianggapnya sebagai perbuatan kriminal,'' katanya. Dalam konsep penerapan hak asasi manusia, di Indonesia, menurut Wiryono, hak ekonomi dipandang sama dengan hak politik seseorang. Sebut saja hak anak yatim piatu untuk mendapat perlindungan dan jaminan sosial. ''Kalau tak ada pembangunan ekonomi, tak ada pertumbuhan, mungkin tak bisa mewujudkan hak bagi anak yatim itu,'' katanya. Tapi negara maju sering mengabaikan hak ekonomi dengan pembangunan itu. Sering hanya meneropong hak perorangan yang ditelantarkan. Sikap negara berkembang semacam itu tampaknya hampir seragam menghadapi penilaian Barat dalam hal penerapan hak asasi manusia. Pemimpin Tanzania, Julius Nyerere, tokoh negara berkembang dari Afrika, pernah mengatakan, ''Apa hak Barat memberi kuliah tentang hak asasi manusia kepada kami? Mereka pernah memenjarakan saya dan rakyat saya.'' Sebab, penjajahan di masa lalu, katanya, bukti tak menghormati prinsip hak asasi itu sendiri. Penjajahan memang sejarah masa lalu bagi sebagian besar negara berkembang. Namun negara berkembang, kata Wiryono, akan melangkah ke depan dengan konsep baru itu. Itu yang akan mereka bawa ke Wina, Juni nanti. ''Kalau mereka (Barat) tak menerima kami, dan sebaliknya, tentu akan dicari jalan tengahnya,'' katanya. ''Yang jelas, Asia sudah menyusun konsep.'' Mulya Lubis, yang menyelesaikan gelar doktor tentang hak asasi manusia di Universitas California, Berkeley, AS, juga menilai, bila Deklarasi Bangkok membuat pertentangan antara hak asasi universal dan lokal, itu justru akan menyesatkan. Apalagi kalau itu hanya dipakai sebagai dalih negara berkembang untuk membiarkan adanya pelanggaran hak asasi. Ia juga menilai, soal prioritas pada hak sosial ekonomi pun masih bisa dipertanyakan. ''Yang ditonjolkan terutama pertumbuhan, bukan pemerataan,'' kata Mulya. Yang juga dipertanyakan kalangan praktisi hak asasi manusia di sini, mengapa Indonesia, yang sudah menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB sejak 1989, tak meratifikasi dua konvensi yang dianggap penting. Yang dimaksud adalah Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, dan satunya lagi Konvensi Internasional dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Memang, kata Mulya, kalau Indonesia meratifikasi kedua konvensi itu, akan berat konsekuensinya. Harus memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan hak asasi ke PBB, dan PBB berhak minta pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran. Dan PBB pun bisa menanyakan macam-macam, seperti kenapa suatu negara tak ada partai politik, tak ada kebebasan berorganisasi, pers, dan lain-lain. Apa pun alasannya, Ali Alatas sudah punya jawaban tangkas. ''Banyak negara belum meratifikasinya. Amerika Serikat saja belum,'' katanya kepada TEMPO. Salah satu alasannya, dalam konvensi itu termaktup beberapa klausul yang sifatnya terlalu mencampuri urusan intern kedaulatan suatu negara. ''Terlalu menuntut negara menjalankan kewajiban yang belum tentu terlaksana, seperti membuat laporan,'' katanya. Karena tak semua negara menerimanya, kedua konvensi itu, menurut Alatas, belum bisa dikatakan universal. Dan Wirjono memberikan gambaran, mungkin Indonesia bisa meratifikasinya kalau sudah punya komisi hak asasi. Dari 24 konvensi hak asasi manusia PBB yang ada, Indonesia memang baru meratifikasi lima buah. Agus Basri, Leila S. Chudori, dan Andi Reza Rohadian
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini