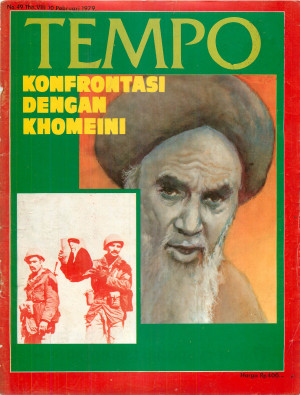SUDAH sejak lama ada pelajaran menggambar di TVRI oleh Tino
Sidin, itu seniman yang selalu memakai baret hitam berkuncir.
Pelajaran menggambar di sekolah, sejak Taman Kanak-kanak sampai
Sekolah Lanjutan Atas, bukan hal asing. Jadi pendidikan kesenian
memang bukan sesuatu yang baru di negeri ini. Tapi kalau
kemudian ada sekolah khusus kesenian, apalagi kalau tingkatnya
perguruan tinggi, ternyata menimbulkan beberapa soal juga.
Di Yogya, 27 Januari sampai 1 Pebruari lalu, ada Seminar Seni
Rupa 1978/1979, dalam rangka mewujudkan pembaharuan Pendidikan
Tinggi Seni Rupa Nasional. Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi
Seni Rupa Indonesia Asri, dan mengundang pembicara dari Bandung
dan Jakarta. Tak kurang dari Menteri P & K sendiri membuka
seminar yang menelan biaya Rp 4,5 juta itu.
"Selama ini pendidikan tinggi seni rupa tak berbeda jauh dengan
sistim sanggar. Di situ ketrampilan lebih dipentingkan,
terrnasuk ekspresi dalam karya. Padahal perguruan tinggi
kesenian itu tingkatnya sama juga dengan universitas. Iari situ
memang jadi perlu untuk pendidikan tinggi seni rupa tidak hanya
mementingkan rasa. Tapi perlu adanya imbangan penalaran," kata
Daoed Joesoef membuka seminar tersebut.
Agaknya soal penalaran dan soal rasa itu jadi fokus perhatian
--tidak saja dalam seminar itu, tapi juga di kalangan mereka
yang berkecimpung dalam pendidikan kesenian. Dua hal tersebut
pada umumnya diakui sama pentingnya. Hanya soal pelaksanaannya
bagaimana, itu yang menimbulkan perdebatan.
Achmad Sadali, pelukis dan dosen Seni Rupa ITB, mengatakan:
"Bila yang ditempuh hanya bahasan teori semata, tidak didampingi
oleh 'merasakan' di dalam kerja studio, akan menjadi sulit
memahami keseniannya itu sendiri." Sadali menunjuk, bahwa yang
penting guna menunjang pendidikan kesenian adalah "bagaimana
seni rupa hidup dan dihidupi di luar sanggar dan lembaga
pendidikan, di tempat pementasan dan museum, di pasar dan
jalanan, di kota dan desa." Dengan lebih terbatas Wiyoso, dosen
Seni Rupa ITB, IKIP Negeri Bandung dan Ketua Akademi Seni Rupa
Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, mengatakan: "Tercapainya
cita-cita pendidikan seni rupa ialah apabila dimulai sejak
sekolah dasar dan erus berkesinambungan." Wiyoso yang dalam
seminar itu khusus menanggapi Sadali kurang lebih menginginkan
adanya pengenalan keseriian sejak kecil, guna membentuk
masyarakat yang apresiatif terhadap seni.
Agaknya penekanan perhatian pada segi ilmiahnya itu, seperti
yang ditunjukkan oleh Edhie Kartasubarna, Kepala Proyek
Pengembangan Institut Kesenian Indonesia, salah satunya
bersumber pada Tridharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian
dan pengabdian pada masyarakat. Juga menurut Doddy Tisna
Amidjaja, Dirjen Pendidikan Tinggi kepada TEMPO: "Sudah ada
sekolah menengah kesenian. Karena itu yang perguruan tinggi akan
lebih ditekankan pada aspek penelitiannya, aspek ilmiahnya."
Malas
Semua itu masih ide, masih gagasan. Masalahnya, apakah
pendidikan kesenian bisa diperlakukan seperti itu -- dengan
hanya menekankan segi ilmiahnya saja? Bagaimana bila seorang
memang hanya berbakat bekerja menciptakan karya dengan kreatif,
tapi tak bisa berbahasa lisan maupun tulisan untuk
mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya? Adakah orang-orang
ini harus terbuang dari pendidikan tinggi kesenian?
Sidharta, dosen Seni Rupa ITB dan Kepala Biro Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan di LPKJ, punya kecenderungan menolak
penekanan pada ilmiahnya saja. "Ada orang yang dilahirkan dengan
kemampuan mengutarakan dengan tepat apa yang dimauinya dari
diperbuatnya. Tapi ada pula yang hanya berbakat intuitif."
Maksudnya dengan "berbakat intuitif" yang hanya mampu berkarya
dengan baik, tanpa bisa menguraikan sebab-musabab kenapa
karyanya jadi demikian.
Keduanya memang harus diberi perhatian. Dan kenyataan yang
dikemukakan oleh Soedarsono, Direktur Akademi Seni Tari
Indonesia Yogyakarta menarik: "Untuk menjadi sarjana rata-rata
anak didik saya malas baca buku. Tapi untuk menciptakan tari dan
mempelajarinya mereka aktif."
Memang kemudian menimbulkan pertanyaan: lalu apa gunanya
pendidikan tinggi kesenian? Apa tidak cukup dengan sekolah
menengahnya saja?
Meski akademi kesenian sudah ada sejak 1950, tapi itu memang
masih jadi pertanyaan yang belum terjawab. Kata Doddy: "Masih
saya mintakan dalam waktu dekat ada seminar atau loka karya
tentang pola pendidikan tinggi kesenian. Misalnya membicarakan
sampaimana pendidikan tinggi kesenian, sampai mana pula
pendidikan yang menengah. Dan bagaimana hubungan antara yang
menengah dan tinggi itu. Juga harus dipikirkan hubungannya
dengan IKIP. Mereka juga punya jurusan keguruan seni. Pokoknya
masih banyak konsep yang harus diperjelas dahulu." Ini
dikatakannya sehubungan akan diwujudkannya IKI.
Sementara itu satu perbandingan yang jelas bisa dilihat di
Yogyakarta. Di sana ada Sekolah Tinggi Seni Rupa. Ada juga
Sekolah Seni Rupa Indonesia. Dalam soal yang berhubungan dengan
teori, memang yang dari STSRI lebih mempunyai bekal. Misalnya
tentang sejarah kesenian, teori komposisi, filsafat kesenian.
Namun bukan berarti dalam soal karya, perbandingan itu pun
berlaku. Mahasiswa STSRI yang datang dari sekolah menengah umum
belum tentu bisa menang -- kalau tidak selalu kalah dalam hal
karya dibanding dengan siswasiswa SSRI.
Maka apa yang dikatakan Wiyoso dalam kertas kerjanya terasa
lebih realistis daripada kertas kerja yang lain. Tulisnya: "Bagi
saya takaran bobot kesenimanan itulah yang sebenarnya tidak ada
sangkut-pautnya dengan pengalaman studi akademik atau tidak.
Sebaliknya bobot kesarjanaan mungkin dituntut keterlibatannya
dengan kegiatan di luar profesi kesenimanan."
Namun tak urung Wiyoso menjawab: "Ingin menghasilkan seniman,"
ketika ditanya LPKJ sebetulnya mau menghasilkan apa.
Barangkali letak kekacauan itu pada istilah "seniman". Sudjoko,
dosen Seni Rupa ITB, pernah menyodorkan ide: bagaimana kalau
istilah seniman itu dihilangkan saja, diganti dengan yang lebih
jelas, lebih menunjuk pada profesi pelukis, pematung, penari,
musikus dan sebagainya. Sulitnya, justru perkembangan kesenian
kini makin membaur. Cabang-cabang kesenian makin saling
mempengaruhi, dan seseorang tak terbatas lagi menggunakan hanya
satu media ekspresi. Ambil saja nama Danarto. Dia ini dulu
melukis, sekarang masih mengajar melukis dan masih sering ikut
pameran, dia juga menulis cerita pendek, naskah drama dan baru
saja menyutradarai satu pementasan drama.
Barangkali juga karena pengertian "seniman" sampai kini tak
jelas yang bagaimana. Apalagi kini ada satu lagi 'seniman' yang
merupakan gelar atau predikat saja. Akademi Seni Karawitan
Indonesia Solo memberikan gelar 'Seniman Karawitan'. "Itu cuma
gelar, seperti dokter atau doktorandus. Kalau berbicara tentang
prestasi kesenimanannya, toh, dokter yang baru lulus itu juga
belum mempunyai prestasi di masyarakat," kata Sedyono Humardani,
direktur ASKI.
Yang kurang mendapat perhatian dalam seminar itu, tapi di luar
cukup menjadi pemikiran banyak orang, ialah tentang pembagian
antara pendidikan scni murni dan seni pakai dalam pendidikan
seni rupa. Yang tidak begitu setuju pada pembagian itu menunjuk,
bahwa kenyataannya mereka yang belajar pada jurusan melukis atau
mematung (seni murni) kebanyakan akhirnya bekerja juga dalam
bidang seni pakai. Mereka bekerja di biro reklame, di biro
arsitek, di majalah dan sebagainya. Kenapa tidak disatukan saja?
Lagipula pembagian itu akan membatasi kemampuan seseorang,
sementara dia belum tahu mana sebetulnya yang paling cocok untuk
dirinya, atau mana sebetulnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Kata Sidharta memberikan alasan perlunya penyatuan itu, karena
penyidikan tak lain dan tak bukan hanyalah "memberikan dasar
sejauh mungkin, memberikan orientasi seluas mungkin." Memang,
pendidikan yang terbatas waktunya itu tentulah tak bisa dengan
pasti mengarahkan orang mau jadi apa. Dalam masyarakat semua itu
akan diuji lagi dan lebih nyata.
Lingkungan Sendiri
Agaknya, akademi kesenian kita hanyalah meniru apa yang sudah
ada di Barat. Pada abad XVIII, di Eropa memang ada pembagian
antara seni murni dan seni pakai. Sementara tradisi seni rupa
kita tidaklah terbagi dalam dua jenis itu. Arca-arca,
lukisan-lukisan, keramik, anyaman, ukiran semua itu indah dan
sekaligus digunakan. Dan lagi, orientasi pendidikan seni rupa
kita -- dan juga seni musik -- praktis Barat. Itu memang tak
ada salahnya. Hanya terasa kurang memberikan alternatif. Kata
Wiyoso "Pendidikan tinggi seni rupa sudah waktunya membuka diri.
Konvensi-konvensi akademik jangan sampai menutup kemungkinan
pendidikan berorientasi pada lingkungan budaya sendiri."
Dengan bahasa Jim Supangkat, alumnus Seni Rupa ITB yang kini
mengajar di LPKJ "Yang kita butuhkan bagaimana lulusan
pendidikan tinggi itu bisa bekerja realistis. Bikin asbak, bikin
patung kecil-kecil, bikin keramik untuk dipasarkan. Sehingga dia
bisa hidup tanpa menggantungkan orang lain. Tentu saja yang
lain, jurusan seni murni itu juga dibina terus. Ini 'kan sudah
menjadi kenyataan. Apa kita mau menutup Balai Seni Rupa Jakarta,
'kan tidak."
Si Jim itu mungkin memang agak ekstrim. Dia menghendaki supaya
lulusan pendidikan seni rupa jangan lari ke lain bidang,
misalnya jadi pemborong rumah. Juga dengan kemampuannya, agar
dihasilkan barang-barang praktls yang juga punya nilai artistik.
Itu gunanya, pendidikan seni rupa atau kesenian pada umumnya,
bagi dia.
Walhasil, pendidikan kesenian memang tidaklah harus menghasilkan
seniman. Kesenimanan tak ada hubungannya dengan pengalaman studi
akademik. Yang diperlukan sebagai hasil akademi kesenian adalah
orang-orang yang kemudian mempunyai bekal pengertian-pengertian
dasar kesenian, yang kemudian bisa menggerakkan dan
mengembangkan kesenian yang sudah dan mungkin berkembang di
sekitarnya.
Orang itu pun perlu mempunyai kelapangan dada untuk memahami dan
menghargai baik seni pakai maupun seni murni, atau juga seni
yang dipelihara di museum-museum atau hanya dijajakan di pinggir
jalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini