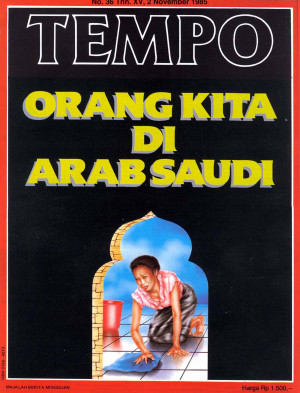KETEGANGAN memuncak sejak pagi. Ratusan penduduk Desa Tubanan berkumpul dekat ladang, menonton dua buldoser yang bersiap meratakan tanah garapan mereka. Teriknya sinar mentari tak lagi digubris para petani gurem di Kecamatan Tandes, Jawa Timur, itu. Emosi mereka sedang tinggi. Beranikah kereta baja itu menggilas tanaman mereka? Maka, begitu kedua buldoser itu merambah tanaman, emosi pun pecah. Sambil berteriak mereka menghambur menyongsong mesin perata tanah itu. Karubi, 50, mengeluarkan katapel yang disiapkannya sejak dari rumah, dan rakyat lain pun memungut batu untuk dilempar. Nenek Paneng yang sudah renta malah lebih nekat. Di depan baja penggusur tanah ia membaringkan dirinya. Beruntung para petugas keamanan cukup sigap, sang nenek diangkat ke tepi sebelum tergilas. Dan korban jiwa pun terelakkan. Bukan berarti tak ada korban lain. Beberapa penduduk sempat terkena pukulan popor. Maklum, kerusuhan yang dimulai pukul 11.00, 21 Oktober lalu itu, baru usai lepas pukul 16.00. Wajar saja kalau petugas tak punya pilihan banyak dalam mengatasi warga yang kalap. Beberapa nenek pun harus merasakan sakitnya didorong-dorong dengan senapan. "Saya sampai terjatuh ke lumpur, kata Seneli, 50, kepada TEMPO. Kejadian ini hampir berulang keesokan paginya, ketika penduduk melihat kedua buldoser itu bekerja sejak pukul 8. Hanya saja kali ini petugas keamanan dari berbagai kesatuan Kodya Surabaya itu, lebih sigap. Para petugas menghadang di depan buldoser dan menghalau mereka. Kerusuhan di kecamatan berjarak 15 km selatan Surabaya ini pun segera mereda. Tapi niat penduduk menuntut ganti rugi tanah tak turut reda. Mereka merasa tertipu oleh pemerintah daerah Surabaya pada 1972. Ketika itu pejabat sementara Wali Kota Surabaya, Soekotjo, membentuk Panitia Pembebasan Tanah untuk Negara (PPTUN). Penduduk dari tujuh desa di Kecamatan Tandes dan Karangpilang dikumpulkan di kecamatan dan diberi tahu bahwa tanah mereka dibutuhkan oleh negara. Untuk itu ditetapkan ganti rugi Rp 145 bagi tanah milik dan Rp 100 untuk tanah garapan serta penggantian untuk tanaman produktif. Penduduk hanya bisa tunduk. Selain saat itu mereka takut dituduh PKI, kabarnya, ada oknum baju hijau yang turut melakukan teror mental. Bahwa pembayaran ganti rugi ternyata tak seperti dijanjikan, waktu itu cuma sedikit menimbulkan percikan. Percikan ini berubah menjadi persoalan besar, 1976. Pada saat itu penduduk mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan ternyata bukan dipakai negara. Persisnya, menurut Edy Pranyoto Ws., Ketua Yayasan Bantuan Hukum dan Penelitian Penyuluhan Masyarakat yang aktif membantu penduduk, tanah seluas 684 ha ini sudah dijual Soekotjo kepada pihak swasta. Perjanjian jual beli itu tertanggal 19 Desember 1972 dan bernilai Rp 1,2 milyar. Direktur PT Pembangunan Darmo Grande, John Wenas, menurut Edy, sudah membayar panjar Rp 150 juta, lima hari sebelum perjanjian itu ditanda-tangani. Penduduk marah karena merasa cuma menerima sekitar Rp 600 juta dari PPTUN. Ada manipulasi ratusan juta? "Itu fitnah," kata Stany, Ketua DPRD Surabaya, yang ditunjuk Wali Kota Surabaya Dr. Purnomo Kasidi untuk memberi keterangan. Ia merasa telah meminta pengacara yang mewakili penduduk itu memeriksa berkas data di instansi kejaksaan dan Polri. "Maksudnya agar pengacara itu tahu bahwa yang mereka bela keliru," katanya. Wakil rakyat ini menganggap penduduk itu tak berhak menerima ganti rugi lagi, tapi sumbangan. Dan itu sudah diberikan. "Jadi, untuk apa mereka sekarang ramai-ramai lagi". BHM Laporan Chairul Anam dan Masduki baidlawi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini