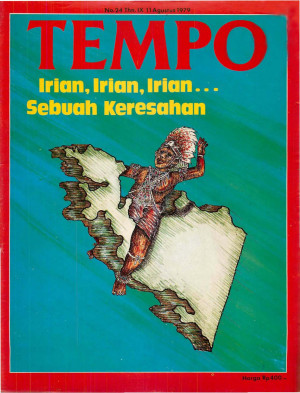SUHU di Lembah Baliem pada ketinggian 1.650 m itu sering
mencapai 14 derajat Celcius. Tapi suku Dani yang mendiami daerah
ini tentu sudah merasa biasa dengan olesan minyak babi sebagai
penghangat.
Hutankah yang mereka diami? Ternyata tidak. Perkampungan tempat
mereka tinggal hanya ditumbuhi pohon yang bisa dihitung
dengan gampang. Dan bersebelahan dengan perkampungan ini
sebidang ladang yang dikotak-kotak dengan pagar tinggi (supaya
tak dirusak babi) bisa kita jumpai. Malah ada juga saluran air
yang cukup dalam untuk membantu kebun mereka. Tampak mereka
sudah agak maju.
Beberapa orang Suku Dani memiliki jari-jari tangan pendek,
bahkan tanpa jari. Mengapa? Karena ternyata jari mereka dipotong
setiap ada kematian untuk menyatakan dukacita. Tapi kebiasaan
ini sudah mereka tinggalkan sejak pemerintah melarangnya.
Ketika wartawan TEMPO Widi Yarmanto, pekan lalu berada di
lembah itu ternyata ada kematian di kampung sebelah yang jauhnya
1 jam berjalan kaki dari kampung Obahorok. Terlihat asap
mengepul sebagai tanda. Babi-babi dibakar, disusul pesta
kematian.
Seorang wanita tua lewat menuju ke arah asap itu. Mukanya seram
dengan badan dioles lumpur, menambah keseraman. Lumpur di badan
itu juga sebagai tanda ikut berdukacita. Kampung yang kesusahan
itu bernama Amigopa. Adik kepala suku dari fam Siap meninggal.
Sakit berak-berak. Tak dibawa ke rumahsakit? "Tidak. Dibawa atau
tidak sama saja. Dulu dibawa ke rumahsakit mati, tidak dibawa
juga mati," kata Pizimaken Siap si kepala suku lewat
penterjemah.
Di kampung yang kesusahan ini berkumpul juga para kepala suku
yang lain. Sebagai tanda dukacita mereka juga menghadiahkan
babi. Kalau babi sudah terkumpul, para anak buah membakar batu
dengan api unggun. Jika batu sudah menyala, maka babi yang sudah
dibuang bagian dalamnya (jeroan) tinggal menarok di batu membara
itu. Ditutupi daun pakis, minyak babi keluar dan daun itupun
menjadi matang.
Sementara mereka membakar babi, dalam rumah panjang terdengar
isak tangis para wanita. Mereka juga meratapi mayat adik kepala
suku. Pesta makan babi dalam upacara kematian ini memang
bervariasi. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang sibuk
kerja dan ada juga yang cuma menatap babi panggang itu.
Sebelum babi dibagi, daun pakis bercampur minyak babi menjadi
rebutan mereka. Anak-anak terutama, getol sekali menyantapnya.
Orang tua yang kurang sabar menanti daging babi juga sibuk
menyantap ini. Berapa babi yang dipotong? Seorang warga suku
Dani yang tubuhnya dicoreng moreng dengan arang dan sudah bisa
sepatah dua kata bahasa Indonesia lalu menghitung tangannya,
lalu menambah dengan jari kakinya 20 ekor. Hitungan selebihnya
cukup dikatakan: banyak.
Dalam lingkungan honie (rumah mereka yang berbentuk setengah
bola) dengan ukuran sekitar 20 x 30 m, sekitar 300 orang kumpul.
Di luar lingkungan ini masih ada juga yang menyatakan dukanya.
Tapi mereka hanya berdempetan di luar saja. Anak-anak kecil yang
merasa kedinginan cukup menyilangkan kedua tangan ke leher.
Daging sudah dibagi. Tapi gerimis tak bisa dibendung. Seorang
pawang hujan berdiri di tengah kerumunan manusia. Dia berteriak
sambil membentangkan tangannya lebar-lebar hza . . . haz . . .
hza . . . Itu saja rasanya nada yang tertangkap telinga. Tapi
apa maksudnya "Itu memohon kepada dewa dengan menyebut nama
leluhur yang sudah meninggal. Supaya mereka juga ikut menerima
arwah yang mati," kata Horalik, warga Dani yang pernah mengenyam
pendidikan sampai klas V SD di Wamena.
Berkali-kali pawang ini berteriak. Makin keras dan makin
lantang. Tapi kehendak Yang Kuasa tak bisa dihindarkan. Hujan
pun tetap deras mengucur. Dan buyarlah mereka.
Mayat orang suku Dani ini dibakar. Di lembah ini ada juga mayat
yang dimumikan. Satu di antaranya di kampung Aikima. Mumi ini
dari fam Kurollik. Dalam posisi duduk. Umurnya berapa, tak
diketahui. Warna mumi ternyata lebih hitam dari mereka yang
masih hidup. Kepalanya diberi hiasan bulu berwarna putih.
Lehernya dikalungi taring babi dan beberapa kerang laut.
Yang dimumikan adalah mereka yang dulunya berjasa banyak untuk
kampung itu, di samping juga sebagai pahlawan perang. Konon
waktu suku-suku di Lembah Baliem perang dengan suku yang lain,
maka mumi itu diarak di barisan paling belakang. Maksudnya untuk
memberi dorongan moril bagi mereka. Dan kalau mumi ini hancur,
maka praktis kekuatan suku itu punah.
Sekarang mumi tidak untuk menambah kekuatan waktu perang karena
perang suku tak ada lagi. Mumi itu dikomersialkan. Yaitu
memungut bayaran dari mereka yang ingin melihatnya. Berapa
jumlahnya tidak tentu. Kalau dulu, sebelum 1975 mereka hanya
mengenal uang merah, maka tahun belakangan ini sudah juga tahu
warna uang hijau dan biru. Selembar daun pisang dihamparkan di
tanah dan yang mau memotret atau melihat, menjejerkan uangnya
hingga penuh di daun itu.
Pemerintah juga sudah turun tangan dengan membuatkan rumah-rumah
untuk mumi ini. Tapi mumi tak pernah ditarok di dalamnya. Mumi
tetap disimpan seperti semula, dalam honie.
Di daerah pegunungan Jayawijaya sebelah barat juga ada mumi.
Bentuknya lebih aneh lagi. Giginya masih melekat di rahang. Dan
katanya, rambut pun masih ada yang bertengger di batok
kepalanya. Dengan bahan apa mereka memumikan orang, masih
dirahasiakan. Adonan untuk menjarangkan anak juga ada, juga
dirahasiakan.
Satu hal yang terlihat di Lembah Baliem sama dengan tempat lain
adalah anak-anak bermain bola. Berkoteka maupun yang bercelana.
Padang rumput memang banyak di sana. Pak Harto yang pernah
berjanji memberi kambing buat Obahorok juga dinanti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini